Malam yang dingin itu saat membuka koran Pikiran Rakyat, edisi Sabtu, 19 Juli 2025, terdapat berita di halaman depan langsung menyita perhatian bertajuk “Tragedi Pesta Wabup Garut.”
Pesta yang seharusnya menjadi momen bahagia dalam rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut Putri Karlina, anak dari Kepala Polda Metro Jaya Inspektur Jenderal Maryoto dengan Maula Akbar Mulyadi, putra sulung Dedi Mulyadi berubah menjadi duka mendalam.
Tiga warga (Vania Aprilia 8 tahun, Dewi Jubaedah 61 tahun dan Bripka Cecep Saeful Bahri, 39 tahun) dilaporkan meninggal dunia dalam kericuhan saat sesi makan gratis di depan Pendopo Garut, Jumat (18/7/2025) siang.
Acara yang digelar sejak pukul 13.00 WIB di Lapangan Otista, Alun-alun Garut itu awalnya berlangsung meriah. Namun saat (satu) gerbang dibuka untuk mengantre pembagian makanan gratis, suasana mendadak kacau.
Massa berdesakan, berebut, saling dorong, hingga terinjak-injak. Ironisnya, tragedi ini justru terjadi dalam acara yang diklaim sebagai “hiburan rakyat.”
Gubernur Jawa Barat, Dedi Mulyadi, menyampaikan permohonan maaf atas insiden dalam perayaan pesta rakyat yang menjadi bagian dari rangkaian pernikahan Wakil Bupati Garut, Lutfhianisa Putri Karlina, dengan Maula Akbar Mulyadi Putra.
“Saya mohon maaf yang sebesar-besarnya atas peristiwa tersebut,” ujarnya.
KDM menginstruksikan stafnya untuk segera menemui seluruh keluarganya dan menyampaikan uang duka darinya sebagai Gubernur Jawa Barat. Keluarga yang mendapat musibah akan diberi uang duka Rp 150 juta per keluarga.
“Ini adalah bagian dari empati kami dan kemudian ke depan, pembelajaran penting bagi siapapun, termasuk keluarga saya sendiri, kalau buat acara itu harus setidaknya diperhitungkan berbagai kemungkinan yang akan terjadi, termasuk juga penyiapan pengamanan yang cukup," tuturnya.
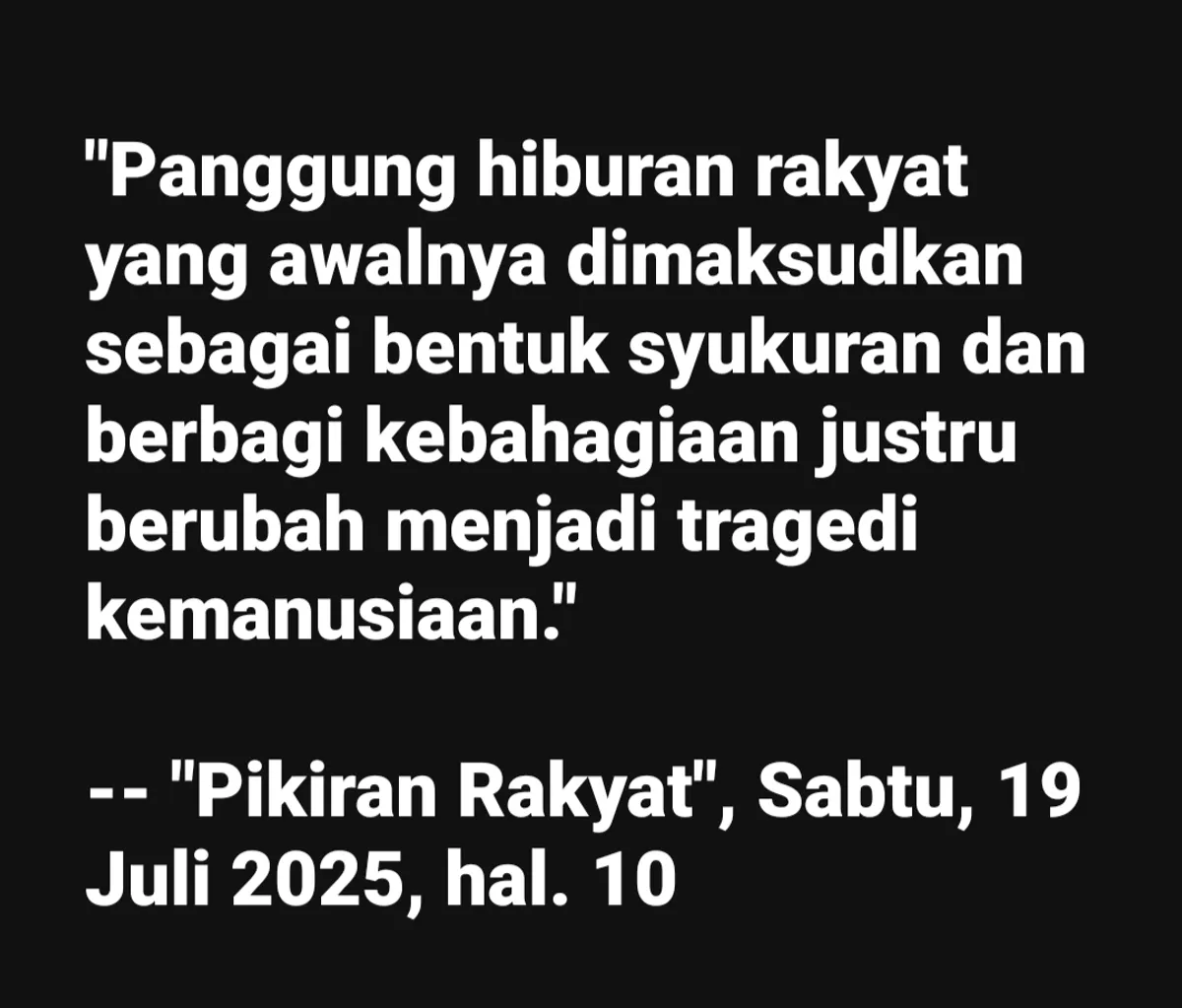
Di tengah-tengah suasana duka mendalam, tiba-tiba seorang kawan, salah satu warga yang tinggal di Garut, melontarkan komentar yang cukup menohok dan mengejutkan,
“Pasta Rakyat (Ceunah)
Dirarame kunu lapar, dipupuja kunu teu boga, dieuleuh-euleuh kunu eweuh.
Mawa kariweuh.
Rarasaanmah nyieun kaalusan teu kudu kikituan. Datangan, asongan (mun perlu huapan) bungan kacida pikeun rahayatmah.
(Ironis, Nu Penting Populis)"
Kujawab dengan singkat, "Luar biasa diksina, Bosque!"
Tentunya, kalimat dalam gaya Sunda itu penuh sindiran yang menangkap esensi persoalan, setiap kemasan populis (borjuis) tak selalu berpihak pada rakyat (wong cilik). Justru kadang hanya menjadi panggung simbolik yang menampilkan empati, tetapi abai pada tata kelola dan keselamatan.
Ya sederhananya, tidak cukup niat baik, apalagi tanpa adanya perencanaan matang bisa berubah menjadi bencana dan petaka kemanusiaan yang melukai hati nurani.
Mari kita bandingkan dengan liputan Kompas edisi Sabtu 19 Juli 2025, bertajuk "Kesenjangan Ekstrem di Balik Tragedi Pesta Syukuran Pernikahan Anak Gubernur Jabar" dijelaskan kasus tewasnya tiga orang dalam pesta syukuran pernikahan anak Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi menjadi potret besar dua persoalan utama masyarakat Indonesia, ekstremitas dan mesianistik kompleks.
Dosen Sosiologi Universitas Gadjah Mada, AB Widyanta, menyampaikan dari kasus ini, publik bisa melihat wajah ekstremitas di masyarakat Indonesia. ”Itu potret ekstremitas atau kesenjangan lebar antara pejabat publik di mana bisa menggelar pesta besar-besaran dan melakukan flexing, dengan menelan biaya besar.
Sementara di sisi lain, ada masyarakat yang hidup dalam kemelaratan yang berharap pada bantuan atau pemberian. Ini bagian dari wajah kita, tentang betapa lebarnya jurang ketimpangan sosial yang terjadi di negeri ini,” tuturnya.
Rupanya kejadian ini menjadi potret buram pejabat publik yang gencar menyuarakan efisiensi, yang justru tidak melakukan efisiensi, tetapi menggelar hajatan mewah dan meriah. Sementara di satu sisi, rakyat terpesona dengan gemerlap pergelaran pengantin itu.
Dari sana terlihat seolah-olah seluruh sumber daya negeri ini ada pada pejabat publik. Sedangkan masyarakat harus berbondong-bondong mendapatkan ”sumber daya” itu dari pejabat. ”Padahal, pejabat publik ini yang harus meredistribusi resources ke rakyatnya. Mereka justru harus melayani. Namun, yang terjadi sebaliknya,” ujarnya.
Masyarakat terjebak dalam orkestrasi selebritas dan kultus individu sosok Gubernur Jabar. Menganggap sosok itu bisa mengentaskan dari kemelaratan dan persoalan hidup.
”Ini jebakan mesianistik kompleks yang terus berulang. Bahwa pejabat atau sosok itu dikira bisa mengentaskan dari kemiskinan dan kesengsaraan. Namun, sejatinya tidak. Ini hanya bagian dari selebrasi atas kultus individu yang melahirkan fans dan berujung petaka,” katanya.
Populisme Alat Demokrasi
Tragedi ini menyisakan pertanyaan mendasar untuk siapa pesta rakyat digelar? Apakah benar-benar bagi warga atau sekadar pencitraan?
Dalam buku Populisme Agama dan Pemilihan Kepala Daerah terdapat bahasa tentang populisme sebagai alat demokrasi.
Kenny dalam bukunya berjudul Populism in Southeast Asia, terdapat dua kelompok mengaktualisasi populisme.
Pertama, populisme diaktualisasi sebagai ideologi. Kedua, populisme diaktualisasi sebagai senjata atau strategi politik konsolidasi mobilisasi emosional rakyat, untuk mendapatkan dukungan, dengan menghilangkan jarak komunikasi antara figur populis (kharismatik) dengan pengikutnya, (Kenny, 2019: 9).
Benjamin Moffet dan Simon Tormey dalam Rethinking Populism: Politics, Mediatisation and Politics Style, populisme diaktualisasikan sebagai ideologi, politik logis, diskursus (wacana), dan strategi, organisasi, (Benjamin Moffit & Simon Tormey, 2013). Populisme diaktualisasikan konsepsi gaya retorika, melalui klaim menyanjung rakyat, tetapi kenyataannya mereka hanya berbicara demi kepentingan diri sendiri (Goldberg, 2018).
Populisme diaktualisasi konsepsi mobilisasi. Mobilisasi yang dimaksud, melalai keterlibatan pemimpin populis (personalist leadership), gerakan sosial (social movement), dan partai politik (political party), mendorong masyarakat bergerak secara kolektif dalam jumlah besar agar mendukung tujuan mereka (Mudde & Kaltwasser 2017: 42).
Populisme diaktualisasikan melalui konsepsi ideologi, logika politik, wacana, gaya, strategi, mobilisasi. Penulis mendefenisi-kan populisme merupakan emosionalisasi, personalisasi gaya komunikasi aktor politik kharismatik mengacu pada rakyat, dikonsepsikan melalui ideologi, wacana, logika politik, mobilisasi, ataupun strategi, tanpa menghilangkan estetika politik.
Keberhasilan populisme diaktualisasikan melalui konsepsi strategi demokrasi, dilihat melalui kemenangan Donald Trump momen pemilihan presiden Amerika 2016, Trump mewacanakan Amerika menjadi negara super power kembali melalui slogan I will make it great again, dikonsepsikan melalui gaya pidato, retorika pembelaaan terhadap partikularisme (kepentingan pribadi, kelompok tertentu)
Privilege ekonomi kelas menengah sayap kanan, melalui strategi produksi isu penyatuan imajiner kolektif politik ketakutan masyarakat terhadap pluralisme, representasi ideologi nasionalisme, anti terhadap imigran terutama imajiner ketakutan terhadap imigran dari negara-negara Muslim secara bertahap akan merusak nilai sosial budaya yang telah exist, (nativisme) (The Guardian, 2016).

Perkembangan dan Dinamika Media
Di dunia terutama Eropa, populisme berkembang sangat cepat, sehingga mempengaruhi panggung perpolitikan dan kebijakan sosial suatu negara. Perkembangan pesat ini dipengaruhi kelenturan sifat populisme serta pengaruh adaptif tehadap perkembangan media. Media dapat dikatakan "Pilar Keempat" dalam demokrasi (Carlyle, 1840: 392, Schultz, 1998, 49).
Media memegang peran penting bagi kegagalan dan kesuksesan populisme, sebagai aktor domestik menjadikan populisme bangkit dan berkembang dalam lanskap sosial politik sejak berakhirnya perang dunia II (Mudde & Kaltwasser, 2016).
Diaktualisasikan melalui lanskap sosial politik, media menyeleksi, membingkai topik (interpretasi) dan opini, sehingga menarik minat pembaca (Esser & Buchel, 2015: 4). Produksi berita media, tidak hanya didorong kebutuhan, tetapi melalui cita rasa dan preferensi konsumen, sehingga berpotensi melahirkan budaya politik populis (Esser & Matthes, 2013).
Populisme mengambil banyak manfaat dari media, kecenderungan menampilkan sesuatu populer, melalui pesan dramatisasi, emosional disampaikan aktor populis, daripada berita politik yang netral (Moffitt & Tormey, 2014: 391-394 dan Wirth & Esser, 2015: 3).
Populis memanfaatkan media untuk menciptakan komunitas bersama dan ikatan emosional dengan rakyat (Henrichsen, 2019: 6). Akses refeodalisasi media konvensional mentrigger hadirnya new media, bermakna kehadiran new media selain merupakan adaptasi jawaban terhadap perkembangan teknologi informasi, juga merupakan revitalisasi ruang publik yang sudah terfeodalisasi.
Kembali masyarakat berharap new media menjadi penguat dan tulang punggung demokrasi, berdasarkan asumsi persamaan karakteristik keduanya. Demokrasi mencerminkan kesetaraan, pengakuan terhadap perbedaan, kebebasan berpendapat, partisipasi, dan perlindungan hak dasar manusia.
New media membuka ruang yang bebas, bahkan terkadang tanpa batas, melalui prinsip kesetaraan dan kebebasan yang dipegang, dan setiap orang berperan sebagai pembuat yang independen.
David Bolter memaknai remediation ruang publik, merupakan mediasi ulang ruang publik sehingga melahirkan sebuah realitas baru (virtual), awalnya ruang publik berbentuk kesatuan bergeser menjadi liquid identity, jika dimaknai berdasarkan komunikasi sosial politik, remediation melahirkan rekonfigurasi modernitas, proses realitas baru perubahan komunikasi pemilih dari konvensional kepada modern (Muzaini, 2014).
Entitas lain yang berpengaruh dalam demokrasi di tingkat lokal adalah elite lokal, atau dapat disebut local strongman, "orang kuat lokal" atau diistilahkan lain local broker, patron, dan client.
Pengaruh orang kuat lokal dikarenakan modal yang mereka miliki, berupa social capital ataupun economic capital yang tidak dimiliki oleh kebanyakan orang, sehingga memiliki legitimasi serta dukungan sosial dikarenakan mereka sebagai tempat pemenuhan kebutuhan masyarakat lokal, legitimasi mereka dimanifestasikan melalui penguasaan politik, opinion leader bahkan sampai ikut mempengaruhi kebijakan pemerintah.
Kemunculan local strongman merupakan keniscayaan bentuk kuatnya kekuasaan mereka pada masyarakat. (Rahman Tahir, dkk [Dewi Kesuma Nasution, 2024:4-6)
Cass Mudde dalam bukunya Populism : A Very Short Introduction menjelaskan adanya dua kelompok besar di masyarakat yaitu the pure people and the corrupt elite. Masyarakat miskin dipandang sebagai pure people yang perlu mendapatkan bantuan dari pemerintah.
Pemerintah akan cenderung memusatkan perhatiannya kepada masyarakat miskin karena jumlah populasinya yang sangat banyak. Maka dari itu, tidak menutup kemungkinan jika masyarakat miskin bisa menjadi korban dari gimmick populisme para aktor yang sedang maupun akan menjabat di pemerintahan.
Dosen Sekolah Tinggi Filsafat (STF) Driyakarya Herry Priyono menjelaskan masyarakat harus menolak tegas segala bentuk populisme. Jaminan rasa aman untuk hidup di Indonesia harus bisa diberikan penguasa.
Penting untuk diketahui bagi pemerintah, populisme yang berarti paham yang berpihak kepada rakyat, tidak hanya semata-mata untuk memenuhi permintaan rakyat sepenuhnya, plus korelasinya dengan dukungan elektoral.
Tragedi Plumpang (Garut) mengajarkan bahwa pemerintah harus tegas dalam memberikan solusi yang adil kepada seluruh rakyat, agar dapat tercapainya rasa aman dan agenda pro-demokrasi dapat berjalan maksimal.(www.pinterpolitik.com)
Ketika ribuan orang memadati Alun-alun Garut demi iming-iming makan gratis, peristiwa itu bukan sekadar bagian dari perayaan, melainkan potret nyata ketimpangan sosial, kelaparan, dan keterdesakan hidup yang selama ini tersembunyi di balik keramaian.
Kemasan populis tanpa perhitungan matang bisa berujung tragis. Pesta rakyat berubah menjadi petaka. Niat baik yang mestinya membawa kebahagiaan justru menelan korban dan menyisakan duka mendalam.
Di era media sosial dan pencitraan instan, istilah "pesta rakyat" kerap dijadikan komoditas komunikasi politik, alat untuk menjual citra kedekatan, membangun simpati, hingga mendongkrak elektabilitas. Namun tanpa etika publik dan tanggung jawab sosial, rakyat bukan lagi subjek yang dimuliakan, melainkan sekadar penonton, bahkan, lebih tragisnya, menjadi korban.
Dalam dunia politik, populisme adalah senjata ampuh yang menawarkan kesan kedekatan dengan rakyat, tapi sering kali mengorbankan substansi demi euforia sesaat. Ketika makan gratis dianggap lebih penting dari manajemen risiko, dan kerumunan lebih berharga daripada keamanan, di situlah kultus populis menemukan wujudnya.
Pernyataan Bambang Eka Cahya Widodo, dosen politik dan pemerhati pemilu, terasa relevan: "Senjata pemimpin populis itu selalu sama, yaitu gimmick, dan jauh dari substansi."
Baca Juga: Antara Kata dan Fakta: Ujian Komunikasi Publik KDM di Tengah Musibah Pernikahan
Tragedi Garut seharusnya menjadi pelajaran bersama. Mencintai rakyat tak cukup dengan membagi nasi kotak (bungkus) menyajikan hiburan massal. Justru yang utama memastikan keselamatan, kesejahteraan, dan martabat warga agar tetap terjaga.
Mencintai rakyat bukan dengan gimmick. Kehadiran warga dalam pesta rakyat tak boleh sekadar menjadi alat pencitraan. Pasalnya keselamatan wong cilik jauh lebih penting dari sekadar euforia sesaat.
Dengan demikian, populisme tanpa etika adalah jebakan. Kultus populis yang menjual keramaian, namun abai terhadap kemanusiaan, adalah bentuk kekosongan yang menyakitkan. Apalagi ketika empati berubah menjadi strategi popularitas, rakyat hanya menjadi ornamen dalam panggung kekuasaan. (*)