AYOBANDUNG.ID - Hari Natal tahun 1926 di Ciparay rupanya tak seromantis kartu pos dari toko kolonial. Tidak ada lonceng, tidak ada kue jahe, hanya ada pisau yang melesat di antara lapak kain dan jeritan pedagang. Seorang penjual kain pribumi bernama Wanta memutuskan untuk mengisi hari suci itu dengan sedikit pertunjukan darah.
Semua bermula di pasar Ciparay, tempat segala urusan ekonomi dan gosip lokal bertemu dalam satu aroma: keringat, ikan asin, dan kain basah. Di sanalah Jo Tjioe Kien, seorang Tionghoa yang mencari rezeki dari perdagangan tekstil, berselisih dengan si Wanta. Perselisihan kecil tampaknya, namun entah soal apa persisnya.
Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië edisi 6 Januari 1926 mencatat keonaran yang dibkin Wnata ini. Keributan mereka menarik perhatian pengunjung lain. Orang-orang berhenti menawar bawang dan tembakau, ikut menonton. Di antara kerumunan itu, datanglah Tan Tian Hoat. Ia mencoba melerai. Sialnya, keberanian itu berujung petaka. Dalam sekejap, pisau muncul dari pinggang Wanta. Sekali hunus, tajamnya menembus lidah Tan, keluar di pipi sebelah.
"Ia mencabut pisau dan menusuk wajah Tan Tian Hoat, melukai lidahnya, dan pisau itu bahkan menembus hingga ke pipi sebelah lain." tulis koran itu menggambarkan kelakuaan Wanta.
Baca Juga: Hikayat Komplotan Bandit Revolusi di Cileunyi, Sandiwara Berdarah Para Tentara Palsu
Darah berceceran. Jeritan terdengar. Tan terjatuh di tanah, wajahnya berlumuran darah, dan pasar berubah jadi kekacauan. Beberapa pedagang Tionghoa buru-buru menolongnya, menyeret Tan keluar dari tengah kerumunan. Sementara Wanta berdiri saja, dengan tangan masih memegang pisau yang sudah berubah warna.
Polisi lapangan datang. Polisi desa datang. Mereka melihat korban, menulis sesuatu di buku catatan, lalu menghilang. Tidak ada borgol, tidak ada perintah tangkap. Wanta tetap di pasar, berjalan tenang di antara lapak-lapak, seperti penjaga keamanan yang baru saja menunaikan tugasnya.
"Dalam keadaan berlumuran darah, korban segera diselamatkan oleh orang-orang Tionghoa lain yang ada di pasar. Polisi lapangan dan polisi desa segera diberitahu, namun anehnya pelaku Wanta tidak ditangkap." demikian tertulis dalam koran.
Kabar penusukan itu menyebar ke seluruh Ciparay. Orang-orang tidak hanya membicarakan darah yang muncrat, tapi juga keberanian Wanta. Dalam obrolan warung kopi, ia bukan lagi penjual kain, melainkan semacam raja kecil pasar. Ada yang bilang ia punya orang dalam. Ada pula yang bilang, ia bagian dari kelompok yang sudah lama membuat onar di wilayah itu.
"Secara umum di Ciparay beredar kabar bahwa Wanta berani bertindak sewenang-wenang karena bekerjasama dengan sekelompok penjahat yang menebar teror di seluruh wilayah Ciparay."
Kemudian nama-nama lain muncul: Karta, sang mandor pasar yang lebih sering mengatur urusan pribadi daripada urusan kebersihan, dan Soekardi, penjaga wesel kereta api Staatsspoorwegen (SS) yang dikenal lebih suka berjudi ketimbang menjaga rel. Mereka bertiga, kata orang-orang, sering terlihat bersama. Di warung, di pasar, atau di pojok kampung saat malam tiba.
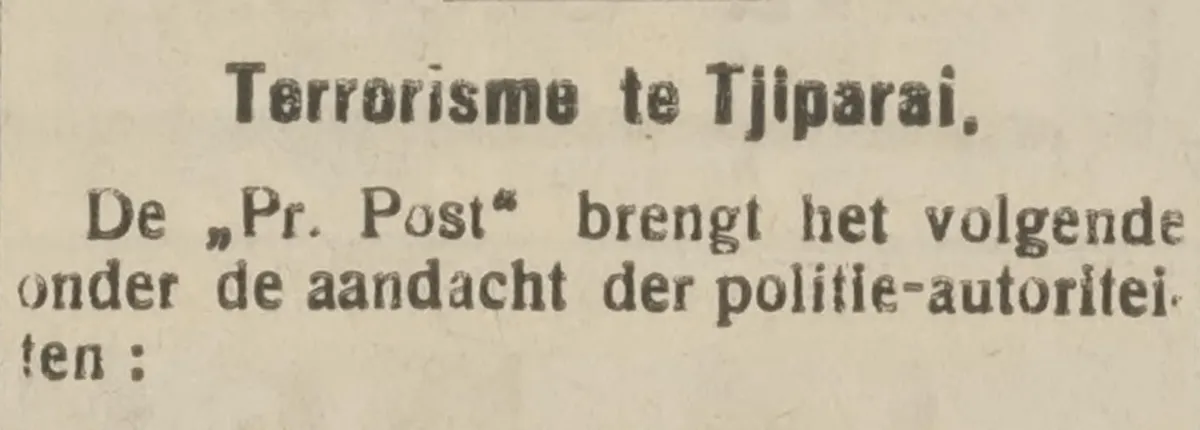
Beraksi Bukan Cuma Sekali
Tanggal 29 Desember, empat hari setelah Natal berdarah itu, Ciparay belum tenang. Malam itu, rumah seorang Tionghoa bernama Joe Koei dilempari batu. Suara pecahan kaca terdengar hingga ke gang belakang. Tak ada yang berani keluar rumah. Setelah puas, geng Wanta beranjak ke rumah lain, milik Jo Laij Hie.
Komplotan ini mengetuk pintu, menuntut uang. Tapi Jo Laij Hie, yang mengaku tidak punya uang di rumah, menjawab dengan jujur. Geng itu tidak suka kejujuran. Mereka membalasnya dengan tinju dan tendangan.
Sejak malam itu, pasar kecil di Lemboer Awi mendadak sunyi. Wanta dan anak buahnya menyebar kabar: siapa pun yang berani datang ke pasar, akan diserang. Ancaman itu cukup untuk membuat para pedagang Tionghoa menutup toko dan tidak keluar rumah.
Pasar yang biasanya ramai dengan suara timbangan dan tawa, berubah jadi tempat kosong. Lalat lebih banyak dari pembeli. Sementara itu, di kantor polisi desa, tak ada yang terjadi. Polisi duduk di kursinya, menatap keluar jendela. Mereka tahu nama pelaku, tahu tempatnya, tapi tangan mereka seperti terikat.
Seseorang menyebut bahwa Wanta punya pelindung. Entah benar, entah hanya gosip, tapi faktanya, ia tetap bebas. Ia masih berkeliaran di pasar Ciparay, membawa pisau seperti tanda jasa. Kadang ia terlihat duduk di warung bersama mandor Karta. Kadang berbincang dengan Soekardi di dekat rel kereta. Tidak ada yang berani menegur.
Ketakutan menyebar seperti demam. Para pedagang Tionghoa tak lagi berani menyalakan lampu malam. Pintu ditutup rapat. Anak-anak disuruh tidur lebih awal. Di jalan-jalan kampung, hanya suara anjing yang terdengar menggonggong panjang.
Kabar itu sampai ke telinga para pejabat di Bandung. Tapi sebelum itu, beberapa orang Tionghoa di Ciparay sudah lebih dulu menulis surat. Mereka memohon kepada Residen Priangan Tengah agar dikirim bantuan. Mereka tidak menulis panjang, hanya memohon perlindungan. Surat itu dikirim lewat pos, diantar oleh seseorang yang juga gemetar saat menyerahkannya.
Koran Het Nieuws van den Dag voor Nederlandsch-Indië menulis panjang lebar rangakaian aksi abndit selebor ala bang jago zaman kiwari ini di bawah tajuk “Terrorisme di Tjiparai.” Kata “terorisme” terdengar besar untuk sebuah pasar kecil di selatan Bandung, tapi itulah cara koran Hindia Belanda kala itu memoles kekacauan lokal agar terlihat serius.
Baca Juga: Jejak Dukun Cabul dan Jimat Palsu di Bandung, Bikin Resah Sejak Zaman Kolonial
Dalam laporan itu juga disebutkan, bukan hanya warga Tionghoa yang ketakutan, tapi juga para pribumi kaya yang merasa ikut diincar. Rumah mereka ikut ditutup, toko mereka ikut dikunci. Di Ciparay, siang hari jadi panjang, malam terasa lebih pekat.
"Bukan hanya warga Tionghoa di Ciparay yang diancam oleh Wanta, tetapi juga para pribumi kaya yang ikut diberi teror olehnya."
Polisi desa tetap diam. Mereka seperti bayangan—ada, tapi tak berfungsi. Di jalan, orang-orang hanya berbisik. Nama Wanta tidak disebut keras-keras. Anak-anak bahkan diajari jangan menatap pria berpeci dengan pisau di pinggang yang sering melintas di depan pasar.
Pasar Lembur Awi yang dulu hidup dari jual beli, kemudian tinggal tersisa debu. Tidak ada pedagang, tidak ada pembeli. Hanya papan nama pasar yang mulai pudar di bawah sinar matahari. Dari balik jendela rumah, orang-orang menatap ke luar dengan rasa cemas yang sama.
Di rumah Jo Laij Hie, bekas pukulan di dinding belum dihapus. Di rumah Joe Koei, kaca jendela yang pecah belum diganti. Di jalan tempat Tan Tian Hoat dulu jatuh, masih ada bekas noda gelap yang tak mau hilang meski sudah sering diguyur hujan.