AYOBANDUNG.ID - Hari ini Jalan Dago dikenal sebagai etalase Bandung. Kafe berderet, sepeda berseliweran, dan trotoar menjadi ruang pamer gaya hidup. Namun jauh sebelum ngopi edgy dan lari pagi menjadi kebiasaan, Jalan Dago punya reputasi lain yang tak kalah terkenal. Ia pernah menjadi salah satu ruas paling rawan kecelakaan di Bandung pada masa kolonial.
Pada awal abad ke-20, Jalan Dago belumlah serapi sekarang. Jalan ini membentang dari pusat kota menuju kawasan utara Bandung yang lebih sejuk, melewati tikungan, tanjakan, dan pertemuan jalan yang kala itu belum dilengkapi rambu memadai. Lalu lintasnya campur aduk. Sepeda, gerobak, truk barang, sepeda motor, hingga mobil pribadi milik pejabat kolonial berbagi ruang tanpa aturan yang benar-benar dipahami semua pihak.
Surat kabar Belanda yang terbit di Hindia Belanda mencatat Jalan Dago bukan sekali dua kali muncul dalam kolom peristiwa. Nama jalannya kerap hadir bersama kata tabrakan, terlindas, atau meninggal dunia. Dari anak pembantu tukang daging hingga pegawai kantor telepon, dari kuli gerobak sampai petugas pos, Jalan Dago menjadi saksi bagaimana modernitas transportasi sering datang lebih cepat daripada kesadaran keselamatan.
Baca Juga: Sejarah Dago, Hutan Bandung yang Berubah jadi Kawasan Elit Belanda Era Kolonial
Koran Het Nieuws van den Dag edisi akhir Januari 1929 melaporkan sebuah kecelakaan yang terjadi pada pagi hari di Jalan Dago. Korbannya seorang anak pribumi yang bekerja sebagai pembantu tukang daging. Anak itu sedang bersepeda bersama temannya dan memilih cara cepat yang lazim kala itu, yakni berpegangan pada truk barang yang sedang melaju. Ketika melihat polisi, mereka panik dan melepaskan pegangan. Salah satunya terjatuh tepat di antara truk dan gandengannya.
"Gandengan itu melindas anak tersebut dan menghancurkan kepalanya. Anak itu meninggal seketika," demikian tulis Het Nieuws van den Dag.
Dalam hitungan detik, gandengan itu melindas tubuh sang anak. Kepalanya hancur, dan nyawanya tak tertolong. Jenazahnya kemudian dibawa ke Rumah Sakit Borromeus yang letaknya tak jauh dari lokasi kejadian.
Dua tahun berselang, De Locomotief mencatat tabrakan lain di Jalan Dago. Kali ini melibatkan mobil dari Semarang yang ditumpangi seorang pejabat kehakiman dan sebuah gerobak yang dikemudikan kuli. Dua kuli terluka, mobil rusak ringan, dan laporan resmi menyimpulkan kesalahan ada sepenuhnya pada pihak kuli.
"Kesalahan sepenuhnya berada di pihak para kuli," tulis De Locomotief.
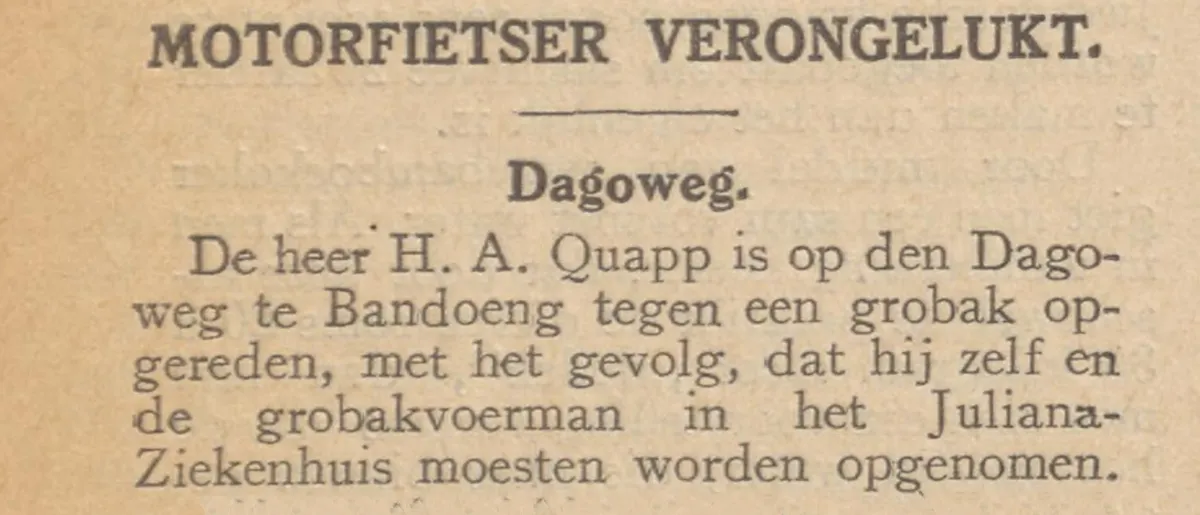
Baca Juga: Hikayat Banjir Gedebage Zaman Kolonial, Bikin Gagal Panen dan Jalan Rusak
Cara pandang kolonial terhadap lalu lintas saat itu nempaknya memang agak lain. Mobil selalu benar, gerobak selalu salah, dan luka manusia sering kali dianggap efek samping yang bisa ditoleransi.
Pada dekade 1930-an, jumlah kendaraan bermotor di Bandung meningkat pesat. Jalan Dago yang semula dirancang untuk promenade elite berubah menjadi lintasan cepat. Kecepatan menjadi simbol modernitas. Sayangnya, refleks manusia tidak berevolusi secepat mesin.
Pada November 1934, Het Nieuws van den Dag kembali melaporkan sebuah peristiwa penting di persimpangan Jalan Dago dan Jalan Riau. Pemerintah kota memasang alat pengatur lalu lintas otomatis, sebuah teknologi baru yang diyakini mampu menyelesaikan masalah kemacetan dan kecelakaan. Alat ini bekerja dengan sistem tekanan dan lampu berwarna, didampingi polisi yang bertugas menjelaskan cara pakainya kepada warga.
Fakta bahwa polisi harus berjaga hanya untuk menjelaskan lampu lalu lintas menunjukkan satu hal: masyarakat belum siap. Jalan boleh modern, tetapi kebiasaan belum ikut berubah. Lampu merah bukan perintah, melainkan saran. Drempel bukan peringatan, melainkan gangguan.
Baca Juga: Sejarah Braga jadi Pusat Kongkow Orang Eropa Baheula, Berawal dari Toko Senapan
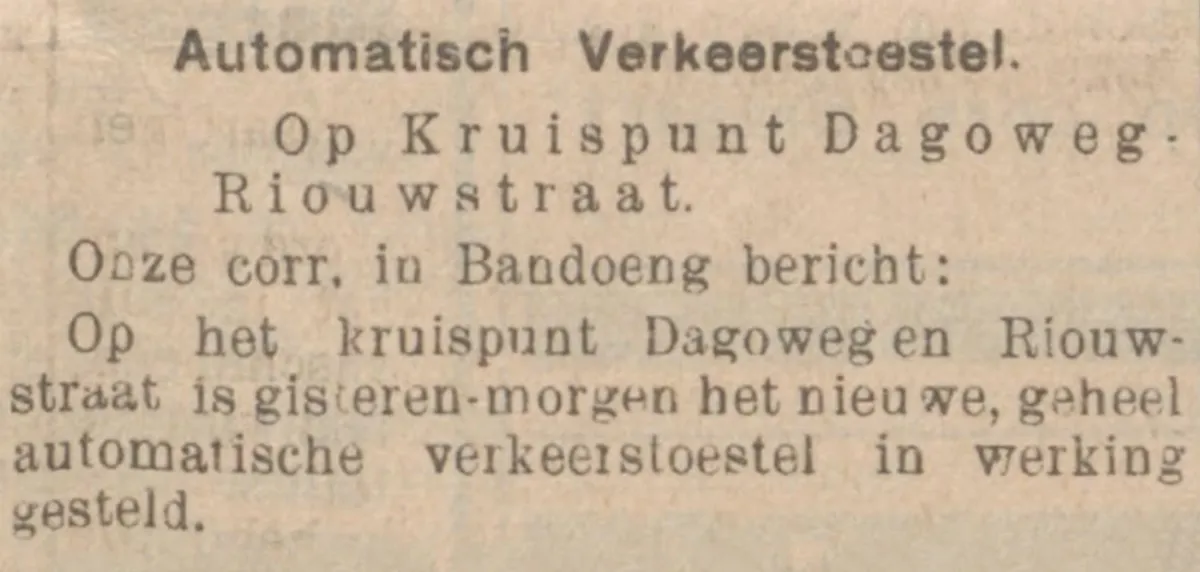
Optimisme bahwa alat otomatis mampu mengatasi masalah lalu lintas rupanya terlalu dini. Setahun kemudian, Maret 1935, De Avondpost melaporkan kecelakaan fatal yang menimpa seorang pegawai telepon Belanda. Ia menabrak gerobak di Jalan Dago, tepat sebelum tikungan dengan laju kecepatan tinggi.
"Pengendara melaju dengan kecepatan tinggi terlihat dari jejak rem yang panjangnya sekitar 30 meter," tulis De Avondpost.
Jejak rem sepanjang puluhan meter menjadi bukti bahwa kendaraan sudah mampu melaju jauh lebih cepat daripada kemampuan manusia mengantisipasi bahaya. Jalan Dago, dengan tikungan dan turunan alaminya, menjadi arena uji coba yang kejam bagi teknologi baru bernama sepeda motor.
Yang menarik, korban dan pengemudi gerobak sama sama bergerak ke arah utara. Kecelakaan ini dipicu bukan soal saling serobot, melainkan soal keterbatasan pandangan. Jalan Dago saat malam hari masih minim penerangan. Lampu kecil pada sepeda motor tidak cukup untuk mendeteksi gerobak kayu yang melaju tenang di depannya. Dalam kondisi seperti itu, tabrakan hampir tak terhindarkan.
Pada Februari 1939, Het Nieuws van den Dag kembali mencatat tabrakan antara oplet dan pesepeda pribumi di dekat persimpangan Cikapayang. Penyebabnya sederhana dan klasik: pengemudi tidak memberikan hak utama. Pesepeda hanya mengalami luka ringan dan mendapatkan perawatan di Rumah Sakit Juliana yang kini bernama Rumah Sakit Hasan Sadikin (RSHS).
Baca Juga: Sejarah RSHS Bandung, Rumah Sakit Tertua di Jawa Barat Warisan Era Hindia Belanda
Beberapa bulan kemudian, pada November 1939, koran yang sama kembali menurunkan laporan tentang tabrakan di Jalan Dago. Kali ini korbannya seorang petugas pos pribumi yang sedang mengosongkan kotak pos. Ia ditabrak mobil penumpang yang melaju menuruni Jalan Dago. Korban terlempar, tidak sadar, dan mengalami gegar otak berat.
Laju mobil sempat terus berjalan sekitar seratus meter sebelum berhenti. Sejumlah anggota militer yang kebetulan melintas memberikan pertolongan dan memanggil dokter. Polisi menyita surat izin mengemudi pengemudi mobil karena diketahui bukan pertama kalinya ia terlibat kecelakaan.
"Para anggota memanggil seorang dokter yang tinggal di dekat lokasi, yang kemudian mengatur agar petugas pos yang mengalami pendarahan dari hidung dan mulut segera dibawa ke Rumah Sakit Juliana," tulis Het Nieuws van den Dag.
Dari rangkaian laporan ini, terlihat bahwa Jalan Dago pada masa kolonial adalah laboratorium lalu lintas yang penuh risiko. Ia menampung sepeda, gerobak, sepeda motor, mobil pribadi, truk barang, dan pejalan kaki dalam satu ruang tanpa kompromi desain. Jalan ini terlalu percaya diri dengan lebarnya, terlalu optimistis dengan teknologinya, dan terlalu cepat mengubah ritme hidup manusia.
Jika hari ini Jalan Dago masih sering macet atau terjadi kecelakaan, itu bukan sepenuhnya cerita baru. Sejak awal abad ke-20, jalan ini memang sudah menyimpan watak berbahaya. Bedanya, dulu ia memikat dengan janji modernitas, sekarang dengan ilusi kenyamanan.