AYOBANDUNG.ID - Pada awal abad ke-20, Pangalengan belum dikenal sebagai destinasi pelarian akhir pekan. Ia belum dipromosikan sebagai surga swafoto, belum pula dipadati vila dengan nama kebarat-baratan. Pangalengan hidup tenang sebagai dataran tinggi yang sibuk bekerja. Udara dingin menjadi kondisi alam, bukan komoditas. Kabut turun tanpa perlu izin, dan jalanan berliku menjadi bagian dari keseharian, bukan tantangan wisata.
Gambaran tentang Pangalengan pada masa itu bisa ditelusuri melalui laporan perjalanan yang dimuat surat kabar Belanda De Preanger-bode edisi 30 November 1912. Ia seperti catatan seorang pejalan yang kelelahan namun puas, yang mencoba mengingat setiap tikungan jalan, setiap kebun, dan setiap pemandangan yang terlalu indah untuk diabaikan.
Dari Pangalengan, tujuan yang paling sering disebut adalah Kawah Wajang. Seolah ada kesepakatan tak tertulis bahwa siapa pun yang datang ke wilayah ini harus terlebih dahulu menyapa kawah tersebut. Dari kejauhan, Kawah Wayang sudah memperlihatkan dirinya lewat tiang-tiang asap belerang yang mengepul tanpa henti. Asap itu tampak misterius, sedikit mengancam, namun justru itulah yang memancing orang untuk mendekat.
Baca Juga: Bandit Laknat Padalarang Zaman Belanda, Kisah Berdarah di Kampung Terpencil
Pejalanan menuju ke sana tidak ada satu jalur tunggal. Sebagian jalan bisa ditempuh dengan kereta, sisanya harus dilanjutkan dengan berjalan kaki atau berkuda. Perkebunan kina Kertamanah sering menjadi titik antara, sebelum perjalanan dilanjutkan melalui jalan setapak yang berliku di antara tanaman. Pada masa itu, melintas di kebun bukan perkara rumit. Para penyewa lahan umumnya memberi izin, seolah paham bahwa keindahan Pangalengan memang sayang jika dinikmati sendirian.
Semakin ke atas, pemandangan terbuka ke segala arah. Di bawah sana terlihat hamparan kebun kina dan kebun teh, atap-atap seng pabrik yang berkilau, serta kampung-kampung buruh yang tampak mungil dari kejauhan. Ladang hijau berselang-seling dengan hutan kecil, rumah-rumah tersebar tanpa pola yang terlalu rapi, dan anak-anak sungai mengalir mengikuti kemauan alam. Situ Cileunca tampak tenang, dengan Gunung Waringin dan Gunung Tilu berdiri sebagai latar belakang yang setia.
Tapi Pangalengan tidak hanya menawarkan keindahan yang jinak. Setelah hutan rimba tercapai, perjalanan berubah watak. Kuda-kuda tak lagi sanggup melanjutkan langkah. Jalan menjadi curam, batang-batang pohon tumbang menghadang, dan kaki manusia harus mengambil alih. Beberapa puluh menit kemudian, kehijauan itu mendadak terputus. Di hadapan terbentang kawasan kelabu dan gundul, kontras dengan kesuburan yang baru saja dilewati.
Kawah Wayang memperlihatkan dirinya tanpa basa-basi. Uap belerang keluar dari ribuan celah, mata air mendidih muncul di sana-sini, lumpur panas bergolak, dan aliran air asam melaju di antara endapan mineral. Tempat ini terasa seperti dapur besar bumi yang pintunya lupa ditutup. Namun dari bongkah-bongkah batu lapuk di tengah kawah, mata masih bisa menangkap kembali dataran Pangalengan yang hijau dan teratur. Kehidupan dan kemandulan berdiri berdampingan, tanpa perlu berdamai.
Baca Juga: Hikayat Pangalengan, Kota Teh Kolonial yang jadi Ikon Wisata Bandung Selatan
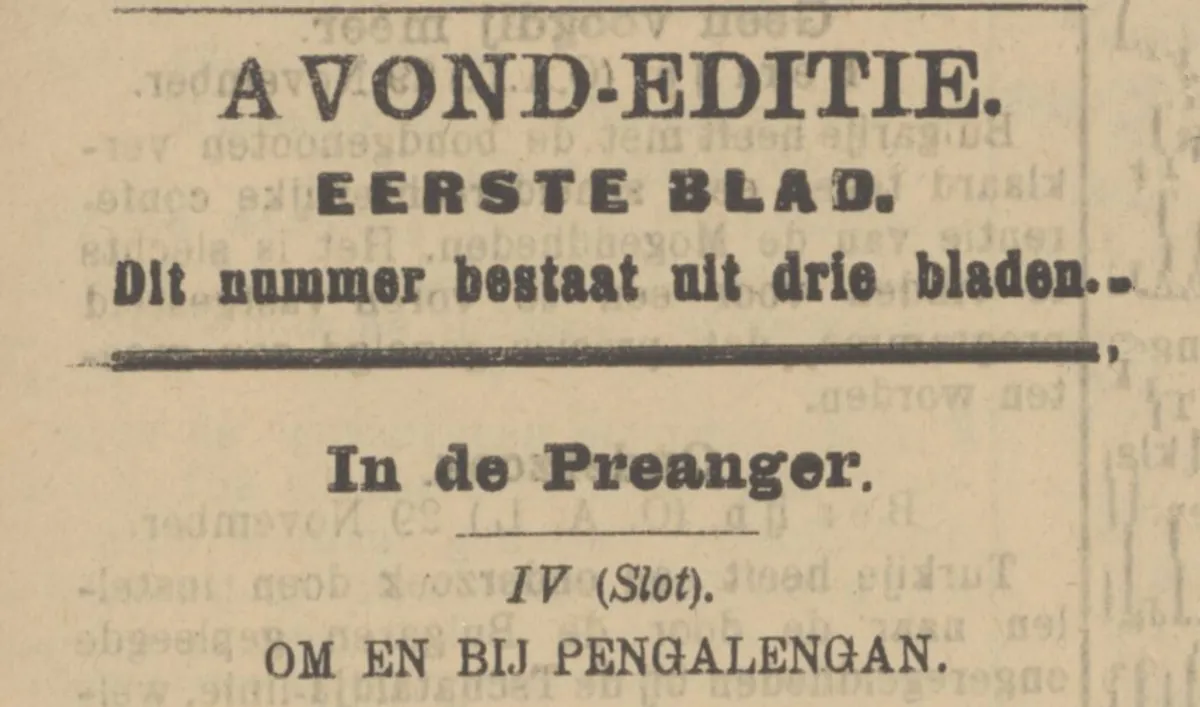
Dari Logawa sampai Ujung Bandung Selatan
Perjalanan lain yang dicatat dalam laporan De Preanger-bode adalah ke Logawa. Rute ini menuntut stamina lebih, sebab jalannya melewati jalur kopi yang tidak selalu tercatat di peta. Jurang datang silih berganti, kali harus diseberangi berkali-kali, dan tanjakan seolah tak pernah kehabisan ide untuk melelahkan pelancong. Lereng Gunung Malabar menjadi saksi betapa perjalanan di Pangalengan bukan perkara santai.
Di Batusirip atau Batu Petak, pemandangan tiba-tiba terbuka. Lembah terhampar, dan jalan dari Cikalong ke Pangalengan terlihat berkelok naik. Pada hari cerah, Banjaran tampak jelas, bahkan Bandung dan Cikudapateuh masih bisa dikenali di kejauhan. Namun Logawa sendiri digambarkan tidak seindah ekspektasi. Pasanggrahan yang dibangun pada masa kejayaan kopi mulai jarang digunakan. Kebun-kebun kopi lama ditebang dan digantikan ladang kentang serta sawah kecil. Sejarah bergerak, dan komoditas pun berganti.
Sebagai penawar kelelahan, perjalanan ke Cinyiruan dianggap lebih bersahabat. Jalannya lebih landai, suasananya lebih tenang. Pada pagi hari, kawasan ini relatif sepi. Anak-anak Sunda tampak bekerja di kebun, menangkap hama tanaman. Pendidikan dan kerja bercampur dalam rutinitas harian. Ketika siang datang bersama hujan deras, kegiatan belajar di sekolah pun dimulai. Sebuah gambaran sederhana tentang bagaimana waktu diatur oleh alam.
Kebun kina Cinyiruan menjadi sorotan penting. Dalam laporan 1912 itu, perkebunan ini digambarkan sebagai contoh pengelolaan tanah pemerintah yang nyaris menyerupai taman. Proses pembibitan, perawatan, penanaman, hingga pengolahan kulit kina berlangsung dalam satu kawasan yang tertata. Di atasnya, rumah tinggal direktur berdiri dengan posisi strategis, menghadap langsung ke dataran Pangalengan. Dari sana, lanskap terbuka lebar, seolah menegaskan siapa yang memegang kendali atas ruang dan produksi.
Baca Juga: Sejarah Braga jadi Pusat Kongkow Orang Eropa Baheula, Berawal dari Toko Senapan
Dari Cinyiruan, jalan yang terawat dengan baik membawa pelancong kembali ke jalur utama Cikalong Pangalengan. Lalu lintas angkutan belum ramai, sehingga perjalanan terasa lengang. Jika dilanjutkan, rute bisa membawa ke Cibeureum, Cipanas, hingga Kertamanah. Sumber air panas menjadi tujuan yang menarik. Air panas hampir mendidih mengalir dari telaga, lalu dimanfaatkan untuk pemandian. Fasilitas ini tidak hanya untuk orang Eropa, tetapi juga disediakan bagi penduduk pribumi. Sebuah detail kecil yang menunjukkan bahwa Pangalengan kala itu adalah ruang pertemuan berbagai kepentingan.
Salah satu jalur yang paling mengesankan adalah jalan penghubung Malabar dan Pangalengan. Jalan ini sudah menggunakan penanda kilometer, bukan lagi pal, menandai pergeseran cara pandang terhadap jarak dan waktu. Di kilometer keenam, perkebunan teh Malabar dimulai. Sejauh mata memandang, hamparan teh terbentang tanpa celah. Pohon demi pohon tersusun rapi, membentuk satu kain hijau raksasa yang menjalar bermil-mil.
Hamparan ini melewati sejumlah wilayah yang kini masuk ke dalam administrasi Kecamatan Kertasari, ujung Bandung Selatan Tanara, Wanasuka, Santosa yang dibangun kembali, Talun, hingga Sedep. Di kejauhan tampak Rakutak, kabut menggantung di sekitar Papandayan, dan kebun-kebun kina Cikembang. Di mana-mana terlihat pembukaan lahan baru. Pangalengan sedang berada di puncak perannya sebagai wilayah produksi agraria.
Di tengah geliat itu, muncul mimpi besar tentang masa depan. Laporan De Preanger-bode 30 November 1912 menyebut rencana masuknya trem listrik ke Pangalengan. Konsesi dikabarkan telah diperoleh, trase disebut sudah ditemukan, bahkan modal pembangunan konon telah tersedia. Jika rencana itu terwujud, Pangalengan akan mudah dijangkau, murah, dan cepat. Desa pegunungan itu diproyeksikan menjadi tempat peristirahatan kesehatan, menawarkan ketenangan dan kesejukan bagi mereka yang ingin menjauh dari panas Bandung.
Baca Juga: Wayang Windu Panenjoan, Tamasya Panas Bumi Zaman Hindia Belanda
Waktu kemudian berjalan dengan caranya sendiri. Trem listrik tak pernah benar-benar datang. Namun mimpi tentang Pangalengan sebagai tempat peristirahatan perlahan terwujud dengan bentuk berbeda. Jalan raya dibangun, wisata berkembang, dan nama Pangalengan terus disebut hingga hari ini.
Dalam catatan koran baheula itu, Pangalengan tampak sebagai wilayah yang sejak awal hidup di antara kerja dan keindahan. Ia tidak dibentuk untuk dipuja, melainkan untuk dijalani. Dari kawah yang mengepul hingga kebun teh yang tak berujung, Pangalengan mencatat sejarahnya bukan lewat peristiwa besar, tetapi lewat perjalanan-perjalanan panjang yang melelahkan, pemandangan yang sulit dilupakan, dan harapan akan masa depan yang selalu terasa sedikit di depan mata.