AYOBANDUNG.ID - Padalarang pada tahun 1935 bukanlah simpul transportasi, apalagi kawasan industri. Ia hanyalah persimpangan sunyi di barat Bandung, tempat rel kereta berderak malas dan malam turun lebih cepat karena lampu jarang. Di wilayah seperti ini, suara anjing menggonggong bisa berarti dua hal. Ada orang pulang larut, atau ada bahaya mendekat.
Pada suatu malam di akhir September 1935, bahaya itulah yang datang ke sebuah kampung yang kala itu dikenal sebagai Sirahcai, Desa Tagogapu. Kampung kecil ini nyaris tak tercatat di peta, kecuali oleh aparat kolonial dan sesekali oleh surat kabar. De Koerier edisi 27 September 1935 menurunkan laporan tentang sebuah peristiwa rampok yang membuat Padalarang mendadak gaduh, setidaknya di atas kertas koran.
Sekelompok orang bersenjata masuk ke kampung saat warga sudah terlelap. De Koerier mencatan koplotan bandit itu berjumlah 20 orang. Mereka menyasar rumah demi rumah, menjarah barang yang masih layak dibawa. Tidak ada brankas tumpukan duit di sana. Harta kampung kala itu berupa kain, perkakas, dan sedikit uang simpanan.
"Sekitar tengah malam, antara 20 orang bersenjata memasuki lima rumah berbeda di kampung tersebut dan menjarah semua barang pribadi yang masih dalam kondisi baik," tulis De Koerier.
Total rampasan ditaksir sekitar 30 gulden, jumlah yang tidak akan membuat seorang pegawai kolonial kaya, tetapi cukup berarti bagi sekelompok rampok yang hidup dari malam.
Soalnya bukan pada nilai barang, melainkan pada darah yang tumpah. Dalam kekacauan itu, seorang warga mengalami luka parah dan meninggal dunia. Beberapa lainnya terluka. Kampung yang terletak jauh dari pusat administrasi itu baru diketahui aparat saat pagi datang. Malam telah lewat, rampok sudah menghilang, dan kampung kembali sunyi dengan cerita yang akan dikenang lama.
Padalarang saat itu memang wilayah yang ramah bagi kejahatan malam. Jarak antar kampung berjauhan, patroli jarang, dan komunikasi nyaris bergantung pada kaki manusia. Teriakan minta tolong bisa teredam oleh kebun dan sawah. Rampok tahu betul peta sunyi ini. Mereka tidak perlu banyak orang. Mereka hanya perlu waktu dan gelap.
"Kampung tersebut terletak 7 km dari desa dan benar-benar terisolasi, sehingga pihak berwenang baru mengetahui kejadian tersebut pada pukul 5:00 pagi ini," tulis koran itu.
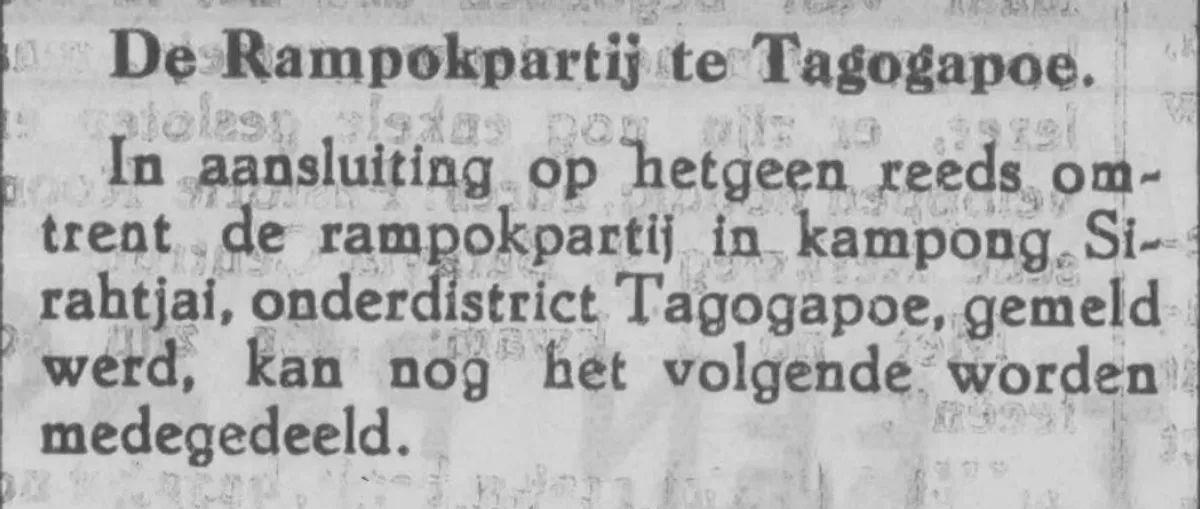
Komplotan Delapan Orang
Beberapa hari kemudian, koran De Koerier edisi 1 Oktober 1935 memuat lanjutan kisah ini. Seperti cerita kriminal klasik, detail yang sebelumnya kabur mulai tampak jelas. Jumlah pelaku ternyata tidak sebanyak dugaan awal. Bukan dua puluh orang, melainkan delapan. Namun delapan orang di kampung sunyi tetap saja terasa seperti satu pasukan penuh.
Para pelaku diketahui berasal dari kawasan Cisarua. Nama-nama mereka dicatat dengan rapi oleh aparat kolonial, seolah-olah daftar kehadiran di sekolah. Di antara nama-nama itu, ada satu yang terus muncul dan menolak tenggelam, Madja.
Sirahcai seperti dicatatsurat kabar kala itu digambarkan hanya memiliki delapan rumah dan terletak sekitar lima kilometer dari Tagogapu. Jarak ini cukup untuk membuat kampung tersebut seperti dunia sendiri.
"Berdasarkan keterangan para tersangka tersebut, bukan 20 orang melainkan 8 orang yang bersama-sama melakukan penyerangan di kampung tersebut, yang terletak terpisah sekitar ±5 km dari Tagogapu dan hanya terdiri atas 8 rumah."
Sosok Marta, korban yang meninggal, bahkan bukan warga Sirahcai. Ia tinggal di dusun kecil lain sekitar empat ratus meter dari lokasi kejadian. Malam itu, ia datang setelah mendengar teriakan minta tolong. Niat membantu justru menjadi jalan menuju kematian.
Dia terkena sabetan senjata tajam di kepala dan kehabisan darah dalam perjalanan menuju rumah sakit. Sementara itu, warga lain bernama Warma yang ikut datang mengalami luka serius akibat hantaman alu penumbuk padi di bagian mulutnya. Dalam laporan lanjutan, aparat menduga luka fatal pada Marta dilakukan oleh Madja.
Sosok Madja bukan pemain baru dalam dunia kejahatan di Bandung. Arsip De Koerier menyebut ia juga terlibat dalam perampokan di Cikalong pada awal September 1935. Dari pengakuan para tersangka, polisi berhasil menangkap pelaku lain bernama Suwarya, Israh, dan Nata, yang semuanya berasal dari Pasirlangu. Seolah ada jaringan kecil yang bekerja rapi, berpindah dari satu kampung ke kampung lain.
Pada Januari tahun yang sama, Madja juga disebut pernah terlibat dalam komplotan rampok lain. Saat itu, rekan-rekannya masuk penjara, sementara ia kembali menghilang. Polanya berulang. Kejahatan terjadi, nama Madja disebut, aparat bergerak, dan ia lolos lagi. Dalam dunia kriminal kolonial, ia termasuk tipe yang membuat frustrasi aparat, licin dan sulit digenggam.
Kisah rampok di Padalarang ini memperlihatkan wajah lain Priangan pada masa Hindia Belanda. Di balik perkebunan, rel kereta, dan administrasi kolonial yang tampak rapi, ada kampung-kampung kecil yang hidup tanpa perlindungan memadai. Hukum hadir, tetapi sering terlambat. Keamanan ada, tetapi jaraknya jauh.
Padalarang hari ini telah berubah wajah. Jalan sunyi diganti jalan tol. Kampung terpencil berubah menjadi kawasan sibuk. Jika komplotan Madja beraksi di lokasi yang sama hari ini, bisa jadi yang dibawa pulang bukanlah duit puluhan gulden dibagi delapan, melainkan kenyataan bahwa gelap tak lagi berkuasa.




















