AYOBANDUNG.ID - Pada peta kolonial Hindia Belanda awal abad ke-20, Cigembong bukanlah nama yang mencolok. Ia tidak setenar Garut sebagai kota peristirahatan orang Eropa, tidak pula sepopuler Pangalengan dengan kebun tehnya. Cigembong hanyalah sebuah kampung di selatan Garut, jauh dari hiruk pikuk kota, hidup dari sawah, sungai kecil, dan ingatan para tetua desa. Namun pada Juni 1924, Cigembong mendadak masuk halaman surat kabar kolonial, bukan sebagai destinasi wisata, melainkan sebagai berita duka yang panjang dan muram.
Sumber utama kisah ini datang dari De Indische Courant edisi 2 Juli 1924, yang memuat laporan resmi Bupati Garut tentang bencana longsor besar di wilayah tersebut. Laporan itu bukan sekadar catatan administratif, melainkan potret detail tentang bagaimana sebuah kampung lenyap, lengkap dengan jumlah korban, hewan ternak, hingga luas sawah yang tertimbun. Bahasa laporannya tenang, khas birokrasi kolonial, tetapi justru di situlah letak kengerian ceritanya.
Cigembong saat itu merupakan bagian dari Desa Nyalindung, Distrik Bungbulang. Kampung ini bukan kampung baru. Menurut keterangan para tetua desa yang dicatat dalam laporan tersebut, usia Kampung Cigembong sudah lebih dari satu abad. Artinya, kampung itu telah melewati berbagai pergantian zaman, dari VOC, Daendels, hingga pemerintahan kolonial Hindia Belanda yang lebih mapan. Ironisnya, ia justru berakhir bukan oleh perang atau kebijakan kolonial, melainkan oleh gerakan tanah yang datang tanpa aba-aba.
Baca Juga: Tamasya Pangalengan Zaman Baheula, Pesona Lanskap Hijau di Ujung Bandung Selatan
Secara geografis, Cigembong berdiri di tempat yang indah sekaligus berbahaya. Kampung ini terletak di lereng Gunung Bodas atau Puncak Ali, dengan lereng yang memanjang hingga Sungai Cilaki. Di kanan kirinya mengalir dua sungai kecil, Cigembong Kidul dan Cigembong Kaler, yang beberapa kilometer kemudian bertemu dan bermuara ke Sungai Cilaki. Bagi petani, lokasi ini adalah berkah. Air melimpah, tanah subur, sawah terbentang di antara dua aliran sungai. Bagi geologi, ini adalah wilayah yang menyimpan potensi petaka.
Pada 12 Juni 1924, sekitar pukul lima sore, keseharian kampung itu berlangsung seperti biasa. Sebagian warga berada di rumah, sebagian lagi masih bekerja di sawah. Tidak ada tanda-tanda alam yang cukup keras untuk membuat orang lari menyelamatkan diri. Tidak ada letusan, tidak ada hujan ekstrem yang disebutkan dalam laporan. Yang terjadi kemudian justru sesuatu yang lebih sunyi namun mematikan.
Laporan Bupati Garut yang dikutip De Indische Courant menyebutkan dengan lugas bahwa bencana itu diawali oleh retakan besar di puncak Gunung Bodas. Retakan ini menjadi pembuka tirai tragedi. Tanah, pasir, batu, dan seluruh isi lereng gunung bergerak turun. Kecepatannya bukan sesuatu yang bisa ditawar oleh refleks manusia.
Dalam laporan koran itu tertulis kalimat bahwa tragedi longsor tersebut hanya berlangsung "dalam hitungan menit." Kalimat ini menegaskan betapa pendek jarak antara kehidupan normal dan kehancuran total. Orang-orang yang berada di dalam rumah tidak sempat keluar. Mereka yang di sawah berlari tanpa arah, panik, bingung, sebelum akhirnya ditelan massa tanah raksasa.
Baca Juga: Sejarah Julukan Garut Swiss van Java, Benarkah dari Charlie Chaplin?
"Dalam sekejap, seluruh wilayah subur di antara kedua sungai tersebut, termasuk jalur sempit di luarnya serta kedua aliran sungai itu sendiri, lenyap di bawah runtuhan tanah." tulis De Indische Courant.
Longsoran tersebut bukan longsor kecil yang biasa terjadi di musim hujan. Ia membentang dari puncak Gunung Bodas hingga sekitar 300 meter dari Sungai Cilaki, dengan panjang kurang lebih tiga kilometer dan lebar sekitar 500 meter. Kampung Cigembong berada di bagian tengah wilayah longsoran, posisi yang secara statistik paling tidak beruntung.
"Longsoran itu membentang dari puncak Gunung Bodas hingga sekitar 300 meter dari Sungai Cilaki, dengan panjang kurang lebih 3 kilometer dan menimbun jalur tanah selebar sekitar 500 meter."
Kampung Cigembong pun hilang dari permukaan bumi. Laporan itu menegaskan dengan kalimat yang nyaris puitis dalam kekosongannya, “Tidak satu pun rumah, bahkan tidak sebatang pohon kelapa pun, yang terlihat walau sedikit saja.” Jika pohon kelapa saja lenyap tanpa sisa, dapat dibayangkan nasib rumah bambu dan kayu yang berdiri di sekitarnya.
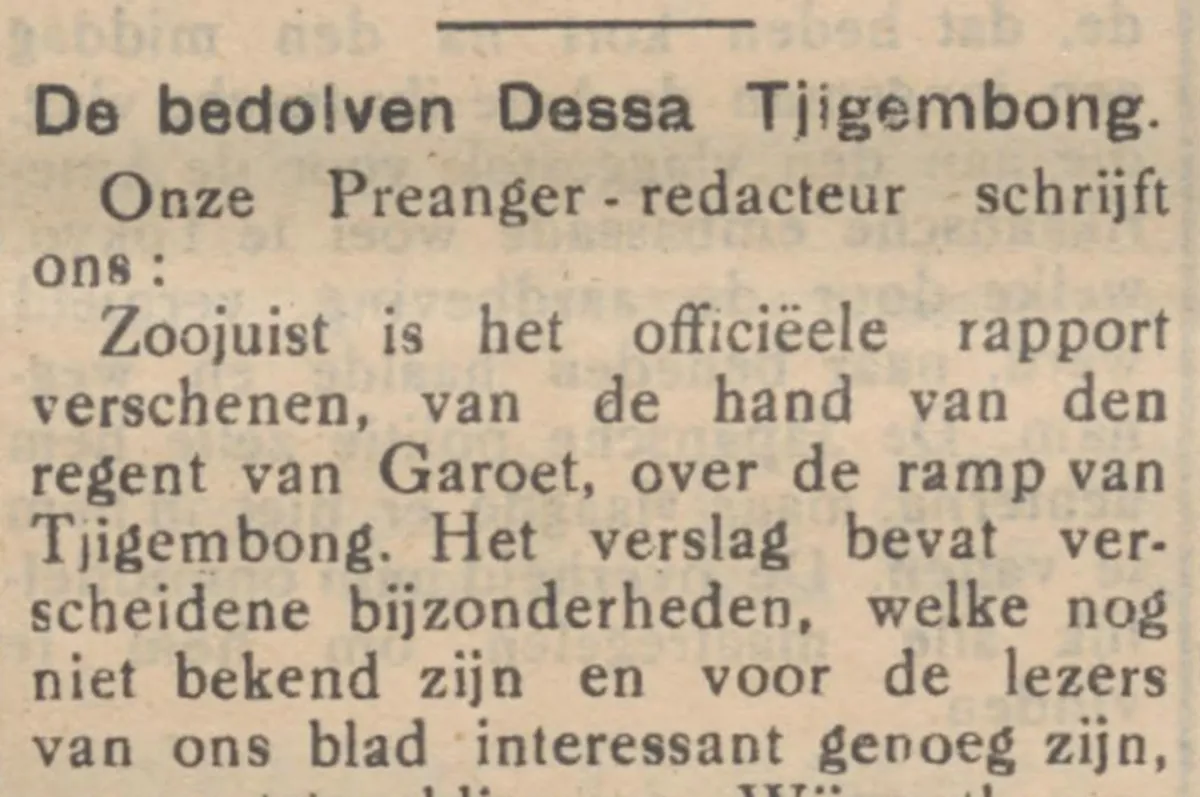
Ratusan Warga jadi Korban, Hewan Tak Selamat
Korban manusia dalam longsor Cigembong tercatat sebanyak 133 orang, terdiri dari laki-laki, perempuan, dan anak-anak. Angka ini besar, terutama untuk ukuran kampung pedesaan pada masa itu. Selain manusia, longsor juga menelan hewan ternak yang menjadi penyangga ekonomi warga.
"Selain itu, turut binasa 11 ekor kerbau, 2 ekor kuda, serta 43 ekor kambing dan domba. Lebih dari 21 bau sawah dan hampir 6 bau tegalan, bersama 26 rumah Kampung Cigembong, hilang tertimbun tanah." tulis koran itu.
Baca Juga: Kapal Laut Garut jadi Korban Torpedo Jerman di Perang Dunia II
Yang menarik, bencana ini tidak langsung selesai pada hari itu. Pada hari berikutnya, tanah di lokasi longsor masih bergerak perlahan. Warga desa sekitar bahkan tidak berani menginjakkan kaki di atas timbunan tanah tersebut. Ketakutan ini bukan tanpa dasar. Pada 13 dan 14 Juni, longsoran kecil kembali terjadi di lereng Gunung Bodas.
Kekhawatiran terbesar pemerintah kolonial saat itu bukan hanya soal korban jiwa yang sudah terjadi, melainkan potensi bencana lanjutan. Laporan Bupati Garut menyebutkan adanya kemungkinan timbunan tanah dan batu bergeser lagi sekitar 300 meter ke arah Sungai Cilaki. Jika itu terjadi, aliran sungai bisa tertutup dan membentuk bendungan alami.
Laporan tersebut lantas mencatat ancaman banjir besar bagi wilayah hulu. Sawah-sawah di desa-desa lain disebut berpotensi terdampak. Ini menunjukkan bahwa sejak hampir seabad lalu, pemerintah kolonial sudah memahami konsep risiko bencana berantai, meskipun istilah mitigasi belum sepopuler sekarang.
“Sehubungan dengan hal itu, sedang dipertimbangkan berbagai langkah untuk mencegah bahaya tersebut.” demikian laporan itu.
Baca Juga: Sejarah Black Death, Wabah Kematian Perusak Tatanan Eropa Lama
Dalam sejarah bencana di Hindia Belanda, longsor Cigembong bukan yang paling terkenal. Ia kalah pamor dibanding letusan gunung atau banjir besar. Tragedi ini terjadi di kampung kecil, jauh dari pusat kekuasaan, tanpa tanda dramatis sebelumnya. Ia datang cepat, mematikan, dan sunyi.