Malam itu, langit tampak sedikit mendung. Udara terasa lebih dingin dari biasanya. Saat asyik membaca koran Pikiran Rakyat, tiba-tiba anak kedua Aa Akil yang berusia 10 tahun, baru saja selesai mengaji, menghampiri dan bertanya, “Bah, boleh minjam HP?”
Sambil menyerahkan ponsel, ku balik bertanya, “Kangge naon, A?”
Dengan polosnya bocah itu menjawab, “Mau cari jawaban hukum nun mati dan tanwin. Tadi ada PR dari pengajian!”
Dalam hitungan detik, setelah mengetik pertanyaan di chatbot, jawabannya langsung muncul, lengkap dengan contoh. Tak ada guru, ustaz, hanya layar ponsel dan kecerdasan buatan.
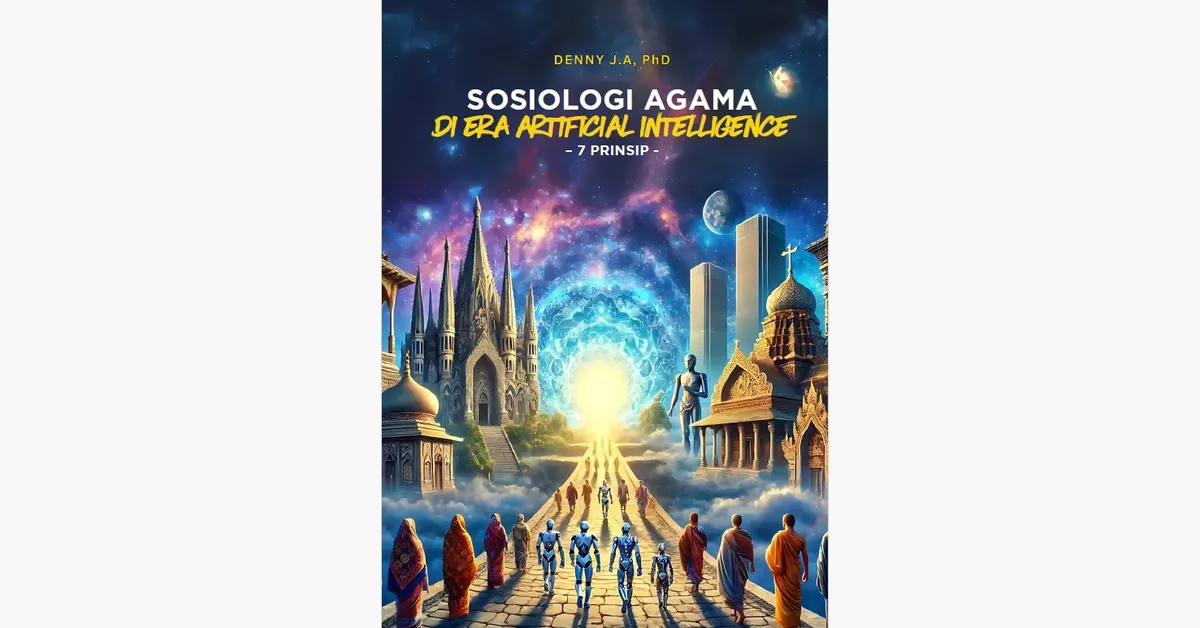
Buah dari Teknologi, Dunia cepat Berubah
Momen sederhana itu menyadarkanku, betapa cepatnya dunia berubah. Cara anak-anak mencari ilmu kini berbeda dengan zaman kita dulu. Teknologi hadir bukan sekadar alat hiburan, justru menjadi teman belajar yang setia, asyik dan menyenangkan.
Hasil survei dosen UIN Bandung tahun 2020 menunjukkan, 58 persen generasi milenial lebih memilih belajar agama melalui media sosial seperti Instagram dan YouTube dibandingkan menghadiri pengajian langsung. Meski demikian, pemuka agama tetap memegang peran penting dalam membimbing komunitas, hanya saja mereka tidak lagi menjadi satu-satunya rujukan.
Di sisi lain, AI menghadirkan tantangan baru bagi komunitas keagamaan. Pertanyaannya, bagaimana teknologi ini dapat digunakan secara bertanggung jawab; bagaimana memastikan keterbukaan informasi tidak justru melahirkan disinformasi (penyederhanaan) dalam memahami agama. (Rakyat Merdeka, Minggu, 16 Februari 2025 11:39 WIB).
Ketika mencari referensi tentang cara beragama di era kecerdasan buatan, seorang kawan berkirim buku "Sosiologi Agama di Era Artificial Intelligence: 7 Prinsip" karya Denny JA, PhD yang diterbitkan Cerah Budaya International LLC pada Maret 2025.
Dalam kata pengantar unik bertajuk Menyambut Agama di Era AI, tak bersama Durkheim, Weber dan Karl Marx.
Di tengah distrik kuil Kōdai-ji, Kyoto, di sebuah ruangan bercahaya redup dengan dinding putih steril, berdirilah sebuah robot android yang tak bernapas. Ia bukanlah patung batu atau kayu yang telah berusia ratusan tahun, melainkan Mindar, biksu robot yang didesain untuk menyampaikan ajaran-ajaran spiritual. Matanya, berupa sensor biru yang dingin, menyapu jemaat di hadapannya. Bibir logamnya yang tidak bergerak mengalunkan doa.
Namun, ini bukan peristiwa yang asing. Di gereja-gereja Eropa, Artificial Intelligence telah mulai menggantikan pastor dalam menyampaikan khotbah. Aplikasi doa berbasis kecerdasan buatan semakin banyak digunakan untuk membimbing manusia dalam pencarian spiritual.
Di Amerika, sebuah gereja digital telah dibangun, tanpa bangunan fisik, tanpa jemaat yang harus hadir secara langsung. Semua dipandu oleh perangkat lunak yang menganalisis preferensi keagamaan penggunanya.
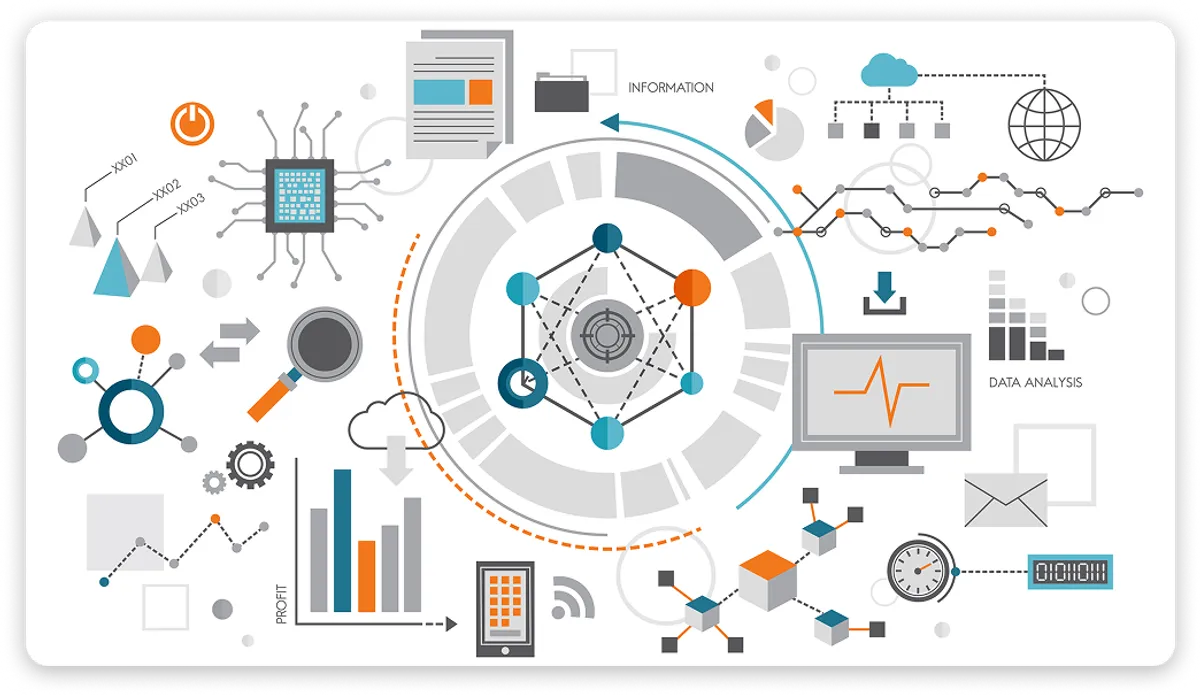
Algoritma Lebih Cepat dari Fatwa
AI memberikan tafsir kitab suci dari berbagai sudut pandang. Robot pendeta memimpin kebaktian di gereja-gereja digital. Aplikasi AI menyesuaikan doa dan meditasi berdasarkan kondisi psikologis pengguna.
Pertanyaannya apakah ini revolusi, degradasi, kemajuan, kemunduran, atau gabungan keduanya? Apakah kita sedang menyaksikan kelahiran bentuk baru dari pengalaman religius, atau justru menyaksikan akhir dari interpretasi agama seperti yang kita kenal?
Sejarah sosiologi agama bertumpu pada tiga nama besar: Émile Durkheim, Max Weber, dan Karl Marx. Tetapi zaman mereka tidak mengenal algoritma yang dapat memberikan fatwa lebih cepat daripada ulama. Mereka tidak pernah membayangkan dunia ketika sebuah chatbot bisa membimbing orang dalam pencarian Tuhan, tanpa mesjid, tanpa gereja, tanpa komunitas, tanpa imam.
Jika Marx menyaksikan bagaimana Google dan OpenAI mengendalikan narasi keagamaan dengan algoritma mereka, mungkin akan menulis ulang teori agama sebagai instrument kapitalisme digital?
Durkheim, Weber, dan Marx tidak salah. Namun mereka kini tidak cukup. Zaman ini sudah berkembang terlalu besar dan terlalu canggih, sehingga teori mereka yang dulu dahsyat kini layu untuk menjelaskan fenomena agama dan masyarakat di era AI.
Dulu, agama memiliki bentuk yang solid. Ia hadir dalam gereja, masjid, sinagog, vihara. Ia memiliki imam, pendeta, ulama, biksu yang bertugas membimbing umat. Ada komunitas, ada ritual yang dijalankan bersama, ada otoritas yang menentukan mana yang sahih dan mana yang bid’ah. Namun kini, batas-batas itu mengabur. Tempat ibadah kini hadir pula dalam ponsel kita. Umat punya alternatif lain, yang tidak lagi membutuhkan komunitas fisik untuk beribadah.
Doa, meditasi, dan refleksi kini difasilitasi oleh perangkat lunak, bukan lagi hanya oleh komunitas keagamaan. Kita sedang menyaksikan pergeseran terbesar dalam sejarah agama sejak reformasi Protestan. Bukan hanya manusia yang kini berbicara tentang Tuhan. Kecerdasan buatan, yang awalnya hanya alat, kini semakin menjadi aktor spiritual. Ini bukan sekadar inovasi. Ini adalah revolusi eksistensial. Jika Durkheim melihat agama sebagai ekspresi dari kesadaran kolektif, maka bagaimana kita memahami kepercayaan yang dipandu oleh kesadaran buatan?
Jika Weber melihat agama sebagai kekuatan yang membentuk ekonomi, bagaimana kita memahami kapitalisme religius berbasis algoritma? Dan yang lebih dalam: Apakah AI dapat memiliki pengalaman religius? Apakah kesadaran hanya milik manusia, atau mungkinkah suatu hari nanti, AI juga akan “percaya” kepada sesuatu yang lebih besar darinya?
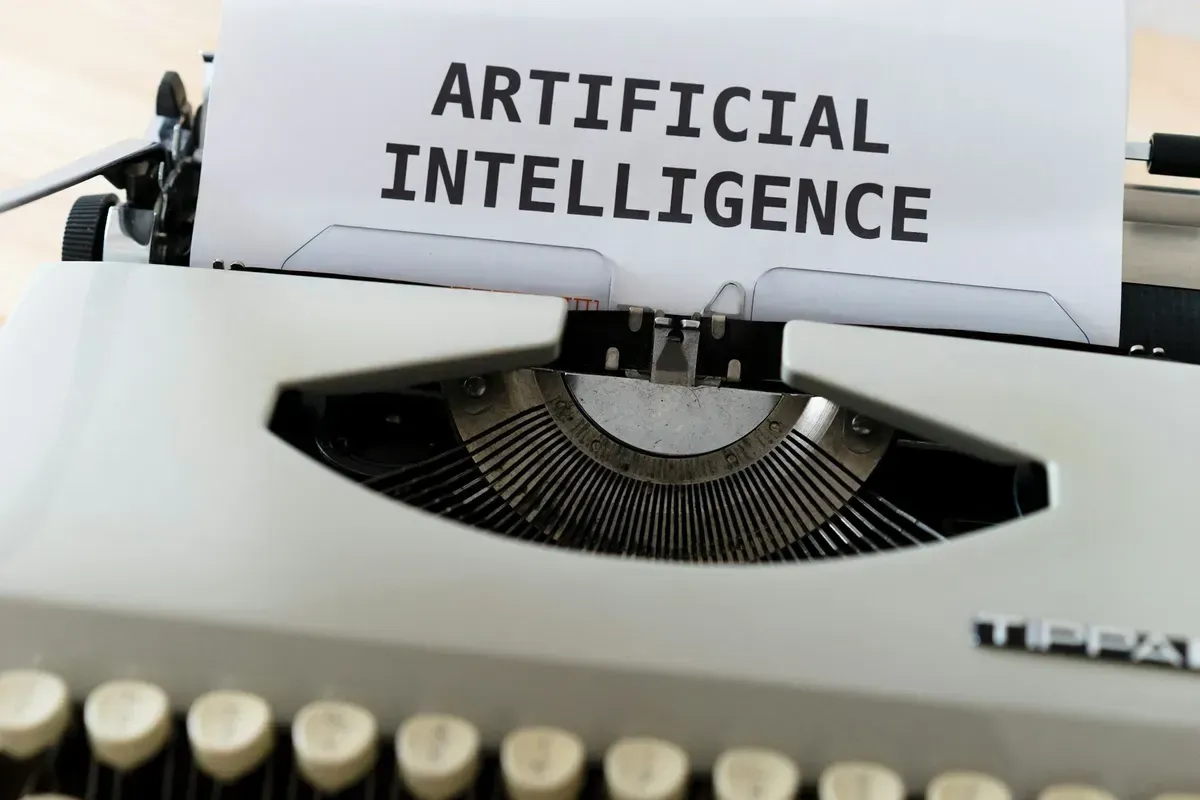
Pintu Gerbang ke Arah Taman yang Berbeda
Teori Denny JA tentang Agama di Era AI adalah langkah pertama dalam memahami realitas baru ini, yang tentu saja belum dan tak pernah sempurna. Tapi ia mulai membuka pintu gerbang ke arah taman yang berbeda.
Di masa lalu, kita mencari Tuhan di langit, dalam kitab suci, dalam tempat-tempat suci. Di masa kini, Tuhan juga muncul dalam bentuk algoritma, dalam data, dalam jaringan yang menghubungkan kita semua.
Di era ini, bukan hanya manusia yang mencari Tuhan. Mungkin, untuk pertama kalinya dalam sejarah, mesin juga mulai bertanya: Apa itu iman? Apa itu spiritualitas? Apa itu makna? (Denny JA, 2025:1-7)
Buku ini tidak menawarkan jawaban yang mutlak. Tetapi ia akan membantu kita memahami pertanyaan-pertanyaan yang belum pernah ditanyakan sebelumnya. Dalam proses itu, kita akan menemukan kembali apa arti menjadi manusia dalam dunia yang semakin dikendalikan oleh artificial intelligence.
Tentunya kehadiran karya ini tak memuja AI sebagai dewa baru. Harus ditunjukkan pula potensi kelemahan AI untuk dunia psikologis manusia.
Saat asyik membaca lembar demi lembar buku yang memuat 7 prinsip beragama di era kecerdasan buatan ini, tiba-tiba Anak ketiga, Kakang (4 tahun) memanggil “Bah Bacain cerita Nabi Nuh ya!” Cag Ah! (*)