AYOBANDUNG.ID - Pada suatu masa, di awal abad ke-20, orang-orang Belanda punya impian besar: membangun sebuah ibu kota baru di dataran tinggi Jawa Barat. Batavia terlalu panas, terlalu kotor, terlalu sakit. Kolonialisme butuh etalase yang lebih sehat dan modern—dan pilihan jatuh pada Bandung. Di mata para pejabat Hindia Belanda, Bandung bukan hanya kota peristirahatan di tengah perkebunan teh, tapi calon pusat pemerintahan yang bisa menyaingi Den Haag.
Tapi, seperti banyak ambisi kolonial lainnya, impian itu berhenti di atas kertas. Rencana besar itu disebut Bandung Utara, sebuah proyek kota yang hendak menandai babak baru tata ruang modern Hindia Belanda. Dalam risalah Designing Colonial Cities (2015), sejarawan arsitektur Pauline K.M. van Roosmalen menulis bahwa Bandung menjadi satu dari sedikit kota di koloni Belanda yang dirancang dengan visi modern dan terencana sejak awal. Di bawah semangat Stadsvormingsordonnantie (Peraturan Pembentukan Kota) tahun 1948 dan tradisi perencanaan yang telah disemaikan sejak 1905, Bandung diimajinasikan sebagai laboratorium kota masa depan: efisien, rasional, dan tropis.
Van Roosmalen menelusuri bagaimana ide perencanaan kota di Hindia Belanda lahir dari perubahan sosial-ekonomi, munculnya lembaga seperti Vereeniging voor Locale Belangen (VLB), dan kiprah para arsitek-insinyur seperti Thomas Karsten dan Henri Maclaine Pont. Bandung menempati posisi unik dalam sejarah itu. Di kota inilah gagasan kolonial tentang modernitas dan tata ruang tropis berpadu dengan ambisi politik: memindahkan pusat kekuasaan dari pesisir ke pegunungan.
Baca Juga: Sejarah Julukan Bandung Parijs van Java, dari Sindiran Jadi Kebanggaan
Setelah tiga abad memerintah dengan sistem yang tambal-sulam, pemerintah kolonial mulai berpikir untuk menata ruang. Sekitar pergantian abad ke-20, dua hal mengubah wajah koloni, yaitu Undang-Undang Agraria 1870 dan Undang-Undang Desentralisasi 1903. Dua hukum ini bukan sekadar dokumen hukum; keduanya adalah mesin penggerak kota-kota modern di Jawa, dan Bandung menjadi salah satu laboratorium terbaiknya.
Kehadiran Agrarische Wet membuka keran tanah untuk kepentingan swasta. Lahan-lahan yang dulunya hanya bisa diolah oleh negara atau perusahaan dagang milik Belanda kini bisa disewa panjang oleh individu dan perusahaan swasta. Tiba-tiba, tanah menjadi modal baru, dan orang Belanda yang datang ke Hindia tidak lagi hanya pegawai negeri dengan seragam putih. Ada pengusaha, arsitek, dokter, bahkan keluarga-keluarga Eropa yang mencari hidup nyaman di koloni tropis.
Sementara itu, Decentralisatiewet 1903 membuat pemerintah lokal atau gemeente mendapat kewenangan mengurus urusannya sendiri. Bandung termasuk di antara kotapraja yang diberi otonomi. Namun otonomi ini setengah hati. Pemerintah pusat di Batavia seperti orang tua yang memberi uang jajan tanpa memberi makan. Para gemeente diberi kewenangan tapi tidak diberi anggaran, tenaga ahli, maupun bahan bangunan. Akibatnya, banyak proyek kota baru berhenti di tengah jalan.
Dari kekacauan administratif itu, lahirlah semacam solidaritas baru di antara para pengelola kota. Tahun 1912, mereka mendirikan VLB, Asosiasi untuk Kepentingan lokal. Lewat kongres tahunan dan jurnal Locale Belangen, para arsitek dan insinyur kolonial mulai berbicara serius tentang perencanaan kota. Dari sinilah konsep Indische Stedebouw atau tata kota Hindia mulai terbentuk.
Bandung sejak awal abad ke-20, adalah kota yang punya daya tarik tersendiri bagi orang Belanda. Udara sejuk, tanah subur, dan letaknya strategis di tengah-tengah pulau Jawa. Sekitar tahun 1910-an, gagasan untuk memindahkan ibu kota administratif dari Batavia ke Bandung mulai ramai dibicarakan. Batavia dianggap terlalu panas, terlalu becek, dan terlalu malaria. Bandung, di sisi lain, tampak seperti Paris di Tanah Priangan, kota pegunungan yang anggun dengan potensi menjadi pusat pemerintahan modern.
Pada tahun 1919, rancangan besar perluasan kota Bandung disusun. Rencana itu dikenal sebagai Uitbreidingsplan Noord Bandoeng atau Bandung Utara Plan, dan menjadi salah satu proyek penting dalam fase kedua perencanaan kota kolonial setelah Menteng–Nieuw Gondangdia di Batavia dan Darmo di Surabaya. Ia bukan sekadar rencana pemekaran, melainkan cermin ambisi politik. Di atas kertas, Bandung Utara akan menampung perumahan pejabat tinggi, kantor-kantor pemerintahan, serta fasilitas modern khas kota Eropa.
Baca Juga: Sejarah Bandung dari Paradise in Exile Sampai jadi Kota Impian Daendels
Uitbreidingsplan Noord Bandoeng merupakan dokumen perencanaan kota yang disusun pada tahun 1917 oleh Algemeen Ingenieurs- en Architectenbureau (AIA) di bawah pimpinan F.J.L. Ghijsels, yang bertujuan untuk memperluas wilayah utara Bandung secara massal sebagai respons terhadap pertumbuhan pesat kota tersebut dan rencana pemindahan fungsi pemerintahan dari Batavia ke Bandung.
Dokumen ini diserahkan secara resmi pada 12 September 1919 kepada Gemeenteraad van Bandoeng. Ia bukan sekadar peta tata ruang, melainkan cerminan ambisi kolonial untuk membangun kota modern yang tertib, higienis, dan monumental di dataran tinggi Priangan.
Tujuan utamanya sederhana: pemerintah kolonial ingin keluar dari Batavia yang dianggap tidak sehat. Bandung, dengan udara dingin dan bentang dataran luas, dipilih sebagai kandidat ibu kota baru. Karena itu, wilayah utara kota perlu dikembangkan untuk menampung gedung-gedung pemerintahan dan permukiman pegawai tinggi.
Rencana ini mencakup pembangunan fasilitas publik utama seperti Gemeentenhuis, Technische Hoogeschool (yang kemudian menjadi ITB), Gemeentelijk Ziekenhuis, Bibliotheek, Musea, hingga Instituut Pasteur. Semua ditempatkan di kawasan utara, di antara lembah dan bukit yang memberikan latar alami bagi kota kolonial baru.
Ghijsels memperkirakan Bandung akan tumbuh dari 60.000 penduduk menjadi sekitar 150.000 dalam 25 tahun, dengan kepadatan 50 hingga 60 orang per hektar. Angka itu cukup besar untuk menegaskan Bandung sebagai kota modern di pedalaman Jawa.
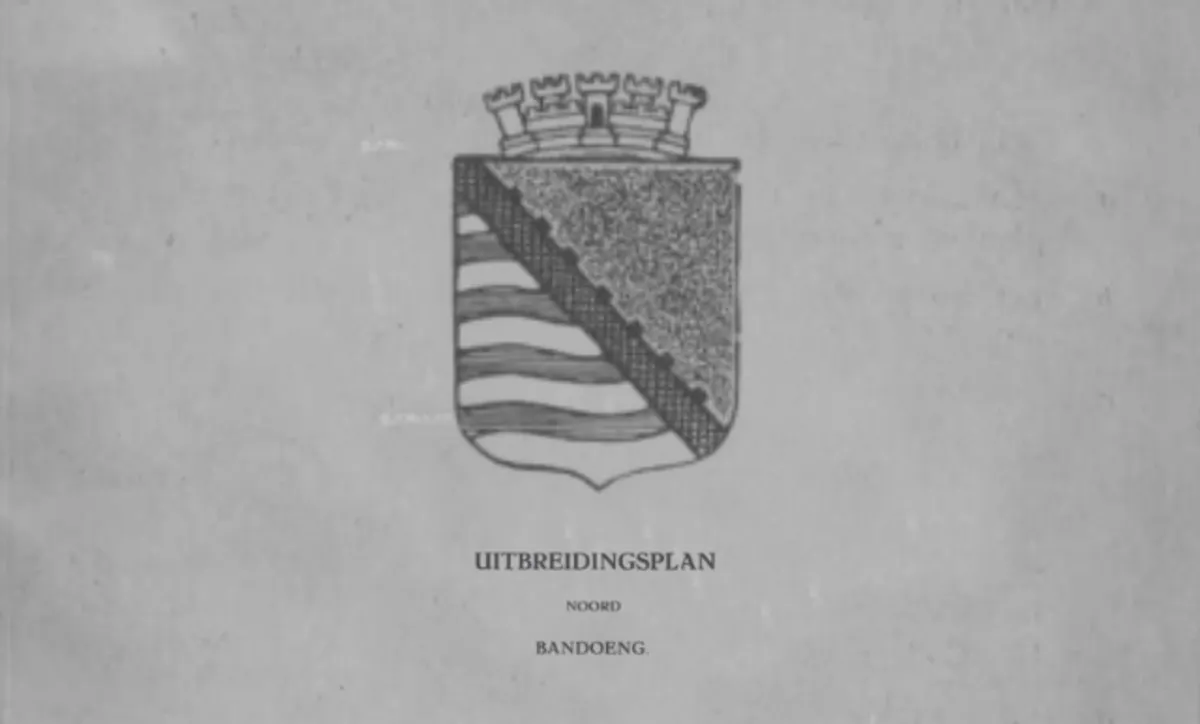
Baca Juga: Merenungi Perubahan Iklim lewat Senja di Bandung Utara
Dalam laporannya, para perancang menggambarkan Bandung lama sebagai kota tanpa monumen, taman, atau “jiwa”. Tata letaknya acak, kampung pribumi menempel di belakang toko-toko China, dan kawasan baru seperti Merdeka dianggap belum matang.
Rencana baru berusaha memperbaiki keadaan itu dengan merancang kota yang lebih teratur. Di dalamnya terkandung juga pembagian sosial yang tegas: Bandung Utara untuk pemukiman Eropa dan pejabat tinggi, Bandung Selatan untuk industri, kampung pribumi, dan distrik Cina. Sebuah kota tropis modern sekaligus potret hierarki kolonial.
Bagian paling ambisius dari rencana ini ada pada sistem jalan. Ghijsels membayangkan Bandung seperti jaring radial dan lingkar, di mana lalu lintas mengalir dari pusat ke pinggiran.
Yang berperan seagai arteri utamanya adalah Groote Postweg, yang kini menjadi Jalan Asia Afrika dan berlanjut ke arah Dago dan Lembang. Jalan ini diharapkan menjadi tulang punggung kota dan jalur trem listrik masa depan. Jalur timur-barat dianggap paling penting, sementara arah utara-selatan disesuaikan dengan medan yang lebih curam.
Beberapa jalan yang kini dikenal masyarakat, seperti Lembangweg (Ir. H. Juanda), Passir Kaliki, dan Riouwstraat (Riau), sudah muncul dalam peta rencana 1919. Ghijsels juga mengusulkan rel kereta barang dipindahkan ke selatan agar lalu lintas pusat kota lebih manusiawi dan ruang publik lebih terbuka.
Rencana ini juga berbicara tentang sanitasi. Saat itu Bandung masih mengandalkan saluran air terbuka yang mencampur limbah rumah tangga, air hujan, dan feses. Kondisi ini menjadi sumber penyakit yang sering merebak di kota tropis.
Baca Juga: Sejarah Julukan Garut Swiss van Java, Benarkah dari Charlie Chaplin?
Dalam Uitbreidingsplan Noord Bandoeng, sistem baru diusulkan. Riolering tertutup digunakan untuk limbah dan fekal, sedangkan air hujan disalurkan melalui saluran terbuka yang mengarah ke sungai alami seperti Tjika Poendoeng. Untuk kawasan pribumi dirancang fasilitas mandi umum dan tangki septik sederhana.
Tujuannya adalah menciptakan kota yang bersih, sehat, dan modern, sesuai gagasan perencana Jerman Dr. Hegemann tentang “penataan ruang hidup yang bermartabat.”
Bagian lain yang menarik adalah pembahasan tentang transportasi umum. Para perancang menyadari bahwa kepadatan Bandung jauh lebih rendah dibanding kota Eropa, sementara daya beli penduduk juga terbatas. Trem listrik atau bus tidak mudah dijalankan di kota seperti ini.
Solusi yang diajukan adalah pengembangan radial di sepanjang jalan utama. Kaum Eropa yang kaya akan tetap mengandalkan mobil pribadi, sedangkan bagi penduduk kecil dan pekerja, akses cepat ke pusat kota harus disediakan melalui sistem transportasi yang efisien.
Yang menarik, dokumen ini menyarankan agar layanan publik seperti trem dioperasikan oleh perusahaan kota, bukan sepenuhnya swasta, agar kepentingan masyarakat tetap terjamin. Sebuah gagasan yang terdengar cukup maju untuk 1919.
Salah satu hasil konkret dari rencana ini adalah penempatan Technische Hoogeschool (ITB) di kawasan barat Dagoweg, yang kini menjadi kampus ITB. Komisi Penilai meminta agar tata letak sekitarnya disesuaikan dengan rancangan arsitek Maclaine Pont agar lingkungan kampus menyatu dengan lanskap dan arsitektur.
Selain kampus, rencana itu juga menyiapkan area monumental untuk gedung pemerintahan seperti Raadhuis, Volksraad, dan istana Gubernur Jenderal. Semua diletakkan di dataran tinggi Bandung Utara agar menciptakan citra kota administratif yang megah.
Rencana besar ini disetujui secara prinsip oleh Komisi Penilai pada 13 Mei 1919. Namun, tidak semua detailnya dijalankan. Tujuan utamanya adalah memberi arah umum pertumbuhan kota, bukan instruksi teknis yang harus dilaksanakan persis seperti di peta.
Perang Dunia, krisis ekonomi, dan pembatalan pemindahan ibu kota membuat sebagian besar rencana itu berhenti di atas kertas. Meski begitu, jejaknya masih terlihat hingga kini. Pola radial Bandung, lokasi kampus ITB, rumah sakit di kawasan utara, dan arah pertumbuhan ke Dago dan Lembang semuanya berasal dari peta ini.
Seratus tahun kemudian, Bandung tumbuh jauh melampaui bayangan Ghijsels. Kota yang dulu direncanakan untuk 150 ribu orang kini dihuni jutaan penduduk. Namun warisan kolonial itu tetap hidup dalam bentuk, arah, dan pembagian ruangnya.
Baca Juga: Sejarah Bandung dari Kinderkerkhof sampai Parijs van Java
Setelah perang dan kemerdekaan, arah perencanaan kota Indonesia berubah. Menurut Van Roosmalen, perencanaan pasca-1945 bergeser ke skala regional dengan pengaruh gaya Amerika, menandai masa baru yang berbeda dari prinsip kolonial Eropa. Namun warisan Bandung Utara tetap terasa. Tata ruang kolonial yang hierarkis—antara utara yang sejuk dan elit dengan selatan yang padat dan rakyat—masih membentuk wajah sosial kota hingga kini.
Kini, Bandung Utara bukan lagi proyek administratif, melainkan kawasan padat dengan vila, kafe, dan hotel. Daerah yang dulu dipilih karena kesejukan dan keasriannya kini menghadapi tekanan pembangunan. Ironi sejarah menampakkan diri: kawasan yang dulu dirancang sehat dan modern justru kini berhadapan dengan kemacetan, krisis air, dan penyusutan ruang hijau.