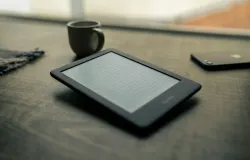AYOBANDUNG.ID - Di Bandung bagian utara, dulu ada sebidang tanah yang lebih sering jadi bisik-bisik daripada cerita resmi. Namanya Kinderkerkhof. Orang Belanda menyebut begitu karena memang isinya makam anak-anak mereka sendiri. Jangankan jadi kota besar, Bandung di awal abad ke-19 masih lebih mirip kampung udik.
Jalanan becek, rumah penduduk seadanya, dan udara sejuk yang ternyata tak cukup menolong bayi-bayi kulit putih agar bisa panjang umur. Jadi jangan bayangkan sejak awal Bandung penuh kembang dan kafe. Awalnya, kota ini malah lebih akrab dengan suara tangisan orang tua Eropa yang kehilangan buah hatinya.
Dalam Sejarah Kota Bandung dari “Bergdessa” (Desa Udik) Menjadi Bandung “Heurin Ku Tangtung” (Metropolitan), Peneliti Balai Pelestarian Sejarah dan Nilai Tradisional Bandung, Nandang Rusnandar mengutip sejumlah risalah kolonial yang menyinggung nasib malang anak-anak Belanda di Priangan.
Penyakit tropis yang tak kenal ampun—malaria, disentri, demam berdarah—lebih lihai merenggut nyawa ketimbang dokter-dokter yang dibawa dari negeri jauh. Alhasil, kuburan kecil itu jadi bukti nyata kalau tinggal di tanah jajahan tak selalu enak. Orang Belanda boleh punya gedung-gedung bagus, tapi anak-anak mereka tetap saja tak jarang harus lebih cepat masuk tanah.
Bandung sendiri waktu itu belum disebut kota. Orang menyebutnya bergdessa, artinya desa udik. Letaknya memang strategis, diapit sungai dan dikelilingi tanah subur. Tapi lebih banyak orang lewat daripada menetap. Jalan utamanya pun bukan jalan raya yang mulus, melainkan tanah merah yang bikin kaki kotor. Baru setelah Herman Willem Daendels membangun Groote Postweg pada 1810, segalanya berubah. Jalan raya raksasa itu membelah Jawa dari Anyer sampai Panarukan, melewati Priangan, termasuk Bandung. Sejak itulah perhatian pemerintah kolonial lebih serius menoleh ke daerah ini.
Baca Juga: Sejarah Bandung, Kota Impian Koloni Eropa yang Dijegal Gubernur Jenderal
Bupati Bandung kala itu, Wiranatakusumah II, kebagian tugas memindahkan pusat kabupaten dari Dayeuhkolot ke lokasi baru yang dekat dengan jalur Postweg. Perintah datang, maka pindah. Dari sinilah berdiri Bandung yang baru, dengan alun-alun, pendopo, dan masjid agung yang jadi pakem tata kota Jawa. Cikal bakal kota lahir, walau bau anyir tanah kuburan anak-anak Belanda belum hilang juga dari angin utara.
Dia menyinggung dalam catatan risalah Belanda, orang Eropa yang datang awalnya kepincut Bandung karena udaranya sejuk. Mereka berharap hidup lebih nyaman dibanding Batavia yang pengap dan penuh malaria. Nyatanya, Bandung pun tidak ramah untuk semua. Anak-anak mereka tetap berjatuhan. Di sinilah psikologi kota mulai terbentuk: Bandung indah, tapi diam-diam menyimpan tragedi. Orang Eropa tetap betah karena dibanding Batavia, Bandung terasa lebih ringan. Setidaknya orang dewasa bisa bertahan hidup lebih lama.
Seiring waktu, kota ini mulai ditata rapi. Jalan-jalan lurus dibuka, rumah-rumah Belanda dibangun agak berjauhan dari kampung pribumi. Konsep tata ruang ala kolonial menempatkan alun-alun di tengah, diapit pendopo dan masjid agung. Itu sebabnya sampai sekarang kalau orang cari pusat Bandung, pasti ketemunya alun-alun di depan Masjid Raya. Dari situlah segala hiruk-pikuk menyebar.

Kawasan Braga, yang belakangan disebut-sebut sebagai simbol “Parijs van Java”, awalnya tak lebih dari jalan kampung yang becek. Nandang mengutip catatan bagaimana jalan itu pelan-pelan berubah setelah pedagang Eropa mendirikan toko-toko, restoran, sampai kafe. Kalau dulu anak-anak Belanda ramai di pemakaman kecil, kini mereka yang selamat bisa tumbuh besar dan nongkrong di Braga, sambil minum kopi atau belanja. Perubahan itu menunjukkan bagaimana kota yang awalnya dikenal lewat kuburan kecil bisa berganti wajah jadi tempat hiburan.
Kendati begitu, bayangan Kinderkerkhof tak hilang begitu saja. Kota ini tumbuh bersama kenangan pahit itu. Gedung-gedung kolonial berdiri megah, tapi di baliknya ada trauma yang jarang diceritakan. Itulah sebabnya Bandung tidak pernah benar-benar polos. Di satu sisi ia cantik, di sisi lain ada lapisan muram yang jadi fondasi.
Baca Juga: Sejarah Bandung dari Paradise in Exile Sampai jadi Kota Impian Daendels
Saat memasuki abad ke-20, Bandung makin mantap jadi kota orang Eropa. Jalur kereta api dari Batavia ke Bandung dibuka, dan itu menambah citra Bandung sebagai tempat liburan sekaligus hunian favorit orang Belanda. Braga makin ramai, toko-toko mode berjejer, bioskop berdiri. Tak salah kalau kemudian muncul julukan “Parijs van Java”. Di sepanjang Braga, orang bisa melihat perempuan Belanda berjalan dengan gaun, lelaki berkepala topi fedora, sambil mampir ke toko roti.
Gedung-gedung art deco muncul di mana-mana. Gedung Merdeka yang dulu jadi Societeit Concordia, Savoy Homann, sampai Villa Isola—semua menjadi saksi bagaimana Bandung jadi panggung gaya hidup Eropa di tanah jajahan. Kalau mau cari kota yang paling “Eropa” di Hindia Belanda, jawabannya bukan Batavia, melainkan Bandung.
Tapi lagi-lagi, ingatan soal kuburan anak-anak tetap ada. Orang boleh menyebut Braga sebagai miniatur Paris, tapi sejarah mencatat bahwa kota ini lahir bersama kuburan. Kontradiksi itu membuat Bandung berbeda: ia tak hanya hasil rekayasa tata kota kolonial, tapi juga hasil kompromi antara penyakit, udara, dan nasib buruk yang dialami para pendatang.
Disebutkan Nandang dalam risalahnya menyusun cerita Bandung seperti perjalanan panjang dari bergdessa hingga heurin ku tangtung. Dari desa udik yang jadi perlintasan, lalu jadi kota kabupaten, kemudian naik kelas jadi kota Eropa dengan segala simbol kemewahannya. Lalu pada akhirnya menjadi kota besar yang penuh sesak. Semua itu berawal dari masa ketika anak-anak Belanda lebih dulu masuk liang kubur sebelum sempat merayakan hidup di tanah Priangan.
Baca Juga: Sejarah Julukan Garut Swiss van Java, Benarkah dari Charlie Chaplin?
Bandung pada masa kolonial memang punya wajah ganda. Di satu sisi, ia jadi pusat hiburan, kota mode, dan simbol modernitas. Di sisi lain, ia menyimpan jejak tragis yang tak tercatat di brosur wisata. Kota yang dipuja dengan julukan manis ternyata pernah dikenal lewat kuburan anak-anak.
Begitulah Bandung: lahir dari sebuah desa udik, dibentuk oleh tangan penguasa kolonial, dibalut dengan gemerlap Eropa, dan dibayang-bayangi nisan kecil di utara kota. Sejarahnya tak melulu soal Braga yang glamor, tapi juga soal tanah becek yang dipenuhi air mata. Dari situlah Bandung tumbuh, sampai akhirnya jadi kota yang dikenal dengan segala julukannya: Kinderkerkhof di awal, lalu Parijs van Java ketika sudah dewasa.