AYOBANDUNG.ID - Padi jarang dianggap berbahaya. Bentuknya jinak, warnanya bersahabat, dan biasanya hadir dalam foto kalender pertanian. Tetapi pada Juli 1919, padi berubah menjadi sumber kepanikan administratif dan alasan sah untuk menembakkan peluru. Lokasinya bernama Cimareme, sebuah wilayah agraris di Garut, jauh dari pusat kekuasaan, dekat dengan sawah, dan terlalu kecil untuk diperhitungkan sebelum akhirnya berdarah.
Hindia Belanda pada masa itu sedang kehabisan napas. Perang Dunia Pertama telah selesai, tetapi efeknya belum pamit. Jalur perdagangan terganggu, kapal tidak datang tepat waktu, gudang beras kosong lebih cepat dari perkiraan. Pemerintah kolonial menghadapi krisis pangan yang terasa seperti soal hidup mati. Seperti biasa, krisis semacam ini jarang diselesaikan dengan berbagi beban secara adil.
Solusi yang dipilih terlihat rapi di atas kertas. Petani diwajibkan menjual padi kepada pemerintah dengan harga yang sudah ditentukan. Harga ini aman bagi kas negara dan tidak ramah bagi perut rakyat. Aturan tersebut diberlakukan di banyak wilayah, tetapi Garut mendapat perlakuan khusus. Kuota dinaikkan. Empat pikul per bau. Angka yang tampak administratif, tetapi memiliki dampak sosial yang kejam.
Baca Juga: Sejarah Longsor Cigembong Garut Zaman Kolonial, Warga Satu Kampung Lenyap Tanpa Jejak
Bagi petani kecil, padi bukan komoditas dagang utama. Padi adalah jaminan hidup, cadangan musim paceklik, dan penentu apakah dapur tetap menyala. Ketika kuota dinaikkan empat kali lipat dalam kondisi panen yang buruk, kebijakan ini berubah menjadi tekanan struktural yang tidak mengenal kompromi. Pemerintah menyebutnya kewajiban. Sawah merasakannya sebagai perampasan.
Di tengah situasi tersebut, muncul nama Haji Hasan Arif. Sosok ini tidak lahir dari kemiskinan ekstrem atau kemarahan spontan. Ia berasal dari keluarga terpandang, memiliki garis keturunan religius yang kuat, dan hidup dalam kecukupan ekonomi. Ulama, juragan tembakau, pemilik sawah luas. Profil yang seharusnya aman dari kebijakan wajib jual padi.
Justru karena posisi itu, sikap penolakannya terasa ganjil bagi aparat kolonial. Penolakan dari petani miskin bisa dicatat sebagai keluhan. Penolakan dari orang berpengaruh dibaca sebagai ancaman laten. Apalagi jika penolakan itu dibungkus otoritas agama dan simpati sosial.
Haji Hasan tidak memulai dengan amarah. Jalur administrasi ditempuh. Surat dikirimkan kepada bupati. Permintaan disampaikan dengan bahasa halus. Isinya sederhana. Kuota dianggap terlalu berat dan tidak seimbang. Cimareme diminta diperlakukan sama dengan wilayah lain. Jawaban yang datang juga sederhana dan dingin. Aturan tetap berlaku.
Baca Juga: Sampai ke Bandung, Sejarah Virus Hanta Bermula dari Perang Dunia 1
Penolakan tersebut mengubah posisi Cimareme dalam peta kekuasaan kolonial. Wilayah ini mulai diawasi lebih ketat. Laporan aparat berubah nada. Aktivitas keagamaan dibaca sebagai mobilisasi. Kepemilikan senjata tradisional dianggap persiapan kekerasan. Kain putih dan jimat, benda yang biasa hadir dalam kehidupan religius pedesaan, mendadak menjadi simbol pemberontakan.
Dalam arsip kolonial, kombinasi ulama, petani, dan simbol agama selalu dianggap rawan. Sejarah sebelumnya sudah cukup memberi peringatan. Maka pendekatan administratif perlahan ditinggalkan. Aparat bersenjata mulai dilibatkan. Keputusan diambil cepat dan tanpa empati.
Baca Juga: Kapal Laut Garut jadi Korban Torpedo Jerman di Perang Dunia II
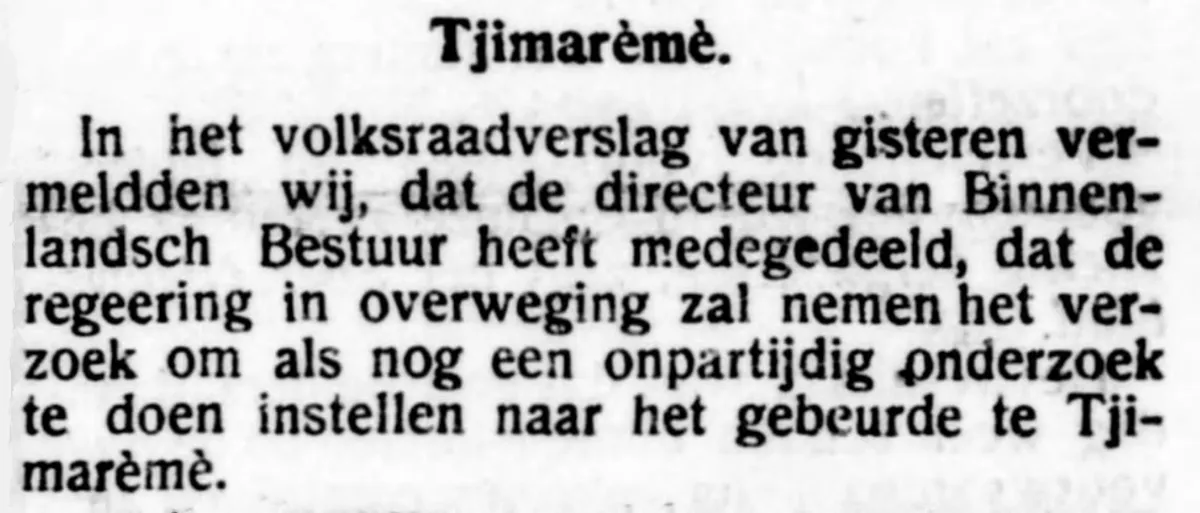
Dari Surat ke Senapan
Rencana penangkapan pertama gagal. Warga berdatangan ke rumah Haji Hasan. Bukan untuk menyerang, tetapi untuk berjaga. Kehadiran massa ini justru memperkuat kecurigaan pemerintah kolonial. Situasi dinilai sudah melewati batas toleransi. Operasi diperbesar. Pasukan infanteri didatangkan dari berbagai daerah. Pejabat sipil dan aparat pribumi ikut serta agar tindakan terlihat sah dan terkoordinasi.
Pada 7 Juli 1919, rumah Haji Hasan dikepung. Cimareme yang biasanya sunyi berubah menjadi panggung operasi militer. Tidak ada dialog panjang. Tidak ada ruang tawar-menawar. Haji Hasan keluar bersama keluarga dan pengikutnya. Pakaian putih dikenakan. Senjata tradisional dibawa. Situasi tegang berakhir dengan suara tembakan.
Pertempuran berlangsung singkat dan timpang. Senjata api menghadapi keyakinan dan besi tua. Haji Hasan tewas di tempat. Beberapa pengikutnya menyusul. Korban dari kalangan perempuan dan anak-anak menambah daftar tragedi. Sawah kembali sunyi, kali ini dengan bekas peluru dan ingatan yang sulit dihapus.
Setelah tembakan berhenti, pekerjaan administratif dimulai. Penangkapan dilakukan secara luas. Puluhan orang ditahan. Proses hukum berjalan lambat, seolah waktu juga ikut menghukum. Dua tahun berlalu sebelum persidangan digelar. Vonis yang dijatuhkan bersifat menyebar dan berat. Pembuangan ke pulau terpencil. Penjara di kota-kota jauh. Pemisahan fisik sekaligus sosial.
Baca Juga: Sejarah Julukan Garut Swiss van Java, Benarkah dari Charlie Chaplin?
Keluarga Haji Hasan tidak luput. Anak-anak dan cucu-cucunya ikut menerima hukuman. Dalam logika kolonial, keterlibatan tidak selalu perlu dibuktikan. Kedekatan sudah cukup sebagai alasan. Cimareme tidak hanya kehilangan pemimpin, tetapi juga mengalami pemutusan generasi secara sistematis.
Represi tidak berhenti pada mereka yang terlibat langsung. Aparat terus memburu orang-orang yang dianggap memiliki hubungan ideologis. Pakaian putih dan jimat kembali dijadikan barang bukti. Tidak ada organisasi modern yang terbukti mengatur peristiwa ini, tetapi semangat perlawanan sudah cukup untuk memicu ketakutan.
Peristiwa Cimareme kemudian hidup dalam bentuk lain. Masuk ke sastra. Menjadi wawacan. Menjadi cerpen. Menjadi bahan tulisan politik. Pemerintah kolonial memandang karya-karya ini sebagai ancaman lanjutan. Penulisnya dipenjara. Karya sastra diperlakukan setara dengan senjata.
Dalam kajian sejarah, Peristiwa Cimareme ditempatkan sebagai bagian dari radikalisme agraria. Istilah ini terdengar rapi dan akademik, tetapi menyembunyikan kenyataan sederhana. Kebijakan terlalu keras bertemu masyarakat yang sudah tertekan. Ledakan menjadi hasil yang hampir pasti.
Baca Juga: Sejarah Tahu Sumedang, Warisan Cita Rasa Tionghoa hingga Era Cisumdawu
Peristiwa ini juga memberi pelajaran pahit bagi pergerakan nasional. Keberanian tanpa organisasi hanya menghasilkan korban. Sejak itu, arah perlawanan mulai bergeser. Disiplin politik dianggap lebih efektif daripada heroisme spontan. Agama tetap penting, tetapi harus diiringi strategi.
Lebih dari satu abad setelah peristiwa itu, Cimareme tetap ada. Nama Haji Hasan Arif diabadikan sebagai jalan. Makamnya diziarahi. Masjidnya berdiri tenang. Tidak ada monumen besar. Tidak ada perayaan resmi. Tetapi peristiwa ini terus hidup sebagai pengingat bahwa kolonialisme sering kali runtuh bukan karena perang besar, melainkan karena kebijakan kecil yang terlalu rakus.
Peristiwa Cimareme 1919 adalah kisah tentang padi yang dipaksa berpindah tangan, tentang negara kolonial yang lupa batas, dan tentang seorang ulama yang menolak patuh ketika kepatuhan berarti membiarkan orang lain kelaparan. Sejarah mencatatnya sebagai catatan kaki. Sawah mengingatnya sebagai luka panjang.