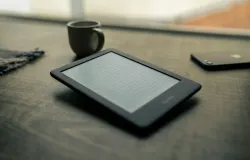AYOBANDUNG.ID - Tahu Sumedang bukan sekadar camilan khas yang bisa ditebus seribuan per biji di warung pinggir jalan. Ia menyimpan riwayat panjang yang dimulai dari keinginan seorang imigran Tionghoa menyenangkan hati istrinya, berkembang menjadi usaha kecil yang nyaris gagal, lalu berubah menjadi kuliner legendaris dari Tanah Priangan. Di balik teksturnya yang renyah dan rasa gurihnya yang khas, tahu Sumedang adalah cerita tentang cinta, migrasi, perjuangan, dan adaptasi.
Kemunculan industri tahu di Sumedang tidak bisa dilepaskan dari kehadiran orang-orang Tionghoa yang menetap di wilayah Jawa Barat sejak akhir abad ke-19. Mereka datang ke Hindia Belanda dalam gelombang besar, terutama setelah sistem tanam paksa seperti cultuurstelsel dihapuskan. Banyak dari mereka yang kemudian tinggal dan membentuk komunitas-komunitas pecinan, termasuk di Sumedang. Di sanalah kelak, sejarah tahu Sumedang dimulai.
Sesuai catatan dari buku Tahu Sejarah Tahu Sumedang terbitan LIPI (2021), komunitas Tionghoa dikenal sebagai pedagang ulung yang juga memperkenalkan berbagai jenis tanaman, seperti teh, kopi, tebu, dan kedelai. Selain membuka perkebunan, mereka mendirikan pabrik kecil untuk mengolah hasil bumi. Di lingkungan pecinan, muncul industri-industri rumahan yang memproduksi makanan khas seperti kecap, bihun, mi, dan tentu saja, tahu.
Di Sumedang, industri tahu dimulai oleh seorang pria Tionghoa bernama Ong Ki No yang tiba sekitar tahun 1900-an. Ia datang bersama istrinya, yang disebut-sebut sangat menyukai makanan khas Tiongkok bernama tao-fu. Karena sayangnya pada sang istri, Ong Ki No rela menjelajah ke wilayah yang belum dikenalnya untuk mencari kedelai—bahan utama tahu. Perjalanannya berbuah manis ketika ia menemukan kebun kedelai di wilayah Conggeang yang menghasilkan kedelai lurik, berwarna seperti telur puyuh.
Baca Juga: Jejak Sejarah Dodol Garut, Warisan Kuliner Tradisional Sejak Zaman Kolonial
Dengan menggunakan kedelai lokal dan air dari mata air Sumedang yang jernih, Ong Ki No mulai bereksperimen membuat tahu untuk konsumsi rumah tangga. Dalam proses pembuatan tahu, air memegang peran penting karena membentuk 70% komposisi bahan. Beruntung, kualitas air di Sumedang—terutama di kawasan antara Cimalaka dan Tanjungsari—pada saat itu sangat baik. Hasil tahu racikan Ong Ki No pun terasa berbeda dari tao-fu asal Tiongkok, meski saat itu bentuknya masih tahu putih rebus.
Tahu buatan Ong Ki No mulanya hanya dibagikan kepada keluarga, tetangga Tionghoa, dan masyarakat pribumi sekitar saat hari raya. Respons masyarakat ternyata positif. Lalu Ong Ki No berpikir untuk menjual tahu secara lebih serius. Sebagai perantau, tentu saja ia berharap usaha ini bisa memperbaiki nasib ekonominya. Apalagi emigrasi besar-besaran dari Tiongkok ke Asia Tenggara pada masa itu memang dipicu oleh kondisi ekonomi yang memburuk, pemberontakan petani, dan perang saudara.
Tapi sayang, upaya dagang Ong Ki No tidak mulus. Tahu putih rebus ternyata tidak banyak diminati masyarakat lokal. Karena merasa usahanya tak membuahkan hasil, Ong Ki No dan istrinya memutuskan untuk pulang ke Tiongkok pada tahun 1917. Saat itulah, tongkat estafet usaha ini dilanjutkan oleh anak mereka, Ong Bung Keng.
Tahu Bungkeng Sang Legenda Hidup
Tak seperti ayahnya, Ong Bung Keng berpikir untuk mencoba pendekatan yang berbeda. Ia melihat bahwa tahu putih rebus bisa diolah lagi. Maka ia mencoba menggoreng tahu putih tersebut. Hasilnya adalah tahu goreng dengan kulit yang renyah dan aroma yang menggoda. Rasanya lebih gurih, teksturnya lebih menarik. Sejak saat itu, potensi tahu sebagai produk kuliner lokal mulai terbuka lebar.
Tahun 1928, ada sebuah kejadian yang konon turut mengubah nasib usaha tahu Ong Bung Keng. Kala itu, Pangeran Soeriaatmadja, Bupati Sumedang, sedang melintasi daerah tempat Ong Bung Keng berjualan. Saat melewati gerobak tahu, beliau mencium aroma sedap yang tak dikenalnya. Ia turun dari kereta kudanya, mencicipi tahu goreng tersebut, dan berkata, “Makanan ini enak. Kalau dijual terus, pasti laku.”
Ucapan tersebut dianggap sebagai semacam doa oleh masyarakat, terutama karena Pangeran Soeriaatmadja dikenal sebagai tokoh yang saleh dan dihormati. Dalam budaya Sunda, ada kepercayaan bahwa ucapan orang saleh akan menjadi kenyataan: saciduh metu, saucap nyata. Maka, sejak saat itu, tahu Sumedang mulai dikenal luas. Nama Ong Bung Keng kemudian diabadikan menjadi merek dagang: Tahu Bungkeng.

Produksi tahu saat itu masih dilakukan secara manual dan terbatas. Dalam sehari, Bung Keng hanya bisa memproduksi sekitar seribu potong tahu berukuran 5x5 cm. Pada 1930-an, harga satu potong tahu sekitar 3 peser. Tahun 1939, tahu mulai dijajakan secara keliling oleh pedagang asongan seperti Odjo Mihardja yang menjual di area terminal.
Baca Juga: Jejak Sejarah Peuyeum Bandung, Kuliner Fermentasi Sunda yang Bertahan Lintas Zaman
Setelah kemerdekaan, industri tahu belum langsung berkembang pesat. Namun Ong Bung Keng mulai membuka kios kecil, tak hanya berkeliling menjual tahu dengan sepeda. Masyarakat pribumi pun mulai tertarik masuk ke bisnis tahu. Mereka menjadi pedagang yang mengambil tahu dari produsen dan menjualnya keliling atau di tempat-tempat ramai.
Pada tahun 1950-an, mulai bermunculan merek tahu lain selain Tahu Bungkeng, seperti Tahu Yoe Fo dan Ojolali. Semuanya masih dikelola oleh warga keturunan Tionghoa. Baru pada 1960, muncul pengusaha tahu dari kalangan pribumi seperti Epen Oyib yang mendirikan Tahu Saribumi. Menurut cucunya, Epen Oyib sempat bekerja di Tahu Yoe Fo sebelum akhirnya membuka usaha sendiri setelah merantau ke Jakarta.
Dari Orde Baru hingga Cisumdawu
Industri tahu makin tumbuh seiring pembangunan yang masif di era Orde Baru. Jalan raya dibangun, kantor pemerintahan bermunculan, dan permukiman warga makin padat. Warga Sumedang banyak yang merantau ke Jakarta atau kota lain. Saat mudik, mereka sering membawa oleh-oleh berupa tahu Sumedang dan ubi Cilembu. Maka tahu Sumedang pun makin dikenal di luar daerah.
Dalam pada 1980-an, industri tahu Sumedang benar-benar melejit. Menurut catatan LIPI, pada tahun 1979 terdapat 40 unit usaha tahu di Sumedang. Jumlah ini bertambah menjadi 50 unit dalam enam tahun berikutnya. Tahun 1989, jumlahnya melonjak menjadi 92 unit usaha. Inilah masa keemasan tahu Sumedang.
Tapi, seperti kata pepatah, roda nasib selalu berputar. Tahun 1998, Indonesia diguncang krisis moneter. Nilai tukar rupiah anjlok, harga bahan baku seperti kedelai naik drastis. Industri tahu terkena imbasnya. Harga tahu naik, daya beli turun. Tapi anehnya, jumlah unit usaha tahu justru bertambah. Pada 1998 tercatat ada 154 unit usaha tahu Sumedang, dan pada 1999 naik menjadi 158 unit.
Kenapa bisa begitu? Jawabannya, karena industri tahu adalah sektor mikro yang tidak terlalu bergantung pada utang luar negeri. Mereka berproduksi dengan skala kecil dan lebih fleksibel menghadapi fluktuasi ekonomi. Menurut catatan Bank Indonesia, UMKM seperti industri tahu justru lebih resilien di masa krisis dibanding perusahaan besar yang terlibat pinjaman dolar.
Tahun 2016, berdasarkan data Dinas Koperasi dan UKM Kabupaten Sumedang, terdapat setidaknya 42 industri tahu yang masih aktif. Jumlah ini belum termasuk cabang atau mitra yang berdiri di luar Sumedang seperti di Bandung atau Jakarta.
Sayang, ancaman baru datang seiring pembangunan jalan tol Cisumdawu (Cileunyi–Sumedang–Dawuan). Jalan tol ini memotong akses utama Kota Sumedang, yang selama ini menjadi jalur vital ekonomi dan distribusi tahu. Banyak pelaku usaha tahu mulai mengeluh karena jalur pembeli berkurang. Mereka berharap pemerintah memberi solusi agar eksistensi tahu Sumedang tetap terjaga meski lalu lintas beralih ke tol.
Baca Juga: Hikayat Java Preanger, Warisan Kopi Harum dari Lereng Priangan
Tahu Sumedang bukan hanya makanan. Ia adalah bagian dari identitas budaya, bukti adaptasi etnis Tionghoa yang kemudian menyatu dalam tanah Priangan. Dari dapur Ong Ki No yang penuh cinta, hingga gerobak Bung Keng yang mengundang selera bupati, tahu Sumedang telah melalui lebih dari satu abad perjalanan.
Hari ini, tahu Sumedang bisa ditemukan hampir di seluruh Indonesia. Tapi tetap saja, rasanya paling nikmat saat dimakan langsung di kota asalnya—panas, renyah, dan disajikan dengan cerita. Sebab di dalam tahu itu, terkandung sejarah yang digoreng dengan cinta, ditaburi perjuangan, dan disajikan dengan kebanggaan.