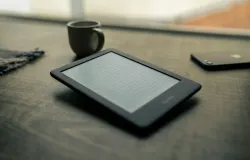AYOBANDUNG.ID - Priangan pada akhir abad ke-17 masih berupa dataran tinggi dengan sawah, hutan, dan tegalan. Tanah subur itu awalnya dihuni masyarakat agraris yang menanam padi, singkong, atau jagung. Kehidupan berjalan dengan ritme sederhana sampai orang-orang Belanda dari kongsi dagang VOC datang. Mereka tak datang untuk menikmati udara sejuk Bandung, melainkan untuk memburu komoditas baru yang sedang laris di pasar Eropa: kopi.
Kopi memang semula ditanam secara sukarela. Petani membuka lahan, menanam, lalu menjual hasilnya sesuai kemampuan. Namun, kebiasaan baik itu segera berubah ketika VOC menyadari keuntungan besar dari perdagangan kopi. Perlahan tapi pasti, apa yang semula sukarela menjadi kewajiban. Rakyat dipaksa menyetor panen dengan harga yang ditentukan sepihak, jauh di bawah harga pasar. Dari situlah dimulai sistem kerja paksa yang kelak dikenal sebagai Sistem Priangan.
VOC tidak pernah terlalu repot turun tangan langsung mengatur kebun kopi. Mereka cukup mengandalkan para kepala pribumi: bupati, wedana, lurah, yang dijadikan alat untuk menggerakkan rakyat. Jan Breman dalam Keuntungan Kolonial dari Kerja Paksa: Sistem Priangan dari Tanam Paksa Kopi di Jawa, 1720–1870 mencatat bahwa cara ini dipilih karena murah. Kolonial bisa menekan biaya administrasi, sementara beban memaksa rakyat jatuh ke tangan bangsawan lokal. Kepala pribumi diperintah agar “mengabdi” dengan memaksa rakyat menyetor hasil dan tenaga mereka.
Daerah Priangan kala itu dianggap frontier, wilayah pinggiran yang belum sepenuhnya terkendali secara politik maupun geografis. Maka penguasaan kolonial bukan hanya soal ekonomi, tetapi juga cara untuk menundukkan masyarakat pedalaman. Kopi menjadi alat pengikat. Setiap keluarga diwajibkan menanam sejumlah pohon, dan setiap musim panen harus menyetor hasilnya ke gudang kolonial. Tidak ada pilihan lain.
Baca Juga: Jejak Kabupaten Batulayang, Lumbung Kopi Belanda di Era Preangerstelsel
Kehidupan rakyat pun berubah drastis. Lahan untuk padi atau palawija harus diganti dengan kebun kopi. Waktu kerja yang biasanya untuk keluarga dan sawah sendiri terkuras habis demi memenuhi kuota. Hasil panen dibeli murah, tapi jumlah yang diminta tidak bisa ditawar. Bila gagal memenuhi, ancaman menanti: hukuman fisik, penahanan, hingga pemindahan penduduk ke daerah lain. Petani Priangan, termasuk di Bandung, perlahan merasa dirinya bukan lagi penggarap tanah, melainkan mesin produksi bagi orang asing.
Dari sudut pandang kolonial, sistem itu tampak “efisien”. Kuota bisa diatur, harga ditetapkan, keuntungan mengalir deras ke Batavia dan Amsterdam. Namun dari sudut pandang petani, semua itu hanya penderitaan. Tak heran bila sejak awal, rakyat mencoba mencari cara untuk melawan.
Gelombang Perlawanan di Tanah Priangan
Perlawanan muncul dalam berbagai bentuk. Ada yang terang-terangan, ada pula yang diam-diam. Banyak petani memilih melarikan diri dari wilayah kerja paksa. Ada pula yang menyembunyikan panenan, atau sengaja menyetor hanya sebagian. Tidak semua tercatat dalam arsip kolonial, tetapi Breman menegaskan bahwa “keengganan mereka yang terus berkelanjutan untuk bertindak sesuai dengan yang diperintahkan oleh pemerintah kolonial merupakan hal yang sangat menentukan dalam kemunduran dan kejatuhan Sistem Tanam Paksa.” Perlawanan semacam ini, meski tampak kecil, perlahan merongrong fondasi sistem yang ditegakkan dengan kekerasan.
Ada pula perlawanan yang lebih terbuka. Nama Prawatasari menonjol dalam catatan sejarah Priangan. Ia dikenal sebagai haji pengembara dari kelompok Giri, yang mengobarkan semangat perlawanan dengan bahasa religius. VOC sendiri mencatat pengikutnya sebagai “penyembah Muhammad”, istilah peyoratif yang menunjukkan kebingungan kolonial apakah gerakan itu murni politik, ekonomi, atau agama. Padahal, ketiganya bercampur menjadi satu. Rakyat merasa diperas hasilnya, dihina keyakinannya, sekaligus direndahkan harga dirinya.
Baca Juga: Hikayat Java Preanger, Warisan Kopi Harum dari Lereng Priangan

Gerakan Prawatasari berkembang di perbukitan Priangan selatan. Ketika tekanan VOC makin kuat, ia dan para pengikutnya mencari perlindungan di Jampang. Penindasan segera dilakukan. Banyak pengikut ditangkap, dipenjara, bahkan mati dalam pengangkutan. Namun ada pula yang berhasil lolos dan terus melanjutkan perlawanan. Meskipun gerakan itu tidak menjatuhkan VOC, ia cukup membuat pihak kolonial repot.
Kepala-kepala pribumi berada dalam posisi serba salah. Sebagai perpanjangan tangan VOC, mereka dipaksa mengawasi rakyat. Namun bila terlalu keras, mereka dicap pengkhianat oleh rakyat sendiri. Bila terlalu lunak, mereka bisa dituduh membangkang oleh kompeni. Bahkan ada tuduhan bahwa sebagian kepala pribumi bersekongkol dengan pemberontak, atau setidaknya tidak menjalankan perintah VOC secara penuh. Dalam keadaan ini, jabatan bupati atau wedana bukan hanya soal kehormatan, melainkan juga soal bertahan hidup di tengah dua tekanan.
Perlawanan rakyat tak hanya berupa senjata atau pemberontakan. Humor gelap juga menjadi senjata. Petani yang harus setor kopi dengan harga murah sering melontarkan sindiran. Konon ada yang menggerutu, “Kopi kita diambil, tenaga kita dihisap, tandanya kita cuma pohon kopi keliling.” Ucapan itu getir sekaligus lucu, mengungkap absurditas sistem kolonial yang memperlakukan manusia seperti alat panen.
VOC pun tak selalu memahami apa yang sebenarnya terjadi. Mereka bingung apakah perlawanan di Priangan murni gerakan keagamaan atau pemberontakan ekonomi. Padahal jelas, rakyat melawan karena gabungan dari ketiganya: tuntutan ekonomi yang tak adil, penghinaan pada keyakinan, dan pelecehan harga diri.
Perlawanan ini, baik yang kecil maupun besar, pada akhirnya menggoyahkan keberlangsungan sistem Priangan. Kolonial memang masih bertahan, tetapi mereka harus terus memperbaiki administrasi, memberi insentif lebih kepada kepala lokal, dan memperketat pengawasan. Semua itu menambah biaya dan kesulitan bagi pemerintah kolonial.
Pada akhirnya, pada tahun 1870, sistem Priangan resmi dihapus. Breman menulis bahwa “titik balik terjadi dengan dihapusnya sistem Priangan pada tahun 1870.” Tentu saja penghapusan itu tidak semata-mata karena perlawanan rakyat, tetapi jelas penolakan yang berkelanjutan membuat sistem itu semakin sulit dijalankan. Kritik internal dari pejabat kolonial sendiri ikut mempercepat kejatuhannya.
Baca Juga: Sejarah Pahit Keemasan Kopi Priangan di Zaman Kolonial, Kalahkan Yaman via Preangerstelsel
Kendati begitu, dampak yang paling penting adalah lahirnya kesadaran baru di kalangan rakyat Priangan. Mereka mulai melihat bahwa tuntutan penyetoran paksa, kerja wajib, dan upeti berlebihan bukan hanya soal ekonomi, melainkan ketidakadilan. Hubungan kuasa yang timpang antara petani, kepala lokal, dan penguasa asing menjadi bahan keluhan yang terus diingat. Kesadaran itu menjadi bagian dari ingatan kolektif rakyat Priangan, termasuk Bandung, yang hingga kini masih terasa dalam cerita-cerita tentang kerja paksa dan perlawanan.
Di masa sekarang, Bandung dikenal sebagai kota modern dengan jalan Braga, kafe Dago, dan aroma kopi yang jadi kebanggaan. Tapi sejarah panjang menunjukkan bahwa kopi di tanah ini pernah berarti kerja paksa dan penderitaan. Petani Bandung pada abad ke-18 dan ke-19 bukan barista yang menyajikan kopi dengan senyum, melainkan kuli yang dipaksa menyetor hasil kebun demi keuntungan kolonial.
Sistem Priangan memang sudah lama berakhir, tapi jejak perlawanan rakyat tetap hidup dalam catatan. Dari lari ke hutan, menyembunyikan panenan, mengikuti gerakan ulama, hingga melontarkan sindiran getir di tengah sawah, semua itu bagian dari sejarah perlawanan rakyat Bandung dan Priangan. Tidak heroik dalam catatan resmi, tetapi nyata dalam kehidupan sehari-hari.