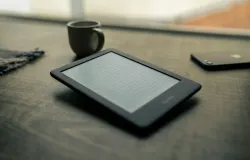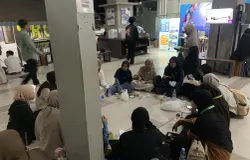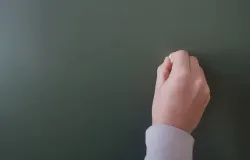Di banyak ruang sunyi hari ini, kita melihat pemandangan yang sama, seseorang menunduk menatap layar, menggulir tanpa henti. Jari bergerak naik-turun seperti mengikuti ritme yang tak berujung. Tidak ada akhir yang jelas, tidak ada tujuan yang pasti, hanya arus gambar, suara, dan kata-kata yang terus berganti. Kita menyebutnya scrolling, para peneliti menyebutnya sebagai ritual baru zaman digital.
Scrolling bukan lagi sekadar tindakan teknologis, ia telah menjadi gaya hidup. Kita menggulir layar untuk mencari kabar, hiburan, atau sekadar mengisi waktu luang.
Namun di balik gerakan sederhana itu tersembunyi logika zaman yang kompleks, logika kecepatan, keterhubungan, dan kecanduan. Scrolling adalah cermin dari bagaimana manusia hidup, berpikir, dan merasa dalam dunia media baru.
Scrolling sebagai Ritual Budaya Media Baru
Dalam The Language of New Media, Lev Manovich (2001) menyebut bahwa media baru memiliki lima prinsip utama: numerisitas, modularitas, otomatisasi, variabilitas, dan transkodifikasi. Kelima prinsip ini membuat media digital bersifat cair, interaktif, dan terus berubah. Dalam konteks itu, scrolling menjadi bentuk paling nyata dari pengalaman “variabilitas” media, setiap guliran menghadirkan konten baru, pengalaman baru, tanpa batas yang jelas antara awal dan akhir.
Desain “infinite scroll” tidak muncul begitu saja, ia adalah produk logika ekonomi perhatian (attention economy). Desain ini diciptakan agar pengguna tetap berada di dalam platform selama mungkin. Setiap gerakan jempol di layar sebenarnya adalah hasil dari user experience design yang memanfaatkan psikologi manusia, yaitu dorongan untuk selalu tahu lebih banyak, melihat lebih banyak, tidak ketinggalan apa pun. Dalam konteks ini, teknologi tidak netral. Ia membentuk kebiasaan, bahkan kesadaran.
Manovich menulis bahwa dalam media baru, struktur logika komputer (database, algoritma) menjadi dasar dari pengalaman kultural. Maka, ketika kita menggulir, sebenarnya kita sedang menavigasi dunia yang disusun oleh logika digital, dunia yang terus diperbarui, selalu bergerak, dan jarang memberi ruang untuk berhenti.
Logika Jaringan dan Fragmentasi Waktu
Manuel Castells (1996) menyebut masyarakat kita sebagai network society, masyarakat jaringan. Di dalamnya, hubungan sosial, ekonomi, dan budaya dibentuk oleh logika jaringan global yang bekerja secara real-time. Informasi mengalir tanpa henti, waktu dan ruang kehilangan batas tegas. Scrolling adalah cara paling khas manusia berinteraksi dengan dunia jaringan itu, kita tidak lagi membaca realitas secara linear seperti membaca buku, tapi melompat dari satu potongan konten ke potongan lain.
Setiap guliran adalah potongan waktu kecil (micro-moments) yang membentuk ritme kehidupan digital. Kita belajar untuk hidup dalam “keterputusan yang terhubung”, berpindah cepat, tapi tetap terikat oleh arus. Dalam budaya seperti ini, keheningan menjadi langka, dan perhatian menjadi sumber daya yang paling langka pula.
Jonathan Crary (2013) menyebut keadaan ini sebagai 24/7 capitalism, di mana waktu manusia sepenuhnya dijajah oleh ritme ekonomi digital. Tidak ada malam bagi media sosial, dan tidak ada istirahat bagi pengguna. Scrolling adalah bagian dari kapitalisme tanpa tidur, kerja emosional tanpa upah, konsumsi tanpa jeda.
Scrolling dan Dunia Simulakra

Namun lebih dalam dari sekadar jaringan dan kecepatan, budaya scrolling juga memperlihatkan sesuatu yang lebih filosofis, bagaimana realitas kini berubah menjadi simulasi. Jean Baudrillard (1981) dalam Simulacra and Simulation menjelaskan bahwa di era posmodern, manusia hidup dalam dunia hiperrealitas, di mana citra dan tanda lebih nyata daripada kenyataan itu sendiri.
Dalam setiap timeline media sosial, kita melihat dunia yang tampak indah, lucu, atau tragis, tapi semua itu adalah representasi, bukan realitas mentah. Kita menggulir bukan untuk memahami dunia, tapi untuk mengonsumsi tanda-tanda tentang dunia. Setiap like, share, dan story adalah fragmen dari simulasi sosial yang menciptakan ilusi kedekatan dan makna.
Scrolling, dalam logika Baudrillard, adalah tindakan partisipasi dalam simulakra. Kita menikmati permukaannya, bukan kedalamannya. Kita terseret oleh citra, bukan isi. Maka, saat kita terus menggulir, yang sebenarnya kita cari bukan informasi, melainkan sensasi, sensasi menjadi ada di tengah arus yang terus bergerak.
Krisis Perhatian dan Kehilangan Kedalaman
Nicholas Carr (2010) dalam The Shallows mengingatkan bahwa otak manusia berubah seiring cara kita berinteraksi dengan teknologi. Semakin sering kita terpapar informasi singkat dan cepat, semakin sulit kita untuk berpikir mendalam dan fokus lama. Budaya scrolling memperkuat pola ini, perhatian kita terfragmentasi menjadi serpihan waktu.
Pierre Bourdieu (1990) mungkin menyebutnya habitus digital, pola kebiasaan baru yang mengatur cara kita merespons dunia. Kita menjadi terbiasa berpikir cepat, bereaksi spontan, dan sulit menahan jeda. Scrolling tidak lagi hanya soal teknologi, scrolling bukan sekadar kebiasaan bermain ponsel. Ia mengubah cara kita memusatkan perhatian dan merasakan waktu. Kita terbiasa berpikir cepat, menatap banyak hal sekaligus, namun kehilangan kedalaman untuk benar-benar memahami.
Mungkin di sinilah tantangan terbesar zaman sekarang, bagaimana tetap sadar di tengah arus yang tak berhenti. Cal Newport (2019) dalam Digital Minimalism menawarkan jalan keluar sederhana, yaitu batasi konsumsi, pilih dengan sadar, dan berani menciptakan jeda. Namun kesadaran digital bukan sekadar soal manajemen waktu, ia juga soal spiritualitas modern, kemampuan untuk hadir, bukan sekadar terhubung.
Scrolling bisa menjadi jendela untuk refleksi: seberapa sering kita menggulir bukan karena ingin tahu, tapi karena takut berhenti? Takut kehilangan koneksi, takut merasa sendiri? Barangkali yang kita cari dalam guliran itu bukan informasi, melainkan makna, sesuatu yang diam-diam hilang dalam kecepatan.
Penutup: Cermin dari Logika Zaman
Budaya scrolling mencerminkan logika zaman digital: cepat, terfragmentasi, dan berbasis atensi. Ia memperlihatkan bagaimana teknologi bukan hanya alat, tapi juga membentuk cara berpikir, merasa, dan hidup. Dalam setiap guliran, tersimpan paradoks manusia modern, semakin banyak yang kita lihat, semakin sedikit yang benar-benar kita pahami.
Mungkin, seperti kata Baudrillard, kita hidup di dunia di mana “realitas lenyap dalam kecepatan tanda-tanda.” Namun kesadaran tentang hal itu bisa menjadi langkah awal untuk mengambil kembali kendali. Karena di tengah arus yang tak berhenti, manusia masih punya satu kemampuan yang belum bisa digantikan algoritma, yaitu kemampuan untuk berhenti, merenung, dan memilih. (*)
Daftar Referensi
- Ahmed, S. (2004). The Cultural Politics of Emotion. Edinburgh University Press.
- Baudrillard, J. (1981). Simulacra and Simulation. Semiotext(e).
- Bourdieu, P. (1990). The Logic of Practice. Stanford University Press.
- Carr, N. (2010). The Shallows: What the Internet Is Doing to Our Brains. W.W. Norton & Company.
- Castells, M. (1996). The Rise of the Network Society. Blackwell Publishing.
- Crary, J. (2013). 24/7: Late Capitalism and the Ends of Sleep. Verso.
- Jenkins, H. (2006). Convergence Culture: Where Old and New Media Collide. NYU Press.
- Manovich, L. (2001). The Language of New Media. MIT Press.
- Newport, C. (2019). Digital Minimalism: Choosing a Focused Life in a Noisy World. Portfolio.