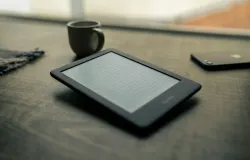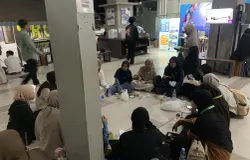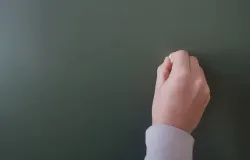Salah satu berita yang akan mengebohkan dalam beberapa pekan, bulan atau bahkan akan dikenang sepanjang masa adalah dilantiknya Sushila Karki sebagai Perdana Menteri sementara Nepal menyusul konflik berdarah selama beberapa hari yang merenggut beberapa korban jiwa.
Pengangkatan Karki sebagai Perdana Menteri ini dilakukan menyusul kekosongan pemerintahan selepas Sharma Oli untuk mengundurkan diri.
Perempuan berusia 73 tahun ini memang bukan perempuan sembarangan. Ia adalah mantan Ketua Mahkamah Agung di Negeri Himalaya ini. Ia tidak hanya dikenal sebagai politisi yang tidak kompromistis terhadap tindak korupsi, tetapi juga dosen, penulis, dan aktivis kebudayaan.
Namun yang membuatnya akan dikenang sepanjang masa adalah bahwa pemilihan Perdana Menteri ini dilakukan secara instant melalui aplikasi Discord, sebuah aplikasi instant messaging dan platform VoIP social yang memfasilitasi panggilan suara, panggilan video, teks, dan media-media lainnya yang dapat diatur sebagai komunikasi private atau dapat pula dalam bentuk komunitas secara virtual.
Fakta ini menjadikan Nepal telah mencetak sejarah sebagai negara pertama yang memperlihatkan “digital politics” sepenuhnya. Terlebih, demonstrasi yang berujung kerusuhan yang melatari peristiwa ini juga diinisiasi oleh Gen-Z dan memang dimobilisasi secara digital secara mandiri.
Meskipun sejak lama kaum muda sering menjadi penggerak perubahan sosial-politik dan kebudayaan, namun Gen-Z di Nepal memperlihatkan bagaimana kekuatan platform digital dalam memobilisasi gerakan sosial dan politik.
Bukan Kali Pertama

Nepal memang bukan yang pertama. Salah satunya, jauh sebelum era media sosial dan platform digital, gerakan serupa juga muncul di Filipina pada tahun 2001 dimana saat itu demonstran tumpah-ruah ke jalan karena seruan melalui SMS Broadcast untuk melawan Joseph Estrada yang korup.
Peristiwa ini kemudian melahirkan sebuah konsep yang dikembangkan oleh Howard Rheingold (2002) dalam Smart Mobs: The Next Social Revolution. Menurutnya, smart mob terdiri dari orang-orang yang bertindak secara bersamaan meski tidak mengenal satu sama lain, namun sama-sama memiliki perangkat komunikasi.
Dalam kasus Nepal, motif penggulingan kekuasaan tidak hanya disebabkan oleh tindakan korup para penguasa, tetapi juga dimotivasi oleh perasaan jengah atas perilaku anak-anak dan keluarga para pejabat yang seringkali flexing. Bahkan mereka menyebut anak-anak pejabat ini sebagai “nepo-kids” yang memperbesar jurang kesenjangan sosial.
Suara-suara sumbang dari rakyat yang diekspesikan di berbagai platform digital ini justru mendorong para penguasa Nepal untuk berencana membatasi sejumlah platform digital yang cukup popular.
Hal ini justru malah menambah kemarahan rakyat yang banyak diistilahkan sebagai digital frustration atau frustrasi digital. Bagi banyak pengamat, faktor inilah yang justru kemudian menciptakan kesamaan kehendak untuk menggulingkan pemerintahan yang korup.
Kekuatan Gen-Z dan Network Society
Smart mob yang digerakkan oleh platform digital ini ternyata hanya langkah awal dari babak baru kehidupan politik di Nepal. Setelah kekuasaan dapat digulingkan, kalangan Gen-Z masih ingin membuktikan bahwa gerakan mereka memang berbeda. Ya, mereka kemudian mengusulkan pemilihan pemimpin baru dengan cara mereka, yakni melalui platform Discord.
Dalam transisi kekuasaan semacam ini, “pemilu digital” menjadi pilihan yang paling masuk akal, karena dapat diselenggarakan dengan cepat, efektif, bahkan tanpa biaya. Benar saja, hanya dalam hitungan beberapa jam, sosok Sushila Karki terpilih dan tidak lama kemudian segera dilantik sebagai Perdana Menteri sementara.
Kasus Nepal memperlihatkan bahwa tidak semua Gen-Z itu “strawberry generation” yang dinilai rapuh dan lemah. Justru sebaliknya, mereka telah membuktikan bahwa kekuatan mereka begitu solid, efektif, efisien, tidak terbayangkan sebelumnya, bahkan oleh para analis politik kawakan.
Secara teoretis, smart mob di Nepal merupakan manifestasi dari “network society” yang mengarah pada sebuah masyarakat yang digerakkan oleh jejaring.
Manuel Castells (2009), pencetus teori ini, menguraikan bahwa dalam network society, kekuatan menjadi lebih terdistribusi dan tidak lagi bersifat hierarkis, hal ini salah satunya ditopang oleh eksistensi platform digital yang bersifat lebih interaktif dan pastisipatoris. Karakteristik inilah yang memungkinkan munculnya smart mob.
Dalam perspektif Rheingold, smart mob merupakan bentuk gerakan atau ekspresi politik gererasi baru. Gerakan sosial-politik di Nepal dan bahkan negara-negara lain yang muncul dengan pola ini, tidak terkecuali di Indonesia—dalam pandangan Rheingold adalah sebuah keniscayaan.
Smart mob bukan hanya disebabkan oleh perilaku menyimpang para penguasa, tetapi mungkin lebih sebabkan oleh gaya komunikasi politik digital Gen-Z dan generasi-generasi berikutnya. (*)