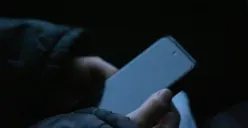Dalam media sosial pejabat publik, terutama berbasis politisi, dan lebih dalamnya lagi sosok Gubernur Jabar KDM (Kang Dedi Mulyadi), maka akan mudah terlihat feed yang dibuat semata kebutuhan audiens.
Ada unsur konten “aspiratif” di sana, karena konten dibuat tak sepenuhnya angan personal, tapi dominan merujuk sesuatu yang sedang ramai, atau mudahnya masyarakat sebut sedang “viral”. Kalaupun tidak sedang trending, unggahan (biasanya video) dibuat agar jadi ramai dibahas warganet (netizen).
Salah satu yang masuk kategori ini adalah video saat KDM menjadi Inspektur Upacara HUT Polri di Polda Jabar, awal Juli lalu. Saat upacara sudah dinyatakan selesai oleh pemimpin upacara, dan di luar kelaziman protokoler kenegaraan, sang gubernur tetiba inspeksi pasukan.
Alih-alih bubar jalan seperti lazimnya upacara peringatan, Dedi selepas inspeksi tersebut kembali ke podium. Dan, ini yang pastinya disukai netizen, dia mengumumkan akan berikan uang puluhan juta bagi anggota polisi tertua yang lama kenaikan pangkatnya mangkrak.
Bergemuruh-lah pemirsa, baik di lapangan Mapolda Jabar dan apalagi di medsos. Prosedur tata acara protokol tak apa dilanggar. Toh konten “khas” KDM nyawer-nyawer selalu ada, anggota polisi ada yang dapat duit dan …. trafik memuncak!
Jauh sebelum ini, sejenak kita kembali ke masa kampanye Pilpres 2024 lalu. Dari tiga paslon, yang berlaku sesuai tuntutan netizen, sudah pasti didominasi sosok yang kini jadi Presiden RI ke-8: Prabowo Subianto. Apalagi kalo bukan sosok baru: gemoy.
Setelah bertarung dalam tiga Pilpres dengan bangun kreasi citra sebagai sosok tegas khas militer, Prabowo berubah total dengan joget di banyak panggung. Bukan sekedar nari-nari tapi juga diiringi dengan musik dan tempik sorak dari Gen Z sebagai pemilih dominan saat itu.
Prabowo tak lagi ber-baret tapi ber-joget. Tak lagi berapi-api tapi berdansa-dansi. Tak lagi teriak kencang tapi menghibur lantang. Persoalan karakter pribadi “tergadaikan” tidaklah mengapa karena yang penting pemilih mayoritas suka dan tak lagi khawatir memilih sosok berbau loreng.
Dan, KDM serta Prabowo, sejatinya adalah gambaran mikroskopik. Nun jauh di negara yang mendaki kampiun demokrasi dunia, Amerika Serikat, kita pun dengan mudah menemukan unggahan politisi yang tak lagi karakter dirinya serta condong penuhi tuntutan “sutradara” khalayak.
Telaahan Cendekia

Apa yang terjadi pada panggung politik ini sejatinya sudah tertera sejak lama (dan termasuk kontemporer) oleh para cendekia humaniora.
Guy Debord dalam bukunya, The Society of the Spectacle (1967), sudah memprediksi lahirnya masyarakat spektakel. Yakni masyarakat yang menghargai yang tampak/visual itu lebih penting daripada karya nyata.
Pemimpin dinilainya akan didorong lebih banyak menangis bersama rakyat daripada membangun sistem yang adil bagi rakyat. Hubungan sosial tidak lagi dibangun berbasis kepercayaan, tapi lebih dominan berdasarkan gambar-gambar yang direkayasa dan disebarkan.
Maka, dalam dunia politik konteks spektakel ini, janji bisa lebih dulu menjadi tajuk berita sebelum menjadi kebijakan yang bisa diukur. “Atraksi” di media sosial yang menghanyutkan rasa dan karsa jauh lebih penting dari kebijakan teknorasi terukur.
Erving Goffman, salah seorang pemikir penting yang banyak dikutip sarjana komunikasi, berpikiran seragam delapan tahun sebelum Guy. Dalam bukunya The Presentation of Self in Everyday Life (1959), dia menyebut bahwa kehidupan sosial adalah panggung. Sementara manusia di atas panggung tersebut, terutama politisi/pejabat publik, adalah aktor yang menampilkan diri sesuai tuntutan audiens. Tidak ada yang benar-benar genuine.
Dalam konteks itu, identitas pemimpin adalah performa yang dibentuk, bukan cerminan kerja nyata. Apakah Prabowo dengan gemoy, serta Jokowi yang blusukan memeriksa saluran got, sesungguhnya merasa nyaman ikuti alur yang ditentukan “sutradara”tersebut? Belum tentu jika merujuk dua premis klasik ini.
Beralih ke pemikiran kontemporer. Paolo Gerbaudo dalam The Digital Party (2018) menyebut fenomena tersebut sebagai populisme digital. Yakni perancangan, pembangunan, dan pemeliharan impresi sebagai wakil rakyat langsung dengan melewati prosedur politik formal.
Politisi Indonesia sudah ngolotok bahwa empati digital itu sering lebih penting dari kedalaman kebijakan. Maka itu, daripada mengedukasi masyarakat terkait tata kelola pemerintahan, populisme digital lebih mementingkan pejabat publik cum politisi harus jadi influencer politik: memikat perhatian dengan spontanitas/terencana, rajin respons isu viral, serta membangun popularitas melalui algoritma konten visual menarik.
Zizi Papacharissi dalam Affective Publics (2015) menyebutkan, medium media sosial adalah pembentuk ruang publik berbasis emosi kolektif. Pemimpin yang mampu memanfaatkan momen krisis atau kisah inspiratif akan mendapat dukungan lebih kuat daripada yang hanya mengandalkan data.
Karenanya, Indonesia hari ini dan sangat mungkin seterusnya, akan terus menemui bukan lagi “Gubernur Konten” tapi juga menteri, kepala dinas, kepala desa, bahkan mungkin RT/RW yang sangat sadar konten bernuansa emosi kolektif.
Pejabat publik boleh jadi lebih fokus membangun komunikasi politik sesuai perilaku konsumsi informasi netizen dan citizen. Di sinilah risiko besar mengaga di negeri ini, manakala risiko jebakan citra akan menepikan program kerja pemeritahan yang terukur, matang, dan berdampak.
Apakah para tokoh publik dengan karakteristik semacam ini lahir dari society of spectacle tersebut? Lalu, sadarkah publik dengan peran mereka yang demikian? (*)