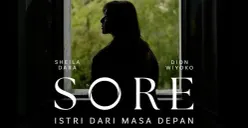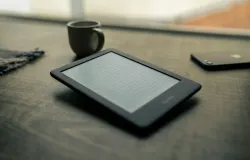Belakangan ini, tragedi Juliana Marins di Rinjani memenuhi linimasa media sosial dan segera menjadi trending topic, terutama di kalangan netizen Indonesia dan Brazil.
Sebagaimana diberitakan, Juliana (26) yang merupakan seorang turis asal Brazil tewas setelah tergelicir saat melakukan pendakian bersama enam rekannya dan seorang pemandu.
Ia diberitakan terjatuh di “jalur neraka” Torean di Gunung Rinjani, salah satu gunung paling ekstrim di Indonesia. Jalur dan cuaca ekstrim menjadi kontra-narasi pemerintah Indonesia yang dituding lambat dalam melakukan penyelamatan hingga Juliana tidak dapat diselamatkan. Bahkan pemerintah Brazil hendak menempuh jalur hukum untuk kasus ini.
Sebagaimana dilansir sejumlah media mainstream, salah satu kritik dan kekecewaan diekspresikan oleh pihak keluarga Juliana terutama terkait prosedur standar yang diterapkan pemerintah Indonesia di kawasan wisata.
Namun mereka juga lupa bahwa langkah penyelamatan juga telah dilakukan sejak awal namun terkendala medan dan cuaca ekstrim. Terlebih lagi, secara bersamaan, gelombang dukungan netizen Brazil berubah menjadi tekanan bagi pemerintah mereka untuk segera menyatakan sikap tegas terhadap Indonesia.
Dalam hal ini, netizen telah menjadi salah satu faktor determinan yang membuat tragedi ini bahkan dapat berdampak pada hubungan diplomasi kedua negara.
Hari ini, netizen mungkin telah berkontribusi besar dalam setiap keputusan politik di beberapa negara dan tidak lagi semata pengguna internet. Michael F. Hauben, sosok dibalik lahirnya istilah ini, menguraikan bahwa netizen merupakan pengguna internet yang berkontribusi aktif pada perkembangan internet dan sekaligus bertindak sebagai warga internet dan dunia.
Oleh karenanya, menarik diamati bagaimana netizen kedua negara kini seolah tengah terlibat dalam perang narasi. Netizen Brazil ramai-ramai “menyerang” akun resmi pemerintah Indonesia dengan mengkritik lambatnya proses penyelamatan Juliana diikuti dengan menggalang aktivisme untuk memboikot Gunung Rinjani sebagai destinasi wisata yang dinarasikan tidak aman bagi pengunjung.
Menghadapi narasi ini, netizen Indonesia pun menyerang balik. Diantara beberapa narasi ini misalnya, sosok Juliana bukanlah seorang pendaki namun turis tanpa skill yang dibutuhkan untuk melakukan pendakian di medan beresiko tinggi.
Kemudian, sebagai kontra-narasi lambatnya proses penyelamatan, sejumlah video di media sosial memperlihatkan bahwa langkah penyelamatan telah dilakukan sejak pertama kali diketahui namun beberapa kali ditunda karena keterbatasan alat dan medan yang ekstrim.
Lebih jauh, mereka bahkan memberikan ulasan negatif terhadap Sungai Amazon di Brazil yang justru lebih mematikan dan lebih berbahaya ketimbang Gunung Rinjani, dan tentu saja, sangat tidak direkomendasikan untuk dikunjungi.
Perang narasi memang sesuatu yang tidak dapat dihindarkan di media sosial. Terlebih, Brazil dan Indonesia merupakan dua negara dengan jumlah pengguna media sosial, terutama Instagram tertinggi ketiga dan keempat di dunia setelah India dan Amerika Serikat.
Dilansir Statistica.com pada tahun 2024, jumlah pengguna Instagram sebanyak 134.6 juta sementara Indonesia sebanyak 100.9 juta pengguna. Boleh jadi, urutan ini juga mencerminkan karakteristik netizen yang serupa. Jadi, tentu tidak terlalu mengherankan jika perseteruan netizen kedua negara ini semakin memuncak.

Secara teori, ragam narasi yang muncul sebagai buntut dari “Tragedi Juliana” ini juga merupakan gambaran dari “participatory culture” atau budaya partisipatif dimana setiap pengguna dapat mengekspresikan pikiran dan pandangannya atas sesuatu yang pada titik tertentu, boleh jadi sama sekali tidak relevan.
Tidak hanya itu, meskipun media sosial sering memperlihatkan efektivitas perannya sebagai ruang publik, namun yang menjadi pertanyaan adalah, sejauhmana setiap pandangan tersebut benar-benar merupakan bagian dari kepentingan publik?
Pada titik ini, fakta tentang keterlambatan penyelamatan korban mungkin dapat dipandang sebagai bagian dari kepentingan publik sehingga pemerintah Indonesia perlu berbenah dan memastikan prosedur standar terutama di kawasan wisata alam ekstrim, tidak hanya di Rinjani.
Namun sebagaimana diungkapkan Zizi Papacharissi, tidak semua pandangan di media sosial menggambarkan kepentingan publik. Sebab, ruang digital memungkinkan terjadinya peleburan antara “publicness” dan “privateness.”
Di jagat media sosial, kita tidak pernah benar-benar tahu batasan antara ekspresi yang merupakan kepentingan pribadi dan kepentingan publik.
Perwujudan netizenship, sebagai idealisasi dari realitas netizen di ranah digital, akan sangat tergantung pada literasi informasi yang dimiliki sehingga mampu benar-benar berpartisipasi dan berkontribusi positif dalam mewujudkan interaksi digital yang lebih sehat dan santun. (*)
Baca Juga: 10 Tulisan Terbaik AYO NETIZEN Juni 2025, Total Hadiah Rp1,5 Juta
Moch Fakhruroji adalah Direktur dan pendiri Center for Digital Culture and Society (CDiCS), sebuah pusat studi yang menaruh perhatian pada fenomena budaya digital dan dampaknya pada kehidupan sosial masyarakat kontemporer beserta seluruh kecenderungannya. Selain itu, beliau merupakan Guru Besar dalam bidang New Media and Communication Studies pada Program Studi Ilmu Komunikasi, UIN Sunan Gunung Djati Bandung dan sebagai dosen tidak tetap di beberapa kampus lain. Sebagai akademisi, ia memiliki minat pada; budaya digital, budaya populer, religious studies, dan new media and communication studies. Sejumlah karyanya tersebar dalam bentuk buku, artikel jurnal, book chapter, dan monograf.