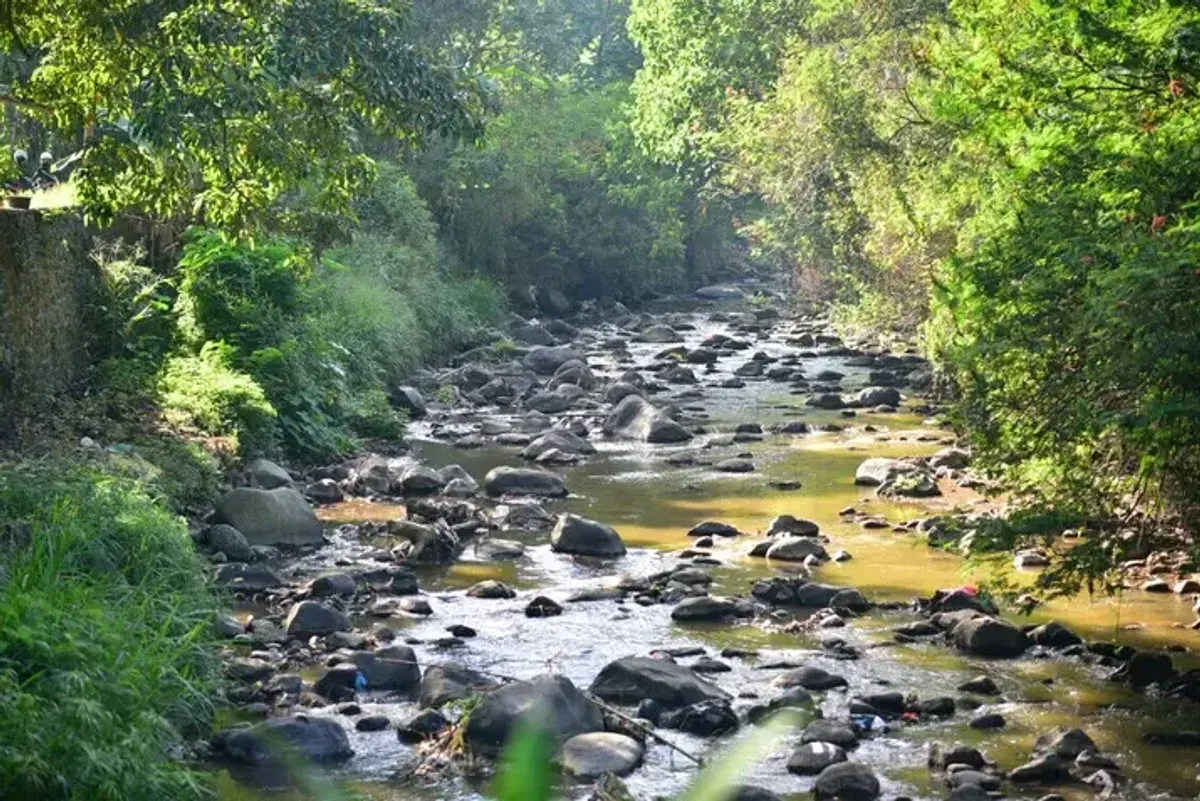Pemerintah kota Bandung tampak lebih sibuk memoles citra daripada memelihara kehidupan. Dari masalah sampah hingga kisruh Kebun Binatang Bandung, keputusan yang diambil justru menunjukkan betapa pendekatan kekuasaan terhadap alam dan kehidupan sosial kini lebih berpihak pada logika bisnis ketimbang empati.
Forum Komunikasi Kader Konservasi Indonesia (FK3I) menyebut bahwa cara pandang Pemkot Bandung terhadap persoalan lingkungan dan konservasi sudah menyimpang dari semangat pengabdian. Soal penyelesaian sampah, misalnya, pemerintah lebih memilih jalur insinerator—teknologi yang diklaim “modern”, tetapi menyimpan jebakan ekologis dan finansial.
Proyek ini akan membebani masyarakat lewat tipping fee, membuka peluang korupsi dan nepotisme, serta berpotensi merusak kualitas udara kota.
Alih-alih menyelesaikan krisis sampah, kebijakan itu malah berpotensi menciptakan krisis baru: krisis kepercayaan publik dan krisis lingkungan yang lebih dalam.
Situasi ini menjadi semakin problematik karena kota Bandung sedang disorot akibat kasus hukum yang menjerat wakil wali kota dan beberapa pihak swasta. Ketika moral penguasa terguncang, sulit berharap kebijakan publik lahir dari hati nurani. Itulah sebabnya, rencana penggunaan sedikitnya sepuluh insinerator dan konflik berkepanjangan di Kebun Binatang Bandung seakan mencerminkan satu hal: kekuasaan sedang buta arah dan kehilangan kesadaran ekologis.
Kisruh Bandung Zoo adalah cermin yang paling telanjang. Selama berbulan-bulan, konflik pengelolaan antara dua yayasan tidak juga diselesaikan, sementara Pemkot Bandung justru terlihat “ikut bermain” dalam lingkaran konflik itu. Tindakan penyegelan area kebun binatang yang dilakukan tanpa memperhatikan dampaknya terhadap satwa, pekerja kecil, dan ruang-ruang seni, menunjukkan betapa birokrasi telah kehilangan empatinya. Ratusan satwa—yang sejatinya titipan negara—dibiarkan dalam ketidakpastian.
Para keeper tetap bekerja, bukan karena upah, tetapi karena hati. Para seniman kehilangan ruang berekspresi, dan masyarakat kehilangan tempat edukasi serta ruang hijau yang berharga.
Padahal, kebun binatang bukan sekadar tempat wisata. Ia adalah ruang konservasi, sejarah, dan pendidikan ekologis. Menutupnya tanpa solusi adalah tindakan gegabah dan kekanak-kanakan. Jika alasan pemerintah adalah menjaga “kondusifitas”, seharusnya koordinasi dengan aparat keamanan sudah cukup—bukan malah menghentikan denyut kehidupan di dalamnya.

FK3I menyebut, jika Pemkot merasa sebagai pemilik lahan, maka sebaiknya meniadakan sewa dan menyerahkan pengelolaan sementara kepada para pekerja dan kementerian yang membidangi konservasi, sampai persoalan hukum antar-yayasan selesai.
Masalahnya kini bukan sekadar teknis, tetapi menyentuh akar moral: mengapa urusan hidup dan mati satwa serta warga kecil harus ditentukan oleh kepentingan bisnis dan politik?
Mengapa ruang publik seni dan konservasi dibiarkan menjadi korban tarik-menarik kekuasaan?
Pertanyaan ini membawa kita pada inti persoalan: krisis nurani ekologis.
Kita hidup di masa ketika keputusan lingkungan diambil bukan dengan rasa hormat terhadap kehidupan, melainkan berdasarkan kalkulasi keuntungan dan relasi kuasa. Pemerintah seolah lupa bahwa keberadaan ruang hijau dan satwa adalah bentuk ibadah manusia terhadap alam.
FK3I dan Walhi Jawa Barat menegaskan akan melakukan konsolidasi lintas aktivis untuk mendesak pemerintah segera sadar akan tugas pelestarian dan kesejahteraan—bukan hanya bagi manusia, tapi juga bagi makhluk lain yang berbagi hidup di bumi ini.
Lebih jauh, Aliansi Bandung Melawan berencana melaporkan dugaan praktik korupsi, kolusi, dan nepotisme dalam pengelolaan Kebun Binatang Bandung ke Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Langkah ini menjadi bentuk perlawanan moral terhadap kekuasaan yang semakin mengabaikan nilai kemanusiaan dan keadilan ekologis.
Bandung yang kita cintai tidak akan bertahan hanya dengan festival dan slogan. Ia butuh keberanian untuk melihat kebenaran yang pahit: bahwa kota ini sedang kehilangan arah moralnya. Ketika hati nurani dikesampingkan, kota berubah menjadi panggung komersial yang menindas warganya sendiri.
Kita mesti kembali pada nilai dasar: bahwa manusia dan alam adalah satu kesatuan kehidupan. Menghormati satwa berarti menghormati kemanusiaan kita sendiri. Karena itu, penyelamatan kebun binatang dan penolakan terhadap proyek insinerator bukan sekadar isu teknis lingkungan—melainkan perjuangan menjaga nurani kota dari pembusukan moral kekuasaan.
Sebagaimana diungkapkan seorang rimbawan sejati, “Tanah air dan udara tidak butuh penguasa, mereka hanya butuh manusia yang tahu berterima kasih.”
Dan mungkin inilah saatnya Bandung mengingat kembali makna itu. (*)