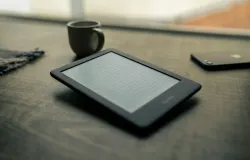Toponimi Patahan atau Sesar Baribis melejit kembali berbarengan dengan gempa-gempa yang menggoyang beberapa kawasan di utara Jawa Barat, seperti yang diumumkan oleh BMKG. Gempabumi dengan kekuatan 4,9 menggoyang wilayah Kabupaten Karawang pada Rabu, 20 Agustus 2025 pukul 19:54:55 WIB.
Selang beberapa hari, Senin, 25 Agustus 2025, gempabumi dengan kekuatan 3,2 menggetarkan Kabupaten Bekasi. Minggu, 21 September 2025, gempabumi terjadi di Kabupaten Bogor dengan kekuatan 3,1, dan pada Senin, 22 September 2025 pukul 12.41 WIB, gempabumi berkekuatan 2,6 mengguncang Kabupaten Bekasi.
Itulah dinamika bumi. Keniscayaan semesta yang tak dapat ditolak, dan tak dapat dipastikan kapan guncangan itu akan berulang. Menurut beberapa sumber, goncangan gempa bumi itu berada di garis patahan di utara Jawa Barat, yang oleh van Bemmelen (1949) dinamai Patahan Baribis.
Patahan yang terbentuk sejak Plistosen, antara 5 juta tahun hingga 2,6 juta tahun lalu itu, garis patahannya membentang antara Purwakarta hingga daerah Baribis, di Kabupaten Majalengka.
Penelitian-penelitian tentang Patahan Baribis terus berjalan saling menyempurnakan. Simanjuntak (1994) berpendapat bahwa garis Patahan Baribis itu menerus ke timur, bersambung dengan Patahan Kendeng, dan melintas hingga di Nusa Tenggara Barat. Simanjuntak menamainya Zona Patahan Baribis-Kendeng.
Penelitian terbaru yang dilakukan oleh Sony Aribowo (2022) menyebutkan, adanya lajur yang memajang barat timur yang dinamai Patahan Aktif Busur Belakang Jawa Barat. Garis patahannya melewati Cirebon, Indramayu, Majalengka, Subang, Purwakarta, Karawang, Bekasi, dan ada indikasi melintasi kawasan di selatan Jakarta yang berbatasan dengan Depok, dan Bogor.
Sony membagi Patahan Aktif Busur Belakang Jawa Barat itu menjadi 12 ruas atau segmen, yaitu: 1. Ruas Kalibayat, 2. Ruas Cisanggarung, 3. Ruas Cereme, 4. Ruas Baribis, 5. Ruas Tampomas, 6. Ruas Cipunagara, 7. Ruas Tangkuban Perahu, 8. Ruas Citarum Depan, 9. Ruas Citarum, 10. Ruas Kalapanunggal, 11. Ruas Salak, dan 12. Ruas Rarata.
Nama geografis Baribis di Kabupaten Majalengka yang oleh van Bemmelen dijadikan nama patahan, secara administratif termasuk Desa Baribis di Kecamatan Cigasong.
Di Jawa Barat, toponimi Baribis bukan hanya ada di Majalengka, tapi ada juga di Kabupaten Bandung, yaitu di Desa Ciburial, Kecamatan Cimenyan. Ada juga Cibaribis di Desa Mekarjaya, Kecamatan Banjaran, dan Cibaribis di Desa Alamendah, Kecamatan Rancabali. Sedangkan Gunung Baribis ada di Kecamatan Bantarkawung, Kabupaten Brebes, Jawa Tengah.
Sejak zaman Hindia Belanda, kawasan Baribis sudah menjadi kawasan yang dijelajahi dan diteliti. Banyak laporan dari Baribis, di antaranya laporan tahun 1907-1908 yang berjudul Onderzoek naar de oorzaken van de mindere welvaart der inlandsche bevolking op Java en Madoera. GGL Kemmerling (1916), menulis laporan berjudul De geologie en de Geomorphologie van Cheribon dalam buku Java en Madoera, di antaranya menuliskan tentang fosil di dekat Desa Baribis.
B van Tricht (1929), dalam laporannya, Levende Antiquiteiten in West-Java, menulis tentang kemegahan bentang alamnya. Siemon (1929) mendeskripsikan beberapa spesies Moluska dari Baribis, dan melaporkan tentang Turritella djadjariensis. Dan Ir LJC Vanes (1931), dalam buku The Age of Pithecanthropus, melaporkan, pada tahun 1926, Vanes menemukan molar Stegodon pada konglomerat dengan kemiringan curam di sekitar Baribis, dan pada tahun 1930 ia menemukan molar Cervus.
Sekitar satu juta tahun yang lalu, Hippopotamus pernah hidup di sungai dan rawa-rawa di Lembah Cisaar, Kabupaten Sumedang. Di kawasan ini banyak ditemukan fosil, seperti fosil gigi hiu Megalodon, Stegodon trigonocephalus, taring Hippopotamus, gajah, badak, kurakura, dan lain-lain.
Keadaan ini dapat menggambarkan geografi purba Lembah Cisaar sejak 10 juta tahun yang lalu sampai 900.000 tahun yang lalu, ketika Lembah Cisaar berupa lingkungan laut dangkal, estuari, dan menjadi lingkungan pengendapan sungai dan rawa.
Lembah Cisaar ditoreh dua anak sungai besar, Ci Peles dan Ci Lutung, yang bermuara di Ci Manuk. Lembah Cisaar dengan kawasan Baribis, hanya dipisahkan jarak 10 km, dengan medan yang datar dengan perbukitan di pinggirnya. Keadaan lingkungan geografi purba yang sama. Pada tahap akhir kawasan ini berupa lingkungan sungai dan rawa-rawa, dengan hutan terbuka di pinggirnya.
Manusia sudah menjelajahi kawasan ini, meninggalkan jejak budaya berupa perkakas batu. Ketika huniannya terus berkembang dari zaman ke zaman, dan lingkungannya masih berupa ranca atau rawa yang sangat luas, keadaan lingkungan berair inilah yang telah menginspirasi penamaan kawasan itu Baribis.
Kata baribis abadi menjadi nama geografis, namun padanan artinya tidak tercatat dalam kamus bahasa Sunda yang pernah terbit. Petunjuk ke arah pemaknaan kata baribis, dalam bahasa Sunda ada kata bibis, yang berarti menciprat-cipratkan air ke nasi yang keras saat masih gigih, saat belum matang.
Kata bibis juga berarti menciprat-cipratkan air ke lembaran tembakau yang terlalu keras. Di rawa alami ada burung air bernama waliwis, balibis, belibis. Jadi, kata bis, bibis itu berhubungan dengan air. Bila mengambil contoh kata lain dalam bahasa Sunda, ada kata seget, sogot, yang berarti gigit.
Namun ada juga kata yang bermakna sama, yaitu sigit, namun tidak produktif dipakai oleh masyarakat dalam berbahasa Sunda saat ini, namun ada di dalam toponimi, seperti Gunung Masigit, yang bermakna ada bagian lereng gunung yang seperti digigit.
Bila menghubungkan kata bibis, waliwis (balibis), dengan kata baribis, kata-kata itu mempunyai asal mula yang sama, yaitu bis, yang menunjukkan arti berhubungan dengan air.
Baca Juga: Ci Sanggiri Sungai yang Menggentarkan
Dan bila disebandingkan kata baribis dengan kata berebes, kedua kata itu pun mempunyai makna yang sama, yaitu berhubungan dengan air yang meleler sebagai matair, atau lahan basah yang bila tertekan, diinjak, misalnya, airnya akan ngaberebes, mbrebes, merembes, meleler, mengalir. Dalam kehidupan sehari-hari ada istilah mbrebes mili, yang berarti berlinang airmata.
Dari uraian di atas saya lebih memilih, bahwa toponimi Baribis itu maknanya sama dengan Brebes, air yang merembes, meleler, mengalir. Mengingat kedua kawasan itu keadaan lingkungan masa lalunya sama, yaitu berupa lahan basah, rawa, kawasan berair yang sangat luas. (*)