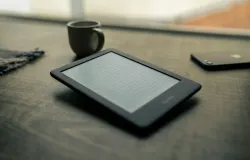AYOBANDUNG.ID - Pada penghujung abad ke-19, saat Eropa sedang keranjingan industrialisasi, Hindia Belanda pun tak mau ketinggalan dalam urusan infrastruktur. Negeri jajahan ini bukan hanya ladang emas berupa kopi, teh, dan kina, melainkan juga medan tantangan yang memaksa para insinyur kolonial untuk memutar otak. Di tengah rimbunnya hutan Priangan, antara lembah dan bukit Cianjur, lahirlah gagasan membangun sebuah terowongan kereta api yang akan menembus perut bumi.
Terowongan itu kemudian dikenal sebagai Terowongan Lampegan, yang kelak menjadi terowongan kereta tertua di Indonesia dan hingga kini masih menyimpan jejak panjang sejarah kolonial, teknologi, bahkan cerita mistis yang terus diwariskan dari mulut ke mulut.
Pembangunan Lampegan dimulai pada tahun 1879, di bawah kendali Staatsspoorwegen, perusahaan kereta api milik pemerintah Hindia Belanda. Staatsspoorwegen kala itu sedang getol membangun jaringan jalur rel di Jawa. Mereka punya ambisi besar: menghubungkan daerah-daerah penghasil komoditas perkebunan di pedalaman dengan pelabuhan-pelabuhan besar di Batavia, tempat kapal-kapal dagang siap mengangkut hasil bumi ke pasar dunia. Priangan, dengan tanah suburnya yang menghasilkan kopi, teh, dan kina kualitas unggul, jelas tidak bisa dibiarkan jauh dari jangkauan rel kereta api.
Baca Juga: Jejak Panjang Sejarah Cianjur, Kota Santri di Kaki Gunung Gede
Tapi, jalan menuju keuntungan tidak semulus brosur iklan. Priangan bukanlah tanah datar seperti sawah di Cirebon, melainkan penuh bukit dan gunung yang membuat keringat para insinyur kolonial mengucur deras. Solusinya adalah menembus bukit dengan terowongan. Setelah studi panjang, dipilihlah sebuah titik di Cianjur untuk digali. Maka, ratusan pekerja pribumi—dengan cangkul, linggis, serta sedikit bantuan bahan peledak sederhana—mulai merobek perut bumi. Proyek ini bukan hanya soal batu dan tanah, melainkan juga simbol masuknya teknologi Barat yang dengan berani menantang geografi Nusantara.
Pada 1882, pekerjaan yang melelahkan itu akhirnya membuahkan hasil. Sebuah terowongan sepanjang hampir 700 meter membelah bukit dengan megah, siap dilalui lokomotif besi yang berasap pekat. Jalur Sukabumi–Cianjur–Bandung pun resmi dibuka. Lampegan menjadi titik krusial dalam rute tersebut karena mengatasi hambatan elevasi yang selama ini memperlambat mobilitas.
Dengan dibukanya jalur ini, ritme ekonomi lokal berubah drastis. Desa-desa yang sebelumnya hanya dilalui pedati dan kuda kini ikut merasakan getar kereta api. Hasil bumi dari pedalaman bisa meluncur cepat ke Batavia, sementara barang-barang dari kota besar lebih mudah masuk ke pedesaan.
Jejak nama Lampegan sendiri kerap menimbulkan perdebatan. Banyak cerita jenaka beredar bahwa nama ini muncul dari teriakan mandor Belanda. Ada yang mengaitkannya dengan kalimat “lampen aan” yang berarti “nyalakan lampu”, atau “lampen gaan” yang berarti “lampu sudah menyala”. Bahkan ada yang lebih kreatif, mengatakan nama itu berasal dari perintah “lamp pegang” yang diteriakkan ketika para pekerja harus menahan lampu agar tidak jatuh. Teori-teori ini tentu menghibur, tapi sebenarnya keliru.
Bukti toponimi menunjukkan nama Lampegan sudah ada jauh sebelum terowongan digali. Peta topografi kolonial mencatat keberadaan Gunung Lampegan, Kampung Lampegan, dan Perkebunan Lampegan. Kata Lampegan ternyata merujuk pada sejenis tumbuhan kecil yang banyak tumbuh di kawasan itu. R. Satjadibrata dalam Kamus Basa Sunda edisi 1946 menyebut lampegan sebagai “ngaran tatangkalan leutik,” atau nama sebuah tanaman kecil. Jadi, nama Lampegan bukanlah hasil teriakan masinis Belanda, melainkan penamaan lokal yang kemudian diwarisi oleh terowongan dan stasiun.
Baca Juga: Sejarah Terowongan Kereta Sasaksaat, Terpanjang di Indonesia
Perjalanan Lampegan ke abad ke-20 dan 21 penuh lika-liku. Selama era kolonial, ia menjadi jalur penting pengangkutan hasil bumi. Namun, setelah Indonesia merdeka, prioritas jalur kereta berubah. Beberapa lintasan regional mulai sepi, termasuk jalur Cianjur–Sukabumi. Lampegan pun mengalami masa suram. Pada tahun 2001, longsor besar menutup jalur di sekitar Stasiun Lampegan. Terowongan ini terpaksa ditutup karena rusak parah. Upaya perbaikan dilakukan pada 2006, tetapi alam tampaknya belum rela. Longsor kembali menimpa kawasan itu, membuat jalur tetap tidak dapat dilalui.
Baru pada 2009–2010 dilakukan perbaikan besar yang lebih serius. Dinding terowongan direkonstruksi, dan panjangnya dipangkas dari sekitar 686 meter menjadi 415 meter agar bagian rawan longsor bisa dihindari. Setelah itu, Lampegan kembali bisa dilalui kereta api. Namun, insiden masih menghampiri. Pada 19 Agustus 2016, Kereta Api Siliwangi dari Cianjur menuju Sukabumi anjlok saat memasuki terowongan. Gerbong terakhir keluar jalur, membuat penumpang panik. Untungnya, tidak ada korban jiwa serius, tetapi kejadian itu menegaskan bahwa Lampegan masih menyimpan risiko yang tak bisa diremehkan.
Walaupun penuh drama, Lampegan tetap berdiri kokoh hingga kini. Ia menjadi jalur vital bagi KA Siliwangi dan jalur-jalur lokal lain, sekaligus bukti nyata bagaimana teknologi abad ke-19 masih mampu bertahan di tengah zaman yang sudah serba digital.

Legenda Ronggeng di Balik Terowongan
Sejarah fisik Lampegan mungkin bisa dicatat dalam arsip, tetapi cerita rakyat yang melekat padanya jauh lebih sulit dihapus. Di balik lengkung batu itu hidup legenda tentang seorang penari ronggeng bernama Nyi Sadea. Cerita tentangnya begitu populer di Cianjur dan sekitarnya, sehingga nyaris setiap orang yang pernah mendengar nama Lampegan pasti juga tahu kisahnya.
Baca Juga: Sejarah Gempa Besar Cianjur 1879 yang Guncang Kota Kolonial
Berdasarkan cerita yang beredar, pada masa pembangunan terowongan sering terjadi kecelakaan misterius. Galian longsor, pekerja tertimbun, proyek terancam gagal. Dalam keresahan itu, muncul bisikan bahwa terowongan membutuhkan tumbal manusia. Maka, seorang ronggeng bernama Nyi Sadea dipilih. Ada versi yang mengatakan ia dikubur hidup-hidup di dalam dinding terowongan sebagai syarat keselamatan, ada pula yang menyebut ia hilang begitu saja setelah menari di dekat lokasi, seolah ditelan oleh dunia gaib.
Terdapat pula kisah lain yang lebih romantis sekaligus menyeramkan. Dikisahkan pada suatu malam pejabat Hindia Belanda mengundang pertunjukan ronggeng untuk menghibur para pekerja. Nyi Sadea menari dengan gemulai, memukau penonton. Setelah itu hujan deras turun, dan ia berteduh di mulut terowongan.
Tiba-tiba terdengar panggilan samar dari dalam kegelapan. Dengan rasa penasaran, Nyi Sadea melangkah masuk. Sejak itu ia tidak pernah terlihat lagi. Masyarakat percaya ia menjadi istri gaib penguasa wilayah terowongan.
Legenda ini semakin hidup dengan cerita penampakan seorang perempuan berkebaya merah di dalam atau sekitar terowongan. Banyak penumpang maupun warga sekitar mengaku pernah melihatnya. Konon, ia menari pelan lalu menghilang, meninggalkan rasa merinding bagi siapa pun yang kebetulan lewat. Walau tak pernah bisa dibuktikan secara ilmiah, kisah Nyi Sadea menjadi bagian tak terpisahkan dari Lampegan. Ia adalah simbol bagaimana masyarakat Jawa menafsirkan kemajuan teknologi yang datang tiba-tiba dengan cara mereka sendiri: melalui mitos, tumbal, dan kepercayaan pada dunia gaib.
Kisah mistis ini tentu tidak mengurangi nilai sejarah Lampegan. Justru sebaliknya, ia menambah daya tarik. Wisatawan yang berkunjung tak hanya bisa menikmati keindahan arsitektur kolonial, tetapi juga merasakan sensasi berjalan di lorong yang konon dihuni arwah penari ronggeng. Perpaduan antara sejarah nyata dan mitos mistis inilah yang membuat Lampegan berbeda dengan terowongan lain. Ia bukan sekadar infrastruktur, melainkan juga panggung cerita yang hidup di imajinasi masyarakat.
Baca Juga: Sejarah Dongeng Si Kabayan, Orang Kampung Pemalas yang Licin dan Jenaka
Kini, Terowongan Lampegan bukan hanya jalur transportasi, tetapi juga destinasi wisata sejarah dan budaya. Orang datang untuk melihat sisa kejayaan teknologi kolonial, mendengar kisah tumbal Nyi Sadea, atau sekadar berfoto dengan latar lengkung dinding batu yang kokoh. Ia menjadi simbol kebanggaan Cianjur, saksi bisu dari masa kolonial hingga Indonesia merdeka, dari zaman lokomotif uap hingga kereta modern. Usianya yang lebih dari satu abad menjadikannya bukan sekadar tua, melainkan legendaris.