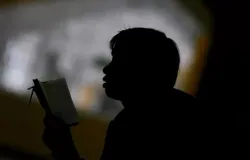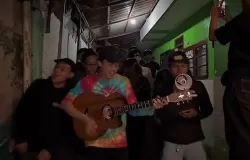Seorang kawan pernah mengajukan pertanyaan, "Adakah Islam bercorak lokal yang menjunjung tinggi harmoni?"
Ku balik bertanya, "Kunaon emang?'" Laki-laki berbadan gemuk itu menjawab, "Karena Jawa Barat kerap diidentikkan dengan radikalisme dan dianggap kurang menghargai kearifan lokal"
Justru pertanyaan itu mengingatkan pada tulisan Sukron Abdilah, Sunda dan Kemajemukan Budaya yang dimuat di Kompas rubrik Forum Budaya edisi 6 Juni 2009, dan Jakob Sumardjo, Mencari Identitas Sunda (Forum Budaya, 13 Juni 2009).
Rasanya tak berlebihan bila kita membaca tulisan Mang Ukon sapaan akrabnya memberikan pesan sekaligus mengingatkan kepada kita ihwan semangat Ki Sunda yang sedari dulu selalu mencoba menjaga kebudayaan non-Sunda untuk hidup di daerahnya.
Pesan damai dan toleran Ki Sunda itu terlihat jelas dari rangkaian larik yang disusun almarhum Mang Koko, yang menjelaskan sikap someah kepada non-Sunda sebagai ciri dari kedewasaan (sawawa) Ki Sunda.

Pudarnya Ki Sunda
Mari belajar dari Mang Koko “Tanah Sunda, gemah ripah/Nu ngumbara suka betah/Urang Sunda sawawa/Sing toweksa perceka/Nyangga darma anu nyata//Seuweu Pajajaran/Muga tong kasmaran/Sing tulaten jeung rumaksa/Miara pakaya memang sawajibna/Geuten titen rumawat tanah pusaka//”
Kiranya, pameo Islam-Sunda dan Sunda-Islam (Endang Saefuddin Ansory) terus disebarluaskan ke seluruh penjuru Tatar Pasundan, hingga Nusantara ini. Tentunya dengan tidak berbuat ‘ulah’ pada kelompok yang berbeda agama (Hindu, Buddha, Katolik, Protestan, Konghucu), keyakinan (Sunda Wiwitan, Madrais, Perjalanan), keagamaan (Muhammadiyah, Persis, Nu, Al-Irsyad, Jama’ah Tablig). Upaya mengislamkan apalagi tak masuk kategori jatidiri Sunda.
Ingat, rumusan identitas Sunda selalu akan berubah dan bahkan akan saling bertentangan karena titik tolaknya pada hal-hal eksternal belaka. Padahal hal-hal eksternal muncul dari kedalaman internal.
Rupanya, kekhawatiran Jakob Sumardjo dalam tulisan “Mencari Identitas Sunda” sangatlah beralasan. Pasalnya, pola hubungan ini kerap searah. Apalagi wilayah ketidaksadaran kolektif (arketife) maupun personal malah semakin terkubur sekaligus jauh dari kehidupan keseharian masyarakat Priangan. Mengerikan bukan?
Kendati, Jakob menegaskan dengan adanya sistem hubungannya secara berulang menunjukan salah satu identitas kesundaannya. Cukupkah berhenti pada pola ini? Apalagi penduduk Tanah Sunda ini acap kali dikenal dengan sebutan ramah (someah) terhadap segala bentuk perbedaan.
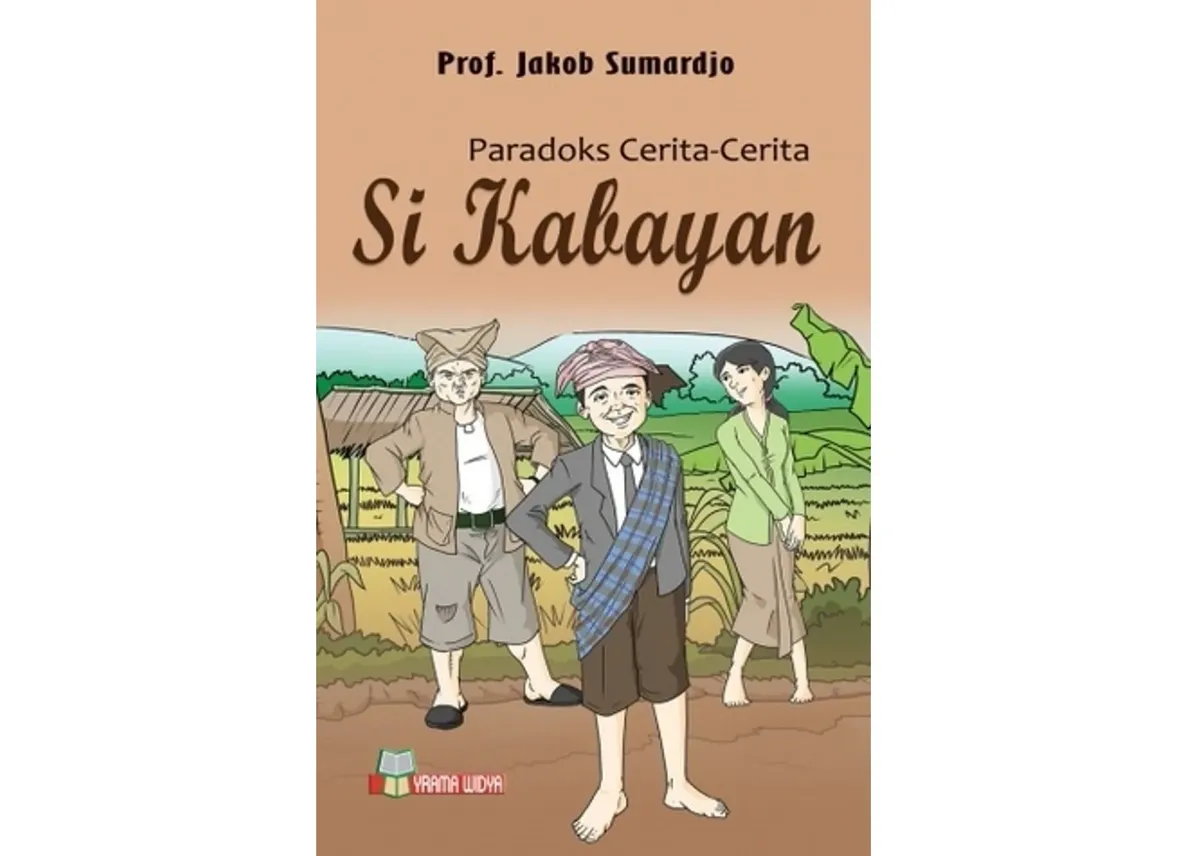
“Ngeunteung” ka Si Kabayan
Lemah-lembutnya tutur bahasa Sunda pertanda kebudayaan beradab. Meski ada yang terkesan vulgar, cawokah, dan penuh jenaka mengisyaratkan rahayat Sunda memang terbentuk oleh watak beragam tersebut. Tengok saja, sosok si Kabayan yang sering dicitrakan urang Sunda. Pasalnya, sosok unik dan beragama dalam cerita folklore. Singkatnya, berbeda wataknya (lepas, cerdas, jenaka, tidak ambisius) saat bercerita dengan orang lain.
Sikap dan kepribadian ini ia praktiknya dalam kehidupan sehari-hari. Kala ia mempunyai keinginan (hanyang ngusep lauk) cukuplah memancing. Saat menang satu ikan berakhirlah ngusepnya. Prinsip ini sangat kuat dipegang Si Kabayan.
Walaupun mendapat caci, maki dari Si Iteng dan Abahnya. Uniknya, kisah-kisah si Kabayan selalu ‘diidentikan’ dengan (ajaran) Islam terutama dalam homor Lebe, marebot, santri dan puasa seperti yang ditulis oleh Moch. Fakhruroji. Perilaku orang-orang yang taat menjalankan ajaran Islam. (Asep S. Muhtadi, 2008)
Sosoknya seakan tak pernah mati, karena mampu “minda rupa” atau berganti peran secara eksistensial. Menyesuaikan diri dengan perkembangan horizon masyarakat Sunda yang kian kompleks. Ya bisa mancala putera, mancala puteri – dalam artian mampu meragamkan pribadi –menjadi sesosok manusia multi-fungsi yang mengasyikkan, menghibur dan menuntun, tulis Sukron Abdilah, Pegiat Sunda dan Kearifan Lokal (Kompas Jabar, Anjungan, 23 Juni 2007).
Inilah wajah Islam dengan citra rasa lokal. Kemanunggalan Sunda-Islam itu terpatri dalam Musyawarah Masyarakat Sunda II (1967). Islam hadir bukan hanya sebagai ajaran yang menata hubungan antara manusia dengan Allah, justru meresap dalam khazanah budaya dan menyatu dalam kehidupan sehari-hari di tengah masyarakat.
Saat Islam bersentuhan dengan kearifan lokal, lahirlah wajah Islam yang lembut, ramah, santun, toleran, damai dan membumi. Dengan demikian, jadi diri Ki Sunda (Islam lokal) ini haruslah dilafalkan dalam satu tarikan nafas, tanpa memperhatikan perbedaan.
Inilah bukti Islam tidak menghapus tradisi, melainkan menyapa dan memperkaya budaya lokal dengan nilai-nilai tauhid, kasih sayang, dan keadilan. Dengan citra rasa lokal, Islam menjadi agama yang mudah diterima, tidak kaku, dan selalu relevan dengan segala perubahan zaman. (*)