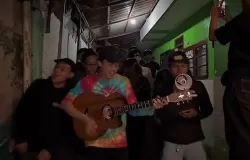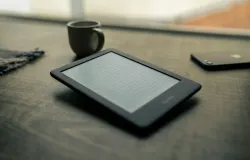Saat ini, masyarakat Indonesia dinilai semakin kritis terhadap kebijakan publik. Aspirasi dan kritik tidak hanya disampaikan lewat forum formal seperti audiensi, tetapi juga semakin deras melalui media sosial. Twitter, Instagram, Facebook, hingga TikTok menjadi kanal baru bagi masyarakat untuk menyuarakan pendapat, mengekspresikan kekecewaan, atau bahkan menggagas solusi alternatif.
Namun, di sisi lain, komunikasi pejabat publik kerap menjadi sorotan karena dinilai kurang hati-hati, minim empati, bahkan kadang kontraproduktif. Kontras inilah yang membuat sinergi antara advokasi kebijakan dan komunikasi pejabat publik menjadi semakin penting untuk diperhatikan.
Sejatinya, advokasi kebijakan adalah jembatan yang menghubungkan aspirasi masyarakat dengan kebijakan pemerintah. Advokasi tidak hanya berarti menyuarakan kepentingan kelompok tertentu, melainkan juga memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada publik, efektif, dan berkelanjutan. Namun, dalam praktiknya, advokasi kebijakan di birokrasi Indonesia masih terbatas, terutama di kalangan analis kebijakan.
Sering kali advokasi hanya diwujudkan dalam bentuk dokumen tertulis, seperti policy brief atau policy paper. Produk-produk ini memang penting, tetapi persoalan muncul ketika dokumen tersebut berhenti di meja birokrasi, tidak sampai ke pengambil keputusan, apalagi ke ranah implementasi.
Padahal, advokasi kebijakan akan lebih efektif jika dikombinasikan dengan pendekatan lisan, baik formal maupun informal. Forum rapat, focus group discussion (FGD), seminar publik, hingga diskusi santai dapat menjadi ruang advokasi yang memungkinkan interaksi langsung dan saling tukar argumen.
Lebih jauh, advokasi kebijakan seharusnya dimulai sejak isu kebijakan masih berupa wacana. Artikel di media massa, tulisan opini, hingga unggahan di media sosial dapat menjadi instrumen advokasi yang memantik diskusi publik. Dalam banyak kasus, tekanan publik yang konsisten justru memaksa pemerintah untuk mengubah arah kebijakannya.
Namun, advokasi tidak bisa berdiri sendiri. Gagasan sehebat apa pun akan kehilangan daya pengaruh jika tidak didukung dengan komunikasi publik yang efektif. Sayangnya, di Indonesia, komunikasi pejabat publik kerap menjadi titik lemah. Pesan yang disampaikan sering kali tidak terstruktur, kurang empati, atau bahkan menyinggung masyarakat. Akibatnya, aspirasi yang sebenarnya bisa dikelola menjadi energi positif malah berubah menjadi kontroversi dan perlawanan.
Di sinilah titik temu antara advokasi dan komunikasi. Advokasi menyiapkan isu, data, serta argumen yang kuat. Sementara komunikasi pejabat publik memastikan pesan itu disampaikan dengan jelas, hati-hati, penuh empati, dan dapat diterima masyarakat. Sinergi keduanya bukan hanya soal strategi, tetapi juga soal legitimasi: masyarakat akan percaya pada kebijakan yang dilahirkan melalui proses terbuka, partisipatif, dan dikomunikasikan dengan baik.
Komunikasi Pejabat Publik
Komunikasi pejabat publik di Indonesia saat ini dinilai masih belum matang. Fenomena “murah bicara” para pejabat dalam menyampaikan pendapat kerap menimbulkan kontroversi, bahkan sampai memicu kemarahan publik. Padahal, setiap kata pejabat publik bukan sekadar opini pribadi, melainkan representasi negara.
Sejarah menunjukkan bahwa pejabat publik pada masa lalu cenderung berhati-hati dalam berkomunikasi. Banyak yang bahkan terkesan “gagap” ketika berbicara di depan publik karena menyadari bahwa setiap kata yang diucapkan adalah sebuah tanggung jawab. Namun, di era digital saat ini, kehati-hatian itu sering diabaikan.
Kasus Ahmad Sahroni, mantan anggota DPR RI, menjadi contoh nyata. Ia menuai kontroversi karena menyebut masyarakat yang menuntut pembubaran DPR sebagai “tolol”. Pernyataan tersebut tidak hanya memicu kemarahan publik, tetapi juga memperburuk citra DPR sebagai lembaga yang seharusnya merepresentasikan suara rakyat. Meski klarifikasi disampaikan, kerusakan reputasi sudah terjadi.
Contoh lain adalah sejumlah pernyataan pejabat terkait kebijakan bansos, kenaikan harga BBM, hingga isu pendidikan. Alih-alih meredam keresahan, pernyataan yang keluar justru menambah bara di masyarakat karena terkesan normatif, arogan, atau tidak memahami penderitaan rakyat. Di era keterbukaan informasi, kegagalan komunikasi semacam ini bisa berlipat ganda dampaknya karena disebarluaskan, diparodikan, dan dijadikan bahan kritik di media sosial.

Di sisi lain, masyarakat Indonesia kini semakin kritis dan cerdas. Media sosial menjadi ruang advokasi modern di mana petisi, kampanye, hingga simbol-simbol gerakan dimunculkan. Dari isu lingkungan, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan fiskal, masyarakat aktif bersuara.
Kekuatan kolektif masyarakat terlihat dalam berbagai gerakan digital. Misalnya, penolakan terhadap revisi UU KPK, kritik terhadap kenaikan iuran BPJS, hingga tuntutan transparansi dalam pembangunan ibu kota baru. Semua ini menunjukkan bahwa publik tidak lagi pasif, melainkan berani bersuara dan memanfaatkan teknologi untuk memperkuat posisi mereka dalam arena kebijakan.
Belajar dari Nepal
Pengalaman di Nepal memperlihatkan bagaimana advokasi bisa menemukan bentuk baru. Generasi muda di negara tersebut membentuk server Discord bernama Youth Against Corruption untuk menggelar debat publik, polling, hingga pemilihan calon pemimpin. Dari sana lahir nama Sushila Karki yang akhirnya benar-benar menjadi perdana menteri sementara. Fenomena ini menunjukkan bahwa masyarakat bisa mendorong perubahan politik melalui jalur nonkonvensional.
Tidak hanya Nepal, beberapa negara lain juga memberikan pelajaran berharga. Di Taiwan, misalnya, platform digital seperti vTaiwan memungkinkan warga untuk memberi masukan langsung terhadap rancangan kebijakan. Di Estonia, sistem e-governance memungkinkan partisipasi publik yang luas dalam proses pengambilan keputusan. Indonesia dapat belajar dari pengalaman ini untuk membangun kanal advokasi modern yang inklusif dan terpercaya.
Meski demikian, advokasi kebijakan di Indonesia menghadapi sejumlah tantangan. Pertama, keterbatasan kapasitas analis kebijakan dan lembaga riset dalam membangun argumen yang kuat, berbasis data, dan komunikatif. Kedua, kultur birokrasi yang masih hierarkis membuat masukan dari bawah sering terhambat. Ketiga, belum optimalnya penggunaan teknologi digital dalam membuka kanal partisipasi publik.
Selain itu, pejabat publik sering kali lebih fokus pada pencitraan jangka pendek daripada komunikasi substantif. Mereka lebih sibuk menjaga elektabilitas daripada menjelaskan rasionalitas kebijakan secara utuh. Kondisi ini memperlebar jarak antara pemerintah dan masyarakat.
Menjawab berbagai tantangan dalam advokasi kebijakan dan komunikasi publik tidak bisa dilakukan secara parsial. Perlu ada langkah strategis yang bersifat menyeluruh, sehingga menghasilkan pemerintahan yang lebih terbuka dan partisipatif. Salah satu kunci penting adalah memperkuat kapasitas advokasi di dalam birokrasi. Para analis kebijakan, misalnya, tidak cukup hanya mahir menyusun policy brief atau rekomendasi tertulis. Mereka juga harus dibekali kemampuan komunikasi publik, keterampilan berinteraksi dengan media, serta kecakapan bernegosiasi. Dengan begitu, produk advokasi tidak berhenti sebagai dokumen statis, melainkan bisa bergerak dan memengaruhi ruang pengambilan keputusan.
Di sisi lain, pemerintah juga perlu membangun kanal komunikasi dua arah yang memungkinkan publik terlibat lebih aktif. Inspirasi bisa diambil dari praktik di Taiwan maupun Estonia, di mana ruang dialog digital dikembangkan secara transparan dan kredibel. Melalui kanal ini, masyarakat bukan hanya menjadi penonton, melainkan juga aktor yang dapat memberikan masukan, kritik, maupun dukungan terhadap setiap kebijakan yang sedang dirancang.
Tidak kalah penting, pejabat publik harus belajar etika komunikasi. Di era keterbukaan informasi, setiap kata yang keluar memiliki resonansi luas. Karena itu, pelatihan komunikasi krisis, manajemen media, dan komunikasi empatik seharusnya menjadi bagian dari agenda pembinaan aparatur negara. Dengan komunikasi yang lebih hati-hati dan berempati, pejabat publik bisa meredam potensi konflik sekaligus memperkuat kepercayaan masyarakat.
Langkah strategis berikutnya adalah mengintegrasikan advokasi masyarakat sipil ke dalam proses kebijakan. Pemerintah perlu mengubah cara pandang terhadap LSM, komunitas, maupun gerakan digital: bukan sebagai ancaman, melainkan sebagai mitra yang memperkaya perspektif. Sinergi ini akan membuka ruang dialog yang lebih sehat, sekaligus memperkuat legitimasi kebijakan yang dihasilkan.
Akhirnya, semua upaya tersebut harus ditopang oleh prinsip transparansi. Semakin terbuka pemerintah dalam menyajikan data dan informasi, semakin besar pula peluang publik untuk percaya dan mendukung kebijakan. Transparansi bukan hanya soal membagikan informasi, tetapi juga tentang memberikan ruang bagi publik untuk menilai, mengkritisi, dan ikut mengawal jalannya kebijakan.
Dengan kombinasi strategi ini, jalan menuju pemerintahan partisipatif bukanlah sebuah utopia, melainkan langkah nyata yang bisa ditempuh. Pemerintahan yang partisipatif tidak hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan bahwa kebijakan yang lahir benar-benar berpihak pada rakyat, dijalankan dengan legitimasi, dan berakar kuat pada aspirasi masyarakat.
Baca Juga: Cara Baru ASN Naik Kelas: Belajar Diakui, Karier pun Melaju
Advokasi kebijakan dan komunikasi publik bukanlah dua hal yang berdiri sendiri. Keduanya adalah pilar yang menopang demokrasi partisipatif. Advokasi memastikan kebijakan berangkat dari aspirasi rakyat, sementara komunikasi publik menjamin kebijakan itu dipahami, diterima, dan dijalankan dengan legitimasi.
Masyarakat harus terus kritis dan berani menyuarakan aspirasi, sementara pejabat publik dituntut untuk lebih bijak, hati-hati, dan empatik dalam menyampaikan pesan. Sinergi ini bukan hanya memperkuat demokrasi, tetapi juga memastikan lahirnya pemerintahan yang benar-benar partisipatif, inklusif, dan berkeadilan. (*)