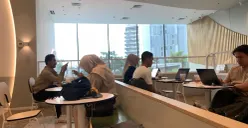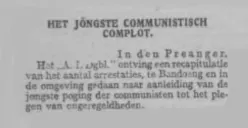Baru saja Bujangga Manik pulang dari ziarah panjangnya di sepanjang Pulau Jawa. Ia rindu untuk menemui ibundanya di kerajaan. Berita kedatangannya dengan cepat menyebar. Juga sampai ke Putri Ajung Larang, putri cantik yang berharap Bujangga Manik akan meminangnya. Ia segera menyiapkan persembahan untuk pujaan yang diangankannya.
Persembahan itu berupa aneka buahtangan yang memancarkan harapan asmara. Hantarannya dibawa oleh si Jompong Larang, isinya berupa: sirih, kapurbakar, pinang, bedak putih, cendana, bunga resa, kasturi, majakani, jaksi, kamisadi, kemenyan, wijen, akarwangi, agur-agur, parfum dari seberang, kain satin, sabuk bermotif wayang, dan keris baja (J Noorduyn dan A Teeuw, Tiga Pesona Sunda Kuna, 2006).
Satu di antara persembahan Putri Ajung Larang itu adalah jaksi (jaksi serta kamisadi, jaksi pandan dan kemenyan). Bila membandingkan dengan banten, sesajian persembahan dalam laku puja saat ini di Desa Peliatan, Kecamatan Ubud, Bali, terdapat bunga pandan pudak, daun pandanharum, dan kembang rampe.
Pandan pudak atau pandang lengis ini menurut beberapa pendapat, adalah nama lain untuk pandan jaksi. Jadi, sangat mungkin, yang disertakan dalam persembahan Putri Ajung Larang kepada Bujangga Manik itu adalah bunganya, bunga jaksi.
Menurut K Heyne (1987) pandan jaksi itu Pandanus tectorius SOL. var., dalam sumber lain ditulis Pandanus tectorius Sol, ex Park. Namun, karena masih adanya beberapa pendapat tentang pandan ini, maka otoritas keilmuan seharusnya dapat menetapkan padanan nama-nama setempat itu ke dalam nama ilmiahnya.
Misalnya, apakah Pandanus tectorius SOL. var. itu sama dengan pandan darat atau pandan laut, pandan temen, pandan jaksi, jaksi, jaksi jalu, pandan samak, atau pandak pudak? Ada yang berpendapat bahwa pandan jaksi itu sama dengan pandan cangkuang. Namun, menurut K Heyne (1987), cangkuang (Pandanus furcatus Roxb.) mempunyai nama lain di Tatar Sunda adalah Harashas dan Solenat.
Pandan-pandanan ini tersebar menyeluruh di berbagai belahan bumi. Marga Pandanus memiliki 700 jenis, dan 16 jenis di antaranya terdapat di Pulau Jawa. Dari 16 jenis itu, pandan samak (Pandanus odoratissimus L.f.) atau disebut juga pandan cucuk, pandan putih, pandan kapur, merupakan jenis pandan yang sudah lama dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, seperti untuk bumbu, pengobatan, tikar, topi, persembahan dalam ritual keagamaan, dan lain-lain.
Jenis pandan yang tumbuh dengan baik di daerah pegunungan rendah di Jawa Barat, tersebar hingga di ketinggian +800 m dpl, adalah pandan jaksi. Walau daunnya lebih pendek, pandan jenis ini daunnya sangat disukai para pengrajin, karena lebih lentur, sehingga mudah dianyam.
Nama pandan jaksi abadi dalam nama geografis, seperti: Cijaksi, yang berada di Desa Licin, Kecamatan Cimalaka, Kabupaten Sumedang.
Di Kabupaten Tasikmalaya ada Kampung Cijaksi dan Kampung Jaksi yang berada di Desa Tanjungbarang, Kecamatan Cikatomas. Masih di Kabupaten Tasikmalaya, ada Kampung Cijaksi di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud, dan Kampung Jaksi di Desa Mandalawangi, Kecamatan Salopa. Di Kabupaten Sukabumi ada Kampung Cijaksi di Desa Sumberjaya, Kecamatan Tegalbuleud. Dan di Kabupaten Garut, ada Babakan Jaksi di Desa Jati, Kecamatan Tarogong Kaler. Sedangkan di Kabupaten Lebak, Provinsi Banten, ada Kampung Leuwi Jaksi di Kecamatan Cimarga. Setidaknya di kawasan itulah pada masa lalu pernah terdapat pandan jaksi, sehingga menjadi ciri bumi.
Pengrajin anyaman pandan yang terkenal adalah di Rajapolah, Tasikmalaya (Provinsi Jawa Barat) dan di Tangerang (sekarang Provinsi Banten).
Antara tahun 1918 sampai tahun 1925, tikar pandan dan kerajinan lainnya telah dikirim ke berbagai daerah, seperti ke: Ambon, Bali, Bawean, Belawan, Bengkulu, Belitung, Jakarta, Jambi, Kalimantan Barat, Kalimantan Timur, Kepulauan Anambas, Lampung, Lhokseumawe, Lombok, Manado, Natuna Selatan, Padang, Palembang, Pantai Timur Sumatra, Pekanbaru, Riau, Semarang, Sibolga, Sigli, Sumatra Barat, Tapanuli, Timor, dan Ujung Pandang. Bahkan, sampai tahun 1925, dilaporkan bahwa Tangerang merupakan salah satu pusat produksi kerajinan pandan di Nusantara, yang produknya dipasarkan ke Amerika Serikat, Australia, Belanda, Italia, Perancis, dan Singapura.
Di Rajapolah, Kabupaten Tasikmalaya, kerajinan anyaman mulai berkembang pesat sejak tahun 1911, yang telah dirintis sebelum itu oleh haji Yasin dan para santrinya (S Dloyana Kusumah, 1985). Yang populer saat itu adalah topi dan samak, tikar pandan.
Hasilnya, topi-topi dan kerajinan lainnya disimpan di bufet yang ada di stasiun kereta api Tasikmalaya. Usaha kerajinan pandan haji Yasin berkembang pesat setelah mendapatkan pesanan dalam jumlah besar dari Tuan Vercizonk.
Popularitas topi kepanduan, tikar, dompet, dll dari pandan jaksi, menjadikan pengusaha dan para pengrajinnya mendapatkan penghasilan yang layak. Ada kampung tempat para pengrajin tinggal, yang kemudian dijuluki Kampung Legok Ringgit, karena kemakmuran warganya, dan toponim itu abadi sampai saat ini.
Menurut K Heyne (1927), pandan jaksi itu daunnya lebih pendek. Pada usia tiga tahun, panjang daunnya kira-kira 75 cm, dan mulai dipotong. Pada tahun kelima, panjang daunnya mencapai 125 cm. Di Kabupaten Tasikmalaya, seperti ditulis K Heyne, pandan jaksi banyak ditanam di lahan pinggir rel kereta api. Ternyata, setelah satu abad lamanya, budidaya pandan jaksi masih ditanam di lahan PT KAI, seperti di Desa Manggungsari, Kecamatan Rajapolah, Tasikmalaya.
Pandan jaksi sangat penting dalam kehidupan manusia, digunakan dalam berbagai keperluan, untuk ritual, pengobatan, isi persembahan, sejak zaman kerajaan hingga kini,bahkan hingga nanti saat mati. (*)