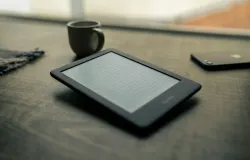AYOBANDUNG.ID - Hari ini, peuyeum makin jarang tampak di warung atau terminal. Di pasar tradisional, jumlah penjualnya menyusut. Sementara di benak generasi muda, nama peuyeum kalah gaul dibanding boba atau mozarella. Padahal, camilan hasil fermentasi singkong ini bukan makanan sembarangan. Peuyeum punya sejarah yang membentang jauh sebelum Indonesia berdiri sebagai negara. Ia tumbuh bersama kebudayaan Sunda, mengakar dalam kehidupan sosial, bahkan tercatat dalam peristiwa-peristiwa penting sepanjang sejarah Tatar Priangan.
Peuyeum, atau tapai singkong, merupakan pangan fermentasi tradisional berbahan dasar singkong yang dikenal luas sebagai “Peuyeum Bandung”—meski asal-muasalnya melampaui batas administratif kota itu sendiri. Nama "peuyeum" berasal dari kata meuyeum dalam bahasa Sunda, yang berarti memeram atau mematangkan. Nama ini bukan sekadar istilah dapur; ia merekam pengetahuan leluhur tentang teknik penyimpanan, pelestarian, dan pengolahan bahan makanan sebelum teknologi pendingin dan pengawet buatan dikenal.
Dari Ladang Dalem Bandung hingga Sentra Citatah
Jejak historis peuyeum bisa dilacak hingga masa pemerintahan R.A.A. Martanagara (1893–1918), Bupati Bandung yang dikenal sebagai tokoh modernisasi pertanian. Dosen Program Studi Ilmu dan Teknologi Pangan Universitas Bakrie, Laras Cempaka, dalam risalahnya di Journal of Ethnic Foods (2021) mengurai bahwa pada masa itu, singkong mulai ditanam secara luas di wilayah Priangan bukan untuk peuyeum, melainkan untuk diolah menjadi aci (tepung tapioka) yang diekspor ke Belanda.
Tapi, di kalangan rakyat, singkong diolah menjadi peuyeum untuk konsumsi sehari-hari. Praktik ini menyebar dari kampung ke kampung, menjadi bagian dari cara hidup orang Sunda—bukan hanya karena nilai gizinya, tetapi juga karena fungsinya sebagai pangan simpan yang murah, praktis, dan mengenyangkan.
Baca Juga: Jejak Sejarah Dodol Garut, Warisan Kuliner Tradisional Sejak Zaman Kolonial
Seiring waktu, sejumlah wilayah berkembang menjadi sentra produksi peuyeum. Desa Citatah di Kabupaten Bandung Barat, misalnya, sudah dikenal sejak tahun 1980 sebagai penghasil peuyeum unggulan. Warga setempat menyebut bahwa peuyeum pertama kali diperkenalkan oleh seorang perantau dari Bendul, Purwakarta, yang mencari nafkah di tanah Citatah.
Di kemudian hari, daerah seperti Cimenyan juga menjadi titik penting dalam distribusi peuyeum, menjual hasil fermentasi mereka ke berbagai pelosok Jawa Barat.
Penyebaran peuyeum juga tercermin dalam budaya lisan. Dalam pupuh Sunda—sastra tradisional dalam bentuk puisi—terdapat bait yang menyebut “pupuh magatru peuyeum sampeu”, yang mengacu pada pembungkus peuyeum dari daun jati. Kalimat sederhana itu membuktikan bahwa peuyeum bukan hanya makanan, tetapi sudah masuk ke ranah simbolik dan estetika masyarakat Sunda.

Santapan Pejuang, Simbol Solidaritas
Peuyeum juga punya tempat dalam sejarah perjuangan Indonesia. Pada masa kolonial dan revolusi fisik, para pemuda yang tergabung dalam Tentara Rakyat membawa bekal peuyeum ketika bergerilya. Selain tahan lama, peuyeum ringan dibawa dan cukup mengenyangkan. Dalam kondisi terdesak, ia menjadi sumber energi sekaligus pengingat rumah.
Tapi, ada pula sisi yang kontras. Di kalangan tentara dan aktivis saat itu, peuyeum sempat dijadikan sindiran. Mereka menyebut pemuda-pemuda yang lemah semangat sebagai "peuyeum"—lembek dan tak berdaya menghadapi musuh.
Kendati demikian, makna solidaritas tetap lebih dominan. Makan peuyeum bersama menjadi bentuk kebersamaan. Bahkan hingga kini, bagi perantau Sunda, menerima peuyeum dari sesama dianggap sebagai tanda persaudaraan. Dalam satu potong peuyeum, tersimpan semacam "rasa pulang". Ia bukan sekadar oleh-oleh, tapi pengikat batin.
Baca Juga: Peuyeum Bandung Sudah Jadi Barang Langka, Padahal Dulu Sangat Berjaya
Seperti ditulis Laras, "makanan tidak memiliki makna jika tidak dilihat dalam konteks budaya atau jaringan interaksi sosialnya." Peuyeum, dalam hal ini, adalah medium untuk memperkuat ikatan sosial. Ia menjadi pengingat identitas kolektif, penghubung antara individu dan komunitas, bahkan menjadi simbol rumah bagi mereka yang berada jauh dari tanah kelahiran.
Warisan Fermentasi, Sampai Kapan Bertahan?
Walaupun tidak dibakukan dalam laboratorium, proses pembuatan peuyeum di masyarakat sebenarnya mengandung prinsip ilmiah yang kompleks. Singkong dikupas, dicuci, lalu direbus setengah matang agar teksturnya lunak. Setelah dikeringkan, singkong diberi ragi, starter fermentasi yang terdiri dari kombinasi jamur, ragi, dan bakteri. Ia lalu dibungkus rapat dan didiamkan selama 48 hingga 72 jam.
Proses pembuatan peuyeum terjadi tanpa perlu udara. Singkong yang sudah dikukus lalu dibungkus dan dibiarkan selama beberapa hari. Dalam keheningan itu, mikroorganisme alami mulai bekerja: membuat singkong jadi lembut, manis, sedikit asam, dan beraroma khas.
Rasanya pun berubah perlahan. Awalnya hanya manis, lalu muncul rasa hangat seperti tape, dengan aroma yang tajam tapi menggoda. Teksturnya juga ikut berubah jadi lebih lembek, tapi tidak hancur.
Secara garis besar, ada empat tahap yang terjadi selama fermentasi: pertama, pati dari singkong dipecah menjadi gula; kedua, gula diubah menjadi alkohol; ketiga, alkohol ini berubah jadi asam; dan keempat, terbentuklah ester yang memberi cita rasa khas peuyeum.
Semua proses ini sudah dikenal sejak lama. Masyarakat Sunda dulu tidak butuh laboratorium untuk tahu kapan peuyeum sudah jadi. Mereka hanya perlu mencium baunya, merasakan teksturnya, atau sekadar mengandalkan pengalaman yang diwariskan dari ibu ke anak, dari generasi ke generasi.
Ironisnya, warisan fermentasi tradisi itu kini dihadapkan pada situasi kritis ihwal senjakala eksistensinya. Zaman berubah, selera ikut berpindah: seolah ada ketegangan antara tradisi dan modernisasi yang sukut ditengahi. Peyeum masih dibuat dengan fermentasi ala warisan tradisi, tapi sampai kapan dia akan awet dalam gerakan zaman?