"Tau ga ? Tadi aing ketinggalan PR, jadi Weh meunang hukuman"
" Sini atuh maneh teh, dudukna tong tebih-tebih teuing"
" Si eta mah emang kitu, meni embung di bawa ke Mall teh"
" Si gue mah tadi jajan cilok Weh"
Beberapa percakapan tadi pernah saya dengar saat bertemu dengan sekumpulan anak-anak sekolah di angkutan umum.
Terdengar lucu dan sedikit menggemaskan, sekaligus miris dan menyedihkan. Penggunaan bahasa Sunda yang tidak hanya kasar tapi juga dicampur penggunaannya dengan bahasa lain. Tapi mungkin bagi mereka itu adalah bagian dari trend di kalangan anak muda.
Di Kota Bandung sendiri, terlebih di lingkungan yang saya tempati, penggunaan bahasa Sunda memang sudah semakin sedikit terdengar terlebih di kalangan anak-anak dan remaja.
Sebagian dari mereka seringkali berkomunikasi dengan bahasa nasional yaitu Indonesia. Adapun beberapa anak yang masih berbincang menggunakan bahasa Sunda seringkali kata yang terucap adalah bahasa kasar. Belum lagi kebiasaan menambahkan imbuhan "anjing" di setiap akhir pengucapan kalimat.
Bahasa Sunda adalah bahasa ibu yang merepresentasikan masyarakat Sunda. Bahasa Sunda adalah bagian yang tak lepas dari perbincangan sehari-hari. Hanya saja hari ini bahasa Sunda sudah menjadi bahasa yang asing ditelinga anak-anak sekolah.
Masalah penggunaan bahasa Sunda tidak hanya berada di tingkat lingkungan keluarga tapi juga menjadi polemik sendiri bagi dunia pendidikan.
Dulu sebelum ramai media sosial, ketika saya duduk dibangku sekolah dasar, bahasa Sunda seringkali hanya diajarkan ala kadarnya. Kami hanya menulis ulang catatan yang ada dalam buku paket milik guru yang kemudian dituliskan oleh sekretaris kelas di papan tulis.
Adapun jika guru yang bersangkutan menjelaskan biasanya hanya seputar pengenalan budaya Sunda perihal Pupuh, dongeng khas Sunda era kerajaan, jaipong atau beberapa alat kesenian yang ada di tatar tanah Sunda.
Sisi komunikasi yang bisa menjalin interaksi berbahasa Sunda hampir tidak ada. Bahkan guru bahasa Sunda yang menjelaskan materi juga tetap menggunakan bahasa Indonesia.
Kegiatan seperti ini berlanjut hingga tingkat SMP dan SMA, mengulang materi yang sama dan pola komunikasi yang sama.
Bahkan ketika masa pendidikan saya cukup tertarik dengan aksara Sunda, hanya saja kajian ini biasanya hanya diulas sepintas dari kurikulum. Guru hanya mengajarkan konsonan saja tanpa merefleksikannya lewat tulisan dari huruf menjadi kata, kata menjadi kalimat.
Tidak adanya media yang mendukung membuat ketertarikan saya terhadap aksara Sunda memudar. Bahkan seiring beranjaknya usia saya lupa begitu saja. Hanya sesekali kadang teringat jika melihat tulisan aksara Sunda yang ditulis di bawah marka penunjuk nama jalan yang ada di Kota Bandung.
Saya sendiri pun belajar bahasa Sunda "lemes" tidak berangkat dari interaksi keluarga tapi dari teman yang saya kenal berasal dari kota Tasikmalaya.
Saat itu saya bekerja di apotek sekitaran Kota Bandung, ada seorang pria Sunda yang membeli obat dengan bahasa Sunda yang lembut, yang sudah jarang terdengar di telinga saya dan sungguh mengejutkan masih bisa dilakukan oleh anak muda.
"Teh punten, tos dua dinten kapengker Abi teh panas tiris. Kawitna mah di panangan Abi teh aya bentol teras ku Abi teh digisik da teu kiat ku ateulna. Eh malah janten lecet teras ieu aya nanahan. Dupi obatna nganggo naon nya teh ?"
Begitulah kiranya bahasa Sunda "lemes" yang keluar dari mulutnya. Saya paham dengan maksud yang ditujukan pria itu tapi ketika hendak membalas pertanyaan dan menjelaskan edukasi obat dengan bahasa Sunda yang lemes, saya sedikit mengalami kesulitan. Sampai pada akhirnya saya juga banyak belajar bahasa Sunda lemes darinya.
Rasanya beberapa bahasa Sunda "lemes" memang lebih akrab bagi mereka yang tinggal jauh dari Kota Bandung, misalnya saja Tasik, Garut, Ciamis dan beberapa daerah yang masih terdapat pesantren. Dalam kesehariannya mereka memang masih memprioritaskan penggunaan bahasa "lemes" dalam berkomunikasi.
Upaya Majalah Mangle dalam Melestarikan Budaya Sunda

Dulu saat sekolah saya sering mendengar nama majalah ini, hanya saja saya belum pernah melihat secara langsung bagaimana bentuk fisiknya.
Di tingkat lingkungan keluarga tidak pernah ada yang mengenalkan majalah ini dan saat kecil saya tidak tahu harus mencari majalah tersebut di mana. Beberapa nama toko buku di Bandung sangat asing bagi saya.
Dulu sesekali saya pernah berkunjung bersama bapak ke area alun-alun kota Bandung tapi saya sedikit lupa dengan nama toko bukunya.
Adapun kunjungan ke toko buku bukan membeli buku untuk dibaca tapi sekedar membeli untuk tugas yang diberikan guru di sekolah.
Majalah Mangle sendiri merupakan majalah budaya Sunda tertua di Jawa Barat yang lahir pada tahun 1957 di Bogor. Kemudian majalah Mangle memindahkan pusat redaksinya ke Bandung karena segala kegiatan pemerintahan dan budaya Sunda berpusat di Kota Bandung sebagai Ibu Kota Jawa Barat.
Belum banyak ditemukan penelitian mengenai majalah Mangle, hanya ada satu yang menarik bagi saya yang pernah ditulis oleh Roni Tobroni & Nunung Sanusi.
Dalam penelitiannya yang berjudul Eksistensi Majalah Berbahasa Sunda Mangle di Era Revolusi Industri 4.0 (2020) menuliskan fenomena beberapa media massa berbahasa Sunda yang sudah punah di Jawa Barat, diantaranya : Sipatahunan, Cupumanik, dan Koran Sunda yang juga tutup dan tidak bertahan lama di pasaran.
Menurut sudut pandang peneliti, majalah Mangle bukan hanya sekedar media massa tapi sebagai cagar budaya yang selayaknya pemerintah dan masyarakat Sunda harus cintai dan turut ngamumule keberadaan Majalah Mangle.
Berdasarkan hasil kesimpulan penelitian disebutkan bahwa salah satu strategi non-redaksi yang dilakukan oleh Mangle demi mempertahankan eksistensinya adalah dengan menjalin kerjasama dengan instansi, dinas dan kampus juga digitalisasi naskah.
Berdasarkan penelitian ini disebutkan bahwa majalah Mangle terbit dalam bentuk fisik dan dalam bentuk digital, meski saya belum menemukan sumber terbitan versi digitalnya di internet.
Bahkan media sosial yang berhubungan dengan majalah Mangle pun tidak ada. Hanya ada dua postingan yang ada kaitannya dengan majalah Mangle.
Pertama, postingan humas Jabar pada tanggal 25 April 2019 ketika mantan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil meresmikan kantor Majalah Mingguan Basa Sunda Mangle.
Kedua postingan kampus ISBI pada 22 Februari 2025 menampakan sebagian tulisan dari majalah Mangle Edisi 3015 dengan judul " Eco Fashion Style, Pidangan Karya Tina Runtah Baju".
Berdasarkan informasi yang saya temukan mulai dari tanggal 20 Mei 2025 Majalah Mangle resmi dipindahtangankan dan dikelola oleh Universitas Pajajaran.
Rektor UNPAD, Prof. Arief S. Kartasasmita dan Kepala Pusat Budaya Sunda, Prof. Ganjar Kurnia ikut hadir dalam peresmian acara tersebut di kampus UNPAD, Jl. Dipati Ukur No.35 Bandung.
Ketertarikan Prof. Dr. Mikihiro Moriyama tehadap budaya Sunda
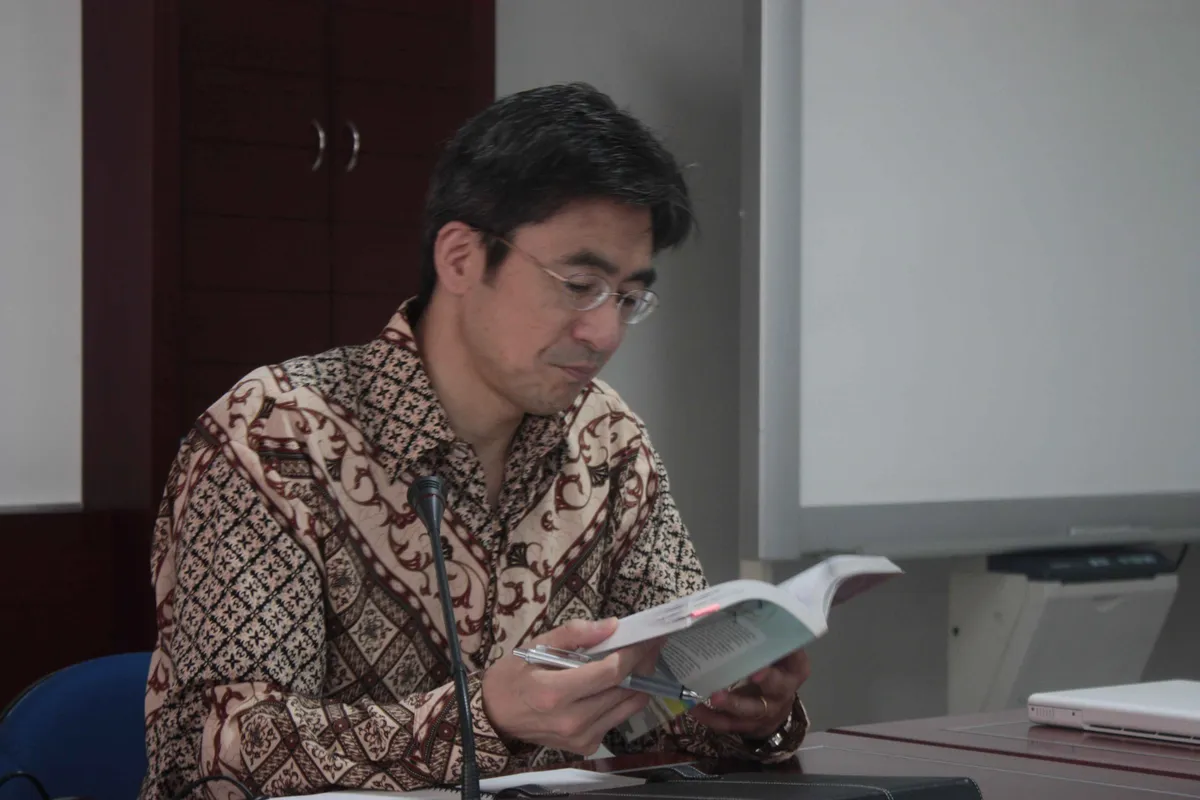
Prof Dr. Mikihiro Moriyama adalah seorang guru besar di Universitas di Nanzan, Jepang. Pria kelahiran 16 September 1960 ini begitu tertarik dengan bahasa Sunda selepas berkenalan dengan Ajip Rosidi seniman Sunda saat bermukim di Jepang. Moriyama amat terkesan terhadap sikap konsisten Ajip Rosidi dalam menggunakan bahasa Sunda meskipun sedang di mancanegara.
Pada tahun 1982-1984 Prof. Moriyama pernah belajar di UNPAD Bandung. Kemudian memperdalam seni Sunda seperti, maenpo, Pupuh, cianjuran, kecapi dan lain-lain di Cikalong kulon Cianjur pada 1984.
Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan oleh Prof. Moriyama, ada keunikan yang ditemukan dari bahasa Sunda. Menurutnya bahasa Sunda tidak bisa lepas dari budayanya. Hal inilah yang menjadi ciri khas orang Sunda dibandingkan dengan etnis lain di Indonesia.
Kecintaannya terhadap budaya Sunda membuat Prof. Moriyama seringkali mengangkat budaya dan bahasa Sunda dalam seminar di mancanegara hingga ke pelosok negeri Afrika seperti negeri Mali. Bahkan budaya dan bahasa Sunda pernah menjadi bahan penelitian disertasinya untuk menyelesaikan program S3.
Selain itu juga Prof. Moriyama pernah memberikan kuliah bahasa Sunda di Leiden Belanda yang dikenal sebagai universitas rujukan keilmuan bahasa Sunda termasyhur di luar negeri.
Dalam sebuah tulisan yang terbit di laman unpad.ac.id, Prof. Moriyama menuturkan bahwa globalisasi justru berpeluang dalam mempopulerkan bahasa Sunda ke kancah global. Baginya hal ini sekaligus memupus anggapan bahwa globalisasi akan menyempitkan eksistensi budaya lokal.
Meski demikian, Moriyama juga berpendapat bahwa salah satu faktor yang bisa menyebabkan bahasa Sunda mendunia adalah jika ada upaya pengajaran yang dilakukan secara kontinyu dan konsisten dari masyarakat suku Sunda sendiri.
Bagi saya kehadiran dan kecintaan Prof. Mikihoro Moriyama terhadap budaya dan bahasa Sunda bisa menjadi pemantik semangat bagi generasi muda untuk turut serta menjaga dan melestarikan budaya bahasa ibu.
Keberadaan Prof. Moriyama juga menjadi pengingat bahwa kita harus senantiasa bangga dan berkontribusi dalam pelestarian budaya dan bahasa Sunda agar identitasnya tidak hilang ditelan masa. (*)