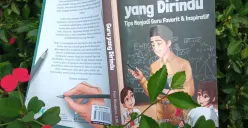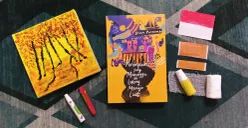Sebelum berpisah dia memandangku sambil berdoa dengan lirih, “Sing cageur bageur, panjang umur, gedé milik, jauh tina balahi. Sing loba nu mikawelas mikaasih, sagala pamaksudan sing tinekanan. Bagja di dunya, jaga salamet di ahérat.”
Rasanya sudah sangat lama aku enggak berjumpa dengannya, seorang nenek yang tinggal di dekat kebun bapak. Aku mengangguk, mata terasa panas, berbalik arah menuju gubug di sebelah atas.
Di Tanah Sunda, doa seperti ini tidak terikat pada ritus atau acara formal. Rapalan khusyu berguman di tengah pergaulan sehari-hari, mengalir di antara pertemuan yang singkat dan perpisahan sederhana. Ia bisa muncul ketika menjenguk orang sakit, kala berpapasan seseorang di pasar, atau ketika melepas tamu dari teras rumah.
Kadang juga sambil lalu, ketika satu sama lain melakukan kebaikan. Doa ini bisa diucapkan dalam suasana bahagia, meskipun sering juga terjadi dalam momen yang mengharukan. Tapi intinya selalu menampakan ketulusan dan menyembunyikan harapan untuk bisa bertemu kembali.
Doa rakyat punya banyak versi. Ada yang memakai ragam bahasa akrab seperti contoh di atas yang singkat dan lugas. Ada juga versi yang lebih panjang dan puitis. Bahkan ada versi campuran Sunda kamalayon yang fleksibel mengikuti lawan bicara. Perbedaan bentuk menunjukkan bahwa doa ini bukanlah formula kaku, melainkan ungkapan rasa yang sejalan dengan situasi dan relasi sosial.
Isi doa mencerminkan harapan sederhana rakyat. Di dalamnya ada permintaan kesehatan (sing cageur bageur), bukan hanya tubuh juga perangai yang baik. Ada cita-cita umur panjang untuk menikmati keberkahan hidup bersama orang-orang terkasih. Ada permohonan rezeki (gedé milik) untuk menunjang hajat hidup dan membantu sesame.
Begitu juga terpanjat permintaan agar dijauhkan dari marabahaya (jauh tina balahi), fisik maupun batin. Kemudian disusul asa agar dikelilingi orang yang berkasih sayang (sing loba nu mikawelas mikaasih), berhadap hidup di jejaring sosial yang hangat dan saling menolong.
Kemudian doa agar semua cita-cita tercapai (sagala pamaksudan sing tinekanan), dan penutup yang menyeimbangkan visi kebahagiaan di dunia dan akhirat.
Secara sosial, doa seperti ini berfungsi sebagai pengikat relasi. Mengucapkannya adalah ekspresi keramahan dan penghormatan. Ia bisa jadi penyambung hati bahkan di tengah situasi yang tegang dan belum akrab, ungkapan rasa cinta dan atensi.
Tidak jarang orang yang baru kenal tetap saling mendoakan saat berpisah, sebuah penanda etik bahwa relasi antarmanusia harus dijaga. Susunannya yang sederhana membuat doa ini inklusif. Semua orang bisa mendaraskannya tanpa harus menghafal teks panjang atau benturan dengan bahasa asing.
Namun di balik kata-kata yang tampak lembut tersebut, tercermin juga potret kehidupan rakyat termasuk isu-isu kesejahteraan yang menyertainya. Kesehatan menjadi doa karena akses layanan medis yang layak belum tersebar merata. Banyak warga menunda berobat karena soal biaya dan jarak.
Begitupun soal harapan memiliki perangai yang baik. Bagaimana mungkin bisa diakses rakyat, jika pendidikan terhambat biaya tinggi, komersialisasi, dan kurikulum percobaan?
Ekonomi yang cukup pun menjadi doa yang abadi, menandakan bahwa banyak keluarga hidup dari penghasilan yang pas-pasan. Rakyat bergantung pada hasil kebun, laba dagang kecil-kecilan, atau upah kerja harian yang tidak menentu. Doa agar terhindar dari bahaya menampilkan wajah kerentanan rakyat terhadap resiko bencana alam, gagal panen, maupun gangguan keamanan.

Di banyak tempat, krisis iklim memperparah ketidakpastian ini. Sementara perlidungan sosial belum mampu menjangkau semua lapisan masyarakat. Kebahagiaan yang dimohonkan bukanlah kemewahan, melainkan ketenteraman hidup dan rasa cukup. Sesuatu yang kini tergerus oleh tekanan kapitalisasi dan modernisasi.
Di tengah kemiskinan struktural, ketimpangan ekonomi, dan konflik yang diperparah krisis iklim, harapan untuk hidup dalam lingkaran kasih sayang terasa makin mustahil. Ketimpangan membuat sebagian orang nekat melakukan kejahatan dari begal, perampokan toko kelontong, hingga kekerasan rumah tangga. Rasa saling percaya terkikis, digantikan curiga dan rasa takut.
Dalam situasi seperti ini, harmoni sosial sulit terbentuk karena setiap orang sibuk bertahan hidup. Akibatnya banyak cita-cita yang tertunda. Seorang anak putus sekolah, usaha kecil terlilit utang pinjaman daring, atau kecemburuan sosial yang memantik kerusuhan penolakan rumah ibadah tertentu.
Doa agar saling mengasihi dan semua tujuan tercapai berubah menjadi sebuah kemewahan yang mahal di tengah realitas hidup yang keras. Harapan akhir rakyat akan hidup yang seimbang baik di dunia maupun akhirat, justru terbentur dengan realitas kekuasaan yang masih saja tidak berpihak.
Di tengah kehidupan kiwari, doa rakyat Sunda ini menjadi pengingat bahwa religiusitas tidak selalu lahir dari ritus besar atau struktur bahasa formal. Ia bisa hadir dalam nafas sehari-hari yang menyatukan kearifan lokal dan rasa kemanusiaan.
Selama masih dirapalkan, doa bukan hanya ibadah tapi juga bentuk solidaritas emosional. Lebih jauh dari itu doa tidak lagi menjadi ungkapan kesalehan, tapi merekam rintihan rakyat akan problem kesenjangan sosial yang masih langgeng. (*)