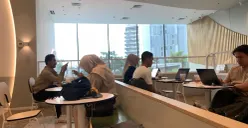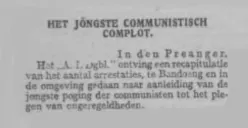Insiden keracunan makanan yang dialami ribuan pelajar di Jawa Barat beberapa waktu lalu mengundang keprihatinan publik. Program makan bergizi gratis (MBG) yang baru saja berjalan, yang digadang-gadang sebagai salah satu program unggulan pemerintah, tiba-tiba menghadapi ujian berat. Alih-alih menampilkan keberpihakan negara pada rakyat kecil, insiden ini justru menyingkap kelemahan tata kelola birokrasi kita.
Program makan bergizi gratis sejak awal diperkenalkan sebagai sebuah kebijakan strategis dengan tujuan yang mulia. Ia dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas gizi anak sekolah, menekan angka stunting, serta membantu meringankan beban keluarga miskin.
Dengan basis manfaat sebesar itu, dukungan publik terhadap program ini relatif besar. Namun, dukungan tidak otomatis berarti kebijakan berjalan mulus. Kasus keracunan massal menjadi pengingat keras bahwa setiap program publik yang menyentuh kebutuhan dasar warga tidak dapat dijalankan dengan logika administratif belaka.
Pemerintah menargetkan distribusi makanan bergizi gratis dapat menjangkau jutaan pelajar dalam waktu singkat. Ambisi ini tentu patut diapresiasi. Akan tetapi, di balik target yang besar, muncul pertanyaan mendasar, apakah rantai birokrasi yang menopang program ini sudah cukup siap? Fakta di lapangan menunjukkan hal sebaliknya.
Birokrasi kita selama ini dikenal lebih sibuk dengan urusan formalitas ketimbang memastikan mutu layanan. Inspeksi dapur penyedia makanan, misalnya, sering kali hanya menjadi rutinitas yang dilaksanakan sekadar menggugurkan kewajiban.
Sertifikasi kelayakan pangan, yang seharusnya menjadi instrumen pengendalian kualitas, tidak selalu dijalankan dengan konsisten. Dalam situasi di mana jutaan porsi makanan harus diproduksi dan didistribusikan setiap hari, kelemahan semacam ini bisa menimbulkan risiko besar.
Kasus keracunan massal di Jawa Barat menjadi bukti nyata. Anak-anak sekolah yang seharusnya mendapatkan manfaat gizi justru jatuh sakit. Orang tua merasa khawatir, dan publik mempertanyakan keseriusan pemerintah dalam memastikan keamanan program. Di balik semua itu, akar masalahnya kembali kepada satu hal yaitu lemahnya pengawasan.
Wajah Birokrasi yang Belum Berubah

Bukan pertama kalinya birokrasi Indonesia menghadapi persoalan serupa. Sejarah kebijakan publik kita kerap diwarnai oleh jurang antara rancangan yang ideal dan implementasi yang penuh kendala. Dari program bantuan langsung tunai, distribusi raskin, hingga subsidi pupuk, persoalan klasik seperti data yang tidak akurat, tata kelola yang lemah, dan pengawasan yang longgar selalu muncul.
Birokrasi kita masih sering terjebak pada logika administratif. Yang lebih diutamakan adalah kelengkapan berkas, jumlah rapat, atau tanda tangan pejabat, bukan dampak nyata di lapangan. Kinerja sering kali diukur berdasarkan output administratif, bukan outcome yang dirasakan masyarakat. Akibatnya, program-program besar mudah kehilangan arah begitu berhadapan dengan kenyataan.
Dalam kasus program makan gratis, kelemahan ini terlihat jelas. Di satu sisi, birokrasi berupaya mencapai target distribusi dalam skala masif. Namun, di sisi lain, mekanisme kontrol mutu berjalan setengah hati. Koordinasi antarinstansi lemah, standar pengawasan tidak konsisten, dan sistem akuntabilitas minim.
Penting untuk disadari bahwa program makan gratis bukanlah kebijakan sederhana. Ia melibatkan banyak pihak: kementerian, pemerintah daerah, sekolah, penyedia jasa katering, hingga masyarakat lokal. Dalam kondisi semacam ini, birokrasi dituntut untuk mampu bekerja secara adaptif, kolaboratif, dan responsif. Sayangnya, kultur birokrasi kita belum sepenuhnya bergerak ke arah itu.
Banyak kebijakan publik di Indonesia masih dikelola dengan pendekatan top-down yang kaku. Instruksi datang dari pusat, lalu diteruskan ke daerah tanpa selalu memperhatikan kapasitas lokal. Padahal, keberhasilan program makan gratis justru ditentukan oleh kesiapan rantai paling bawah seperti dapur penyedia makanan di daerah, sekolah yang menjadi tempat distribusi, serta petugas lapangan yang memastikan kualitas makanan terjaga.
Kelemahan di titik-titik ini tidak bisa ditutup dengan retorika. Masyarakat yang merasakan langsung dampaknya lebih cepat menilai. Ketika ribuan anak sakit, publik melihat program bukan dari data keberhasilan yang diumumkan pemerintah, tetapi dari pengalaman nyata di lapangan.
Sejumlah negara pernah menjalankan program serupa dengan hasil yang beragam. India, misalnya, memiliki Mid-Day Meal Scheme yang menyediakan makanan bergizi gratis bagi anak sekolah sejak 1995. Program ini terbukti menekan angka kelaparan dan meningkatkan partisipasi sekolah. Namun, India juga mengalami beberapa kasus keracunan massal akibat lemahnya pengawasan. Perbaikan kemudian dilakukan dengan memperkuat standar higiene, meningkatkan transparansi penyedia, serta melibatkan masyarakat dalam proses pengawasan.
Brasil dengan program Fome Zero juga memberi pelajaran. Kesuksesan program tersebut tidak hanya terletak pada distribusi makanan, tetapi juga integrasi dengan kebijakan lain seperti pengentasan kemiskinan, dukungan bagi petani lokal, dan pendidikan gizi di sekolah. Keberhasilan itu dimungkinkan karena birokrasi Brasil bertransformasi menjadi lebih transparan, melibatkan masyarakat sipil, dan konsisten menegakkan standar mutu.
Pengalaman internasional ini menunjukkan bahwa program makan gratis dapat berhasil bila birokrasi memiliki kapasitas, standar pengawasan yang jelas, serta ruang partisipasi publik yang memadai.
Insiden keracunan massal harus menjadi momentum untuk melakukan perbaikan mendasar. Ada beberapa langkah yang bisa ditempuh.
Pertama, penguatan sistem pengawasan. Pemerintah harus memastikan bahwa setiap dapur penyedia makanan melewati inspeksi ketat dengan standar yang seragam. Proses ini tidak bisa sekadar administratif, melainkan harus melibatkan pihak independen, termasuk organisasi profesi kesehatan atau lembaga pengawas pangan.
Kedua, peningkatan kapasitas birokrasi daerah. Tidak semua pemerintah daerah memiliki kemampuan yang sama dalam mengelola program berskala besar. Pemerintah pusat perlu memberikan dukungan teknis, pelatihan, serta anggaran yang memadai agar daerah mampu melaksanakan tugas dengan baik.
Ketiga, pelibatan masyarakat dalam pengawasan. Orang tua, komite sekolah, dan organisasi masyarakat sipil dapat menjadi mitra strategis dalam memastikan kualitas program. Dengan keterlibatan publik, transparansi meningkat dan risiko penyimpangan bisa ditekan.
Keempat, integrasi dengan kebijakan lain. Program makan bergizi gratis sebaiknya tidak berdiri sendiri, melainkan dikaitkan dengan upaya penguatan gizi, pemberdayaan petani lokal, serta pendidikan kesehatan. Dengan demikian, dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.
Birokrasi dalam Ujian

Kasus ini sejatinya adalah ujian bagi birokrasi Indonesia. Program makan gratis menjadi cermin sejauh mana birokrasi mampu bertransformasi menjadi pelayan publik yang adaptif dan berintegritas. Di tengah tuntutan masyarakat akan layanan yang cepat dan berkualitas, birokrasi tidak bisa lagi berlindung di balik prosedur yang berbelit atau jargon evaluasi yang tak kunjung tuntas.
Publik menunggu langkah nyata. Evaluasi harus disertai tindakan korektif, bukan hanya laporan di meja rapat. Setiap celah pengawasan yang ditemukan harus segera ditutup, dan setiap pihak yang lalai harus bertanggung jawab. Hanya dengan cara itu, kepercayaan masyarakat bisa dipulihkan.
Program makan bergizi gratis adalah sebuah kebijakan yang patut dipertahankan. Ia menyentuh aspek fundamental seperti gizi anak, masa depan generasi, dan rasa keadilan sosial. Namun, keberhasilan program ini sepenuhnya bergantung pada kualitas tata kelola birokrasi. Jika birokrasi masih terjebak dalam rutinitas administratif, program sebesar apa pun akan mudah tergelincir.
Insiden keracunan massal menjadi pelajaran berharga. Bukan sekadar soal makanan yang basi atau dapur yang kotor, tetapi tentang birokrasi yang belum sepenuhnya berbenah. Di sinilah ujian terbesar birokrasi Indonesia: berani berubah menjadi pelayan publik yang sejati, atau terus terjebak dalam lingkaran kelemahan yang berulang. (*)