Sejak 2017, saya menapaki perjalanan panjang di dunia agama-agama, belajar di kelas hingga turun langsung ke lapangan. Di Bandung dan Jawa Barat, saya banyak berjumpa dengan orang-orang dari berbagai latar, bercanda bersama mereka, sekaligus mengikuti isu-isu terkait.
Dalam perjumpaan itu, saya menemukan banyak konsep dan istilah baru yang kadang terasa asing, menantang batas pemahaman saya tentang ritual, iman, etika, dan spiritualitas. Apalagi ketika saya kembali pulang ke kampung, ketika harus menjelaskan ide-ide ini dengan warga akar rumput.
Seiring waktu, saya menyadari bahwa bahasa bukan sekadar sarana komunikasi, tetapi juga wadah budaya, cara memandang dunia, dan medium untuk menangkap makna terdalam.
Di situlah saya mencoba membumikan kata-kata itu dalam alam pikir Sunda, berdialog dengan orang-orangnya, mencari petuah, membaca literatur, dan memperhatikan kehidupan publik Sunda. Usaha ini bukan sekadar menerjemahkan kata, tetapi juga untuk berusaha menangkap kekayaan budaya, filosofi, dan estetika yang melekat di dalamnya.
Dengan cara ini, saya mencoba menghadirkan ide global ke dalam konteks lokal. Ataupun malah sebaliknya, mendokumentasikan pengetahuan rakyat Sunda. Inilah sebuah refleksi bebas sekaligus eksperimen kreatif lewat bahasa.
Patali-Igama (Interreligious)
Sepintas lalu artinya tampak jelas hubungan antaragama (interreligious). Istilah ini terinspirasi dari patalimarga, yang dalam bahasa Sunda berarti hubungan antarmanusia, antara manusia dan Tuhan, serta antarkota, negara, atau bangsa. Sedangkan igama merupakan kata lain untuk agama, yang berasal dari bahasa Sanskerta dan telah diadaptasi ke dalam bahasa Sunda.
Saya membayangkan patali-igama, sebagai padanan yang pas untuk istilah-istilah populer seperti lintas agama, lintas iman, interfaith, dan sejenisnya. Di sini igama juga merangkul semua ekspresi religius dan yang disekitarnya, termasuk pada kategori yang disebut faith (keyakinan).
Sebagai catatan, bagi saya sangat jelas bahwa patali-igama hanyalah sebuah penegasan spesifik dari apa yang sesungguhnya sudah dikenal oleh orang Sunda melalui konsep patalimarga.
Kaluginaan Pangageman (Kebebasan Beragama)
Frasa ini terdiri dari dua unsur, lugina dan ageman. Lugina mengacu pada rasa senang dan lega karena telah menyelesaikan semua kewajiban, atau merasa bebas dan merdeka. Sedangkan ageman berarti cecekelan (pegangan) yang baik, segala sesuatu yang dipegang atau dijalankan.
Kata pangageman mendapat imbuhan pa- dan -an, kita melihatnya pada contoh pangajaran (pengajaran) atau pagawéan (pekerjaan). Dari sana saya melihatnya sebagai segala hal, suasana, atau cara kita menjalankan agama. Jadi, kaluginaan pangaageman dapat dipahami sebagai kondisi kelegaan dan kemerdekaan bagi kita untuk menganut ‘pegangan’ tertentu.
“Merdéka wé urang mah,” (Kita itu merdeka) ujar seorang sesepuh penghayat di Lembang, kalimat yang selalu terngiang dalam ingatan saya.
Begitu pula ungkapan-ungkapan yang sering saya dengar dari mulut orang Sunda di berbagai tempat, seperti “nu penting mah teu ngarugikeun batur,” (Asal tidak merugikan orang lain) atau “Keun antep, hirup-hirup manéhna ieuh,” (Biarkan itu hak dia). Kata-kata itu mencerminkan pandangan hidup yang menekankan nilai kebebasan beragama yang secara alami tumbuh dalam interaksi sosial kita.
Silih (Toleransi)
Dalam tradisi Sunda, nilai toleransi tercermin melalui berbagai ungkapan seperti silih hurmat (saling menghormati), silih ajénan (saling menghargai), silih béla (saling membela), atau silih simbeuh (saling menolong). Semua konsep ini berakar kuat pada adagium silih asah, silih asih, silih asuh yang hadir meluas di seluruh Tanah Sunda.
Meski tidak ada istilah tunggal yang merangkum seluruh khazanah tersebut, maka dibutuhkan kepekaan kita dalam memilih istilah yang sesuai konteks. Asalkan maknanya tetap jelas sebagai rasa hormat dan penghargaan terhadap keragaman, yang menuntut sikap aktif untuk hidup bersama secara damai, bukan sekadar pembiaran pasif atau bahkan konsesi.
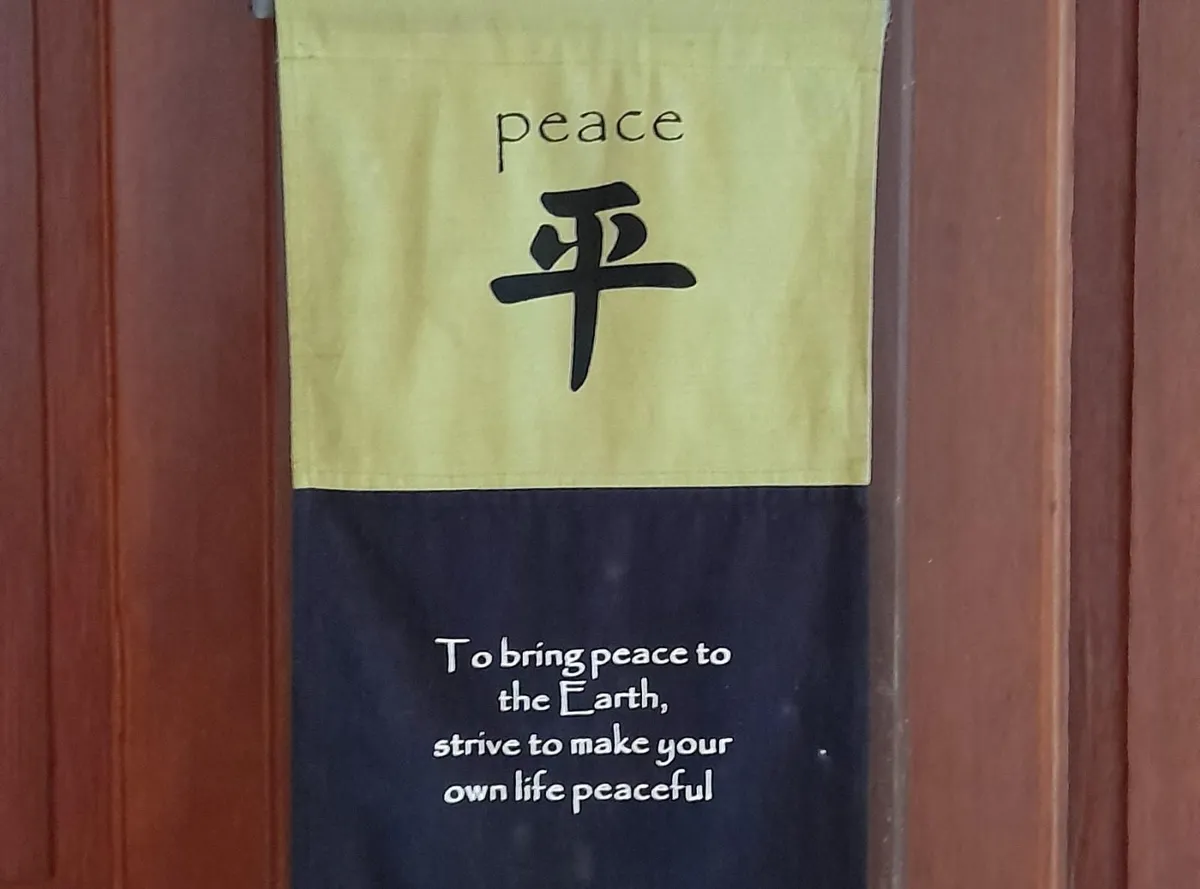
Di masyarakat Sunda, prinsip ini mudah dipahami secara intuitif, tercermin dalam ungkapan sehari-hari seperti “Ieuh, urang mah hirup kudu silih nya, saling wé,” (Hei, hidup kita itu harus saling ya). Orang Sunda akan otomatis menangkap makna positif dari kata silih tanpa harus menjabarkannya satu per satu.
Satu hal yang menarik, konsep silih- juga menekankan dimensi timbal balik yang bersifat vertikal, di mana setiap individu didorong untuk aktif berbuat baik kepada sesama.
Paguneman (Dialog)
Paguneman sering kita temui dalam buku dan LKS mata pelajaran bahasa Sunda di sekolah. Kata ini biasanya digunakan sebagai judul untuk percakapan atau teks drama. Memang, dialog adalah padanan langsung dari paguneman ini.
Namun di balik itu ada banyak istilah lain yang mengacu pada hal serupa, misalnya gunem catur, sedangkan istilah seperti ngawangkong (ngobrol), badami atau barempung (tukar pikiran, rapat), sawala (debat, diskusi), dan maduan (adu argumentasi) memperkaya makna sosialnya.
Suasananya selalu menekankan pentingnya ungkapan lisan, tetapi paguneman tidak hanya sebatas itu. Ia juga mencakup perjumpaan, tukar cerita, saling bantah, saling menyimak, bercanda, curhat, dan berbagai bentuk interaksi sosial yang mempererat hubungan masyarakat Sunda.
Pasalia (Konflik) dan Kakasaran (Kekerasan)
Dalam bahasa Sunda, istilah pasalia (yang berasal dari kata salia atau sulaya) menggambarkan keadaan berlainan, bertolak belakang, atau berselisih. Istilah ini cocok dengan makna konflik, yang muncul dari perbedaan pandangan, kepentingan, atau nilai tertentu.
Tentu hal tersebut jauh berbeda dengan kekerasan, yang merujuk pada sifat atau keadaan yang agresif, menyakiti, atau menindas. Dalam bahasa Sunda, kita mengenalnya dengan kata kasar. Ia menampilkan keadaan yang tidak lembut, tidak halus, tidak sopan, bahkan kurang nyeni. Sinonim lainnya ialah abrag, perilaku atau sifat yang menonjol dan kasar.
Kekerasan hadir dalam berbagai bentuk, kakasaran teges, ngawaruga (langsung fisik), sugal (verbal), kakasaran pinisti (struktural), kakasaran budaya (kultural), dan kakasaran pangaweruh (epistemik).
Ada banyak diksi, ada banyak cerita yang menunggu untuk kita gali. Dari rampak seja (doa bersama), pasamoan (titik temu), buméla (advokasi), amengku (inklusi), papak (setara), malinding sanak atau pilih kasih (diskriminasi), karageman (pluralitas), hingga répéh-rapih atau runtut-raut (damai) dan layeut (harmoni), sedikit demi sedikit merangkai jejak perjalanan lintas agama saya.
Kata-kata ini tentu menjadi jendela untuk melihat nilai, pengalaman, dan makna hidup yang saling bertaut. Ia membangun jembatan antara gagasan global dan kearifan lokal Sunda. Dan saya senang ada di dalamnya. (*)