Singaparna tahun 1944, sinar matahari menyoroti Asia. Para ulama dan ratusan santri berdiri tegak di tengah lapangan dipaksa menundukkan kepala dan membungkuk ke arah Tokyo.
Di bawah todongan senjata, sebagian besar menurut dengan gerakan terpaksa. Tapi Sang Ajengan, pemimpin Pesantren Sukamanah, tetap berdiri tegak sebagaimana imannya. Dengan langkah pasti, ia membalikkan badan dan meninggalkan lapangan, meninggalkan bayang-bayang teror militer Jepang yang murka.
Bagi K.H. Zainal Mustafa sikap ini adalah bentuk penyembahan. Penolakannya di Lapangan Singaparna bukanlah aksi yang spontan, melainkan puncak dari kebencian mendalam terhadap kolonialisme baru yang menginjak-injak hak beragamanya.
Meski Rezim Militer Jepang tidak menyentuh pesantren secara langsung, namun aturan semacam ini yang diwajibkan kepada umat Islam di sekitar Singaparna termasuk Desa Cimerah tempat tinggalnya, hanya bisa memicu amarah. Apalagi saat ia melihat petani setempat menderita akibat perampasan padi yang menguras hasil bumi. Bagi Sang Ajengan, itu semua adalah penindasan yang nyata.
Ini adalah sikap simbolik K.H. Zainal Mustafa yang menolak tunduk pada ideologi Rezim Militer Jepang. Namun begitu ketika penjajahan beroperasi makin brutal, perlawanan seketika berevolusi menjadi pemberontakan yang terbuka. Perampasan ratusan pucuk senjata milik kekuasaan dan pengeroyokan terhadap militer yang menyiksa warga bersatu padu dan meletus melawan ketidakasilan.
K.H. Zainal Mustafa telah membuktikan bahwa teladannya bukan sekadar protes ritualistik, melainkan bibit nasionalisme yang sejati. Begitulah catatan yang yang ditulis Laili Mardhatilah dalam "Perlindungan K.H. Zainal Mustafa Terhadap Pemerintahan Pendudukan Militer Jepang di Sukamanah Tahun 1944" (2019).
Dari Tasik ke Garut
Di bawah bayang-bayang bendera matahari terbit, Garut adalah saksi yang lain. Sejarah pernah memperlakukannya sebagai medan penindasan terhadap agama dan budaya rakyat. Salah satu instrumen represi paling menyakitkan yang diterapkan Rezim Militer Jepang kala itu adalah saikeirei, praktik penghormatan wajib kepada Kaisar Jepang, Tenno Heika, “Baginda Penguasa Surgawi”.
Setiap pagi, sebelum matahari mencapai puncaknya, para pelajar dan pegawai penyelenggaraan kekuasaan di Garut disuruh berdiri tegak di halaman sekolah atau kantor. Dengan gerakan terpaksa, mereka membungkukkan badan ke arah Tokyo, ibu kota Kekaisaran Jepang, sebagai simbol ketaatan mutlak.
Praktik ini bukan sekadar ritual, melainkan senjata yang berupaya menghapus identitas lokal dan menggantinya dengan kesetiaan kepada kaisar.
Bagi Rezim Militer Jepang, gerakan membungkuk adalah bukti penyerahan diri rakyat Indonesia kepada "Dewa Matahari". Namun bagi masyarakat Garut yang mayoritas muslim, saikeirei tak lain dengan aksi benturan antara politik dan iman. Para ulama setempat dengan lantang menolaknya, memandang gerakan itu serupa dengan rukuk dalam salat, ibadah yang hanya ditujukan kepada Allah semata. Membungkuk kepada manusia, apalagi seorang kaisar, diyakini sebagai penyimpangan akidah yang tidak bisa diterima.
Penolakan mesti dibayar mahal. Mereka yang melawan saikeirei dihadapkan pada kekejaman Kempetai (polisi Rezim Militer Jepang). Pelajar yang lupa membungkuk, pegawai yang terlambat mengikuti upacara, atau warga yang menolak dengan dalih agama, akan dihukum di depan umum.
Tamparan di wajah hingga telinga berdenging, tendangan yang membuat tubuh terjengkang, atau penjemuran di bawah terik matahari yang menyengat. Bagi Rezim Militer Jepang, ini adalah disiplin. Bagi rakyat Garut, ini adalah penghinaan terhadap martabat kemanusiaan dan agama.
Seperti diungkap Kunto Sofianto dalam “Garut Pada Masa Pemerintahan Pendudukan Jepang 1942–1945” (Sosiohumaniora, 2014), saikeirei menjadi titik balik persepsi masyarakat Garut terhadap Rezim Militer Jepang. Klaim "saudara tua" pembebas dari Rezim Kolonial Hindia Belanda adalah penindas baru yang lebih bengis daripada era sebelumnya.
Harry J. Benda dalam “Bulan Sabit dan Matahari Terbit: Islam Indonesia pada Masa Pendudukan Jepang 1942–1945” (1980) menyoroti resistensi umat muslim tersebut sebagai bukti ketahanan religius. Saikeirei merupakan pertarungan antara ketaatan kepada Tuhan dan ketaatan kepada tirani. Fenomena ini jelas mencederai praktik kebebasan beragama kala itu.
Saikeirei di Antara Propaganda
Miftachul Amri dalam “Ojigi: The Ethics of Japanese Community’s Nonverbal Language (Atlantis Press, 2019) menerangkan bahwa saikeirei adalah bentuk ojigi (membungkuk) yang paling dalam dan penuh rasa hormat dalam budaya Jepang. Gerakan ini melibatkan gestur membungkuk sekitar 45° atau lebih, dan digunakan untuk menunjukkan penghormatan tertinggi, baik kepada individu dengan posisi sangat tinggi, seperti kaisar atau pejabat tinggi, maupun dalam situasi permintaan maaf yang serius.
Selain itu, saikeirei juga digunakan dalam konteks ritual keagamaan, misalnya saat berdoa di kuil. Sebab awalnya penghormatan ini hanya diberikan kepada para dewa atau kaisar.
Dalam skema tingkatan ojigi, saikeirei menempati posisi yang paling tinggi. Ia berada di atas eshaku (membungkuk ringan sekitar 15° untuk teman atau kenalan) dan futsuu no ojigi (membungkuk formal sekitar 30° untuk permintaan maaf atau salam formal). Saikeirei menekankan kedalaman dan kesungguhan gerakan, sehingga berfungsi sebagai simbol penghormatan dan kesopanan tertinggi dalam interaksi sosial maupun upacara resmi.
Namun demikian, di tengah bayang-bayang pendudukan, Saiful Umam dalam “Historiography of Japanese “Islamic Policy” in Indonesia” (Islamika Indonesiana, 2014) memandang saikeirei bukan sebagai gerak ritus yang netral. Ia adalah aturan yang menyasar umat Islam di Jawa, strategi gagal Rezim Militer Jepang yang penuh kontradiksi. Kekuasaan yang berniat meraih loyalitas umat muslim, justru menimbulkan kegelisahan hati dan rasa sensitif yang tak terduga. Dalam ketegangan propaganda, saikeirei menjadi cermin dari kesalahan awal Jepang.
Shinto pada Masa Perang Dunia II
Qin Lianxing dalam “The Rethinking of “State Shinto” in Japanese Academia After World War II (Cultural and Religious Studies, 2023) melihat bahwa sepanjang Perang Dunia II Shinto berfungsi sebagai desain kekuasaan Rezim Militer Jepang, bukan sekadar praktik keagamaan lokal.
State Shinto dijadikan alat untuk menanamkan loyalitas mutlak terhadap kaisar dan negara, serta membentuk kesetiaan pada ideologi ultranasionalisme dan militerisme. Ritual, upacara persembahan, dan pendidikan moral dipaksakan, mengubah spiritualitas menjadi propaganda perang yang membungkus doktrin kekaisaran.
Kuil-kuil Shinto dan pemujaan kaisar menjadi simbol dominasi negara, menuntut rakyat tunduk sepenuhnya pada wacana nasional, dan setiap tindakan keagamaan diarahkan untuk mendukung kepentingan militer. Dengan demikian, Shinto selama perang bukan lagi sekadar agama atau tradisi, melainkan arsitektur ideologis rezim, memperkuat militerisme, menormalisasi ultranasionalisme, dan menjustifikasi kekerasan sebagai kehendak yang dipandang ilahian dari kaisar.
Helen Hardacre dalam “Shinto: A History” (2017) mencatat narasi transformasi Shinto menjadi alat politik nasionalisme Jepang dan perannya selama Perang Dunia II melalui pola keterhubungan simbolis yang mendalam.
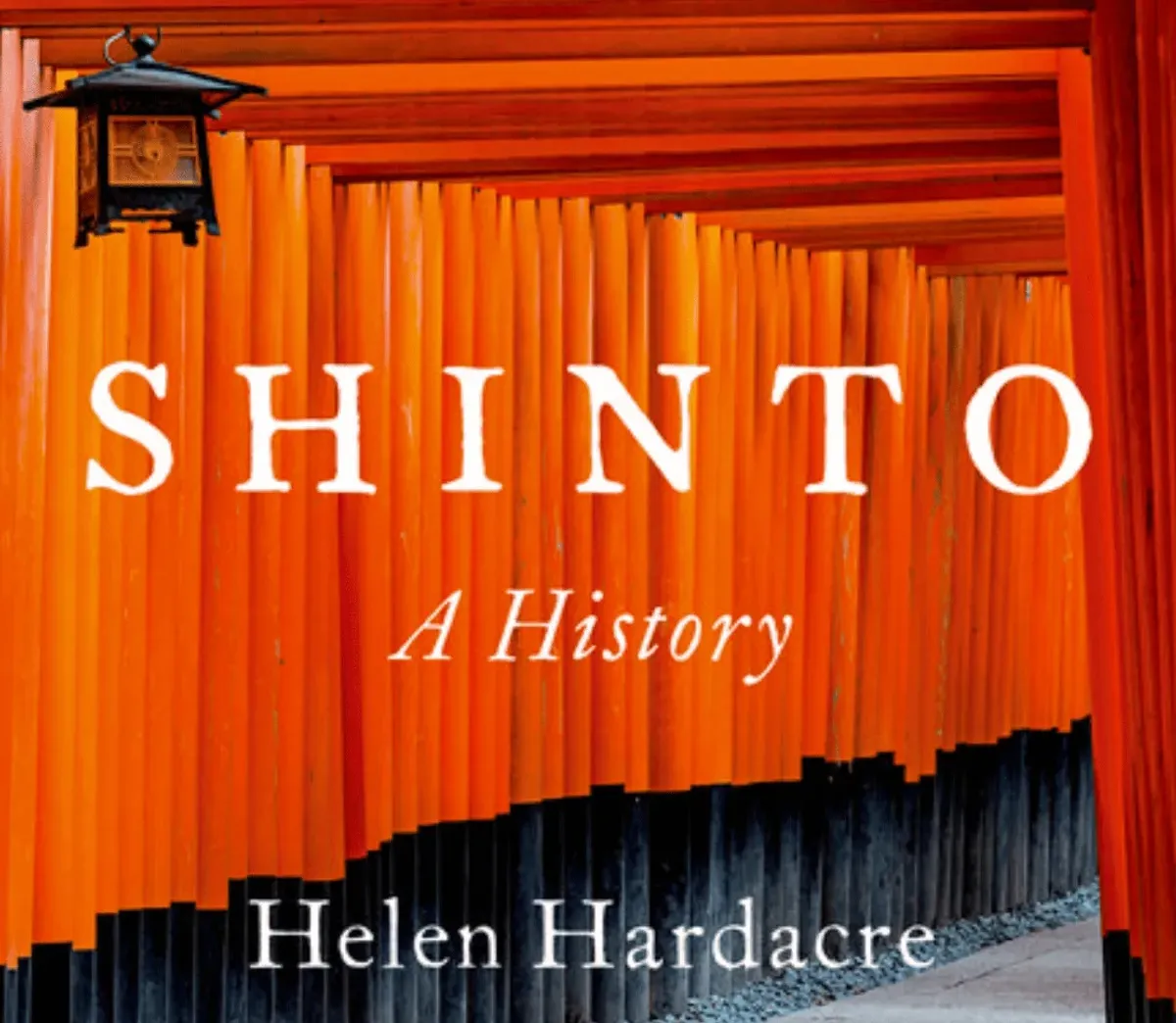
Setelah Restorasi Meiji 1868, kekuasaan memisahkan Shinto dari Buddha (Shinbutsu Bunri) dan membentuk “State Shinto” (Shinto Negara) sebagai sistem ritual resmi yang mengaitkan Dewa Matahari Amaterasu, kaisar, bendera Hinomaru, nama Jepang (Nippon/Nihon), dan lagu kebangsaan Kimigayo dalam satu ideologi tunggal.
Amaterasu, sebagai leluhur wangsa kekaisaran, menjadi fondasi mitos bahwa kaisar adalah Arahitogami (dewa yang menjelma sebagai manusia), pemegang mandat ilahi untuk memimpin. Bendera Hinomaru (matahari merah di latar putih) melambangkan kekuasaan Amaterasu, sementara nama Nippon (asal matahari) menegaskan Jepang sebagai shinkoku (tanah suci) yang sakral. Lagu Kimigayo memuja keabadian kekuasaan kaisar sebagai penerus tak terputus dari Amaterasu.
Selama Perang Dunia II, “State Shinto” digunakan untuk melegitimasi ekspansi militer Jepang di Asia. Kaisar Hirohito diposisikan sebagai pemimpin spiritual dan politik, sementara doktrin Hakko Ich'u (Delapan Pojok Dunia di Bawah Satu Atap) menyatakan misi suci Jepang memimpin Asia.
Kuil Yasukuni didedikasikan untuk menghormati arwah prajurit, termasuk yang gugur saat menjajah Asia, sebagai pahlawan yang mengorbankan diri untuk kaisar dan negara. Shinto juga diintegrasikan ke dalam pendidikan. Buku teks seperti Kokutai no Hongi mengajarkan bahwa penjajahan Asia adalah tugas suci untuk menyebarkan peradaban ilahi Jepang di bawah naungan Amaterasu.
Dan di tengah-tengah inilah, ritual saikeirei berada.
Pasca-1945, Sekutu membongkar “State Shinto” melalui Dekrit Kekaisaran yang menyangkal status keilahian kaisar, kemudian serta memisahkan agama dari negara. Namun, warisan simbolis ini tetap mempengaruhi politik Jepang modern, seperti kontroversi kunjungan pejabat ke Kuil Yasukuni yang masih memicu protes internasional.
Hardacre menyoroti kisah Shinto, yang awalnya merupakan religiusitas lokal dan pemujaan terhadap Kami, diubah menjadi mesin politik yang mengikat identitas kebangsaan pada narasi kesucian dan superioritas ilahi. Sebuah pola yang memperlihatkan bahaya ketika agama disatukan dengan ambisi kekuasaan.
Catatan Akhir
Saikeirei selama pendudukan Rezim Militer Jepang menyingkap benturan antara iman, kekuasaan, dan identitas lokal. Dari Singaparna hingga Garut, umat Islam di Tanah Sunda dihadapkan pada dilema yang tak ringan, tunduk pada ritual yang dipaksakan, yang bertentangan dengan nilai-nilai keagamaan dan adat istiadat mereka.
Sikap K.H. Zainal Mustafa yang tetap tegak di tengah tekanan militer bukan sekadar penolakan fisik, tetapi simbol keteguhan iman sekaligus refleksi masyarakat Sunda. Dalam pikiran seorang Sunda kala itu, kehormatan, martabat, dan prinsip religius harus dipegang teguh, sehingga menolak saikeirei berarti mempertahankan identitas spiritual dan sosial yang telah diwariskan turun-temurun.
Lebih dari sekedar gerakan membungkuk, saikeirei menjadi alat propaganda yang menguji loyalitas dan kesetiaan, sekaligus mengungkap cara kekuasaan bisa merusak tradisi sakral. Fragmen sejarah ini mengingatkan bahwa ketika agama dan adat dipaksa melayani politik, ia bisa menjadi medan perlawanan, simbol ketahanan komunitas, dan cermin harga diri masyarakat Sunda yang tak tergoyahkan. (*)




























