Agama Baha’i pertama kali menapak di Nusantara pada tahun 1878, dibawa oleh dua pedagang, Jamal Efendi dan Mustafa Rumi. Di Sulawesi mereka disambut hangat dan menarik perhatian para raja lokal. Pesan persatuan Baha’i akhirnya menyebar ke pulau-pulau lain, merajut cerita baru dan kita termasuk di dalamnya.
Perjalanan Baha’i di Indonesia adalah petualangan mengarungi suka dan duka. Pada tahun 1962, Keppres No. 246/1962 terbit melarang kegiatan komunitas ini bersama dengan beberapa organisasi lain, membungkam langkah mereka di tengah arus sejarah
Baru setelah era Reformasi, lewat Keputusan Presiden No. 69/2000, Gus Dur membuka jalan lagi bagi kebebasan beragama. Belasan tahun berlalu, surat cinta dari Kementerian Agama yang bernomor SJ/B.VII/1/HM.00/675/2014 akhirnya tiba. Ia laksana lentera hukum yang menegaskan Baha’i sebagai agama mandiri dan membuka ruang pemenuhan hak-hak sipil serta akses administrasi yang setara dengan pemeluk agama lain. Di sana ditegaskan bahwa keberadaan komunitas ini adalah bagian sah dari kehidupan berbangsa.
Suka
Di Bandung, kisah komunitas Baha’i dimulai pada akhir dekade 1950-an, ketika Dokter Jae Hoon tiba bersama istri dan anaknya. Di meja praktik Rumah Sakit Hasan Sadikin, ia menata buku-buku tentang Baha’i, seolah membiarkan dunia tahu bahwa agamanya adalah bagian dari dirinya. Bahwa Baha’i tetap terbuka bagi segala orang yang ingin mengenalnya.
Sepuluh tahun kemudian, angin dari Persia membawa Dokter Samandari dan Ezzieh sebagai istrinya, menapaki udara sejuk yang sama di Bandung. Saat mereka datang pada 1969, komunitas Baha’i telah bertumbuh sekitar selusin jiwa yang teguh, termasuk Ibu Warsa, Ibu Hermiati, Pak Karmita, Edi beserta istrinya, dan beberapa mahasiswa ITB.
Nopiah Ulfha dalam penelitiannya “Eksistensi Agama Baha’i di Kota Bandung: Studi Deskriptif di Jl. Baladewa, Pajajaran, Kecamatan Cicendo, Kota Bandung” (2018) melanjutkan paparannya.
Dia menemukan bahwa perkembangan Baha’i di Bandung bukan didesain lewat strategi penyiaran agama yang terencana. Komunitas ini justru bergeliat dengan lembut. Dari permulaan yang kecil, hanya puluhan orang di Kota Bandung dan Kabupaten Bandung, mereka perlahan bergenerasi seiring waktu. Hingga 2018, jumlah mereka meningkat, menapak ratusan di kabupaten dan puluhan lagi di kota, tersebar di berbagai lingkungan dan hidup berbaur dengan tetangga yang berbeda.
Komunitas itu dipimpin oleh Majelis Rohani Setempat. Muda dan tua, perempuan dan laki-laki, saling berbagi soal nilai kesetaraan yang tidak lagi jadi basa-basi. Mereka juga datang dari berbagai profesi, wiraswasta, mahasiswa, pekerja swasta, dan teguh disatukan oleh ajaran yang sama.
Di bawah bimbingan ajaran Baha’ullah, mereka menata hidup demi kesatuan umat manusia. Ada doa bersama, pendidikan rohani untuk anak-anak, program pemberdayaan remaja, dan pendidikan bagi muda-mudi serta dewasa. Ada Pertemuan Sembilan, di mana doa dan tulisan suci didaraskan, musyawarah dihidupi, dan rencana sosial serta administrasi dibicarakan dengan penuh kesungguhan.
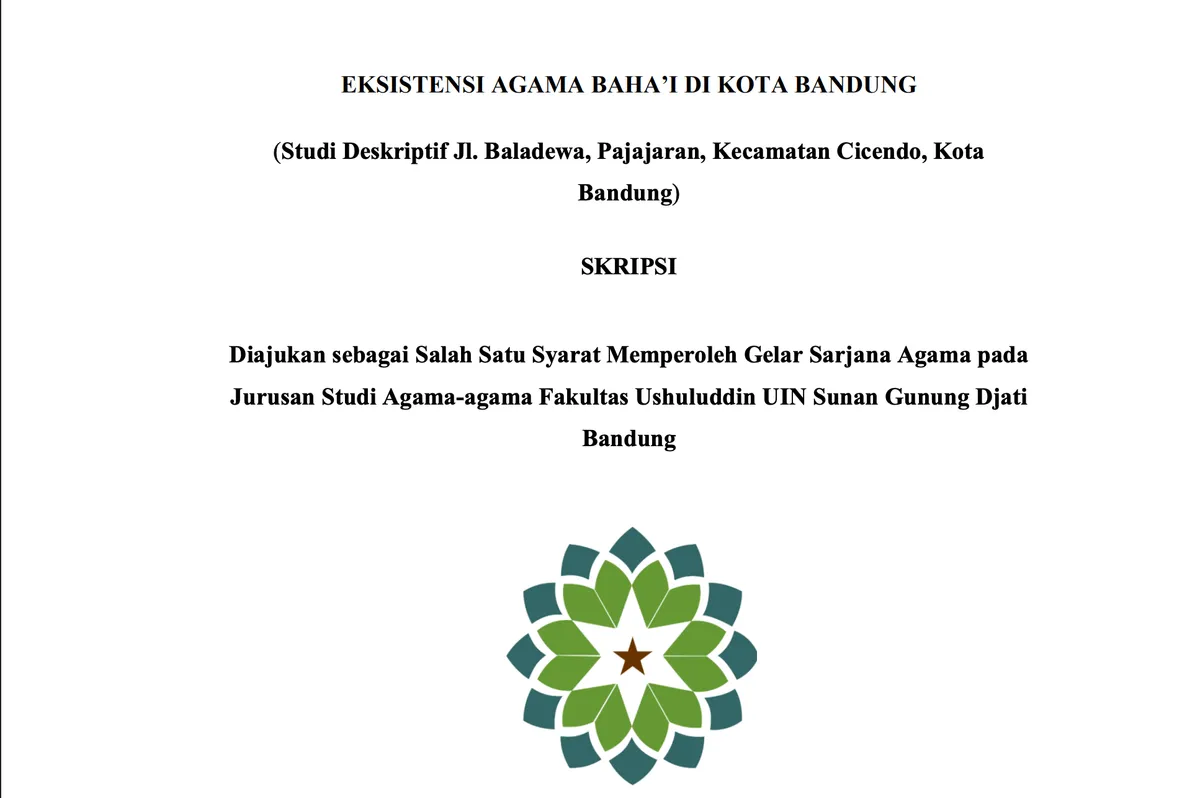
Mereka selalu membuka diri. Misal tradisi doa bersama yang mengundang siapa saja dari berbagai anasir lintas keyakinan. Begitu juga momen perayaan Naw-Ruz dan Hari Lahir Baha’ullah, menjadi ajang berbagi, pengakuan, dan persaudaraan. Semua orang diajak merasakan keterikatan dengan Sang Pencipta yang satu, agama yang satu, dan manusia yang satu.
Tidak ada ritual komunal yang mengikat. Mereka percaya pencarian kebenaran harus dilakukan secara mandiri, mereka juga memegang teguh bahwa pendidikan adalah wajib bagi umat manusia.
Meski kecil secara jumlah, komunitas Baha’i Bandung teguh menunjukkan eksistensinya dengan rendah hati, menjaga harmoni, dan kebersamaan. Dalam setiap doa, perayaan, dan makan bersama, mereka menenun nilai universal yang bisa dinikmati tanpa batas.
Duka
Di Indonesia, agama seperti Baha’i sering terperangkap di antara tafsir hukum dan kenyataan. Meskipun Pasal 29 UUD 1945 telah menjamin tegas soal masalah kebebasan beragama. Keadilan itu semestinya substantif, tapi apa daya kala data empiris masih terbatas dan membuat penyelenggara negara kesulitan merumuskan kebijakan yang bermakna bagi komunitas yang tidak populer ini.
Dalam konteks itulah, penelitian “Problematika Pelayanan Hak-Hak Sipil Umat Baha'i di Bandung" yang dituangkan oleh Kustini dan Syaiful Arif dalam buku “Baha’i, Sikh, Tao: Penguatan Identitas dan Perjuangan Hak-Hak Sipil” (Kementerian Agama RI, 2015) menjadi penting. Riset ini mendokumentasikan sisi lain dari kehadiran komunitas Baha’i di Bandung, terutama dengan berbagai kendala pada pemenuhan hak-hak asasinya.
Selain bisa bergelayut dan tumbuh sebagai komunitas yang sehat, komunitas Baha'i di Bandung juga menapaki hari-hari yang penuh tantangan. Mereka berada di persimpangan antara janji konstitusi dan kenyataan birokrasi.
Kustini dan Syaiful Arif mengungkap rintangan yang paling nyata yakni sekeping kartu, KTP yang seharusnya bisa menegaskan identitas mereka. Kolom agama masih menjegal. Dan di sinilah para mukmin Baha’i harus memilih antara menyamarkan diri, mengosongkan kolom, atau tunduk pada aturan yang tak sepenuhnya menghitung keberadaan mereka.
Kesulitan tidak berhenti pada identitas. Pernikahan dan kelahiran, fase-fase hidup yang sederhana bagi sebagian orang, menjadi teka-teki hukum bagi pasangan Baha'i. Akta nikah sah sulit didapat, pencatatan kelahiran anak menjadi jalan berliku yang penuh ketidakpastian.
Begitu juga anak-anak kerap menghadapi ketidakadilan pendidikan agama. Sekolah-sekolah belum menyediakan kurikulum yang memadai, sehingga mereka harus menempuh pelajaran agama kelompok dominan.
Akar persoalan itu dipandang bukan bersumber dari kekurangan regulasi hukum, melainkan pada pemahaman yang tumpul dari aparat dan masyarakat. UU No. 1/PNPS/1965 dan Putusan MK No. 140/PUU-VII/2009 sebenarnya memberi hak komunitas Baha’i untuk berkembang dan diperlakukan dengan setara. Namun fakta di lapangan tetap berjarak dari kata-kata resmi “dibiarkan adanya”. Frasa itu sering disalah tafsirkan sebagai sekadar toleransi pasif, bukan pengakuan nyata terhadap eksistensi.
Di tengah segala keterbatasan tersebut, komunitas Baha'i memilih jalur dialog, pendidikan, dan sosialisasi. Tujuan mereka bukan proselitisme, melainkan pemenuhan hak sipil sebagai warga negara. Hak untuk dilindungi, dipenuhi, dan dihormati sebagaimana mestinya.
Suka dan Duka dalam Pupuh
Di Bandung, di tanah yang tak pernah habis untuk menimba khazanah agama-agama, suka dan duka komunitas Baha’i mengalun bagai pupuh Sunda.. Kehangatan doa bersama di rumah-rumah, perayaan hari suci, dan pendidikan rohani menjadi nada-nada penguat, sementara rintangan administratif dan ketidaktahuan masyarakat menjadi irama yang menguji kesabaran.
Di sinilah mereka belajar membaca dunia, menyesuaikan langkah dan ritme tanpa kehilangan inti ajaran, tetap konsisten mewartakan seruan persatuan. Dari pengalaman itu, kita diajak meneguk kearifan, mendendangkan arti penting dialog dan kebersamaan.
Di sela perjalanan itu juga, akhirnya kita kembali mendengar gema lagu-lagu kecil dari bangku sekolah. Bagian sekar tandak dari pupuh Juru Demung lirih mengalun
Mungguh hirup di alam dunya
Ku kersaning Anu Agung
Geus pinasti bakal panggih
Suka bungah jeung kasedih
Dua rupa nu tumiba
Sakabéh jalma di dunya
Senang patumbu jeung bingung
Éta geus tangtu kasorang
Di Bandung, di Tanah Sunda, alunan suka dan duka komunitas Baha’i bukan hanya pengalaman mereka sendiri, tapi menjadi bagian dari simfoni kehidupan kita semua. Kisah satu keluarga besar umat manusia.
Dua penelitian di atas menjadi pengingat bahwa hidup adalah tentang tenunan rasa, di mana setiap senang maupun sedih menempati tangga nadanya masing-masing.
Namun tetap ingatlah bahwa dua hal yang menimpa semua manusia di dunia, jangan pernah dicerap sebagai alunan indah semata. Duka harus tetap diatasi, penyelenggara negara selaku dirigen mesti segera berbenah mengoreksi suara yang sumbang. (*)



























