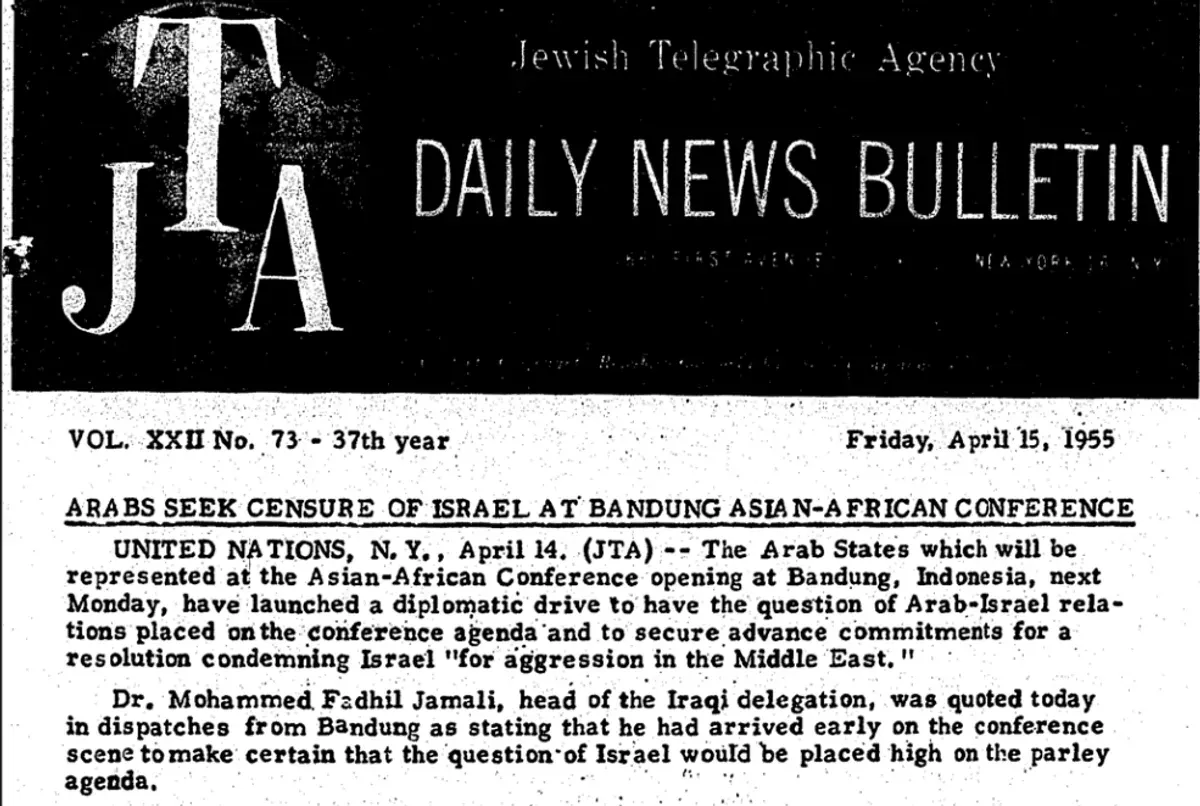Katanya, pas zaman kolonial dulu, Jalan Braga di Bandung pernah jadi “ghetto” kecil untuk orang Yahudi. Beberapa keluarga seperti Roth, Godstein, Tatarah, Goldberg, dan Ephreim konon tinggal di sana.
Kabar bilang, mereka tidak hanya tinggal tapi juga meramaikan kota. Masuk ke dalam jaringan perdagangan, usaha, dan interaksi budaya di tengah keragaman Bandung waktu itu (Kumeok Memeh Dipacok, Agama Yahudi di Bandung Jaman Dulu, blog pribadi, Agustus 2015).
Bandung juga pernah jadi simpul gerakan Zionis. Ir. B. Wurbik di Jalan Riau dan S.I. van Creveld di Jalan Cikapayang jadi penggeraknya. Ceramah Dr. A. Goldstein pada 1927 dan kunjungan Benzion Shein pada 1934 menyalakan semangat tersebut. Dalam tiga minggu, terkumpul 14.500 gulden dari Bandung, Batavia, Semarang, dan Surabaya (Bambang Arifianto, Pikiran Rakyat, 16 Desember 2023).
Di Bawah Bayang Rezim Kolonial Hindia Belanda
Leonard Chrysostomos Epafras dan Rotem Kowner dalam “From a Colonial Settlement to a New Identity: The Rise, Fall and Reemergence of the Jewish Community in Indonesia” (2022) menerangkan soal komunitas Yahudi di Indonesia, khususnya di Bandung tersebut sebagai kisah tentang identitas yang tipis, tersebar, namun gigih meninggalkan jejaknya di tanah jajahan.
Sejak awal abad ke-20, Yahudi Belanda (Ashkenazi) dan Yahudi Baghdadi telah menjejakkan kakinya di Bandung, kota dengan latar pegunungan Sunda dan jalan-jalan yang ramai oleh aktivitas kolonial. Mereka datang sebagai pedagang, profesional, dan pegawai administrasi, membawa warisan Eropa, Levant, dan Dunia Arab, sekaligus membangun kehidupan yang berpadu dengan lanskap rezim Hindia Belanda.
Komunitas ini mendirikan majalah Erets Israel, yang awalnya lahir di Padang, lalu dipindahkan ke Bandung, sebagai jendela untuk meneguhkan identitas dan komunikasi di antara mereka. Meski tak memiliki sinagoga resmi atau rabbi, mereka tetap menjaga ikatan melalui organisasi Zionis dan jaringan sosial yang tersebar.
Pada masa itu, Bandung menjadi titik pertemuan, meski jumlah mereka tak pernah melebihi beberapa ratus jiwa.
Kedatangan mereka bukan tanpa alasan. Antisemitisme yang meningkat di Eropa, terbatasnya kesempatan, dan janji kehidupan lebih bebas di Hindia Belanda membuat Bandung menjadi semesta bagi identitas baru. Mereka beradaptasi, menjalankan perdagangan dan bisnis, sambil tetap menjaga tradisinya.
Namun sejarah berubah. Pendudukan Jepang (1942-1945) dan perjuangan kemerdekaan Indonesia menandai awal kemunduran komunitas ini. Di antara mereka akhirnya banyak yang memilih migrasi ke Belanda, tanah yang diklaim Israel, atau Amerika, meninggalkan Bandung sebagai saksi sunyi dari fragmen identitas Yahudi di Tanah Sunda.

Wardani Dwi Jayanti dalam skripsinya yang berjudul “Sejarah komunitas Yahudi di Indonesia Tahun 1926-1957” (Universitas Sebelas Maret, 2019) juga mencatat Bandung sebagai salah satu pusat aktivitas Yahudi yang vital di luar Pulau Jawa bagian timur. Kota ini menjadi ruang bagi Ashkenazi dan Sefardi untuk memperkuat identitas keagamaan dan budaya mereka.
Sejak 1930-an, kursus bahasa Ibrani dan pelajaran Yudaisme digelar di ruang-ruang publik seperti De Concurrent di Bragaweg (sekarang Jalan Braga) dan B.S.V School di Riouwstraat. Puluhan peserta dari berbagai usia datang untuk belajar, dipimpin tokoh seperti A. Elburg dan didukung organisasi pemuda Rewid Zahav, yang tetap aktif hingga 1942 menjelang pendudukan Jepang.
Selain pendidikan, Bandung juga menjadi markas cabang Nederlandsch Indische Zionisten Bond (NIZB) dan Vereeniging voor Joodsche Belangen (VVJB). Mereka mengkoordinasikan gerakan Zionisme, menyelenggarakan penggalangan dana melalui Keren Hajesod, sekaligus merayakan Purim dan Hanukah.
Kota ini bahkan menjadi basis militer Yahudi, Achawah. Serikat tentara Yahudi ini berdiri pada 1926. Kemudian diikuti dengan pembangunan Joodsche Militaire Tehuis, rumah singgah bagi prajurit Yahudi, simbol solidaritas di tengah KNIL.
Kehadiran mereka di Bandung bukanlah kebetulan. Kota administratif yang strategis dan lingkungan sosial yang relatif stabil memungkinkan komunitas ini berkembang tanpa gangguan signifikan hingga 1942.
Tokoh seperti P. Boeken (ketua NIZB Bandung) dan Isidore Hen (pemrakarsa Keren Hajesod) menjadi motor penggeraknya. Interaksi dengan non-Yahudi juga terjadi melalui acara publik, termasuk pemutaran film propaganda Zionis The Land of Promise (1936) yang dihadiri pejabat kolonial.
Puncak aktivitas komunitas ini berlangsung antara 1930-1941. Kursus bahasa Ibrani, pelajaran agama, dan penggalangan dana untuk pengungsi Yahudi Eropa berjalan bersamaan, paralel dengan perjuangan global melawan antisemitisme.
Meski pragmatis, semua aktivitas ini menunjukkan adaptasi komunitas Yahudi di tanah Sunda, menjadikan Bandung episentrum diaspora yang hidup dan dinamis hingga perubahan geopolitik menandai akhir rezim Hindia Belanda.
Balik Arah Setelah Kemerdekaan
Setelah Indonesia merdeka, Bandung bukan hanya kota pegunungan yang teduh sekaligus penuh dengan sejarah kolonialismenya. Ia juga tumbuh tapi jadi panggung politik dunia.
Sepuluh tahun pasca-proklamasi, April 1955, kota ini jadi pribumi bagi Konferensi Asia-Afrika. Sebuah pertemuan bersejarah yang mengumpulkan negara-negara tertindas. Di jalan-jalan yang dulu menyimpan jejak komunitas Yahudi, kini berkumpul delegasi Arab, India, Burma (Myanmar), dan Mesir, memperbincangkan isu kemanusiaan dan pembebasan di Tanah Sunda.
Dr. Mohammed Fadhil Jamali dari Irak datang lebih awal, memastikan agar masalah Israel masuk ke agenda. Gamal Abdel Nasser, pemimpin Mesir, menekan Nehru untuk ikut mengecam. Tapi India tampak ragu, diplomatnya Arthur S. Lall bahkan menyiratkan lebih baik isu itu disisihkan.
Israel sendiri tak diundang, meski U Nu dari Burma sempat mendukung. Harian Al Akbar di Kairo menulis lantang, Konferensi Bandung akan jadi panggung untuk membela Arab (Jewish Telegraphic Agency, “Arabs Seek Censure of Israel at Bandung Asian-African Conference,” 15 April 1955, Daily News Bulletin, Vol. XXII, No. 73).
Ahmad Rizky M. Umar dan kawan-kawannya dalam “Bandung Conference 70 Years On: Visions of Decolonisation for a Multipolar World Order.” (Global South Review, 2025), menulis, bahwa meski puluhan tahun telah berlalu dan 116 negara telah meraih kemerdekaan setelah peristiwa itu, bayangan kolonialisme belum sepenuhnya sirna.
Satu contoh yang paling nyata adalah Palestina. Di tengah gema solidaritas Asia-Afrika, hak menentukan nasib sendiri bagi bangsa Palestina terus tertunda.
Bandung tampil sebagai kota penuh paradoks. Di pusat peradaban Sunda modern ini, jejak Zionisme pernah bersemi dan berkelindan dengan bayang kolonialisme yang terpatri pada rezim Hindia Belanda. Beberapa keluarga Yahudi menetap, berbisnis, dan hidup berdampingan, menambah warna bagi mosaik Bandung yang kosmopolit pada awal abad ke-20.

Namun secara ironi, di kota yang sama, hanya beberapa dekade kemudian, suara berlawanan bergema. Setelah Indonesia merdeka, Bandung justru menjelma panggung yang mengutuk kolonialisme, dan menyuarakan solidaritas bagi Palestina yang tertindas oleh proyek Zionisme.
Kota yang pernah jadi ruang hidup bagi komunitas Yahudi di Indonesia, berbalik arah menjadi ruang lahirnya seruan melawan ketidakadilan. Bandung seolah menampilkan wajah ganda sejarah, satu sisi keterhubungan dengan kolonialisme, sisi lain keberpihakan pada kemerdekaan sejati.
Menjernihkan Pikir dengan Mehidupi Semangat KAA
Dalam pikiran kita, sering kali istilah Yahudi, Yudaisme, Israel, dan Zionisme dicampuradukkan seolah-olah satu maknanya. Padahal nama-nama tersebut memiliki konteks berbeda yang perlu dipahami agar tidak jatuh pada kesalahpahaman.
Yahudi adalah identitas agama sekaligus kebangsaan yang sudah ada ribuan tahun, hadir dalam diaspora di berbagai belahan dunia, termasuk di Tatar Sunda. Yudaisme cenderung merujuk pada sistem religinya, kita biasa menyebut dengan agama Yahudi.
Israel sendiri punya dua pengertian. Dalam tradisi keagamaan, ia menunjuk pada Bani Israel, sebuah identitas spiritual yang berakar pada narasi kitab suci. Sementara dalam arti modern, Israel adalah negara yang diklaim berdiri pada 1948 sebagai hasil dari proyek politik tertentu.
Adapun Zionisme adalah ideologi politik yang muncul pada akhir abad ke-19, bertujuan mendirikan dan mempertahankan negara tersebut di Palestina.
Ketika batas-batas ini dikaburkan, muncullah mispersepsi publik. Dalam konteks kolonialisme dan konflik global, kebencian terhadap Zionisme seringkali bergeser menjadi kebencian terhadap orang Yahudi secara keseluruhan.
“Zionisme didirikan atas keyakinan bahwa antisemitisme tidak mungkin bisa dihapus sepenuhnya, hanya bisa dikurangi. Tapi hari ini semakin jelas bahwa proyek Zionis telah gagal dalam misinya yang katanya untuk menjamin keselamatan orang Yahudi.” (Shane Burley dan Ben Lorber, 2024)
Inilah yang melahirkan antisemitisme, sebuah bias yang menempatkan identitas etnis dan agama sebagai musuh, padahal problem utamanya adalah proyek kolonial Zionisme. Kita
bisa membaca itu semua dengan jelas dalam, Susan Landau, “‘Thou Shalt Not Stand Idly By’: Jews of Conscience on Palestine” (2025).
Bandung, yang pernah menyaksikan jejak komunitas Yahudi sekaligus menjadi panggung anti-kolonial, memberi kita pelajaran penting bahwa melawan penindasan tidak berarti menghapus identitas orang atau kelompok tertentu.
Semangat Konferensi Asia-Afrika 1955 jelas, menolak segala bentuk kolonialisme. Spirit ini relevan untuk menegaskan bahwa perlawanan terhadap Zionisme adalah bagian dari solidaritas global melawan penjajahan, bukan seruan untuk menghapus eksistensi Yahudi.
Anti-kolonialisme di Bandung menolak penindasan atas bangsa Palestina, sekaligus menolak jebakan kebencian yang buta. Dengan meluruskan jejak ini, kita bisa menjaga warisan Bandung sebagai ruang perlawanan yang adil. Kita mengutuk kolonialisme, tapi tetap menghormati keberadaan identitas dan tradisi Yahudi yang berbeda dari Zionisme itu sendiri. (*)