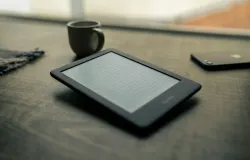Di Kota Bandung, ada restoran bernama Kehidupan Tidak Pernah Berakhir yang unik. Semua makanannya ramah lingkungan. Dari sayuran organik sampai piring daur ulang, restoran ini sengaja mengajak pengunjung peduli pada bumi.
Penelitian menunjukkan bahwa citra restoran sebagai tempat yang “hijau” dan nilai produknya yang ramah lingkungan bisa membuat orang lebih percaya dan puas saat makan di sana (Yoningsih dan Hidayat, “Pengaruh Green Brand Image dan Green Perceived Value Terhadap Green Trust untuk Meningkatkan Green Satisfaction (Studi Pada Restoran Vegetarian Kehidupan Tidak Pernah Berakhir Kota Bandung)”, Jurnal Bisnis dan Manajemen West Science, 2023).
Ternyata, banyak orang yang masih belum begitu mengenal restoran ini. Menariknya, bukan pengetahuan mereka yang paling menentukan, tapi cara restoran menampilkan diri dengan label “hijau” itu. Gabungan pengetahuan dan citra merek cuma memengaruhi sekitar seperempat keputusan beli, sisanya masih bergantung pada banyak hal lain yang membuat orang penasaran mencoba makanan ramah lingkungan (Oktaviani dan Yusiana, “Pengaruh Green Brand Knowledge dan Green Brand Positioning terhadap Green Purchase Intention di Restoran Kehidupan Tidak Pernah Berakhir Kota Bandung Tahun 2019”, e-Proceeding of Applied Science, 2019).
Tren makanan hijau di Indonesia kini semakin mengarah ke pola makan vegetarian dan vegan, yang bukan hanya soal rasa, tapi juga pertimbangan etika dan kesehatan. Pola makan masyarakat cepat berubah, dipengaruhi kesadaran akan kesehatan pribadi sekaligus gaya hidup berkelanjutan (Viviana Arwanto, dkk “The State of Plant-Based Food Development and Its Prospects in The Indonesia Market”, Heliyon, 2022).
Kesadaran etis dalam memilih makanan sebetulnya bukan fenomena baru di dunia. Berbagai budaya dan tradisi keagamaan sejak lama menekankan pentingnya menghormati kehidupan makhluk lain, baik sebagai bentuk spiritualitas maupun pedoman moral.
Dalam konteks modern, perhatian terhadap kesehatan, lingkungan, dan kesejahteraan hewan membuat nilai-nilai etis ini kembali relevan, sekaligus memberikan dasar filosofis bagi orang yang memilih pola makan vegetarian atau vegan. Dengan begitu, tren makanan hijau tidak hanya mengikuti gaya hidup kontemporer, tetapi juga mencerminkan nilai moral yang mendalam, yang sejatinya sudah menjadi bagian dari kekayaan dunia kita.
Aturan Makan yang “Ketat”
Jeffery D. Long dalam “Jainism: An Introduction” (2009) menyoroti Jain sebagai komunitas religius kecil yang perannya berpengaruh secara signifikan. Meski ideal asketik hanya dicapai oleh sebagian kecil penganut, ajaran mereka terutama prinsip ahimsa atau penghindaran kekerasan, membentuk praktik sehari-hari yang menghormati semua makhluk bahkan hingga tingkat mikroskopik.
Pendekatan ini tentunya menghasilkan etika lingkungan yang kuat dan relevan dengan gaya hidup modern, termasuk kesadaran akan makanan ramah lingkungan.
Penganut Jain menghindari daging, ikan, telur, madu, bahkan sebagian menolak susu dan produk turunannya. Umbi-umbian seperti kentang, wortel, bawang, atau jahe juga tidak dimakan karena mencabut akar yang dianggap membunuh tanaman dan mikroorganisme tanah.
Mereka juga pantang makan setelah matahari terbenam, demi mencegah tanpa sengaja membunuh serangga kecil. Selain itu, makanan fermentasi seperti alkohol, cuka, dan tape dilarang karena melibatkan mikroba, bahkan sebagian buah berbiji banyak dihindari karena dianggap mengandung potensi kehidupan baru.
Larangan dan disiplin ini jelas bukan semata aturan diet, melainkan pancaran dari sebuah filsafat religius yang sudah berakar dalam sejarah panjang India. Untuk memahami kedalaman prinsip Jain, kita perlu melihat cara mereka menafsirkan kehidupan, jiwa, dan tujuan akhir manusia. Dari sinilah tampak bahwa praktik makanan hanyalah salah satu bentuk konkret dari perjalanan batin yang lebih luas.
Ahimsa
Sejak lama, manusia menatap cakrawala dan menelusuri sunyi, mencari Kebenaran yang abadi, yang berdenyut di dalam nadi, di setiap hembus angin pagi, dan di pelupuk mata sendiri.
Dari tanah India yang subur, lahirlah banyak ajaran yang berusaha menjawab kegelisahan itu. Jain Dharma menorehkan cahayanya, menyingkap tabir batin yang tersembunyi. Parveen Jain dalam “An Introduction to Jain Philosophy” (2019) menjelaskan bahwa dalam pandangan Jain, Kebenaran Tertinggi menyinari banyak sudut, menunggu manusia yang mampu melihat dunia tanpa bias.
Dharma dipahami sebagai perjalanan menuju kesucian, di mana jiwa menjadi lentera abadi dan kebahagiaan lahir dari cahaya batin, bukan dari kenikmatan inderawi.
Yang Mulia Mahavira, tirthankara ke-24 yang hidup pada abad ke-6 SM di Bihar, menegaskan bahwa setiap pikiran, kata, dan perbuatan yang menyakiti makhluk lain akan menutupi cahaya jiwa. Dharma, melalui pengetahuan yang benar dan perilaku yang baik, menuntun manusia mengendalikan diri dan hidup selaras dengan semua makhluk.
Ajaran ini dirumuskan dalam lima anuvrata yakni ahimsa (non-kekerasan), satya (kebenaran), asteya (tidak mencuri), aparigraha (tidak serakah), dan brahmacarya (pengendalian diri), dilengkapi praktik meditasi, penghormatan kepada para tirthankara, serta diet vegetarian yang ketat.
Tradisi ahimsa klasik memang menekankan penarikan diri dari dunia, tetapi dalam praktik modern generasi baru Jain memandangnya secara lebih aktif. Lana E. Sims dalam “Jainism and Nonviolence: From Mahavira to Modern Times” (The Downtown Review, 2015) mencatat keterlibatan mereka dalam pelayanan sosial, perlindungan hewan, dan aktivisme lingkungan. Di tengah diaspora, terutama di Amerika Serikat, Jain juga menjadi lebih inklusif terhadap perempuan dan generasi muda, sambil tetap mempertahankan prinsip-prinsip utamanya.
Ahimsa Jain pun menjelma sebagai inspirasi bagi tokoh dan gerakan non-kekerasan dunia, dari Thoreau, Gandhi, hingga Martin Luther King Jr., serta memberi warna pada gerakan lingkungan di Barat. Dari asketisme ekstrem hingga praktik aktif yang berorientasi pada pelayanan, Jain berkembang menjadi jalan spiritual yang menekankan cinta, perlindungan, dan penghormatan terhadap semua makhluk.
Selalu Kembali Pulang pada Pangkuan Ibu Kita
Keberadaan restoran Kehidupan Tidak Pernah Berakhir di Bandung seperti sebuah tanda kecil yang mengingatkan kita bahwa makanan bisa menjadi jembatan antara manusia dan semesta. Menu nabati, piring daur ulang, dan pesan ramah lingkungan yang mereka suguhkan bukan hanya soal selera modern, melainkan undangan untuk melihat makan sebagai tindakan etis.

Dalam skala yang lebih luas, kesadaran ini menemukan gema dalam praktik religius Jain. Bagi penganutnya, ahimsa adalah nafas kehidupan. Di sana, makan bukan sekadar mengenyangkan perut, melainkan cara untuk berjalan lebih ringan di atas kemelut dunia.
Menariknya, jika kita menoleh ke pangkuan ibu kita sendiri, Sunda, nilai-nilai serupa sesungguhnya juga sudah lama hadir dalam budaya makan tradisional. Lalab yang diambil dari kebun atau pekarangan tanpa banyak olahan, kisah Nyi Pohaci yang menekankan kesakralan padi, atau tradisi ngabotram di atas daun pisang yang minim limbah. Semuanya adalah bentuk penghormatan pada kehidupan.
Yumna Alifa dan kawan-kawan dalam “Peran Salapan Cinyusu dalam Pelestarian Budaya Pangan Nabati Sunda dan Dampaknya terhadap Gastro-Tourism” (ETNOREFLIKA, 2024) menunjukkan bahwa praktik ini tidak hanya soal kuliner, melainkan juga cermin hubungan harmonis manusia dengan alam. Ada kesadaran halus bahwa tumbuhan bukan sekadar objek konsumsi, tetapi bagian dari kosmos yang mesti dirawat.
Dari sinilah, kita bisa melihat sebuah benang merah, baik Jain, restoran di Bandung, maupun tradisi pangan Sunda sama-sama menempatkan makanan sebagai jalan etika.
Satu sama lain mengajarkan bahwa pilihan yang sederhana dapat menjadi bentuk kasih, penghormatan, dan tanggung jawab.
Di tengah arus modernisasi, pertemuan nilai ini membuka ruang refleks bahwa makan ramah lingkungan bukan sekadar tren gaya hidup, melainkan cara kita menjaga keseimbangan dengan dunia. Dari piring sederhana di restoran kota kita telah belajar, dan kini setiap suapan adalah janji untuk tidak menyakiti kehidupan. (*)