Beberapa waktu terakhir, isu tentang perubahan identitas agama menjadi “Penghayat Kepercayaan” di kolom KTP kembali ramai diperbincangkan. Fenomena tersebut mengingatkan kita pada tahun-tahun di windu ini yang riuh membahas soal kelompok yang sama, muncul di forum-forum kita.
Kehadiran salam “Rahayu” naik-turun di panggung kenegaraan, sesekali mencuat, kadang tenggelam dalam kesunyian. Menampilkan beragam pandangan dari sesama anak bangsa di balik layar, ada yang betul peduli, sebatas kenal, dan bahkan menaruh curiga.
Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XIV/2016 menjawab sebagian pertanyaan itu, memberi kepastian dan perlindungan hukum bagi hak-hak sipilnya yang wajib dihargai dan dipenuhi oleh negara. Negara pun menyiapkan kerangka administrasi lain melalui Dirjen Bina Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat di Kementerian Kebudayaan, menandai bahwa religiusitas ini memiliki ruang resmi yang sah meski belum sepenuhnya dipandang setara sebagai “agama” sebagaimana Islam, Katolik, Protestan, Hindu, Buddha, atau Konghucu.
Rekognisi ini merambah pada dunia pendidikan. Pada 2021, Program Studi S1 Pendidikan Kepercayaan Terhadap Tuhan Yang Maha Esa (PKT-TYME) resmi didirikan di Universitas 17 Agustus 1945 Semarang, membuka jalur formal untuk mempelajari dan menurunkan tradisi religi dan spiritual lokal.
Berbagai pertanyaan, ketaksaan dan rasa penasaran banyak orang, serta sikap penyelenggara negara pada eksistensi Penghayat Kepercayaan berkelindan menjadi satu seolah mengingatkan kita pada amanat UUD 1945 pasal 29 ayat 2 yang menegaskan bahwa “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.”
Semua ini tampak seperti memberi isyarat bahwa agama di Indonesia tidak pernah berhenti diperbincangkan di ruang yang hampa.
Sebuah Refleksi Kritis
Di tengah denyut nadi kebangsaan yang senantiasa tensinya berubah-ubah, kita kerap melupakan bahwa spiritualitas lokal juga hadir menabur wewarah dan menuturkan kisah keteladanan. Terlebih pada situasi belakangan ini, kita sebagai bangsa tampaknya tiada henti terjebak pada diskursus kulit yang normatif, bermain-main kata dengan bahasa kebijakan publik.
Akhirnya kita terpaksa harus mengarungi ombak yang kurang bersahabat. Jengah melihat berbagai regulasi yang ingkar pada rakyat, melulu merusaki lingkungan hidup, praktik korupsi yang merajalela, hingga sensasi para pejabat yang terus menerus mewarnai layar gawai kita.
Dalam hiruk pikuk ini, kami ada di tengah-tengah Penghayat Kepercayaan, pada rangkaian penelitian demi penelitian, kolaborasi kegiatan, atau sekedar menjalin persaudaraan kebangsaan dengan obrolan ringan. Tak terhindarkan kami menyaksikan betul cara individu dan warga Penghayat bertahan menghadapi pergumulan ini. Bukan kata orang, bukan menurut kabar angin.
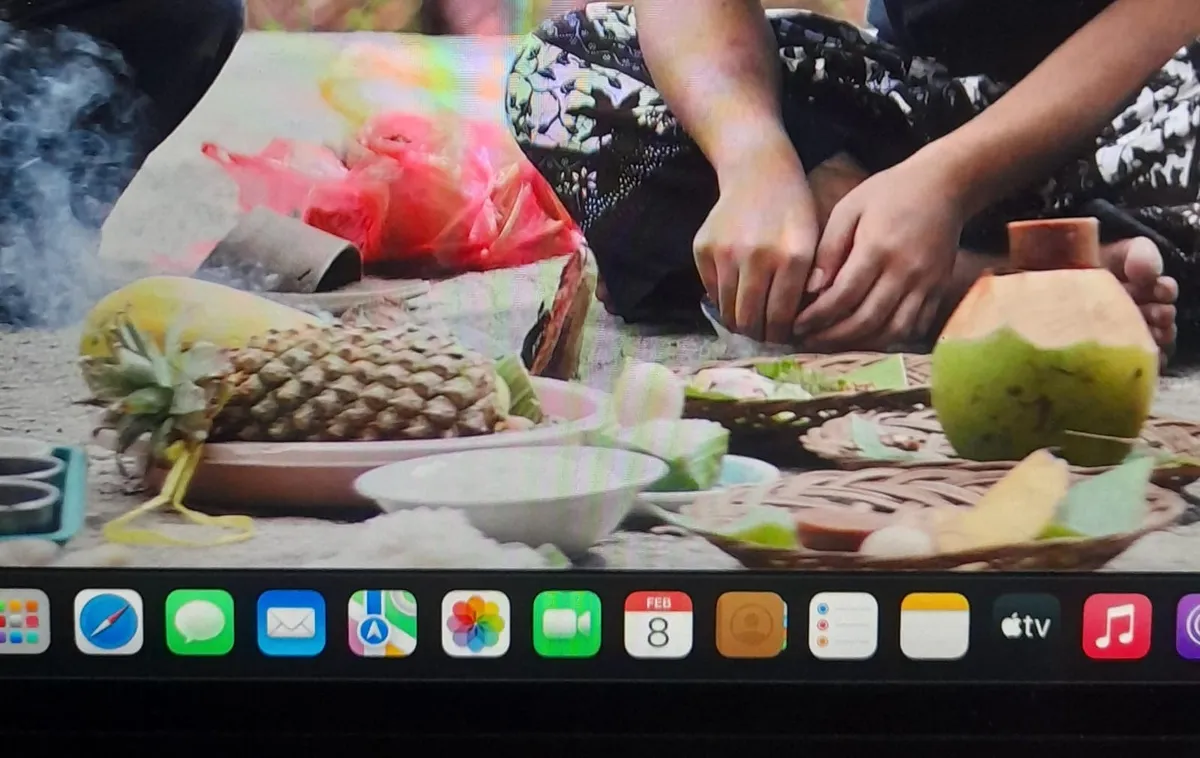
Penghayat Kepercayaan hadir dalam senyap, diusik-usik statusnya saja tanpa mau dikenali lebih mendalam dan manusiawi. Padahal Penghayat Kepercayaan memiliki tiga ajaran hidup yang layak kita telusuri. Buku Saku “Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat” (2021) yang diterbitkan oleh Direktorat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dan Masyarakat Adat, Direktorat Jenderal Kebudayaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi, menyebutnya dengan (1) Menyatu dengan Sumber Hidup, (2) Bermanfaat dalam Hidup, dan (3) Kembali ke Sumber Hidup.
Ajaran ini perlu disingkap, bukan untuk dihakimi tapi untuk digali dalam rangka mengudar prasangka liar yang masih saja bergejolak sampai kiwari. Menjadi tanda ketidaktahuan, menjadi sumbu yang selalu menyulut perpecahan dan kekerasan. Pada sisi yang lain, ia juga setia mencurahkan kebijaksanaan di tengah persimpangan sejarah, kuasa, dan identitas yang terus diperselisihkan. Kami juga merasa penting untuk menangkap spiritnya, guna memahami berbagai tragedi dan komedi kemanusiaan kontemporer yang lebih luas.
Tiga Ajaran Pokok
Manunggaling Kawula Gusti sebagai padanan lain dari ajaran soal menyatu dengan Sumber Hidup bukanlah sekedar mistisisme, tapi nilai yang menegaskan bahwa rakyat dan penguasa berada dalam satu kesatuan yang utuh. Di dunia ini tidak ada kelas dan sekat yang absolut termasuk di antara yang memerintah dan yang diperintah. Ajaran ini tidak hanya romantisasi kosmik, namun gagasan yang brilian tentang martabat dan kesetaraan manusia yang substantif.
Bersatunya hamba dengan tuan-puannya, adalah bahasa yang mesti dimengerti secara kontekstual dalam wajah demokrasi kiwari. Ajaran ini bisa menjadi indikator untuk melihat kualitas republik, misal apakah bangsa ini sudah menjamin penyelenggaraan kebebasan berpendapat, pers, demonstrasi, dan menyuarakan kritik tanpa ditakuti bayang-bayang pembungkaman dan penangkapan yang sewenang-wenang?
Begitupun Memayu Hayuning Bawana sebagai artikulasi ajaran bermanfaat dalam Hidup, membawa kita ke alam dan ruang sosial yang lebih luas. Ia menuntun manusia untuk memperindah dan menjaga dunia, bukan hanya fisik tapi juga sosial dan spiritual. Dalam konteks modern, hal ini bisa dibaca sebagai tanggung jawab ekologis dan sosial. Misalnya saja proyek strategis nasional yang kerap kali mengincar kawasan adat, tanpa memperdulikan kepekaan atas ruang hidup warga yang sedang berlangsung di sana. Papua berkali-kali dipandang sebagai tanah yang kosong.
Penghayat Kepercayaan meyakini bahwa dunia kita adalah jagat rame, yang dihuni bukan hanya oleh makhluk yang bernama manusia. Nilai ini tidak berhenti sebagai tuntutan budi pekerti yang normatif, tetapi kerangka etika yang lebih utuh dalam memandang relasi manusia dengan sesamanya yang dilimpahi percikan ilahi. Artinya mineral bumi, hutan, laut, gunung, dan fauna, mesti dihargai keberadaannya.
Namun sepanjang penyelenggaraan negara masih berpatok pada pengangunan yang semu, yang berorientasi pada keuntungan oligarkis dan mengabaikan aspek keberlanjutan, maka selama itulah kita gagal melaksanakan nasionalisme sebagai sikap mencintai tanah air sendiri dengan sungguh-sungguh.
Terakhir ialah Sangkan Paraning Dumadi padanan dari ajaran kembali ke Sumber Hidup yang membuka tabir kesadaran akan asal usul dan tujuan diri. Seperti dua poin sebelumnya, ajaran ini mengajak kita untuk berani menelusuri lapisan-lapisan kompleks yang membentuk kedirian kita. Kita adalah manusia hibrid, terinskripsi oleh sejarah, terpapar kolonialisme, identitas gender, etnisitas, agama, kelas sosial, hingga trauma tertentu. Membaca nilai ini secara kritis berarti menyadari bahwa identitas kita tidaklah tunggal. Tapi sekaligus kita adalah manusia yang sama.
Tentu relevansinya bertaut jelas dengan semboyan Bhinneka Tunggal Ika sebagai identitas bangsa, yang kerap dalam praktiknya melulu menghadapi tantangan. Jika kita yakin bahwa bangsa ini berasal dari sumber penderitaan penjajahan dan perjuangan kemerdekaan yang sama, mengapa pada akhirnya golongan-golongan tertentu saja yang dapat keistimewaan?
Kita masih banyak PR soal “kebijakan” yang jawasentrisme, keterwakilan perempuan di badan legistatif yang sepertinya mentok pada afirmasi di permukaan, sulitnya pendirian rumah ibadah, hingga akses yang layak bagi orang dengan disabilitas.
Yang Penting Itu Perbuatan
Narasi-narasi di atas adalah buah dialog bertahun-tahun, yang kami tenun dari luar dan dalam khususnya bersama warga Penghayat Kepercayaan di Jawa Barat. Kami celik juga bahwa hal ini tidak lebih dari interpretasi. Sebuah usaha yang diarahkan untuk melahirkan panduan praktis, yang diharapkan bisa menuntun kita pada spiritualitas yang kritis dan beretika.
Dari cara bersalaman, pakaian yang bersahaja, ikhtiar mendidik generasi mudanya, dari sikap bertetangga dan mau berbaur dengan warga lainnya. Bagi kami semua ini tampak berdiri di sebuah puncak gunung es, dari perjalanan panjang diskriminasi sebagaimana didokumentasikan sangat apik dalam karya Samsul Maarif lewat “Pasang Surut Rekognisi Agama Leluhur dalam Politik Agama di Indonesia” (2017).
Kami kira inilah poin penting yang harus kita teladani, yakni mengutamakan “perbuatan” di atas segalanya. Kami pikir di titik inilah seharusnya kita dan negara sama-sama mengambil inspirasi untuk segera bertindak sedini mungkin. Lepas dari identitas keagamaan dan kepercayaan, kita seharusnya lebih banyak berbuat, melakukan perbaikan, aksi konkret dalam rangka menyelenggarakan cita-cita kemerdekaan dengan seadil-adilnya. (*)