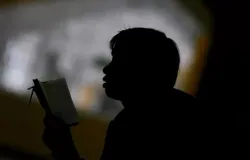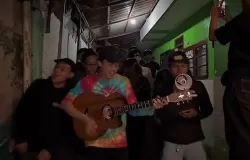AYOBANDUNG.ID - Bandung, kota yang katanya romantis, konon mulai merasa sesak. Bukan karena cinta yang kandas, tapi karena terlalu banyak yang ingin merasakan dinginnya Lembang, gemerlap kafe Dago, dan macetnya Jalan Pasteur. Di tengah kepadatan itu, seorang dosen dari Universitas Padjadjaran, Panji Hadisoemarto, melontarkan sindiran manis namun getir di Threads.
“Orang luar Bandung yang berkunjung ke Bandung, apakah kalian sudah meninggalkan Bandung? Karena orang Bandung juga ada perlu di Bandung.” Kalimat itu seperti undangan untuk bertengkar argumen, tapi dengan tata bahasa yang baik.
Unggahan itu viral. Disaksikan puluhan ribu orang dan dikomentari ratusan, ia membuka kotak Pandora bernama overtourism. Salah satu pengguna, @royhnx, menimpali lantang, “Warga lokal Bandung ternyata enggan dan risih dengan wisatawan.” Ini seperti membaca status mantan dan langsung menyimpulkan dia belum move on—cepat, tajam, dan mungkin salah sasaran.
Panji menanggapi dengan akademis. Ia tak bilang risih, tapi memperingatkan: pariwisata perlu manajemen. Ia menyebut Spanyol sebagai studi kasus; negara itu sedang kerepotan menampung wisatawan sampai rakyatnya turun ke jalan. Bandung, katanya, belum sampai titik itu. Tapi fasilitas umumnya? “Bolehlah dibantu menilai,” katanya.
Lalu debat bergulir seperti ban mobil yang meluncur di flyover Pasupati. @royhnx balik menegur, “Kalau risih sama wisatawan luar Bandung, ya bilang aja.” Ia mengingatkan bahwa wisatawan datang untuk membantu ekonomi, bukan merusak trotoar. Dan trotoar rusak, menurut logika sehatnya, adalah tanggung jawab pemerintah, bukan pelancong yang baru turun dari travel Cipaganti.
Hal apa yang sebenarnya sedang terjadi? Apakah ini overtourism? Bandung memang belum over secara angka, tapi sudah mulai over secara rasa. Ada kesan tersurat bahwa warga lokal mulai merasa menjadi figuran di kota sendiri. Jalanan dipenuhi mobil luar kota. Kafe-kafe lebih ramah pada pengunjung daripada tetangga. Di sinilah letak masalahnya: bukan pada jumlah, tapi pada siapa yang merasa berhak atas ruang.
Overtourism: Ketika Wisata Jadi Beban
Overtourism secara umum didefinisikan sebagai kondisi ketika jumlah wisatawan yang datang ke suatu destinasi melebihi kapasitas yang dapat ditoleransi, sehingga mengganggu kualitas hidup penduduk lokal maupun pengalaman wisatawan.
Istilah overtourism terdengar baru bagi sebagian orang. Namun fenomenanya sudah lama dirasakan di banyak destinasi wisata dunia. Popularitas istilah ini mulai melejit pada 2016 setelah media pariwisata global Skift memopulerkannya. Menurut Skift, overtourism adalah ancaman nyata yang bisa memunculkan masalah sosial, budaya, ekonomi, dan lingkungan. Jika tidak dikendalikan, pariwisata bisa jadi senjata makan tuan.
Organisasi Pariwisata Dunia (UNWTO) mendefinisikan overtourism sebagai “dampak pariwisata pada suatu destinasi atau bagian darinya yang mempengaruhi secara berlebihan kualitas hidup warga dan/atau pengalaman pengunjung dengan cara yang negatif.” Definisi ini menekankan pada aspek persepsi dan pengalaman; baik warga lokal maupun turis bisa mengalami dampak negatif dari lonjakan wisata.
Kamus Oxford bahkan menetapkan overtourism sebagai salah satu Words of the Year tahun 2018. Mereka mendefinisikannya secara sederhana sebagai “suatu situasi ketika tempat wisata dikunjungi oleh terlalu banyak wisatawan.” Di banyak tempat, menurut Oxford, overtourism memicu reaksi keras dari masyarakat setempat.
Fenomena ini umumnya dikenali lewat tanda-tanda seperti kemacetan parah, polusi, lonjakan harga, hingga perasaan terasing yang dialami warga lokal di tempat tinggal mereka sendiri. Ketika protes sudah sampai ke media dan membentuk gerakan sosial, itu pertanda overtourism telah mencapai titik kritis.
Sebuah risalah oleh Ko Koens dan koleganya (2018) menyebut ada lima ciri utama overtourism: padatnya ruang publik (termasuk kemacetan); perilaku turis yang mengganggu; turistifikasi (yakni perubahan ruang kota yang dulunya milik warga menjadi milik industri wisata); penggusuran warga karena gentrifikasi; dan tekanan besar pada lingkungan.
Panorama Overtourism: dari Barcelona hingga Bali
Di Eropa Selatan, kritik terhadap pariwisata berlebih sudah menjadi agenda tahunan. Jaringan aktivis Southern Europe Network Against Touristification bahkan menjadwalkan aksi serentak pada 15 Juni 2025. Di kota-kota seperti Barcelona, Lisbon, hingga Venesia, warga berencana memblokade bus wisata, menggelar unjuk rasa, dan bahkan piket di bandara.
"Kami tidak ingin menyakiti siapa pun. Kami hanya ingin mereka sadar akan dampak kehadiran mereka terhadap tempat ini dan orang-orang yang tinggal di sini," kata Elena Boschi, seorang guru bahasa Inggris dan aktivis dari Genoa, Italia, dikutip The New York Times.
Protes ini bukan barang baru. Pada 2017 lalu, ketegangan akibat lonjakan wisatawan telah muncul di kota-kota seperti Barcelona, Mallorca, San Sebastián, dan Venesia. Di Barcelona, kelompok pemuda radikal Arran bahkan sempat merusak ban sepeda sewaan dan bus wisata.
Di Venesia, kota kecil dengan penduduk sekitar 55 ribu jiwa tetapi menerima lebih dari 20 juta wisatawan per tahun, protes soal polusi dan sewa mahal terus menggema. Di Barcelona, slogan “tourists go home” kembali terdengar pada 2024.

Pariwisata yang semula dianggap berkah perlahan menunjukkan sisi gelapnya. Studi terkait panorama plesir di Barcelona dan Venesia menyatakan overtourism di kedua kota membawa dampak gentrifikasi yang kentara. Data pemerintah kota Barcelona menunjukkan tren penurunan usaha tradisional warga, digantikan oleh bisnis kuliner dan penginapan berbasis wisata. Begitu pula di Venesia: penduduk menyusut, tapi toko dan restoran terus bertambah.
Peneliti menyebut ini sebagai tekanan berlapis: dari mahalnya kebutuhan pokok, sulitnya akses terhadap ruang publik, hingga terkikisnya kehidupan sosial komunitas lokal.
"Pada akhirnya, terdapat tekanan terhadap warga lokal untuk berpindah tempat tinggal akibat aktivitas pariwisata di Barcelona dan Venesia. Penduduk kota terpaksa pindah karena kesulitan menemukan toko untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari, harga barang yang semakin mahal, spekulasi properti, rusaknya kehidupan sosial, meningkatnya kekhawatiran terhadap keamanan, dan berkurangnya akses ke ruang publik akibat privatisasi," papar peneliti.
Di Indonesia, Bali kerap dirujuk sebagai contoh kasus. Pulau Dewata sering kali masuk dua daftar sekaligus: destinasi terbaik dan destinasi yang paling terdampak overtourism.
Dalam laporan Time bertajuk Can Bali Ever Solve Its Overtourism Conundrum? yang terbit Maret 2025 lalu, jurnalis Chad de Guzman menyebutkan bagaimana keberadaan wisatawan asing bergerak dalam bandul paradoks. Selain menggerakkan ekonomi lokal, mereka juga menjadi sumber dari sejumlah persoalan mendasar: kemacetan, pelanggaran norma adat, kerusakan lingkungan, dan ketegangan sosial.
“Wisatawan asing di Bali adalah penggerak utama ekonomi sekaligus sumber masalah terbesar. Wisatawan yang berperilaku buruk menyebabkan kemacetan, keributan publik, menyinggung nilai-nilai lokal, mencemari lingkungan, dan merusak situs-situs suci,” tulis de Guzman.
Firma travel guide berbasis di Amerika Serikat (AS), Fodor's, bahkan menempatkan Bali di posisi teratas dalam No List 2025, daftar tempat-tempat yang dinilai paling terdampak oleh pariwisata berlebihan. Sementara itu, Condé Nast Traveller justru menobatkan Bali sebagai pulau terbaik di Asia tahun 2024. Citra Bali jadi penuh ironi: dicintai sekaligus dikeluhkan.
Pada 2023, organisasi global seperti World Travel and Tourism Council (WTTC) menyatakan Bali tengah mengalami overtourism. Sementara CNN International menyebut Bali sebagai salah satu destinasi dengan tingkat overtourism terburuk di dunia.
Peneliti pariwisata I Wayan Suyadnya berpendapat bahwa Bali sudah overtourism. Dalam risalah di Jurnal Sosiologi Masyarakat (2021), ia mengurai bagaimana transformasi yang mencirikan gentrifikasi di kawasan Sanur, Kuta, dan Ubud dapat ditelusuri melalui beberapa tahapan waktu. Sebelum pariwisata, masyarakat Sanur, Kuta, dan Ubud hidup sebagai petani dan nelayan.
Di Ubud, transformasi dimulai tahun 1937 ketika Tjokorde Gede Raka Sukawati mengubah rumah Walter Spies menjadi guesthouse, cikal bakal “desa wisata.” Sanur berkembang setelah Soekarno membangun Hotel Bali Beach tahun 1963, disusul pembentukan Yayasan Pembangunan Sanur pada 1965. Kuta mulai dilirik wisatawan sejak 1960-an oleh para hippie; warga menyewakan kamar rumah mereka seharga satu dolar semalam.
Gentrifikasi menguat sejak 1980–1990-an saat pemerintah gencar mempromosikan Bali lewat event budaya dan pariwisata. Modal besar masuk menggandeng pengusaha lokal. Pada 2010, tercatat 184.182 migran masuk Bali, 45 persen di antaranya ke Sanur, Kuta, dan Ubud, mayoritas bekerja di sektor jasa informal.
Kini, ketiga kawasan ini menunjukkan ciri gentrifikasi pariwisata: perubahan demografi, tekanan pada ruang hidup, dan budaya lokal yang tergusur. Pariwisata tumbuh liar hingga memicu overtourism, meninggalkan warga dalam posisi tawar yang kian lemah.
"Kondisi ini menandakan bahwa perkembangan pariwisata Bali sudah harus dikaji dalam kerangka overtourism, terutama dengan menurunnya kualitas destinasi. Gentrifikasi bisa dibaca sebagai alarm atas situasi ini."
Tapi tidak semua pihak sependapat dengan label tersebut. Menteri Pariwisata Indonesia, Widiyanti Putri Wardhana, membantah bahwa Bali mengalami overtourism. Menurutnya, kepadatan di destinasi tertentu bukan karena jumlah wisatawan yang berlebih, melainkan karena penyebaran wisatawan yang belum merata karena menumpuk di Bali bagian selatan.
Ia menegaskan potensi wisata di bagian utara dan barat Bali masih sangat besar namun belum tergarap optimal. “Kementerian Pariwisata tidak tinggal diam,” kata Menpar. Pada September 2024, pemerintah telah meluncurkan paket wisata 3B yakni Banyuwangi–Bali Barat–Bali Utara, yang diharapkan dapat mendorong pemerataan kunjungan wisatawan. Paket tersebut mencakup destinasi berbasis alam, budaya, desa wisata, hingga produk wisata buatan.
Bandung di Bawah Bayang-Bayang Gentrifikasi
Bandung mungkin belum masuk daftar merah destinasi overtourism global seperti Bali atau Venesia, tetapi gejalanya mulai tampak. Ciri-ciri klasik overtourism seperti yang dipetakan oleh Ko Koens—kemacetan, turistifikasi, tekanan lingkungan, dan gentrifikasi—tak sulit dirasa.
Setiap kali libur panjang tiba, antrean mobil mengular masuk kota. Jalan-jalan di Dago, Lembang, hingga Punclut mendadak berubah jadi lautan kendaraan. Lalu lintas macet, ruang gerak menyempit, dan warga lokal memilih mengurung diri di rumah. Warung kopi di sudut-sudut gang disulap jadi tempat nongkrong estetik viral berumur pendek, lahan kosong cepat berubah menjadi café with a view—menciptakan gejala yang disebut turistifikasi.
Tekanan terhadap lingkungan? Jangan ditanya. Debit air menurun, sampah naik, ruang terbuka hijau menyusut. Lahan-lahan miring di perbukitan yang dulunya kosong kini berdiri vila dan resor. Dan di balik semua itu, proses gentrifikasi berlangsung diam-diam—penduduk lama hengkang, berganti dengan wajah-wajah baru yang bisa membeli harga baru.

Di Bandung, geliat pariwisata kerap tak sepenuhnya berlangsung di jantung kota. Justru, denyut paling kuat dari sirkulasi kapital turisme terasa di kawasan pinggiran yang berhawa sejuk. Area perbukitan di luar kota menjadi medan utama bagi aktivitas plesir—mulai dari wisata alam, hamparan kebun bunga, hingga glamping yang kian menjamur. Sementara pusat kota lebih sibuk dengan wisata kuliner, sejarah, dan belanja, arus utama pembangunan sektor wisata justru mendorong perubahan signifikan di wilayah rural.
Gentrifikasi, sebagai gejala yang tak bisa diabaikan, terus muncul sepanjang epos. Di Awiligar, kawasan Dago misalnya, geliat perubahan ruang dan sosial sudah mulai tercatat sejak 1990-an.
Studi etnografi peneliti dari UGM menulis bahwa antara 1990 hingga 1997, warga kampung di kawasan Dago mulai menjual tanahnya ke pengembang Dago Resort yang membangun kawasan wisata dan hunian mewah. Dari transaksi itu, lahirlah deretan fasilitas elite seperti Intercontinental Bandung Dago Pakar, Mountain View Golf Club, Kencana Resort Club, hingga Marbella Suites Bandung.
Setelah menjual tanah, sebagian warga kampung pindah ke kota kecil seperti Indramayu, Garut, hingga Tasikmalaya. Namun, mayoritas memilih pindah ke sekitaran Awiligar karena aksesibilitasnya. Perpindahan ini menyebabkan kepadatan penduduk meningkat tajam di kampung-kampung Cibeunying. Di tengah kawasan hunian dan hotel mewah, sisa-sisa komunitas lokal kini terhimpit di ruang-ruang yang kian sempit.
Cihideung di Bandung Barat pun mengalami dinamika serupa. Dalam laporan yang mengukur gentrifikasi di kawasan tersebut, dipaparkan bahwa sejak akhir 1990-an lahan pertanian mulai terkonversi menjadi bangunan dan fasilitas wisata. Transformasi ini turut mendorong petani untuk beralih dari menanam sayur ke bunga hias demi meraih keuntungan lebih besar. Sebelumnya, desa ini sejak era kolonial telah dikenal sebagai kawasan perkebunan teh dan kopi.
Perubahan semakin masif ketika sekitar 220 hektare lahan diubah menjadi destinasi wisata besar bernama Kampung Gajah yang kini terbengkalai. Setelah itu, investor berlomba-lomba membangun vila, restoran, kafe, hingga spa. Peneliti mencatat beberapa perubahan memang membawa manfaat, seperti pertumbuhan ekonomi dan perbaikan akses spasial. Namun, di balik itu muncul sejumlah dampak negatif, terutama terhadap lingkungan dan budaya lokal.
"Selain itu, tekanan yang muncul meliputi kenaikan harga properti, kebisingan, dan polusi—gejala khas gentrifikasi wisata secara global, di mana pariwisata menyebabkan penggusuran penduduk lokal serta transformasi lingkungan tradisional menjadi kawasan berorientasi wisata."
Studi juga menunjukkan sebagian warga yang tergusur justru memperoleh kompensasi finansial yang memungkinkan mereka meningkatkan kualitas hidup. Namun demikian, ditemukan pula bahwa aspek lingkungan dan tata ruang belum optimal. Desa ini belum bisa disebut sepenuhnya layak huni karena tekanan terhadap lingkungan meningkat dan tata ruang tidak selalu sesuai dengan kebutuhan warga.
"Penilaian menunjukkan bahwa aspek sosial dan ekonomi mendapat nilai tinggi, namun aspek lingkungan dan spasial berada di bawah nilai maksimal."
Fenomena pertumbuhan Airbnb di Bandung juga menunjukkan wajah baru dinamika hunian jangka pendek di kota ini. Penelitian di jurnal City, Culture and Society yang terbit Desember 2023 mencatat dalam lima tahun terakhir, dari 2013 hingga 2018, jumlah listing di platform tersebut meningkat tajam, terutama terkonsentrasi di wilayah utara seperti Hegarmanah, Dago, dan Cipaganti.
"Ketiga kelurahan ini terletak di Kecamatan Coblong dan Cidadap, yang berada di wilayah utara Kota Bandung. Namun demikian, beberapa kelurahan di Bandung tidak memiliki listing Airbnb sama sekali."
Secara umum, sebagian besar kelurahan di Bandung mengalami tren stabil atau naik dalam jumlah listing Airbnb, meskipun tidak semua menunjukkan pola yang signifikan secara statistik. Menariknya, tidak ada satu pun kelurahan yang mencatatkan tren penurunan. Ini menunjukkan bahwa pasar hunian sementara masih terus tumbuh dan merambah ke berbagai sudut kota, sekaligus memberi sinyal akan berubahnya wajah hunian di Bandung.
Belum ada konsensus yang lantang menyatakan Bandung ada di ambang overtourism, namun gejala menuju ke arah sana boleh jadi tak terbendung. Seperti halnya gentrifikasi, prosesnya sering kali berjalan tanpa perlu deklarasi.
Seperti selebritas yang menolak tua, Bandung terus merias wajahnya dengan destinasi baru. Setiap lekuk jalan harus instagramable, setiap sudut bisa dijadikan konten. Tapi di balik semua itu, ada kerutan yang tak bisa disamarkan: hilangnya ruang tinggal, naiknya harga tanah, dan kian jauhnya warga dari rumahnya sendiri. Kota ini memang tak menua, tapi warganya sudah terlalu lelah.