AYOBANDUNG.ID - Bagi sebagian orang, cerobong Pembangkit Listrik Tenaga Uap (PLTU) mungkin hanya terlihat sebagai bagian dari lanskap industri—tinggi, menjulang, dan kerap dianggap simbol pasokan listrik yang menjaga kota tetap menyala. Namun bagi warga yang tinggal tak jauh dari sana, cerobong itu menjadi penanda perubahan dalam hidup mereka. Perubahan yang tidak pernah mereka minta.
Suasana diskusi publik itu tidak hanya diisi paparan data dan grafik. Satu per satu warga berdiri dan menceritakan pengalaman hidup di sekitar PLTU. Kisah mereka datang dari wilayah berbeda, tetapi memiliki benang merah yang sama: perubahan lingkungan dan rasa cemas yang terus tumbuh.
Cirebon
Sarjum, warga Desa Kanci Kulon, Cirebon, masih mengingat jelas kondisi pesisir sebelum PLTU berdiri. Sejak kecil, ia mencari kerang dan ikan di laut dangkal. Bermodalkan ban dalam mobil, ia bisa membawa pulang lauk untuk keluarga.
“Dulu kalau cuma ada nasi di rumah, saya tinggal ke laut. Setengah jam sudah dapat kerang atau ikan. Bahkan bisa dijual,” katanya.
Ia menyebut kerang bangku, kerang kukur, dan rajungan sebagai hasil tangkapan yang dulu mudah ditemukan. Pada akhir pekan, pesisir bahkan ramai oleh warga dari luar daerah yang ikut mencari hasil laut.

Namun sejak proses pengurukan lahan pada 2007 dan PLTU mulai beroperasi pada 2012, menurutnya kondisi berubah drastis.
“Sekarang cari sepuluh biji saja susah. Yang ada cangkangnya saja. Kalau ikan, satu pun sekarang susah,” ujarnya.
Kini, di usia 47 tahun, Sarjum mengatakan banyak nelayan pesisir terpaksa beralih profesi. Ada yang menjadi buruh bangunan, ada pula yang bekerja serabutan. Ia sendiri tidak lagi sepenuhnya bergantung pada laut.
“Saya dan teman-teman sudah jarang melaut karena susah. Sekarang kerja apa saja, kadang di bangunan, yang penting dapur ngebul,” katanya.
Bekerja di PLTU bukan pilihan mudah bagi warga sekitar.
“Mau kerja di PLTU minimal ijazah SMP atau S1. Itu pun kadang harus bayar Rp2 juta sampai Rp5 juta. Belum tentu keterima,” ujarnya.
Ia menggeleng. “Uang segitu buat beli beras bisa dapat dua sampai lima karung.”
Sejak pembangkit beroperasi, Sarjum juga merasakan perubahan lingkungan. Debu lebih sering menempel di rumah, udara terasa berbeda, dan kekhawatiran tumbuh perlahan di antara warga.
“Dulu kami hidup biasa saja. Sekarang rasanya selalu ada yang mengganjal. Debu sering ada, anak-anak batuk. Kami tidak tahu persis apa yang terjadi di dalam sana, tapi ini yang kami rasakan,” ujarnya.
Bagi Sarjum, yang paling berat bukan hanya kondisi fisik lingkungan, tetapi rasa tidak didengar.
“Kami ini hidup di sini, bukan datang sementara. Kalau ada dampak, ya kami yang paling dulu merasakan. Harusnya kami juga yang paling dulu diajak bicara,” katanya.
Rumahnya berjarak sekitar 500 meter dari area PLTU. Debu batu bara kerap terlihat, terutama saat musim kemarau.
“Kalau kemarau, meja di pinggir jalan hitam. Di rumah juga banyak debu,” ujarnya.
Sebagai ketua RW, ia juga mencatat peningkatan keluhan kesehatan.
“Dalam satu dusun pernah 27 orang meninggal dalam sebulan. Banyak yang sesak napas,” katanya.
Ia mengingat, sejak awal proyek dimulai pada 2007, tidak ada sosialisasi memadai.
“Enggak ada amdal, enggak ada sosialisasi ke nelayan. Tahu-tahu mau dibangun besar,” ujarnya.
Menurutnya, sosialisasi baru dilakukan setelah alat berat masuk.
“Sosialisasi itu datang belakangan, tahun 2009. Dua tahun setelah pengurukan,” katanya.
Ia mengaku cucunya pernah dirawat karena gangguan pernapasan. Karena itu, sejak awal ia aktif menyuarakan penolakan.
“Saya bukan melawan untuk diri sendiri. Saya mau selamatkan anak cucu dan warga ke depan,” ujarnya.
Pada 2017 dan 2023, Sarjum bahkan berangkat ke Jepang untuk menggugat lembaga pendana PLTU.
“Saya ketemu langsung direkturnya. Media Jepang siaran langsung. Tapi sampai sekarang belum ada tindakan,” katanya.
Menurutnya, persoalan ini bukan sekadar proyek.
“Kalau dulu menjajah pakai perang, sekarang pelan-pelan lewat proyek besar. Masyarakat dibunuh perlahan,” ujarnya.
Di pesisir Cirebon, laut mungkin masih membentang luas. Namun bagi Sarjum, ruang hidupnya terasa makin sempit. Selama masih mampu berdiri, ia memilih terus menggugat.
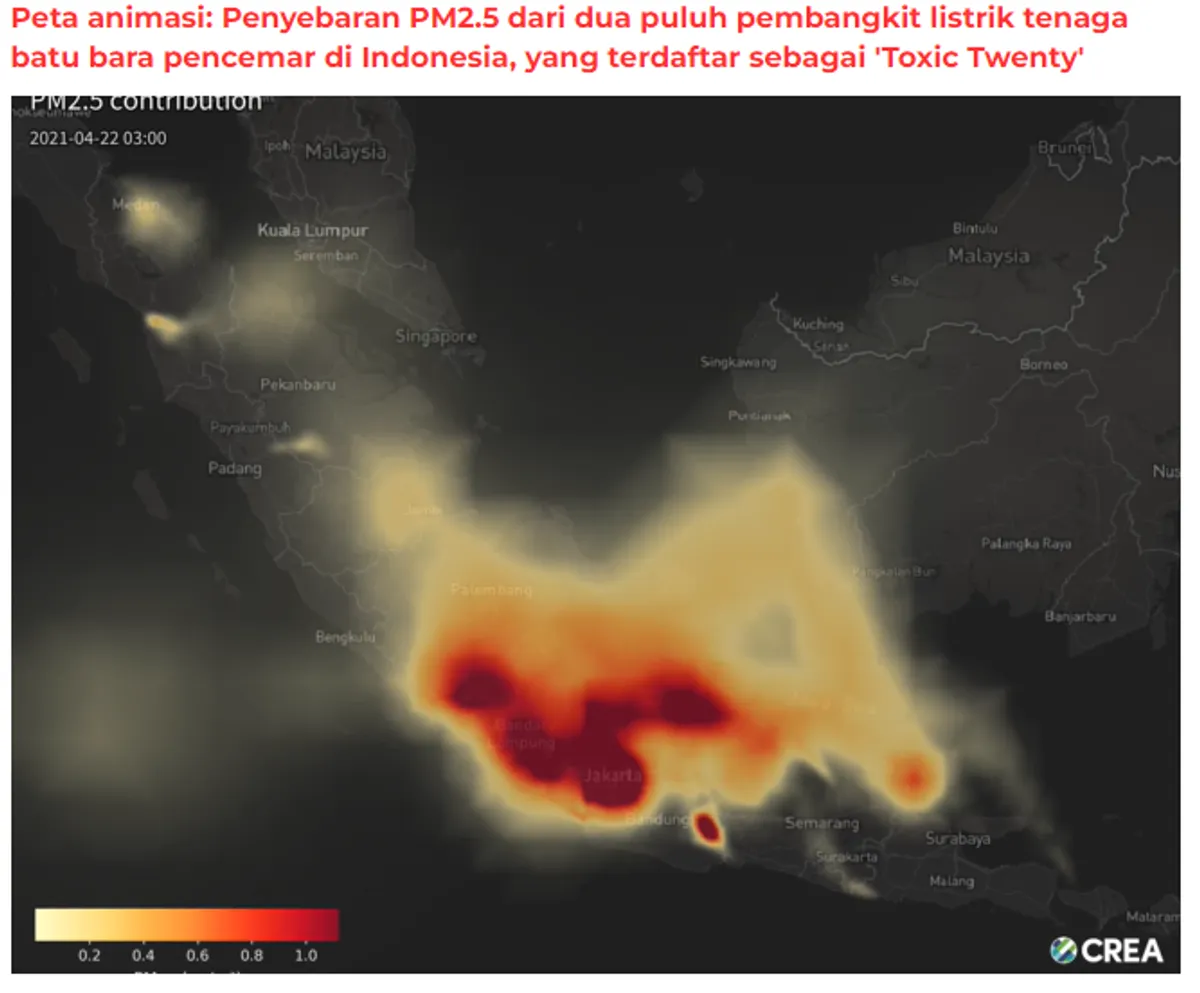
Indramayu
Cerita serupa datang dari Desa Mekarsari, Kecamatan Patrol, Indramayu. Ahmad Yani, warga setempat, menuturkan perubahan sejak PLTU beroperasi.
“Kalau angin kencang, debunya masuk ke rumah,” katanya.
Mayoritas warga desa itu adalah petani dan buruh tani. Sawah bukan sekadar mata pencaharian, tetapi warisan hidup.
“Dulu tanah kami subur. Apa saja tumbuh,” ujar Ahmad.
Kini, ia merasakan perubahan.
“Setelah dipupuk, bukan makin subur, malah seperti mati. Padi tumbuh, tapi hasilnya putih semua,” katanya.
Ia menyebut banyak pohon kelapa mati setelah PLTU beroperasi.
“Dulu sekali panen bisa lima truk. Sekarang cari satu saja susah,” ujarnya.
Ketika rencana pembangunan PLTU 2 muncul, warga mulai melawan.
“Karena dampak PLTU 1 sudah kami rasakan,” katanya.
Perlawanan itu tidak mudah. Sejumlah warga mengalami kriminalisasi.
“Tujuh orang pernah kena. Tapi kami tetap berjuang,” ujarnya.
Bagi Ahmad, perjuangan ini soal mempertahankan hak hidup.
“Kami hanya ingin lahan subur lagi dan bisa menanam dengan tenang,” katanya.
Sukabumi
Dari pesisir dan sawah, cerita berlanjut ke hulu hutan Sukabumi. Fajri Mulyono, Ketua LMDH Waluran Mandiri, tinggal di kawasan hutan Hanjuang Barat.
“Kampung kami memang sejak dulu di dalam hutan. Ini hutan titipan,” katanya.
Wilayah ini menjadi sumber air bagi banyak kecamatan di Sukabumi Selatan.
“Kalau hulu rusak, yang kena bukan cuma kami,” ujarnya.
Kekhawatiran Fajri muncul sejak program co-firing biomassa disosialisasikan.
“Produksinya lima ton per jam. Kami langsung berpikir, kayunya dari mana?” katanya.

Ia khawatir pembukaan lahan merusak resapan air. Kekhawatiran itu menguat setelah banjir dan longsor pada Desember 2024.
“Air jadi keruh, rumah tersapu. Dulu tidak pernah sebesar itu,” ujarnya.
Menurutnya, pembukaan lahan berkontribusi pada bencana.
“Resapan sudah tidak normal,” katanya.
Sebagai Ketua LMDH dengan 230 anggota, ia memilih bersuara.
“Kami menolak bukan karena anti pembangunan, tapi takut hutan kami hancur,” ujarnya.
Di tengah keterbatasan, ia memilih jalan sederhana: menanam dan mengedukasi generasi muda.
“Sanajan saetik tapi mahi. Sedikit tapi berarti,” katanya.
Cerobong-cerobong itu mungkin tetap menjulang, menjaga kota tetap terang. Di atas kertas, ia simbol kemajuan.
Namun di Cirebon, laut tak lagi seberlimpah dulu. Di Indramayu, tanah tak lagi seramah masa lalu. Di Sukabumi, hutan mulai dihitung sebagai bahan baku.
Sarjum berbicara tentang laut yang menyempit. Ahmad Yani tentang sawah yang kehilangan kesuburan. Fajri tentang hulu yang perlahan dibuka.
Mereka hidup di wilayah berbeda, dengan lanskap tak sama. Namun satu benang merah menyatukan cerita mereka: ruang hidup yang berubah tanpa pernah benar-benar mengajak mereka menentukan arah perubahan itu.
Mereka tidak berbicara dengan bahasa teknis. Mereka berbicara tentang rumah, udara, sekolah, anak-anak, dan masa depan—serta harapan agar suara mereka tidak berhenti di ruang diskusi.






















