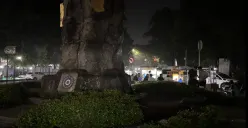AYOBANDUNG.ID - Di balik lalu-lalang kendaraan dan riuhnya pasar tradisional Majalaya, ada jejak sejarah yang tak lekang oleh waktu. Kampung kecil di Kabupaten Bandung ini pernah menjelma menjadi poros penting industri tekstil Indonesia. Saking besarnya kontribusi ekonomi yang dihasilkan dari ekspor kain dan sarung tenun, Majalaya dijuluki “kota dolar” sejak dekade 1970-an hingga 1990-an. Namun seperti banyak kejayaan lain, masa emas itu kini tinggal kenangan yang perlahan memudar bersama bunyi mesin tenun yang tak lagi nyaring terdengar.
Dalam Menelusuri Jejak Sarung Tenun di Kota Dolar, Peneliti Balai Pelestarian Kebudayaan Jawa Barat, Risa Nopianti menyebut industri tekstil Majalaya bermula dari aktivitas rumahan. Sejak sebelum abad ke-20, masyarakat sudah mengenal alat tenun bukan mesin (ATBM) seperti gedogan atau kentreung, yang digunakan dalam posisi duduk bersila. Lebarnya sempit, sekitar 60 cm, cukup untuk menghasilkan kain sarung berukuran kecil. Pada masa itu, alat ini banyak digunakan oleh ibu rumah tangga yang menenun di sela-sela kesibukan domestik mereka.
Perubahan besar terjadi ketika mesin tenun tustel masuk ke Desa Namicalung pada 1940-an. Alat ini memungkinkan pembuatan kain dengan lebar dua kali lebih besar dan waktu produksi yang jauh lebih singkat. Jika sebelumnya satu lembar kain tenun memerlukan waktu satu hingga dua minggu untuk diselesaikan, maka dengan tustel, produksi bisa rampung dalam dua hingga empat hari. Kemajuan ini memicu pertumbuhan industri skala rumahan yang masif.
Desa Namicalung kemudian dikenal sebagai pusat kelahiran sarung tenun khas Majalaya. Sejak 1960-an, hampir setiap rumah di desa ini memiliki mesin tustel. Sebagian besar rumah tangga memproduksi sarung secara mandiri dan menjualnya melalui pengepul yang tersebar di Bandung dan sekitarnya. Produksi meningkat tajam, dan permintaan pasar tak hanya datang dari dalam negeri tetapi juga dari luar negeri, terutama kawasan Timur Tengah dan Afrika.
Baca Juga: Hikayat Dinasti Sunarya, Keluarga Dalang Wayang Golek Legendaris dari Jelekong
Tenun Majalaya punya motif sangat khas, dengan corak kotak-kotak yang dalam istilah lokal disebut poleng. Terdapat setidaknya 12 motif utama yang berkembang, di antaranya poleng camat, poleng goyobod, poleng salur, gudang garaman, hingga samarindaan dan kapiyur. Setiap motif punya cerita dan fungsi sosialnya masing-masing, menjadikan sarung Majalaya lebih dari sekadar produk tekstil—ia adalah artefak budaya.
Kota Dolar yang Tergerus Waktu
Puncak kejayaan Majalaya sebagai kota dolar terjadi pada era 1980-an. Salah satu pabrik besar di daerah ini bahkan mampu memproduksi hingga 90.000 kodi sarung per bulan. Produk mereka laris manis di pasar ekspor, mencetak devisa negara dalam jumlah besar. Merek-merek seperti Dua Gajah, Al-Majali, dan Al-Jazuli menjadi simbol kejayaan tekstil lokal yang mendunia.
Tapi masa kejayaan itu mulai redup menjelang akhir dekade 1980-an. Pemerintah saat itu memberlakukan pembatasan impor benang katun dari Jepang dan Tiongkok sebagai bagian dari strategi ketahanan industri dalam negeri. Akibatnya, pengrajin tenun di Majalaya mengalami kesulitan mendapatkan bahan baku utama. Produksi terganggu, dan rumah-rumah tenun perlahan mulai gulung tikar.

Di saat yang sama, para pemodal besar, terutama dari komunitas Tionghoa, mulai membangun pabrik-pabrik tekstil modern di Majalaya. Mereka menguasai sistem distribusi dan bahan baku, memperkuat dominasi mereka di sektor hulu dan hilir industri tekstil. Pada awal 1940-an saja, pemodal Tionghoa telah menguasai lebih dari sepertiga alat tenun tangan di wilayah Bandung. Pada 1942, dominasi mereka di Majalaya meningkat drastis, dengan kendali atas lebih dari 75 persen pabrik tekstil yang ada.
Baca Juga: Puting Beliung Rancaekek Sudah Terjadi Sejak Zaman Belanda
Industri rumahan pun tak kuasa bersaing. Mereka tidak punya cukup modal, kehilangan akses terhadap benang, dan tak mampu mengimbangi efisiensi produksi pabrik besar. Ketergantungan kepada sistem pengepul dan tengkulak membuat posisi mereka semakin rentan. Dalam waktu dua dekade, sebagian besar rumah tenun tradisional di Namicalung dan sekitarnya berhenti beroperasi.
Sejalan dengan kedaan, motif-motif khas Majalaya pun mulai hilang dari pasaran. Pasar lebih tertarik pada kain tenun dari daerah lain seperti songket, ulos, tapis, dan tenun ikat yang dianggap lebih eksotik dan komersial. Alih-alih memproduksi motif sendiri, banyak pabrik tekstil di Majalaya kini justru memproduksi ulang motif tradisional dari berbagai daerah Indonesia untuk dijual kembali ke daerah asalnya. Majalaya beralih peran: dari pusat inovasi menjadi pusat distribusi.
Upaya Lestarikan Warisan yang Kian Samar
Kehilangan motif khas dan mesin-mesin tenun tradisional menggugah kesadaran sebagian warga untuk mencoba membangkitkan kembali warisan yang nyaris punah ini. Di Desa Namicalung, masih ada beberapa artefak sarung tenun yang dibuat antara tahun 1930 hingga 1960-an. Keberadaannya menjadi pengingat bahwa Majalaya pernah punya identitas kuat sebagai penghasil sarung tenun terbaik di Jawa Barat, bahkan Indonesia.
Tapi upaya pelestarian ini tidak mudah. Keterampilan menenun hampir tidak diwariskan lagi ke generasi muda. Pengetahuan tentang konstruksi alat tenun, teknik pewarnaan, hingga penciptaan motif nyaris hilang. Mereka yang masih menguasainya kebanyakan sudah sepuh. Dibutuhkan pelatihan, dukungan pemerintah, serta komitmen kolektif dari berbagai pihak agar tradisi tenun Majalaya tidak benar-benar hilang dari peta budaya.
Baca Juga: Sejarah Gang Tamim, Pusat Permak Jins Sohor di Bandung
Kini, Majalaya masih menjadi salah satu sentra tekstil terbesar di Indonesia, tapi dengan wajah yang berbeda. Suara mesin-mesin besar telah menggantikan denting ritmis kentreung dan tustel. Dan meski julukan “kota dolar” masih dikenang, ia tak lagi menggambarkan realitas ekonomi warga di sana.