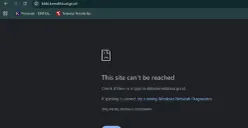Beberapa hari terakhir, di dekat rumah hadir sebuah alat berat bernama stum atau vibro roller. Alat ini digunakan untuk memadatkan permukaan tanah dan aspal agar lebih rata, kuat, dan halus. Biasanya stum kita jumpai dalam proyek pembangunan jalan, jembatan, atau kawasan industri.
Namun bagi saya, kehadiran stum bukan sekadar tanda proyek infrastruktur. Ia justru menjadi pintu kenangan yang membawa ingatan kembali ke era 1980-an, saat saya masih duduk di bangku sekolah dasar.
Kala itu, jika ada stum meratakan jalan di dekat kampung, saya dan teman-teman selalu menyempatkan diri menonton. Sepulang sekolah atau sore hari, kami berkumpul di pinggir jalan, terpaku menyaksikan mesin besar itu bergerak perlahan sambil menggetarkan tanah. Ketika pekerja berhenti dan stum beristirahat, kami memberanikan diri meminta izin kepada operator untuk sekadar naik dan duduk di atasnya. Kadang kami bahkan diizinkan ikut naik sebentar saat mesin berjalan. Betapa bangganya kami. Pengalaman itu menjadi cerita seru yang dengan penuh antusias kami bagikan kepada teman-teman lain.
Bukan hanya anak-anak yang tertarik. Orang dewasa pun ikut menyaksikan. Ibu-ibu datang sambil menyuapi anak kecilnya, bapak-bapak mengangkat anak lelaki mereka ke pundak agar bisa melihat lebih jelas. Di sekitar lokasi proyek, tercipta suasana silaturahmi alami: berbincang, bercanda, dan berbagi cerita sambil menyaksikan pembangunan jalan desa. Sebuah hiburan sederhana yang menyatukan warga.

Pada masa itu, hiburan memang terbatas. Televisi masih hitam putih dan acaranya belum beragam. Dunia anak-anak lebih banyak berlangsung di luar rumah: bermain petak umpet, gatrik, kelereng, gobak sodor, dan berbagai permainan kreatif lainnya. Pelepah pisang bisa berubah menjadi pedang atau kuda-kudaan, pelepah kelapa menjadi kendaraan mainan yang ditarik bersama. Luka lecet di lutut atau siku bukan alasan berhenti bermain. Yang ada hanyalah tawa, keberanian, dan kebersamaan.
Jalan Raya Margahayu–Soreang pada tahun 1980-an sudah beraspal dan dua arah, tetapi belum selebar dan sepadat sekarang. Di sepanjang Margahayu, Katapang hingga Soreang, hamparan sawah, kebun, dan pepohonan rindang masih mendominasi. Kendaraan yang melintas pun terbatas: angkutan pedesaan, bus Bandung–Ciwidey, sepeda motor lawas, sepeda, serta delman atau gerobak.
Sore hari menjadi waktu favorit kami. Kami bergerombol di pinggir jalan menyaksikan kendaraan lalu-lalang. Jika ada gerobak lewat, kami berlari menghampiri dan bergelayut di bagian belakangnya. Dua anak di kiri dan kanan, berlomba siapa yang paling lama bertahan. Tidak ada rasa takut jatuh, yang ada hanya rasa bangga dan kegembiraan khas masa kanak-kanak.
Baca Juga: Bahasa Terus Tumbuh, tapi Negara Selalu Tertinggal? Membaca Ulang Arah KBBI di Era Digital
Semua itu terasa sangat berbeda dengan kondisi anak-anak saat ini. Kemajuan teknologi informasi dan digitalisasi telah banyak mengubah pola interaksi sosial generasi muda. Anak-anak kini lebih akrab dengan gawai, layar, dan dunia virtual. Interaksi langsung semakin berkurang, kreativitas spontan mulai tergeser, dan daya tahan menghadapi tantangan sering kali melemah karena terbiasa dengan serba instan.
Teknologi ibarat dua sisi mata pisau. Ia sangat bermanfaat jika digunakan secara bijak: memudahkan belajar, membuka akses informasi, dan memperluas wawasan. Namun jika tidak terkontrol, ia dapat melukai: mengurangi empati sosial, kedekatan keluarga, dan kepekaan lingkungan. Banyak peringatan sudah disampaikan melalui seminar, kajian, maupun media, namun kesadaran kolektif masih menjadi pekerjaan rumah bersama.
Pada akhirnya, kemajuan zaman tidak dapat dihindari. Yang dapat kita pilih adalah bagaimana menyikapinya. Mengambil manfaatnya tanpa kehilangan nilai-nilai kebersamaan, keberanian, kreativitas, dan kedekatan sosial yang dahulu membentuk karakter kita. Seperti stum yang memadatkan jalan agar kokoh dilewati, semoga kenangan masa lalu juga memadatkan nilai-nilai kehidupan kita agar tetap kuat melangkah di tengah perubahan zaman. (*)