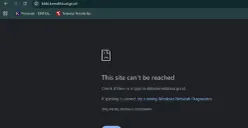Siang itu di ruang kelas, saya ingin menguji sebuah hipotesis sederhana: apakah nilai-nilai lama masih punya tempat di telinga generasi masa kini? Sebagai mahasiswa PPK (Praktik Profesi Keguruan), saya mencoba membuka kelas dengan sebuah amunisi klasik yang dulu menjadi pegangan hidup saya saat menghadapi badai kegalauan memilih PTN hingga karya yang tak terapresiasi kawan sebaya.
Saya pun berujar dengan mantap: 'Ingat ya, anjing menggonggong kafilah berlalu.'
Saya menunggu binar di mata mereka—sebuah tanda pemahaman. Namun, yang saya temukan justru deretan tatapan kosong yang menerka-nerka, seolah saya baru saja merapalkan mantra dari bahasa asing yang sudah punah. Saya mengerutkan dahi, setengah tak percaya, 'Kalian ... benar-benar nggak tahu peribahasa ini?'
Kompak, mereka menggeleng. Ruang kelas seketika hening, menyisakan jarak literasi yang terasa makin lebar. Saya pun mencoba memutar otak, mencari jembatan agar nilai ini sampai ke dunia mereka.
'Lalu, kalau Stoik kalian tahu tidak? Itu loh, yang sering seliweran di TikTok!'
Barulah satu-dua kepala mulai mengangguk. Di sinilah saya tersadar: mereka mungkin tahu trennya, tapi mereka telah kehilangan akarnya.
Saya sadar bahwa bahasa gaul atau slang internet bukanlah sebuah dosa. Seperti yang pernah diulas National Geographic, penggunaan slang justru menunjukkan kreativitas bahasa anak-anak kita dalam merespons zamannya. Namun, masalah intinya bukan pada munculnya deretan kata baru, melainkan pada hilangnya kata-kata lama yang memiliki kedalaman makna—seperti peribahasa.
Beberapa murid saya mungkin pernah mendengar kata 'Stoik' lewat potongan konten di TikTok yang estetik. Namun, seperti yang diperingatkan dalam ulasan Holopis, ajaran ini kerap disalahpahami oleh Gen Z hanya sebagai sikap 'bodo amat' atau mati rasa. Padahal, esensi Stoikisme sebenarnya sangat dekat dengan kearifan lokal kita: Anjing menggonggong kafilah berlalu. Keduanya sama-sama mengajarkan ketangguhan mental dan fokus pada tujuan, bukan sekadar ketidakpedulian yang kosong.
Jika kita bedah lebih dalam, peribahasa 'Anjing menggonggong kafilah berlalu' sebenarnya adalah ilmu tingkat tinggi tentang bagaimana menjaga fokus di tengah noise atau kebisingan dunia digital. Masalahnya, ketika murid-murid kita kehilangan peribahasanya, mereka sebenarnya sedang kehilangan senjatanya.
Baca Juga: Zaman Sudah Serba Digital, Penjual Arloji Lawas Masih Bertahan di Jalan ABC
Banyak dari mereka hanya mengenal 'Stoik' sebatas tren permukaan yang mungkin saja hanya dipakai untuk caption Instagram. Namun, jika mereka benar-benar paham akan makna peribahasa kita, mereka akan memiliki akar budaya untuk tetap tangguh. Mereka tidak akan mudah tumbang atau depresi hanya karena satu komentar miring di akun media sosialnya. Mengapa? Karena mereka menyadari identitas diri mereka yang sebenarnya: mereka adalah 'kafilah' yang sedang menempuh perjalanan menuju tujuan besar, dan gonggongan di pinggir jalan tidak akan pernah bisa menghentikan langkah mereka.
Memang benar bahwa bahasa itu dinamis dan terus berkembang, namun jangan sampai akar (peribahasa) dicabut demi daun (kata viral) yang cepat layu. Terkadang kita terlalu sibuk mendigitalisasi kelas, namun lupa memanusiakan pemikiran.
Pemerintah melalui Balai Bahasa sebenarnya sudah berupaya serius, salah satunya lewat inovasi seperti Krida Kartu Sanusa untuk meningkatkan literasi sastra secara interaktif. Namun di lapangan, sebagai mahasiswa PPK, saya melihat tantangannya jauh lebih besar dari sekadar ketersediaan alat peraga. Ini adalah soal bagaimana kita, sebagai pendidik, mampu mengembalikan 'rasa' pada bahasa dan logika pada setiap kata yang mereka ucapkan.
Resolusi saya untuk tahun 2026 sederhana saja: saya ingin murid-murid di Indonesia bukan hanya cerdas dalam menggunakan gawai, tapi juga tangguh dalam prinsip. Saya ingin mereka menjadi 'kafilah' yang terus melaju, meski 'gonggongan' di dunia digital tak pernah berhenti. Karena pada akhirnya literasi bukan soal seberapa banyak kata viral yang kita tahu, tapi seberapa dalam makna yang sanggup kita genggam. (*)