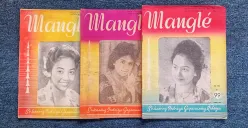Bayangkan duduk di sofa dengan sebaskom keripik, menonton film animasi di Netflix. Warna‑warna cerah, musik yang mengalun, dan karakter yang lucu membuat kita larut. Tapi pernah nggak sih kepikiran, “Cerita ini sebenarnya tentang apa?” Lebih dari sekadar tontonan dan hiburan? Ketiga film—Guillermo del Toro’s Pinocchio (2022), Pachamama (2018), dan Over the Moon (2020)—secara tak langsung memberi kita cara baru memahami agama, budaya, identitas, dan kekuasaan. Kita bisa membacanya sebagai wacana tentang kolonialisme, pascakolonialisme, dan dekolonialisme, tanpa harus pusing dengan istilah akademik.
Ketiga film ini didistribusikan di platform global Netflix, yang kini menjadi rumah bagi banyak cerita lintas budaya. Paradoks antara komitmen pada inklusivitas atau pendangkalan perspektif yang dengan mudahnya dikomodifikasi. Sebuah fakta yang menunjukkan bahwa cara kita melihat cerita ini sangat dipengaruhi oleh siapa yang memilih dan menyebarkannya ke jutaan pemirsa dunia.
Guillermo del Toro’s Pinocchio (2022)
Kalau kita sudah menonton Pinocchio versi ini, rasanya memang seperti menyimak dongeng yang berbicara dengan nada sangat dewasa. Pinocchio bukan sekadar boneka kayu yang ingin menjadi anak manusia, tetapi tubuh kecil yang terus-menerus ditarik oleh aturan, kepatuhan, hukuman, dan definisi tentang anak baik. Hampir di setiap adegan ada suara normatif yang menekan “jangan menyimpang!”. Del Toro menempatkannya dalam konteks sejarah yang keras, Italia era rezim fasis Mussolini, dengan bayang-bayang militerisme, perang dunia, dan nasionalisme yang menuntut ketaatan total pada negara, gereja, dan otoritas laki-laki.
Latar Gereja Katolik tampil sebagai institusi disipliner—tempat moral, dosa, dan keselamatan diproduksi melalui kepatuhan bukan relasi. Pada saat yang sama, dunia sirkus memperlihatkan sisi lain dari kuasa, soal kapitalisasi tubuh dan talenta. Pinocchio boleh berbeda, asal perbedaannya bisa dijual, dipertontonkan, dan menguntungkan. Di sini kolonialitas bekerja secara halus lewat normalisasi, yang pantas hidup adalah ia yang berguna bagi pasar dan negara.
Del Toro menyisipkan lapisan eksistensial yang sunyi. Ada sosok ilahi—peri kayu dan figur-figur dunia kematian—yang memberi Pinocchio kehidupan tanpa syarat moral tertentu. Ia hidup karena semata diberi kesempatan untuk menjadi. Dunia kematian yang ia masuki berulang kali bukan sekadar ruang hukuman, melainkan ruang kontemplasi tentang kefanaan, pilihan, dan makna eksistensi. Di sana, pertanyaan mendasarnya “apa arti hidup jika waktu terbatas?” Justru melalui relasinya dengan kematian, Pinocchio menemukan kebebasan yang tak bisa dikontrol oleh gereja, negara, maupun pasar.
Pachamama (2018)
Pachamama membawa kita ke pegunungan Andes, ke dunia kosmologi yang berpusat pada Ibu Bumi. Kita mengikuti perjalanan seorang bocah dan teman-temannya Tepulpai dan Naira yang berusaha menyelamatkan artefak leluhur (huaca) dari tangan orang luar. Latar film ini dipenuhi ritual adat, harmoni manusia dan alam, serta simbol-simbol Agama Leluhur.
Namun begitu film ini menolak berhenti pada romantisasi tradisi. Ia memperlihatkan bahwa masyarakat lokal mengalami opresi ganda. Dari atas oleh elite Kekaisaran Inca Empire yang memusatkan kuasa dan ritual resmi, dan dari luar oleh kolonial bersenjata zirah besi (Spanyol) yang datang membawa kekerasan, penjarahan, dan logika dominasi. Artefak leluhur dirampas sebagai simbol pemutusan relasi religius dengan tanah dan nenek moyang. Di sini kolonialisme tampil terang sebagai usaha penghancuran kosmologi.
Dalam tekanan itu, nilai Pachamama menjadi poros perlawanan. Ibu Bumi merupakan subjek yang dihormati—tanah yang hidup, memberi, sekaligus menuntut tanggung jawab. Relasi dengan alam bersifat timbal balik bukan eksploitatif. Maka perjuangan anak-anak dalam film ini tidak sekadar menyelamatkan benda, tetapi menjaga keseimbangan dunia dengan mempertahankan cara hidup yang melihat bumi sebagai ibu. Di situlah wajah dekolonial yang hidup muncul, keberanian, imajinasi, dan kesadaran bahwa identitas budaya selalu dinegosiasikan di tengah tekanan kuasa yang bertingkat.
Over the Moon (2020)
Sebuah musikal animasi yang mengikuti perjalanan seorang anak perempuan, Fei Fei, yang membangun wahana ke bulan untuk bertemu Dewi Chang’e dari legenda Tiongkok. Secara visual ia penuh warna, lagu, dan imajinasi khas film anak-anak. Namun di kedalamannya, film ini menghadirkan dialektika yang menarik antara sains, mitologi, dan emosi keluarga. Fei Fei memulai perjalanannya dengan logika astronomi—perhitungan roket, eksperimen, pembuktian ilmiah bahwa bulan bisa dijangkau. Ia percaya sains dapat “membuktikan” keberadaan Chang’e. Tetapi ketika ia tiba di sana, dunia yang ditemuinya adalah lanskap religiusitas dan pengalaman personal yang hidup.

Ketegangan produktif itu bekerja ketika sains modern dan imajinasi kartun anak-anak tidak saling meniadakan, malah berdialog dengan tradisi. Legenda Chang'e tampak sebagai memori kolektif yang dirawat melalui ritual seperti kue bulan dan altar penghormatan bagi ibu yang telah tiada. Bulan menjadi ruang pertemuan antara rasionalitas dan duka, antara teknologi dan kenangan. Fei Fei tidak hanya ingin membuktikan mitos, juga sedang bernegosiasi dengan kehilangan ibunya, mencoba mempertahankan kesetiaan pada memori keluarga di tengah perubahan.
Nilai bakti dan kelekatan keluarga menjadi poros emosional film ini. Tradisi adalah jembatan yang menghubungkan generasi—antara anak, orang tua, dan mereka yang telah meninggal. Dengan begitu, film ini dapat dimaknai sebagai usaha menempatkan mitologi Tiongkok menjadi pusat narasi, menunjukkan bahwa modernitas ilmiah dan warisan tradisi dapat berdampingan. Dunia tidak harus dipahami hanya lewat satu bahasa pengetahuan. Ada ruang bagi sains, bagi imajinasi, dan bagi kesetiaan pada nilai keluarga yang membentuk kita.
Baca Juga: Kenangan Indah Menonton Film di Bioskop Bandung Era 1980-an dalam Nuansa Ramadan
Tontonan, Tuntunan
Jika kita melihat Pinocchio, Pachamama, dan Over the Moon secara bersamaan, tampak sebuah pola tentang bagaimana cerita bekerja dalam relasi kuasa. Pinocchio memperlihatkan narasi dominan yang membentuk standar moral yang terasa normal, padahal lahir dari struktur nilai tertentu. Pachamama menunjukkan bahwa budaya lokal tidak hanya menjadi korban dominasi, tetapi mampu bernegosiasi dan bertahan melalui ingatan, ritual, dan solidaritas komunitas. Sementara Over the Moon membuka ruang alternatif, menempatkan mitologi dan pengalaman non-Barat sebagai pusat cerita. Ketiganya memperlihatkan bahwa kisah bukan sekadar hiburan di layar gawai, akan tetapi bermanifestasi jadi arena tempat aturan, perlawanan, dan pembebasan saling berkelindan.
Kehadiran ketiga film ini di balik industri raksasa Netflix patut dicatat bahkan dicurigai, mengingatkan kita bahwa distribusi cerita berlangsung di era algoritma, strategi pasar, dan kurasi global yang ikut menentukan narasi mana yang menjangkau jutaan penonton. Artinya, menikmati film hari ini juga berarti menyadari logika produksi dan sirkulasi yang membingkainya. Cerita-cerita lokal bisa tampil mendunia, tetapi selalu dalam negosiasi dengan kepentingan cuan. Kesadaran ini membuat kita tidak hanya menjadi konsumen, juga penonton yang peka terhadap konteks di balik layar.
Begitulah, menonton menjadi lakon yang reflektif. Ketiga film tersebut mengajak kita bertanya, cerita mana yang selama ini kita anggap wajar? Siapa yang diberi ruang berbicara? Dan apa yang berubah ketika suara dari pinggiran tampil di panggung utama? Cerita selalu bergerak—mengikuti perubahan zaman, identitas, dan perjumpaan budaya. Karena itu, tugas kita sebagai penonton tidak hanya menekan tombol “play” saja, yang lebih penting membuka diri pada kemungkinan makna yang berlapis. Di sanalah film dengan akses berlangganan itu menjadi lebih dari tontonan, ia menjadi tuntunan bercermin, sekaligus jendela, untuk melihat dunia dengan mata yang baru. (*)