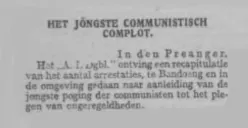AYOBANDUNG.ID - Gunung Burangrang sudah lama berdiri di antara kabut Lembang, tetapi ia baru benar benar menjadi objek kekaguman ketika orang Eropa di Bandung membawanya masuk ke dalam dunia catatan wisata. Di awal abad ke 20, para penulis kolonial menganggap Burangrang bukan sekadar gunung, melainkan laboratorium alam yang mesti ditaklukkan dengan sepatu kulit, topi lebar, dan satu dua kuli yang siap menebas semak di depan.
Buku Gids van Bandoeng en Midden Priangan terbitan 1927 bahkan memperlakukannya sebagai semacam monumen raksasa yang menunggu disingkap dengan cara yang paling Eropa: dengan ketertiban, peta triangulasi, dan keyakinan bahwa setiap lereng bisa dimenangkan asal ada jalur dan catatan yang tepat.
Dari semua pintu masuk yang ada, penulis panduan itu Steven Anne Reitsma memilih satu tempat yang dianggap paling cocok bagi pendaki kolonial: perkebunan kina Sukawana. Letaknya ideal bagi mereka yang datang dari Lembang atau Cisarua, dan bisa dicapai dengan mobil, hal yang pada masa itu sudah cukup membuat petualangan tampak modern. Jalan masuknya disebut berada tepat di seberang peternakan milik keluarga Ursone, lalu melewati jurang Sungai Cihideung yang dalam.
Baca Juga: Hikayat Pangalengan, Kota Teh Kolonial yang jadi Ikon Wisata Bandung Selatan
Jika dibaca sekarang, penjelasannya terasa seperti karya kartografer yang sedang berpuisi kecil sembari menurunkan petunjuk. Tetapi bagi orang Eropa tempo dulu, itu adalah cara paling aman agar para pelancong tak tersesat di antara lembah Priangan yang lembap dan rimbun.
Dari Bandung sendiri, Burangrang tampak jinak dan teratur, seolah hanya sebuah runcingan panjang dengan beberapa puncak yang berjajar. Namun orang orang Eropa yang menulis panduan itu mengingatkan bahwa pemandangan dari kejauhan sering menipu. Begitu mendekat, Burangrang berubah menjadi kaldera tua yang dipenuhi punggungan naik turun, seperti cincin patahan raksasa yang seolah ingin menguji kesabaran siapa pun yang mencoba menapakinya.
Deskripsi Reitsma mengurai bahwa dari kaki gunung, Lembang melekat pada lereng, Cisarua tampak lebih dekat, dan Bandung muncul sebagai siluet samar dengan bangunan pemerintahan yang menjadi titik orientasi.
Ia melihat semuanya dari ketinggian dengan kegembiraan khas linguis petualang, lalu menuliskannya seolah Burangrang adalah ruang kelas geologi yang sudah disiapkan oleh alam khusus bagi orang asing yang haus petualangan di tanah jajahan.
Baca Juga: 5 Rekomendasi Wisata Bandung Zaman Kolonial, Plesiran Orang Eropa dalam Lintasan Sejarah
Pendakian dari Sukawana digambarkan sebagai perjalanan yang penuh kejutan. Pertama, seseorang akan dibawa menyusuri jalan hutan cantik menuju onderafdeling Cisuren, lalu menyeberangi lembah Sungai Cimahi. Dalam catatan 1927 itu, ada momen ketika para pelancong diwajibkan berbelok ke kiri memasuki hutan melalui jalur kecil yang hanya pada bagian awal masih pantas disebut jalan. Setelah itu, istilahnya lebih cocok disebut tekad.
Hutan Burangrang digambarkan sebagai ruang lembap yang membuat napas tersengal. Para penulis Eropa mencatat suhu yang panas dan udara yang menempel di kulit, seolah hutan ingin mengingatkan bahwa tubuh manusia, terutama tubuh orang Belanda, selalu kalah dari tropis. Tetapi sesak itu segera terbayar ketika mereka mencapai dinding kaldera tua yang disebut Gedogan.
Dari sana, pemandangan terbuka lebar dan seisi dunia Priangan tampak seperti hamparan yang disusun rapi. Sukawana berada jauh di bawah, Tangkuban Parahu terlihat lebih rendah daripada biasanya, dan jalur jalur baru pembukaan lahan kina tampak seperti goresan kecil pada tubuh pegunungan.
Keasyikan mereka makin bertambah saat mendapati betapa Burangrang bukan satu gunung panjang, melainkan cincin setengah patah yang membentuk sebuah kawah tua. Bagian selatan, barat, dan timurnya menjadi dinding tebal yang ditumbuhi pohon raksasa. Di balik cincin itu tergeletak kawah hijau tua yang rapat oleh vegetasi.
Baca Juga: Yang Dilakukan Ratu Belanda Saat KAA Dihelat di Bandung

Hanya bagian timur yang terbuka, memberi ruang bagi Tangkubanparahu untuk menjulurkan tubuhnya. Bagi para penulis kolonial, susunan itu seperti trik geologi yang sedang memamerkan kejeniusannya. Dari atas, mereka merasa seolah Parahu sedang tumbuh dari dalam kawah Burangrang.
Jalur-jalur yang ada di sepanjang punggungan buritan itu digambarkan sempit dan nakal. Di beberapa titik, jalurnya begitu sempit sampai mereka yang mudah pusing disebut mungkin harus memejamkan mata jika tidak ingin gentar. Untungnya, tumbuhan rapat di kiri kanan menutupi jurang curam yang bisa membuat lutut gemetar. Kesan jenaka muncul ketika catatan itu menyebut betapa jalur yang sempit, terabaikan, dan menanjak turun itu seperti dibuat bukan untuk dilalui manusia, melainkan makhluk hutan yang lebih sabar.
Puncak puncak Burangrang seolah tak habis. Setiap kali satu puncak dilewati, puncak berikutnya sudah menunggu. Hingga akhirnya, para pelancong itu mencapai puncak tertinggi, ditandai tiang triangulasi di ketinggian 2065 meter. Bagi mereka, triangulasi adalah simbol kemenangan modernitas. Bahwa pegunungan sebesar itu pun bisa diberi titik ukur, diatur, dan dipetakan dengan teliti.
Baca Juga: Hikayat Cipaganti Group, Raksasa Transportasi Bandung yang Tumbang Diguncang Skandal
Dari puncak itulah para penulis melihat dataran Plered dan Purwakarta bersinar diterpa cahaya matahari. Sementara ke arah timur, Parahu tampak teduh dan berhutan lebat seperti Burangrang sendiri.
Reruntuhan Vulkanik yang Disulap Jadi Destinasi Wisata
Catatan 1927 itu menutup petualangannya dengan saran jenaka. Bila seseorang sudah puas berputar putar di sepanjang cincin kaldera, jangan lupa turun kembali lewat jalur timur menuju puncak terdekat. Dari sana, perjalanan menuju Cisarua bisa ditempuh dalam waktu hampir tiga jam. Sementara dari Sukawana ke puncak membutuhkan hampir empat jam. Para kuli pembuka jalan dari Sukawana dianggap wajib, karena merekalah yang mengubah hutan rapat menjadi lorong kecil yang bisa dilalui petualang kolonial.
Saat membaca catatan itu hari ini, Burangrang tampak seperti panggung besar di mana orang Eropa tempo dulu memainkan imajinasi petualangan mereka. Gunung ini dimaknai sebagai hutan perawan tempat anggrek dan kantong semar tumbuh tak terkira. Sebuah gunung yang menuntut peluh tetapi memberi pemandangan yang membuat mereka merasa menemukan lanskap baru di tanah jajahan yang terus mereka tafsirkan.
Baca Juga: Dari Hotel Pos Road ke Savoy Homann, Jejak Kemewahan dan Saksi Sejarah Pembangunan Kota Bandung
Kini, hampir seabad berlalu, Burangrang masih berdiri dengan bentuk cincin kawah tuanya yang misterius. Ia tak lagi membutuhkan kuli pembuka jalan, dan para pendaki tak lagi membawa panduan wisata berbahasa Belanda. Namun kisah-kisah kolonial itu tetap menjadi jejak menarik, terutama untuk memahami bagaimana orang asing pernah melihat pegunungan Priangan sebagai ruang eksotik yang harus dipetakan, ditaklukkan, dan dituliskan.