AYOBANDUNG.ID - Pada suatu masa ketika lemari es belum dikenal dan bau amis adalah bagian wajar dari pasar, ikan pindang menjadi penyelamat dapur orang Bandung. Murah, asin, tahan lama, dan mudah diolah. Ia bisa menemani nasi panas di pagi hari, atau disimpan untuk makan malam. Tapi di balik kepopulerannya, pindang juga menyimpan kisah gelap yang beberapa kali membuat Bandung geger pada awal abad ke-20.
Surat kabar kolonial menyebutnya dengan nada panik sekaligus heran. Orang-orang jatuh sakit, keluarga seisi rumah tumbang, bahkan ada yang meninggal dunia hanya karena makan ikan pindang. Dari Cibangkong hingga Lembang, dari pasar kota sampai desa-desa pinggiran, pindang berubah dari lauk rakyat menjadi tersangka utama.
Kisah ini bukan dongeng. Arsip media Hindia Belanda mencatatnya dengan cukup rinci, lengkap dengan nama desa, jumlah korban, dan kebingungan para pejabat kolonial yang harus menjelaskan bagaimana ikan asin bisa mematikan.
Baca Juga: Hikayat Sarkanjut, Kampung Kecil yang Termasyhur di Priangan
Perkara konsumsi pindang ini sebenarnya sudah jadi bahan gunjing administrasi kolonial sejak awal abad ke-20. Pada 11 Oktober 1901, Residen Bandung pernah mengeluarkan keputusan yang melarang penjualan cue atau ikan pindang karena dianggap membahayakan kesehatan. Namun, seperti banyak kebijakan kolonial lainnya, larangan itu tidak bertahan lama. Ia dicabut, pasar kembali ramai, dan orang-orang kembali makan pindang dengan lahap.
Sering masa berganti, larangan itu seperti menuntut balas.
Pada Juni 1908, surat kabar Het Nieuws van den Dag menurunkan laporan yang membuat alis pejabat kolonial terangkat. Di Cibangkong, satu keluarga yang terdiri dari sembilan orang jatuh sakit setelah memakan pindang. Di Kejaksaan Hilir, empat orang mengalami nasib serupa. Dan di Lembang, kabar paling buruk datang. Tidak kurang dari sepuluh orang pribumi dilaporkan meninggal dunia akibat keracunan ikan.
Pemerintah kolonial kelabakan. Dokter Jawa dikirim, dokter sipil disibukkan dari pagi sampai malam, dan kepala polisi ikut turun tangan.
Baca Juga: Bandit Laknat Padalarang Zaman Belanda, Kisah Berdarah di Kampung Terpencil
Yang menarik, sumber kecurigaan tidak hanya datang dari dokter atau pejabat. Penduduk pribumi pun punya penjelasan sendiri. Laporan koran itu mencatat pengakuan warga tentang praktik pembuatan pindang. “Biasanya pindang dibuat dari ikan yang tidak laku dijual, dan tanpa dibersihkan dengan baik,” tulis koran itu dalam terbitan edisi 13 Juni 1908.
Ikan tongkol, selar, dan kembung yang seharusnya sudah dibuang, justru direbus ulang dan diasinkan.
Di balik penjelasan itu, ada pula cerita yang lebih mistis sekaligus botanis. Warga menyebut bahwa ikan yang dimasak dengan kayu rengas bisa berubah menjadi racun. Rengas memang terkenal dalam cerita rakyat sebagai pohon berbahaya, getahnya bisa menyebabkan gatal parah. Apakah api kayunya bisa meracuni ikan? Para pejabat kolonial ragu, tetapi cerita itu terlanjur hidup di kampung-kampung.
Pertanyaan pun muncul kembali, sama seperti tujuh tahun sebelumnya. Apakah penjualan ikan pindang akan kembali dilarang? “Tampaknya arah kebijakan memang cenderung ke sana.” tutup Het Nieuws van den Dag.
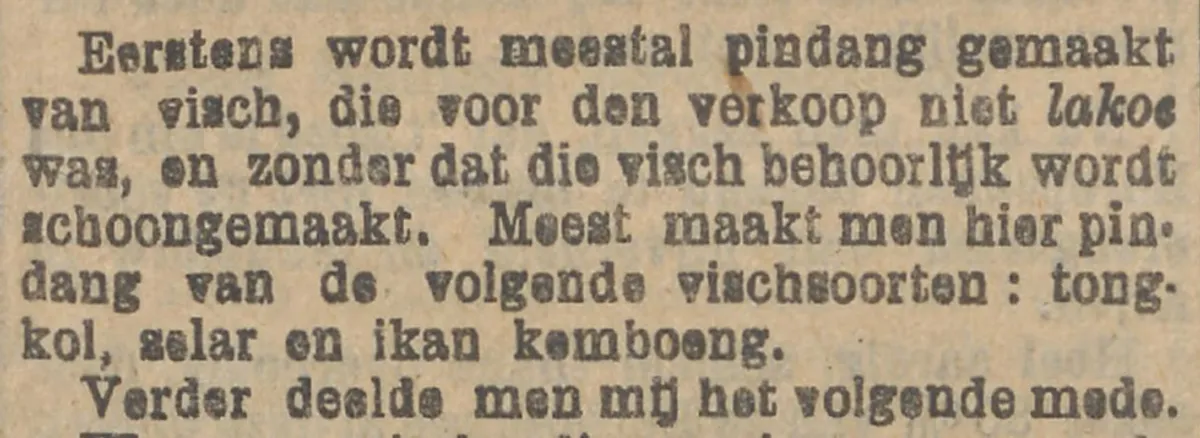
Beberapa hari kemudian, De Locomotief melaporkan kabar yang sama. Mengutip De Preanger-bodr, koran ini menyebut bahwa sebagian pindang yang menyebabkan keracunan didatangkan dari Karawang.
Jumlah korban yang tercatat sekitar 30-40 orang, menurut terbitan edisi 16 Juni 1908 koran itu. Tetapi laporan itu juga jujur mengakui, tidak semua kasus dilaporkan kepada pemerintah. Bisa dipastikan jumlah sebenarnya jauh lebih besar. Sebagian pindang berhasil disita dan disimpan di kantor wedana, sementara para korban diberi obat-obatan seadanya. Sebagian besar selamat. Tidak semuanya.
Baca Juga: Hikayat Komplotan Bandit Revolusi di Cileunyi, Sandiwara Berdarah Para Tentara Palsu
Dari Uler Lempê hingga Racun Halus dalam Pindang
Yang membuat kisah keracunan pindang semakin menarik adalah keragaman penjelasan yang beredar dari tahun ke tahun. Tidak semuanya menunjuk pada ikan busuk semata.
Sekitar dua dekade sebelumnya, tepatnya pada Oktober 1890, De Nieuwe Vorstenlanden sudah mencatat kepercayaan para ahli ikan Jawa. Mereka menyebut bahwa ikan pindang pada dasarnya tidak beracun, tetapi bisa menjadi berbahaya jika ikan tersebut memakan uler lempê. Makhluk ini digambarkan sebagai peralihan antara ikan dan cacing, hidup di kolam-kolam ikan. Penjelasan ini terdengar ganjil bagi pembaca modern, tetapi pada zamannya dianggap masuk akal.
Kasus serupa terus muncul di dekade berikutnya. Pada Juni 1926, De Indische Courant melaporkan tiga puluh orang pribumi jatuh sakit di Soreang setelah memakan ikan pindang. Tiga di antaranya meninggal dunia. Setahun kemudian, Agustus 1927, De Nieuwe Vorstenlanden kembali menurunkan kabar dari Binong, Distrik Ujungberung. Sembilan orang dewasa dan delapan anak jatuh sakit akibat memakan pindang ikan sepat.
Baca Juga: Sejarah Longsor Cigembong Garut Zaman Kolonial, Warga Satu Kampung Lenyap Tanpa Jejak
Dalam kasus Binong, semua korban akhirnya pulih. Seorang dokter dari Bandung segera datang setelah diberi tahu Asisten Wedana. Terhadap penjual pindang bernama Asmali, dibuatkan berita acara. Sebuah isyarat bahwa pemerintah kolonial melihat persoalan ini bukan sekadar musibah alamiah, tetapi juga soal tanggung jawab dagang.
Namun penjelasan paling gelap datang dari laporan-laporan tentang racun yang disengaja. Soerabaiasch Handelsblad edisi 29 Maret 1935, mengutip Deli Courant, menulis panjang lebar tentang peranan racun di Hindia Belanda. Tanah Sunda, disebutkan, tidak memiliki nama baik dalam banyak kisah peracunan, meskipun sering kali dibumbui unsur berlebihan.
Laporan itu menyebut praktik mencampurkan gadung, akar tareba, akar cermai, dan kelutut ke dalam pindang ikan. Racun ini tidak membunuh seketika, tetapi perlahan. “Yang konon menyebabkan kematian dalam waktu dua puluh hari,” tulis surat kabar tersebut. Ada pula penggunaan arsenik dan senyawa logam berat seperti tembaga dan timah, diberikan berselang-seling agar gejala penyakit sulit dikenali dan tak mudah dibuktikan secara kimia.
Risalah ini seolah memberi kesan bahwa kasus keracunan pindang adalah hasil kejahatan terencana.
Baca Juga: Jejak Dukun Cabul dan Jimat Palsu di Bandung, Bikin Resah Sejak Zaman Kolonial
Terlepas dari itu semua, pindang adalah kebutuhan bagi warga pribumi. Bagi pemerintah kolonial, ia adalah masalah kesehatan publik yang sulit dikendalikan. Dan bagi sejarah Bandung, ia meninggalkan jejak yang agak pahit, agak amis, tetapi juga menggelitik. Siapa sangka, di balik lauk sederhana yang akrab di lidah orang Sunda, tersimpan hikayat panjang tentang larangan, kecurigaan, dan racun yang bekerja pelan-pelan.
Di meja makan kolonial, ikan pindang mungkin hanya lauk murahan. Tetapi di arsip sejarah, ia adalah saksi bisu betapa rumitnya kehidupan sehari-hari di kota yang kelak dikenal sebagai Parijs van Java.





















