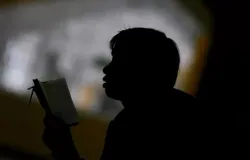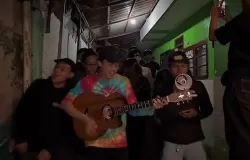AYOBANDUNG.ID - Di jalan-jalan kampung Subang, setiap kali ada anak lelaki disunat, suasananya tidak pernah sepi. Bukan karena tangisan, melainkan gegap gempita iring-iringan. Anak itu duduk di atas replika singa bermahkota emas, diangkat delapan pria kekar yang menari mengikuti ritme musik gamelan dan terompet. Ini bukan pawai biasa. Inilah Sisingaan, kesenian rakyat Subang yang sudah hidup sejak zaman tanam paksa, dan masih bertahan sampai kini.
Sisingaan bukan sekadar pertunjukan. Ia simbol identitas, perlawanan, juga bentuk syukur. Dari pelataran rumah hingga pentas nasional, singa kayu ini berjalan tanpa henti. Diangkat oleh warga, ditunggangi oleh anak-anak, dan dipertahankan oleh sejarah.
Tak ada sejarah yang tunggal, begitu pula asal-usul Sisingaan. Tapi semua sepakat: kesenian ini lahir di Subang. Peneliti Badan Pelestarian Nilai Budaya Jawa Barat Suwardi Alamsyah dalam makalahnya Sisingaan; Kesenian Kabupaten Subang menyebut nama Sisingaan diambil dari alat utama pertunjukan: replika singa dari kayu, yang dalam bahasa Sunda disebut “sisingaan”, gabungan kata “si”, “singa”, dan “-an”, yang berarti tiruan singa.
Sebelum tahun 1989, masyarakat mengenal kesenian ini dengan berbagai nama: Gotong Singa, Kuda Ungkleuk, Singa Depok, hingga Pergosi. Barulah pada seminar kebudayaan di Subang tahun itu, disepakati satu nama resmi: Sisingaan.
Baca Juga: Sejarah Tahu Sumedang, Warisan Cita Rasa Tionghoa hingga Era Cisumdawu
Dua pendapat besar berkembang soal akar kesenian ini. Pendapat pertama menyebut Sisingaan lahir pada masa kolonial sebagai bentuk sindiran terhadap penjajahan Belanda dan Inggris. Singa kayu dianggap sebagai simbol tuan tanah kolonial. Anak-anak yang menungganginya melambangkan rakyat Subang yang "menaklukkan" penguasa asing. Dalam narasi ini, sisingaan bukan hanya hiburan, tapi juga satire visual yang kuat.
Pendapat ini dikuatkan oleh peneliti kesenian Edih AS, yang menyebut tahun 1857 sebagai titik mula kemunculan Sisingaan. Ia menunjuk Demang Mas Tanudireja dari Kademangan Ciherang sebagai pelopornya. Dari penelusuran Edih, bahkan pada tahun 1910-an sudah ada lurah dan anak-anak sunat yang diarak keliling kampung dengan Sisingaan. Artinya, tradisi ini sudah berlangsung lebih dari satu abad.
Pendapat kedua datang dari Mas Nanu Munajar, seniman akademisi Subang. Ia melihat akar Sisingaan sebagai kelanjutan dari Odong-odong, kesenian agraris yang bersifat ritual. Jauh sebelum masuknya agama-agama besar, masyarakat Subang mengenal tradisi arak-arakan berbentuk binatang sebagai penghormatan terhadap kekuatan supranatural, hasil panen, dan keselamatan desa. Benda-benda yang diarak menyerupai garuda, elang, kuda, atau macan.
Kalau menurut versi ini, Sisingaan berkembang dari bentuk-bentuk awal Odong-odong. Barulah saat Subang hendak mengirim delegasi ke Taman Mini Indonesia Indah, nama Sisingaan dipatenkan sebagai representasi seni daerah.
Kendati berbeda akar, keduanya sepakat: Sisingaan bukan seni buatan mendadak. Ia tumbuh dari napas masyarakat, berevolusi, dan bertahan karena maknanya terus hidup—baik sebagai bentuk rasa syukur maupun simbol perlawanan.

Dari Khitanan ke Panggung Dunia
Sampai hari ini, Sisingaan tetap eksis di tengah masyarakat Subang. Fungsi awalnya sebagai hiburan khitanan masih dominan, meski kini sering pula tampil dalam acara resmi, pawai budaya, atau pertunjukan di luar negeri.
Proses pertunjukan Sisingaan khas dan penuh ritus. Sehari sebelum arak-arakan, anak yang akan disunat dimandikan air bunga dan dirias seperti tokoh pewayangan—Gatotkaca lengkap dengan kumis, bedak, dan pakaian warna emas-hitam. Ia ditemani “Arjuna kecil”, lalu keduanya dinaikkan ke atas dua singa kayu yang siap diusung.
Baca Juga: Hikayat Dinasti Sunarya, Keluarga Dalang Wayang Golek Legendaris dari Jelekong
Sementara itu, di halaman rumah, para penggotong sudah bersiap. Mereka menari, membentuk formasi, dan mengangkat sisingaan dengan gerakan kompak, dinamis, dan atraktif. Iringan musik gamelan dan tiupan terompet mengatur ritme gerakan mereka. Terkadang, atraksi akrobatik ditampilkan: berputar seperti katak, menendang di udara, hingga melompat sambil menggendong singa.
Gerakannya tak sembarangan. Dalam versi jalanan, tariannya berlandaskan pola ketuk tilu: jurus, minced, gurudugan. Dalam versi panggung, lagunya berganti-ganti: arang-arang, kidung, kangsreng, gondang, hingga ditutup Jaipongan. Atraksi pun dipertontonkan: dari bankaret hingga putar katak, dari nincak acak hingga melak cau.
Walaupun fungsi awalnya berubah, makna Sisingaan tetap utuh. Ia adalah seni rakyat yang menghibur, menggerakkan, dan menyatukan. Anak-anak yang ditandu bukan cuma simbol keberanian menghadapi sunat, tapi juga bagian dari warisan budaya yang membanggakan.
Hari ini, Sisingaan tak hanya milik Subang. Ia sudah tampil di Jakarta, Bali, bahkan luar negeri. Tapi jiwanya tetap Subang: kampung yang tak pernah berhenti menari bersama singa dari kayu.