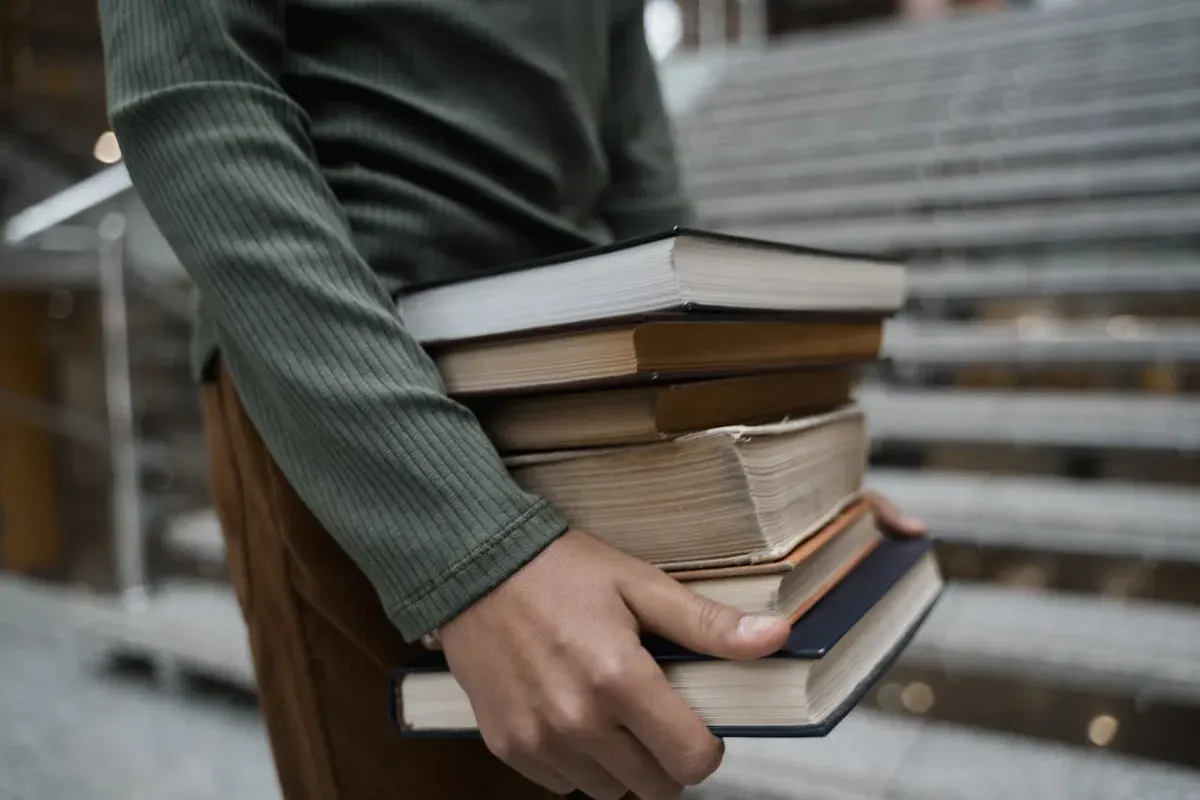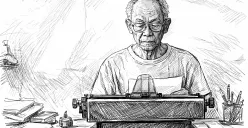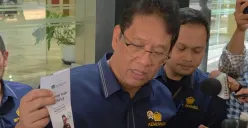Ketika sastra hadir di tengah gemuruh zaman yang serba instan dan transaksional, sastra berdiri sebagai suara lirih yang sering tak terdengar. Ia hadir bukan untuk meramaikan pasar, melainkan untuk menyuarakan perenungan, luka, dan harapan kolektif.
Namun ironisnya, para penulis yang mengabdikan diri pada sastra justru terjebak dalam kondisi yang disebut prekariat—kelas sosial yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi, tanpa jaminan kerja tetap, tanpa perlindungan sosial, dan kerap kali tanpa pengakuan yang layak.
Meminjam catatan Goenawan Mohamad (jurnalis dan sastrawan), bahwa sebutan sastrawan atau penyair adalah status sosial yang tidak jelas. Sebutan ini tidak masuk dalam penggolongan klasifikasi baku lapangan usaha Indonesia. Artinya, tidak diakui sebagai salah satu jenis pekerjaan. Status yang menjadi ambivalen antara pekerja seni (seniman) atau sebagai penulis.
Sastra yang sering diagung-agungkan dan didengungkan dalam sendi-sendi kehidupan, karena menjadi oase dalam muara keilmuan. Baik sejarah, filsafat, bahasa, kesenian dan yang lain. Sastra yang kerap kali muncul sebagai tulang punggung budaya, tapi dalam perjalanannya sering hanya mampu memupuk harapan yang tidak seindah frasa dalam puisi. Bahkan terkadang harus berjibaku dengan intrik yang menjadi imbas dari berbagai kebijakan publik dan politisasi.
Dengan semangatnya, seperti sebuah pergolakan yang tidak kunjung usai, sastra terus menghasilkan karya-karya dan orang hebat di dunia sastra, meski dengan harapan hampa: “Mungkinkah seorang sastrawan Indonesia mampu meraih hadiah Nobel Sastra?” Sesuatu yang hanya bisa diamini, tanpa mampu dijawab dengan sebuah kepastian. Bukankah hidup itu adalah sebuah perjalanan untuk menunda kekalahan?
Di tengah era globalisasi dan kapitalisme digital, sastra—yang selama ini menjadi wadah permenungan dan kritik sosial—justru mengalami kemunduran dalam hal kesejahteraan para pelakunya. Dianggap sebagai bagian dari kebudayaan tinggi, sastra dihormati dalam diskursus intelektual, tetapi diabaikan dalam kebijakan ekonomi.
Para penulis sastra, terutama di negara berkembang seperti Indonesia, banyak yang hidup dalam ketidakpastian ekonomi. Mereka tergolong dalam kelas sosial baru yang disebut prekariat, yakni kelompok yang hidup dengan pekerjaan tak tetap, minim perlindungan sosial, dan jauh dari jaminan kesejahteraan.
Kita sering terbelenggu dengan budaya ‘ewuh-pekewuh’, apakah sastra menjadi warisan simbolik tanpa nilai ekonomis?
Fakta sosial menunjukkan bahwa di banyak negara, termasuk Indonesia, pekerja seni dan budaya—terutama penulis sastra—masih jauh dari sejahtera. Menerbitkan buku bukan jaminan pendapatan. Mengikuti lomba sastra atau mengisi acara budaya pun tidak selalu berarti memperoleh honor yang layak.
Banyak dari mereka yang harus menambal penghidupan dari profesi lain: menjadi guru, jurnalis, pekerja lepas, atau bahkan buruh kreatif di industri yang tidak ada hubungannya dengan sastra. Hal ini menciptakan ironi besar: budaya yang diagungkan sebagai identitas bangsa justru tidak mampu menghidupi para perawatnya.
Dari sisi budaya, sastra sering diletakkan di altar tinggi: ia dianggap luhur, sakral, dan intelektual. Namun dalam kenyataannya, penghormatan tersebut bersifat simbolik, bukan ekonomis. Sastra dijunjung, tapi tidak dibeli. Dikutip, tapi tak pernah dibayar. Diundang, tapi kadang hanya dibayar dengan “eksposur”. Ketegangan antara penghargaan simbolik dan ketidaklayakan ekonomi inilah yang melahirkan paradoks dalam dunia kesusastraan: semakin tinggi nilai budayanya, semakin rapuh posisinya dalam struktur ekonomi.
Inilah konteks pertentangan yang jarang dibicarakan secara terbuka: antara fakta sosial yang menindas para pelaku sastra dan imajinasi budaya yang terus mengidealkan mereka. Sastra dianggap sebagai warisan, tapi tidak diurus sebagai profesi. Negara menyebutnya penting, tapi tak membentuk sistem pendukung yang memungkinkan sastra tumbuh dan berkelanjutan. Sementara pasar, yang lebih menyukai sensasi dan hiburan, meminggirkan karya-karya yang menantang pikiran dan menggugah hati.
Jika dibiarkan, kondisi ini akan menciptakan jurang yang makin lebar: antara idealisme kesusastraan dan realitas kehidupan para sastrawan. Anak muda mungkin tetap menulis, tapi akan semakin enggan menjadikan sastra sebagai jalan hidup. Maka yang tersisa nanti adalah suara-suara yang terengah-engah, mencoba tetap bernyanyi dalam ruang yang makin sempit.
Sudah saatnya kita berbicara tentang sastra tidak hanya dalam kerangka estetika, tapi juga dalam kerangka keadilan ekonomi. Sudah saatnya negara, lembaga, dan masyarakat memberikan tempat yang layak bagi para pencipta makna—bukan hanya sebagai simbol budaya, tapi sebagai pekerja budaya. Sebab tanpa dukungan nyata, sastra bisa mati bukan karena tak ada pembaca, tapi karena tak ada lagi penulis yang mampu bertahan.
Dalam banyak budaya, sastra sering dikaitkan dengan kemuliaan intelektual dan kedalaman spiritual. Ia menjadi bagian dari identitas bangsa, simbol peradaban, bahkan alat diplomasi budaya. Namun, simbolisme ini tidak serta-merta berbanding lurus dengan nilai ekonomis yang diterima oleh para penulis. Buku puisi yang memenangkan penghargaan bergengsi bisa jadi hanya terjual puluhan eksemplar. Cerpen-cerpen yang dimuat di media besar belum tentu memberikan imbalan yang cukup untuk menutup biaya hidup sebulan. Sementara itu, media dan penerbit kerap memanfaatkan nama besar penulis sebagai kapital simbolik, bukan sebagai aset yang harus diberi kompensasi adil.
Pertanyaan-pertanyaan yang muncul dari para sastrawan acapkali dan sangat relevan dengan membuka ruang pembahasan penting dalam kajian kontemporer antara sastra, ekonomi politik budaya, dan konsep prekariat. Para ilmuwan dari berbagai disiplin ilmu—sosiologi, sastra, ekonomi budaya, hingga kajian media—telah menyoroti hubungan antara produksi sastra dan ketidakstabilan ekonomi yang dihadapi oleh para pelaku budayanya.

Dalam pandangan beberapa ilmuwan terhadap hubungan sastra dan prekariat, antara lain:
1. Guy Standing – Konsep “Prekariat” (2011) dalam buku The Precariat: The New Dangerous Class. Standing tidak membahas sastra secara spesifik, tetapi konsep “prekariat” yang ia rumuskan sangat relevan untuk dunia sastra.
Ia menjelaskan munculnya kelas baru dalam masyarakat neoliberal: pekerja yang hidup dalam ketidakpastian, tanpa keamanan kerja, tanpa jaminan sosial, dan rentan secara ekonomi maupun psikologis. Banyak penulis, seniman, dan pekerja budaya yang masuk dalam kategori ini karena mereka bekerja tanpa kontrak tetap, bergantung pada proyek atau royalti, dan tidak dilindungi negara. Standing menyebut mereka sebagai bagian dari “kelas berpendidikan yang tercerabut,” yang sekaligus rawan eksploitasi namun bisa menjadi agen perubahan jika diberdayakan.
Di sini, penulis sastra adalah bagian dari kelas prekariat budaya yang sering bekerja tanpa perlindungan ekonomi, walau menghasilkan nilai budaya yang tinggi.
2. Pierre Bourdieu – Field of Cultural Production (1993). Bourdieu menganalisis bagaimana dunia seni dan sastra bekerja sebagai sebuah medan dengan aturan dan modalnya sendiri. Ia menyebutkan adanya dua jenis modal utama: modal ekonomi (uang, aset) dan modal simbolik (pengakuan, prestise). Dalam medan sastra, penulis sering mengejar modal simbolik—penghargaan, reputasi—tetapi mengorbankan modal ekonomi. Hal ini menciptakan ketegangan antara seni sebagai panggilan idealistik dan seni sebagai pekerjaan.
Dalam relevansinya dengan prekariat: banyak sastrawan berada dalam posisi subordinat secara ekonomi karena struktur medan budaya menghargai “kemurnian” dan mengabaikan kebutuhan material, menjadikan mereka rentan secara sosial.
3. Angela McRobbie – Be Creative: Making a Living in the New Culture Industries (2016). McRobbie menyoroti bagaimana industri kreatif, termasuk sastra, mendorong pekerja untuk tampil sebagai individu kreatif yang “bebas”, padahal mereka terjebak dalam logika pasar yang menuntut fleksibilitas dan kerja terus-menerus.
Ia menyebut adanya “romantisisasi penderitaan” dalam dunia seni dan budaya, di mana kemiskinan atau kerja keras dianggap bagian dari perjuangan kreatif.
Sementara itu, negara dan pasar menghindar dari tanggung jawab struktural atas kondisi kerja yang tidak layak.
McRobbie mengkritik sistem yang merayakan “kreativitas” tapi menutup mata terhadap kenyataan eksploitasi dan ketidak-nyamanan hidup para kreator, termasuk penulis sastra.
4. Mark Fisher – Capitalist Realism (2009). Fisher membahas bagaimana kapitalisme modern menciptakan kesan bahwa “tidak ada alternatif lain”. Dalam konteks budaya, termasuk sastra, Fisher menunjukkan bagaimana karya-karya yang kritis atau alternatif sulit bertahan secara ekonomi, karena pasar hanya memberi ruang bagi produk yang “aman” dan menguntungkan secara komersial.
Ia juga menyinggung kecemasan mental dan beban psikologis yang dialami oleh para pekerja budaya dalam sistem ini. Penulis sastra sering kali beroperasi di luar logika pasar dominan dan karena itu dipinggirkan. Mereka mengalami beban psiko-sosial akibat tekanan ekonomi dan ketidakjelasan masa depan.
5. Slavoj Žižek – Ideologi dan Budaya Populer. Žižek menyoroti bagaimana ideologi neoliberal masuk ke dalam budaya populer dan menggantikan kritik ideologis dengan hiburan yang mudah dikonsumsi.
Sastra yang mendalam, lambat, atau reflektif semakin tersingkir karena tidak sesuai dengan logika budaya instan. Para penulis yang mencoba mempertahankan kedalaman makna dalam karyanya justru sering menjadi bagian dari kelompok yang terpinggirkan dalam sistem distribusi budaya.
Secara umum, para ilmuwan melihat bahwa: sastra sebagai praktik budaya bernilai tinggi tidak mendapatkan dukungan ekonomi yang setara. Para penulis berada dalam posisi prekariat: bekerja tanpa jaminan, pendapatan tidak tetap, dan minim dukungan institusional. Ada ketimpangan struktural antara nilai simbolik dan nilai ekonomi karya sastra. Sistem budaya dan pasar saat ini lebih mendukung produksi cepat, konsumsi massal, dan mengabaikan karya yang mendalam atau kritis.
Tanpa perubahan kebijakan dan paradigma, dunia sastra akan terus menghasilkan nilai budaya, tetapi tidak akan bisa menjamin kelangsungan hidup penciptanya.
Konsep prekariat, yang dipopulerkan oleh sosiolog Guy Standing, menjelaskan adanya kelas baru dalam masyarakat modern: mereka yang bekerja tanpa kepastian, tanpa jaminan, dan tanpa masa depan ekonomi yang jelas. Di dalam dunia kesusastraan, kelompok ini sangat kentara. Banyak penulis yang menggantungkan hidup dari proyek-proyek lepas, mengajar kelas menulis, menjadi editor freelance, atau mengandalkan pekerjaan sampingan di luar dunia sastra.
Tanpa perlindungan institusional, para sastrawan ini tidak hanya rentan secara ekonomi, tetapi juga terancam kehilangan daya kritisnya. Ketika sastra menjadi aktivitas sambilan demi bertahan hidup, maka ruang untuk bereksperimen, menyuarakan kritik, dan menulis dengan jujur akan semakin menyempit.
Sastra dihadapkan pada ketimpangan antara wacana dan kebijakan. Ironisnya, negara sering menyuarakan pentingnya kebudayaan, termasuk sastra, dalam pidato resmi, kurikulum pendidikan, atau ajang penghargaan nasional. Namun, di level kebijakan, dukungan terhadap pekerja sastra masih sangat minim. Tidak ada skema jaminan sosial, subsidi, atau kebijakan insentif yang secara spesifik menyasar penulis sastra. Dukungan yang ada sering bersifat event-oriented, seremonial, atau sekadar proyek musiman.
Di sisi lain, pasar buku juga tidak ramah terhadap karya sastra. Genre populer seperti self-help, thriller ringan, atau novel romansa jauh lebih dominan. Sastra yang bersifat reflektif, eksperimental, atau politis, justru dianggap “tidak laku”. Akibatnya, banyak penerbit enggan menerbitkan karya-karya sastra murni, apalagi membayar penulisnya dengan layak.
Sudah saatnya pembicaraan tentang sastra tidak hanya berputar pada wacana estetika dan kritik ideologis, melainkan juga pada aspek ekonomi dan struktural. Sastra tidak cukup dijaga dengan penghargaan simbolik; ia perlu ditopang oleh sistem yang adil. Negara, lembaga pendidikan, penerbit, hingga masyarakat luas harus menyadari bahwa keberlangsungan sastra sebagai ekosistem kreatif sangat bergantung pada kesejahteraan para penciptanya.
Jika tidak ada perubahan struktural, maka yang akan tersisa hanyalah nostalgia—tentang masa ketika sastra pernah menjadi suara nurani, sebelum akhirnya dibungkam oleh kemiskinan yang sistemis. (*)