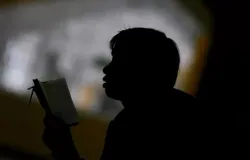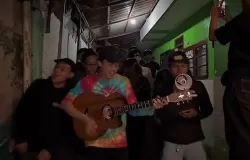Setengah jam hujan deras dan angin kencang di kawasan Ujungberung, Bandung Timur, pada awal November lalu sudah cukup untuk menguji banyak hal, kekuatan atap rumah warga, kesiapsiagaan aparat, dan kemampuan sistem kota dalam menahan guncangan kecil dari langit. Puluhan rumah rusak, beberapa pohon tumbang, dan aliran listrik terputus di sejumlah titik.
Peristiwa itu bukanlah bencana besar, tetapi peringatan keras. Di kota dengan topografi cekung, dikelilingi pegunungan, dan beriklim lembap seperti Bandung, setiap peristiwa cuaca ekstrem, betapapun singkat selalu membawa pesan bahwa urusan langit dan bumi tak bisa lagi dipisahkan dari urusan tata kelola manusia.
BMKG telah memperingatkan, selama 7–10 hari ke depan, wilayah Bandung Raya akan berada dalam kondisi cuaca dinamis, dipengaruhi oleh Madden-Julian Oscillation dan anomali suhu permukaan laut. Pola awan hujan yang semula terkonsentrasi di siang hari kini bergeser ke sore dan malam. Intensitas angin meningkat, suhu udara siang naik cepat, sementara kelembapan bertahan tinggi. Kombinasi yang sempurna untuk melahirkan hujan lebat, petir, dan angin puting beliung lokal.
Namun, yang lebih menakutkan dari cuaca ekstrem bukanlah kekuatan alamnya, melainkan ketidaksiapan sosial dan kelembagaan kita menghadapinya.
Bandung secara geografis berada di cekungan yang dikelilingi gunung. Setiap tetes hujan yang jatuh di Lembang, Cimenyan, atau Dago pada akhirnya mengalir ke jantung kota seperti Cikudapateuh, Batununggal, dan Gedebage. Ketika volume air meningkat, sistem drainase yang sempit dan saluran yang tersumbat menjadi bumerang. Dalam satu jam, jalan bisa berubah menjadi sungai kecil, dan rumah warga menjadi bendungan darurat.
Fenomena ini berulang setiap tahun, tetapi responsnya seringkali musiman. Kita menunggu laporan rusaknya rumah, baru kemudian muncul reaksi cepat. Kita menunggu genangan menelan jalan utama, baru mengingat pentingnya normalisasi saluran air. Padahal, mitigasi bencana perkotaan seharusnya menjadi kerja harian, bukan hanya reaksi darurat.
Kota Bandung sudah memiliki Rencana Penanggulangan Bencana Daerah. Namun, implementasi di lapangan masih menghadapi tiga tantangan klasik yaitu koordinasi sektoral, keterbatasan data, dan lemahnya partisipasi masyarakat.
BPBD bekerja di satu sisi, Dinas PUPR di sisi lain, sementara dinas lingkungan hidup berjuang sendiri mengendalikan sampah yang ikut menumpuk di selokan.

Bandung memiliki citra kota kreatif, kota kuliner, dan kota pendidikan. Tapi di tengah semua label itu, kita kerap lupa bahwa Bandung juga kota rawan. Rawan longsor di Cimenyan dan Mandalamekar, rawan genangan di Gedebage, rawan angin kencang di Ujungberung.
Kesiapsiagaan bencana bukan hanya soal logistik dan posko, melainkan juga kemampuan sosial untuk merespons lebih cepat daripada bencananya sendiri. Sayangnya, di tingkat warga, sistem peringatan dini berbasis komunitas belum terbangun secara serius. Warga belum memiliki kanal pelaporan cepat selain media sosial pribadi. Ketika angin datang dan atap beterbangan, kebanyakan hanya berharap pada bantuan spontan tetangga.
Padahal, pengalaman di beberapa kota Asia menunjukkan, community-based disaster risk reduction (CBDRR) terbukti efektif dalam mengurangi dampak bencana mikro. Di Manila, Bangkok, dan Surabaya, sistem peringatan dini sudah terintegrasi sampai level RW dengan pelatihan sederhana. Bandung belum sampai ke sana.
ASN dan Peran Publik Baru
Bagi aparatur sipil negara (ASN) di kewilayahan, bencana bukan sekadar peristiwa alam, melainkan ujian manajemen publik. Seberapa cepat mereka mendata kerusakan, mengoordinasikan warga, dan melaporkan kebutuhan logistik darurat menjadi ukuran nyata dari kapasitas birokrasi yang tanggap.
Namun, sering kali, ASN di lapangan bekerja dengan sumber daya minim. Data risiko bencana yang mereka miliki masih berbasis dokumen cetak, tidak terhubung dengan sistem informasi spasial yang dinamis. Padahal, di era digital, setiap laporan warga bisa langsung dipetakan. Setiap kejadian bisa menjadi data. Setiap data bisa menjadi dasar kebijakan real-time.
Kita memerlukan ASN yang tidak hanya administratif, tetapi juga naratif dan proaktif yang mampu menjelaskan risiko kepada warga dengan bahasa yang sederhana namun menyentuh. Dalam kondisi seperti ini, komunikasi publik menjadi sama pentingnya dengan kemampuan teknis.
Kota modern adalah kota yang mampu membaca langit melalui data.
BMKG telah membuka data cuaca dalam format terbuka. Perguruan tinggi seperti ITB dan Unpad memiliki sistem sensor hujan mikro yang tersebar di beberapa titik. Potensi ini bisa disinergikan menjadi dashboard risiko perkotaan yang diperbarui setiap hari dan diakses publik.
Melalui sistem seperti ini, pemerintah bisa memprediksi area rawan genangan, mengirim peringatan dini ke warga lewat pesan singkat, hingga mengatur jadwal pembuangan sampah agar tidak bersamaan dengan puncak hujan. Kota Bandung memiliki kapasitas intelektual untuk mewujudkan itu, yang dibutuhkan hanyalah kemauan politik dan konsistensi anggaran.
Dalam manajemen risiko, ada satu prinsip sederhana: bencana kecil adalah peringatan besar.
Setiap rumah yang rusak karena angin, setiap pohon tumbang di jalan kota, setiap listrik padam di tengah hujan semua adalah early warning system sosial bahwa sistem kita masih rapuh.
Pemerintah kota perlu menggunakan momentum ini untuk melakukan audit kesiapsiagaan cepat, berapa posko yang aktif, berapa jalur evakuasi yang layak, dan berapa lama waktu respons setelah laporan masuk. Lebih jauh lagi, Pemkot perlu melibatkan komunitas kampus, relawan, dan dunia usaha dalam membangun kota tangguh iklim (climate-resilient city).
Tidak ada bencana yang benar-benar alami. Semua bencana adalah hasil pertemuan antara alam dan manusia. Jika sistem sosialnya kuat, yang datang hanyalah gangguan. Jika sistemnya rapuh, yang datang adalah tragedi.
Menata Ulang Relasi dengan Alam
Di banyak kota, bencana telah memaksa warga menata ulang relasi dengan alam. Di Bandung, hal itu seharusnya tidak perlu menunggu banjir besar. Mulailah dari hal sederhana seperti tidak menutup saluran air rumah dengan semen, tidak membakar sampah di musim kering, dan menanam pohon di pekarangan.
Namun, perubahan perilaku warga tidak akan terjadi jika pemerintah tidak memberikan contoh yang konsisten. Setiap proyek drainase, trotoar, dan pembangunan jalan harus memiliki komponen mitigasi iklim. Setiap izin bangunan harus memuat kajian risiko lingkungan. Kota yang tangguh bukanlah kota yang tidak pernah kebanjiran, melainkan kota yang mampu belajar dari setiap tetes hujan.
Baca Juga: Ciwidey Segar Menggoda, Jalan Gelap Mengintai Bahaya
Bandung yang kita cintai bukan hanya tentang aroma hujan dan langit kelabu yang romantis. Ia juga tentang kemampuan kita sebagai warga dan birokrasi untuk membaca tanda-tanda zaman.
Cuaca ekstrem adalah ujian, bukan untuk menakuti, tetapi untuk memperkuat cara kita hidup bersama.
Di masa depan, ketika hujan turun deras di sore hari, warga tidak lagi menunggu laporan bencana di televisi. Mereka akan tahu ke mana harus melapor, siapa yang harus dihubungi, dan apa yang harus dilakukan. Itulah wajah baru kota Tangguh yaitu ketika reaksi warga dan birokrasi lebih cepat daripada bencananya sendiri.
Bandung hari ini mungkin masih di bawah langit yang gelisah, tapi justru di sanalah kita diuji, apakah kota ini hanya kreatif di waktu cerah, atau juga tangguh di tengah badai. (*)