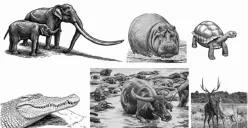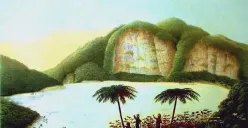Terpilihnya Gibran Rakabuming Raka sebagai Wakil Presiden Republik Indonesia membuka satu babak baru dalam sejarah politik kita. Ia menjadi Wapres termuda yang pernah menjabat, tetapi juga simbol kuat dari perubahan wajah demokrasi yang tengah bergerak ke arah semakin personal, visual, dan digital.
Dalam waktu yang terbilang singkat, Gibran melewati lompatan politik yang luar biasa: dari pengusaha katering, menjadi Walikota Solo, lalu kini menduduki kursi orang nomor dua di republik ini.
Namun yang menarik bukan hanya kecepatannya menanjak, yakni dari sisi digitak public relations, adalah bagaimana ia hadir ke publik lebih sebagai figur yang atraktif secara media, ketimbang sebagai pemimpin yang menyampaikan arah kebijakan negara.
Sebagai Walikota Solo, Gibran dikenal aktif di media sosial, sering melempar komentar ringan, membalas keluhan warga dengan gaya santai, dan sesekali menggunakan meme sebagai medium komunikasi. Ia hadir seperti warganet senior yang kebetulan menjabat kepala daerah. Publik menyambut hangat, terutama generasi muda yang merasa terhubung dengan gaya informalnya.
Kini saat ia menjabat Wakil Presiden, gaya itu tetap dipertahankan. Gibran masih menjadi tokoh yang dekat secara digital, tetapi publik belum melihat peran yang jelas dalam urusan-urusan strategis kenegaraan.
Ia jarang tampil sebagai pengusung gagasan dalam isu sistemik seperti reformasi pendidikan, transformasi birokrasi, penguatan kelembagaan negara, atau kebijakan tata kelola digital. Padahal sebagai Wapres, posisinya tentu lebih dari sekadar pendamping simbolis. Ia seharusnya menjadi bagian dari arsitektur kebijakan negara, menjadi penghubung antara kebijakan makro dan suara akar rumput.
Fenomena ini mencerminkan apa yang oleh banyak pengamat ilmu sosial disebut sebagai demokrasi narsistik (Verhulst, 2020; de Marsilac, 2023), yaitu kecenderungan politik hanya sebagai panggung pencitraan, bukan arena kerja kebijakan. Keduanya menyimpulkan, efek algoritma dan digitalisasi terhadap demokrasi menciptakan budaya “like” dan konsumsi informasi massal yang membentuk subjek digital narsistik—lebih mementingkan citra personal dan interaksi dangkal ketimbang diskursus publik yang bermakna.
Dalam model ini, pemimpin hadir bukan untuk memperkuat sistem, tetapi cukup tampil di hadapan publik, memberi kesan dekat dan responsif. Sering kali, persepsi menggantikan prestasi, dan gaya bicara lebih menentukan citra ketimbang rekam jejak kerja.
Dalam sistem seperti ini, eksistensi digital lebih penting daripada posisi institusional. Seorang pejabat tidak perlu menjelaskan kebijakan yang rumit, cukup hadir dengan senyum, balasan komentar, atau video yang relatable. Padahal, efektivitas pemerintahan sangat bergantung pada kerja kolektif, desain sistem, serta kapasitas membangun institusi yang tahan terhadap perubahan figur.
Gibran memang bukan satu-satunya contoh, tetapi ia adalah figur paling terang-benderang dari era politik yang lebih mengutamakan impresi ketimbang intensi. Ia berada di persimpangan penting, antara melanjutkan karier sebagai bintang media sosial atau membuktikan diri sebagai negarawan.
Posisi Wapres seharusnya bukan ruang sunyi yang hanya diisi rutinitas protokoler, tetapi ruang pengaruh yang bisa digunakan untuk menggerakkan reformasi dan inisiatif kebijakan baru.
Evaluasi Kinerja

Sebagai figur publik, tentu wajar jika Gibran tetap memelihara kedekatan dengan masyarakat melalui kanal-kanal digital. Namun di saat yang sama, publik juga berhak menagih keberpihakan kebijakan. Komunikasi digital memang penting, tetapi akan kehilangan makna jika tidak dibarengi keberanian menyuarakan posisi terhadap isu-isu strategis.
Saat ini publik belum melihat arah itu. Wacana-wacana besar tentang kualitas pendidikan nasional, daya saing teknologi, ketimpangan sosial, atau janji 19 juta lapangan kerja, justru sepi dari suaranya.
Itulah sebabnya publik perlu mulai mengevaluasi kehadiran pemimpin bukan hanya dari cara mereka tampil, tetapi dari gagasan apa yang mereka tawarkan. Apakah Gibran punya visi kebijakan? Apakah ia sedang membangun sistem atau hanya mengisi panggung? Apakah publik cukup puas dengan wakil presiden yang akrab di layar gawai, tetapi tak terdengar dalam perdebatan kebijakan publik?
Demokrasi bukan reality show. Ia membutuhkan pemimpin yang tak sekadar hadir di hadapan kamera, tetapi mampu menyusun arah perubahan. Kita butuh lebih dari sekadar sosok yang akrab, tetapi yang juga punya keberanian mengambil posisi dalam isu penting negara. Popularitas memang memberi jalan, tetapi yang menentukan kualitas demokrasi tetaplah kapasitas kepemimpinan.
Jika Gibran ingin menulis sejarahnya sebagai pemimpin nasional, ia perlu mulai bicara kebijakan. Ia harus mampu mengambil peran substantif secara proporsional dalam pemerintahan, bukan hanya mengelola impresi publik.
Kesempatan itu terbuka, dan masyarakat sebaiknya tak ragu menagihnya. Ia punya modal politik dan popularitas yang tak dimiliki oleh semua pejabat. Tapi modal itu hanya akan menjadi kekuatan transformasi jika dipakai untuk memperbaiki struktur, bukan sekadar memperindah permukaan.
Dan pada titik itu, publik pun perlu berubah. Tak cukup menjadi penonton yang hanya menyukai gaya pemimpin, tetapi perlu berperan aktif menilai arah dan dampak dari setiap kebijakan. Demokrasi yang sehat bukan hanya soal siapa yang tampil paling sering, tetapi siapa yang bekerja paling nyata untuk rakyat.
Sudah cukup kita memilih pemimpin berdasarkan citra digital. Sudah saatnya kita kembali pada pertanyaan dasar demokrasi: siapa yang bisa memimpin dengan gagasan, membangun sistem, dan berani berpihak pada kepentingan rakyat secara nyata. (*)
Jangan Lewatkan Podcast Terbaru AyoTalk: