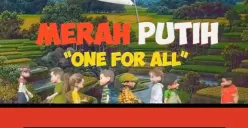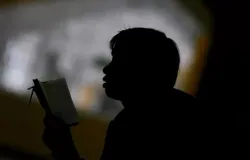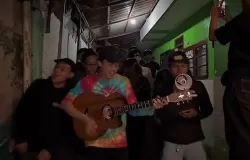Delapan puluh tahun perjalanan komunikasi publik Indonesia menyimpan ironi yang tidak selalu disadari. Kita merayakan kebebasan berekspresi, namun di saat yang sama membiarkan ruang publik kita dipenuhi kebisingan.
Kita menikmati akses informasi tanpa batas, tetapi tak jarang terjebak dalam ruang gema yang sempit. Di balik setiap kemajuan teknologi komunikasi, selalu ada pertanyaan yang menggelitik: apakah kita benar-benar semakin dekat pada demokrasi yang sehat, atau justru semakin jauh terperangkap dalam ilusi kebebasan?
Sejak kemerdekaan, komunikasi publik Indonesia mengalami pergeseran besar dari pola siaran negara yang terpusat menuju arena digital yang terbuka dan partisipatif.
Empat dekade pertama, arus informasi berjalan satu arah di bawah kendali penuh negara. Lembaga humas pemerintah menjadi garda depan dengan dukungan media resmi seperti radio nasional dan surat kabar yang berada dalam ekosistem pengawasan ketat.
Pada masa Demokrasi Terpimpin hingga Orde Baru, komunikasi publik dipandang sebagai instrumen stabilitas, sementara perbedaan pandangan dipersempit melalui regulasi pers yang keras.
Penanda penting hadir pada 24 Agustus 1962 ketika TVRI mengudara untuk pertama kali. Selama hampir tiga dekade, TVRI menjadi satu-satunya stasiun televisi dengan seluruh konten disesuaikan kebijakan resmi. Pergeseran mulai terjadi pada 1989 saat RCTI lahir sebagai televisi swasta pertama, walau kendali pemerintah terhadap keragaman pandangan tetap kuat.
Era Reformasi 1998 membawa keterbukaan signifikan. Pembubaran Departemen Penerangan, liberalisasi izin penerbitan, dan kemunculan media baru memicu ledakan surat kabar, majalah, stasiun radio, dan televisi di berbagai daerah. Internet mulai dimanfaatkan walau akses masih terbatas, perlahan menjadi kanal penting distribusi informasi dan pembentuk opini publik.
Namun keterbukaan ini juga membawa dinamika baru seperti polarisasi isu dan tantangan menjaga integritas informasi.
Memasuki 2008 hingga 2018, ponsel pintar dan media sosial mengubah wajah komunikasi publik. Facebook, Twitter, YouTube, dan Instagram memberikan panggung setara bagi pemerintah, politisi, aktivis, dan warga.
Algoritma menentukan visibilitas pesan, kecepatan viral mengalahkan akurasi, dan hoaks mulai bertebaran. Ruang publik digital pun kerap berubah menjadi arena persekusi, dengan serangan pribadi menenggelamkan argumen substantif. Politik personalistik menguat, dengan citra pemimpin dibentuk melalui konten emosional yang dirancang untuk memantik simpati warganet.
Kerangka hukum pasca Reformasi mencoba mengatur komunikasi publik yang lebih sehat. UU Penyiaran 2002, UU Keterbukaan Informasi Publik 2008, dan UU Informasi dan Transaksi Elektronik 2008 menjadi tonggak penting, walau praktik di lapangan kerap menunjukkan ketegangan antara kebebasan berekspresi dan kontrol berlebihan.
UU Perlindungan Data Pribadi 2022 hadir untuk melindungi warga di ruang digital, namun lambannya pembentukan lembaga pengawas membuat regulasi ini belum maksimal.
Paradoksnya, akses informasi dan kebebasan berekspresi kini berada pada puncak sejarah, namun dibayangi polarisasi, manipulasi algoritma, dan kelelahan partisipasi. Keterbukaan sering dimanfaatkan untuk mempertebal sekat perbedaan. Teknologi yang memungkinkan percakapan lintas batas justru sering mengurung warga dalam ruang gema.
Demokrasi digital membutuhkan ekosistem komunikasi sehat, tetapi yang terjadi justru ruang publik ramai dengan minim perjumpaan gagasan.
Empat Langkah

Untuk keluar dari paradoks ini, empat langkah perlu diperkuat.
Pertama, literasi digital yang konsisten agar masyarakat mampu menilai akurasi informasi sebelum membagikannya. Guess et al. (2020) menunjukkan literasi media berskala besar dapat meningkatkan kemampuan membedakan berita arus utama dan berita palsu.
Kedua, desain sistem rekomendasi media sosial harus mendorong keberagaman perspektif melalui audit algoritmik sebagaimana disarankan Helberger (2011).
Ketiga, pendidikan perspektif yang menumbuhkan empati lintas kelompok, dengan framing tujuan pembelajaran sosial sebagaimana diperingatkan Bail et al. (2018).
Keempat, memperluas arena partisipasi publik deliberatif yang inklusif, selaras dengan temuan Perez (2018) tentang demokrasi elektronik kolaboratif.
Masa depan komunikasi publik Indonesia akan ditentukan oleh kemauan kolektif negara, media, platform digital, dan masyarakat untuk membangun ruang dialog beradab dan aman.
Delapan puluh tahun perjalanan ini mengajarkan bahwa komunikasi publik yang sehat bukan hanya soal teknologi, tetapi komitmen moral untuk menjaga keberagaman suara sebagai napas demokrasi itu sendiri. (*)