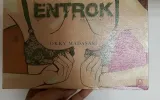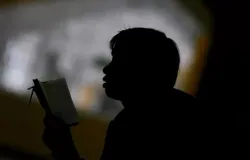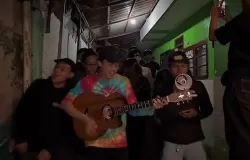Bayangkan suatu hari, di mana anak-anak bangun pagi dengan mata berbinar, bukan karena takut terlambat upacara atau terlambat masuk kelas, tetapi karena penasaran: apa yang akan aku pelajari hari ini?
Bayangkan ruang kelas di mana guru bukan sekadar "tukang ceramah" di depan papan tulis, tetapi fasilitator yang memantik diskusi—tentang mengapa Siti Nurbaya menolak tunduk pada adat yang mengekangnya, bagaimana perspektif Marxis membaca kemiskinan di kampung-kampung, atau apa hubungan algoritma TikTok dengan kebebasan berekspresi.
Sayangnya, kenyataan kita justru berbanding terbalik. Sistem pendidikan kita masih terjebak dalam mentalitas kolonial: mencetak pekerja patuh, bukan pemikir merdeka. Kita mengajarkan Pancasila sebagai teks hafalan, bukan sebagai pisau analisis untuk mengupas ketidakadilan sosial.
Kita dulu mengagungkan nilai UN, kini nilai AKM, tapi abai pada pertanyaan mendasar: apa artinya semua angka itu kalau anak-anak tak mampu berpikir jernih tentang masalah nyata di sekitar mereka?
Kebebasan yang Ditakuti
Goenawan Mohamad pernah menulis bahwa kebebasan bukanlah “keliaran”, melainkan ruang untuk tumbuh. Tetapi lihatlah kelas-kelas kita: murid dimarahi karena menjawab di luar “kunci jawaban”, siswa SMK dipaksa kerja rodi di pabrik atas nama “magang”, mahasiswa dibungkam karena dianggap “mengganggu ketertiban”.
Kita begitu takut pada kebebasan berpikir, seakan lupa bahwa semua terobosan besar dalam sejarah lahir dari keberanian melawan pakem.
Paulo Freire, seorang pemikir pendidikan asal Brasil, mengkritik hal ini lewat konsep pendidikan gaya bank. Dalam model itu, guru seperti kasir yang “menyetor” informasi ke kepala murid, seakan otak anak hanyalah brankas kosong.
Tak ada ruang dialog, tak ada proses bertanya balik. Bagi Freire, pendidikan sejati adalah dialogis: guru dan murid sama-sama belajar, bertukar pandangan, dan membentuk kesadaran kritis (critical consciousness). Tujuannya bukan sekadar “tahu”, tetapi sadar—agar bisa mengubah dunia di sekitarnya.
Banyak yang mengira pendidikan berkualitas tinggi harus penuh ujian, ranking, dan persaingan. Finlandia membuktikan sebaliknya. Di sana, ujian standar hampir dihapus; satu-satunya tes nasional dilakukan ketika siswa berusia 16 tahun. Tak ada ranking sekolah, tak ada lomba nilai antar-murid.
Guru dipercaya penuh untuk merancang kurikulum sesuai kebutuhan lokal—bahkan dua kelas di sekolah yang sama bisa punya pendekatan berbeda, asalkan tujuannya jelas: membuat anak mengerti, bukan sekadar mengingat.
Jam belajar pun lebih singkat daripada di Indonesia, memberi ruang untuk bermain, berorganisasi, atau sekadar menikmati waktu bersama keluarga.
Anehnya, justru dengan “longgar” seperti ini, Finlandia konsisten berada di peringkat atas dalam tes internasional seperti PISA. Mengapa? Karena mereka memahami bahwa pendidikan bukan maraton hafalan, melainkan proses menumbuhkan rasa ingin tahu dan kemampuan berpikir kritis.
Tradisi Kebebasan Berpikir di Nusantara

Sebagian orang menolak gagasan kebebasan akademik dengan dalih “itu budaya Barat”. Padahal, sejarah Nusantara penuh dengan contoh tokoh yang berpikir merdeka jauh sebelum istilah liberal arts dikenal di kalangan kita.
Syekh Yusuf Al-Makassari, misalnya, bukan hanya ulama, tapi juga aktivis yang menentang tirani kolonial dan membela martabat manusia. Ia menulis tentang pentingnya akal sehat dan keberanian moral, meski itu berarti berseberangan dengan penguasa.
Kartini pun demikian. Dalam surat-suratnya, ia berani menggugat adat dan dogma yang membelenggu perempuan Jawa. Ia tak menolak budaya, tapi menolak kemapanan yang menghalangi kemajuan.
Baik Kartini maupun Syekh Yusuf mengajarkan kita bahwa keberanian berpikir kritis bukanlah impor dari Barat—ia lahir dari tanah ini, dari hati orang-orang yang menolak diam ketika ketidakadilan dibiarkan.
Kalau begitu, bagaimana memperbaiki keadaan? Kita harus berani mengganti budaya hafalan dengan budaya dialog. Biarkan siswa bertanya bahkan pada hal-hal yang dianggap “suci”—termasuk otoritas guru. Berikan kebebasan bagi guru untuk mengajar sesuai konteks muridnya, tanpa takut disalahkan karena tidak mengikuti “script” dari pusat.
Hilangkan hierarki kaku: kepala sekolah bukan raja kecil, tapi fasilitator proses belajar. Jadikan kelas sebagai forum membahas isu-isu yang benar-benar relevan—korupsi, kesenjangan, radikalisme—agar anak-anak terbiasa membedakan fakta, opini, dan propaganda.
Keberhasilan jangan lagi diukur dari angka di rapor, melainkan dari kemampuan bernalar, berempati, dan mengambil keputusan. Sebagaimana kata Einstein, “Jangan nilai ikan dari kemampuannya memanjat pohon.”
Kita Tidak Butuh Revolusi
Indonesia tak perlu menjadi “Barat” untuk maju. Kita hanya perlu menghentikan kebiasaan membungkam potensi anak-anak dengan alasan takut pada kebebasan. Goenawan pernah bertanya:
"Kalau kita melihat manusia tumbuh bebas dan memilih, mampukah kita bersikap optimistis bahwa mereka pada akhirnya akan memilih dengan benar dan baik?"
Pendidikan sejati bukan soal mencetak generasi patuh, tapi generasi yang berani bertanya—bahkan pada generasi sebelum mereka. Bayangkan suatu hari nanti, seorang anak di pelosok Flores berkata:
"Sekolah adalah tempat di mana aku belajar bukan hanya untuk lulus ujian, tapi untuk memahami dunia—dan mengubahnya."
Itulah pendidikan yang memerdekakan. Dan itu mungkin terjadi, jika kita berani membuka pintunya. (*)