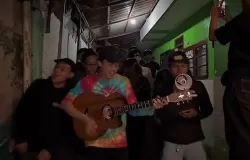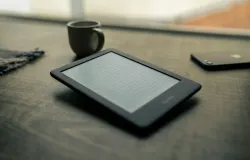Pekan ini, warga Jawa Barat boleh jadi dibuat kaget keputusan Pemerintah Provinsi Jawa Barat menghapus alokasi hibah pesantren dalam APBD Perubahan 2025.
Sebelumnya, Gubernur Jabar KDM (Kang Dedi Mulyadi) pernah berjanji bantuan itu akan dimasukkan dalam APBD Perubahan, seperti diberitakan Kompas pada 28 April 2025.
Jauh sebelum kejadian ini, bantuan kepada pondok pesantren sudah ketok palu disepakati APBD sebelumnya, senilai sekitar Rp 153,5 miliar, sesuai Perda Nomor 1 Tahun 2024 per 8 November 2024 oleh PJ. Gubernur Bey Machmudin. Sekarang? Janji tinggal janji, sarana prasarana pesantren yang biasa dipugar lewat dana hibah, sirna sudah.
Putusan ini memberikan kesan bahwa janji-janji ternyata tidak didasarkan rencana riil, melainkan sebatas lebih banyak retorika. Publik telah disuguhkan kenyataan wacana yang disampaikan, namun (lagi-lagi) tidak diikuti realisasi!
Dalam konteks politik dan komunikasi publik, janji bukanlah sekadar wacana. Setiap kata yang keluar dari mulut kepala daerah, termasuk KDM, menjadi kontrak moral dan politik. Studi komunikasi politik menunjukkan, pemimpin dituntut lebih berhati-hati dalam berwacana dibanding publik biasa (Kondolele, 2025).
Dalam riset berjudul The nexus between public communication and policy implementation ditekankan, efektivitas kebijakan sangat bergantung kualitas komunikasi publik yang dilakukan dengan cermat, selektif, dan disertai validasi, bukan sekadar wacana.
Komunikasi terburu-buru atau tanpa perencanaan sama saja dengan menanam ekspektasi tanpa benih ajaib yang bisa tumbuh, sehingga publik akan kecewa dan kepercayaan tergerus.
Sebuah ungkapan lama menyebut bahwa diam itu emas. Dalam konteks pemerintahan dan demokrasi, diam dan bekerja adalah bentuk komunikasi nonverbal yang jauh lebih bermakna dibanding retorika tak berdasar.
Rakyat lebih menghormati pemimpin yang berbicara seperlunya, tetapi membuktikan banyak melalui langkah nyata. Janji tanpa bukti hanya menciptakan jurang antara harapan dan realitas.
Isu pesantren bukan sekadar angka anggaran. Ini menyentuh nilai luhur dan sensitivitas lembaga pendidikan, spiritualitas keluarga, dan pemerintahan yang memperlihatkan keberpihakan. Ketika janji semacam itu tidak ditepati, rasa kecewa akan melebar ke ranah yang lebih luas, memicu skeptisisme terhadap kebijakan dan pejabat yang membuatnya.
Seharusnya, jika realisasi tidak memungkinkan sesuai janji awal, pemerintah bisa menempuh narasi strategi transparan: mengajak dialog, menjelaskan kendala teknis, dan menawarkan solusi adil dan layak. Daripada diam-diam membatalkan tanpa penjelasan, pendekatan terbuka akan lebih menjaga citra kebijakan dan institusi.
Dalam demokrasi yang sehat dan negara hukum sejati, kepercayaan publik bukan dibangun melalui retorika mewah, tetapi melalui integritas tindakan. Pemimpin yang percaya diri bukan yang banyak berjanji, tetapi yang membiarkan hasil berbicara pada waktunya.
Kualitas demokrasi akan lebih tercermin ketika alat komunikasi politik digunakan dengan kejujuran, akurasi, dan tanggung jawab. Sampai kapan ingkar janji, wahai penguasa? (*)