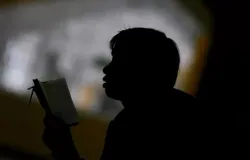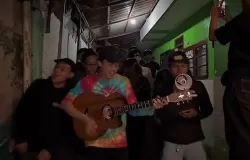AYOBANDUNG.ID -- Setiap pagi, sebelum matahari benar-benar terbit, debu putih sudah lebih dulu menyelimuti atap-atap rumah di Kampung Cisaladah, Desa Gunungmasigit, Kecamatan Cipatat, Kabupaten Bandung Barat. Bukan kabut, partikel halus itu batu kapur yang melayang dari cerobong-cerobong pabrik penggilingan di sekitar permukiman.
Tak cuma debu putih halus, cakrawala kampung itu kerap pengap oleh asap hitam pekat dari tungku raksasa yang membakar hasil tambang gamping. Warga menyebut tungku itu sebagai lio, sebuah pembakaran batu tradisional berbahan bakar: ban bekas, sampah, hingga batu bara.
Debu dan asap pekat itu bukan hanya mengaburkan pandangan, tapi juga perlahan-lahan menggerogoti kesehatan dan harapan hidup warga setempat. Bagi mereka, menghirup udara bersih kini terasa seperti kemewahan yang semakin langka.
"Bukan hanya di luar rumah, kalau angin sedang mengarah ke sini masuk rumah," kata Abah Iya, 86 tahun, warga yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari tungku lio dan pabrik penggilingan.
Sejak tahun 1970-an, kawasan pegunungan karst Citatah meliputi 4 desa yakni Padalarang, Gunung Masigit, Citatah, dan Cipatat mengalami ekploitasi besar-besaran dengan hadirnya aktivitas tambang dan industri penggilingan batu gamping. Kondisi itu terjadi seiring meningkatnya kebutuhan bahan baku batu gamping untuk beragam industri seperti peleburan baja, pembuatan semen, kosmetik, keramik, hingga pakan ternak.
Baca Juga: Legenda dari Citatah: Kisah Harry Suliztiarto Menaklukkan Tebing Utara Gunung Eiger
Kegiatan pemanfaatan sumber daya alam secara ekstraktif ini sontak membawa beragam persoalan serius di kawasan karst. Bukit-bukit batu gamping yang menjulang unik hasil karstifikasi jutaan tahun lamanya nampak bopeng oleh tambang. Permukaan batu yang dulu bertekstur alami kini berubah menjadi bidang-bidang curam yang terkelupas, meninggalkan warna pucat dan kesan gersang.
Di sekitar pabrik, debu kapur melayang di udara, menutupi pepohonan dan permukiman sekitar dengan lapisan putih tipis. Suara mesin pemecah batu mengisi langit, menggantikan ketenangan yang sebelumnya mendominasi.
Iya menunjuk ke arah halaman rumahnya yang dipenuhi lapisan tipis debu putih. Bahkan dedaunan pohon mangga miliknya tampak pucat, seolah tak lagi mampu berfotosintesis dengan sempurna.
Aktivitas penggilingan dan tambang batu kapur memang menjadi sumber penghidupan bagi sebagian warga, tapi di saat yang sama menjadi momok yang meracuni kehidupan mereka. Mesin-mesin besar yang menggiling batu terus bekerja tanpa henti, memproduksi suara bising dan menyemburkan debu halus ke udara.
"Jadi kalau dari pabrik itu kan pakai mesin dampaknya asap putih halus dari penggilingan. Nah kalau dari lio dampaknya asap hitam, karena pakai bekas ban," jelas Iya.
Iya tinggal bersama 4 orang anggota keluarga terdiri dari dua anak dan dua orang cucunya. Pilihan tinggal di kawasan pengolahan pabrik pengolahan kalsium karbonat bubuk bukan soal sehat atau sakit, melainkan pilihan untuk bertahan hidup lebih lama.
Di usia senjanya, Iya hanya bisa duduk di beranda rumahnya sambil sesekali mencabut rumput liar dan perdu, mengamati kepulan asap dari tungku pembakaran yang mengepul tak jauh dari halamannya. Batuknya tak kunjung reda, tapi untuk pindah dari desa ini—satu-satunya tempat yang ia kenal seumur hidup—tak pernah menjadi pilihan, bukan karena tak ingin, tapi karena tak mampu.
"Mau pindah ke mana? Rumah ini saja saya bangun dari sedikit demi sedikit uang jual hasil kebun dulu," gumamnya lirih.
Iya tahu asap itu perlahan merenggut napasnya, namun ia juga tahu bahwa meminta pabrik ditutup berarti mencabut mata pencaharian para tetangga, para keponakan, dan cucu-cucu tetangganya yang masih menggantungkan hidup dari debu kapur itu. Ia memilih diam, pasrah dalam pengap dan kepulan, terjebak dalam dilema yang tak berpihak padanya.
"Kata orang biar menekan dampaknya pakai masker dan rutin minum susu. Saya gak bisa kalau tiap hari, paling banter minum susu seminggu sekali. Mudah-mudahan tetap sehat," tandasnya.
Baca Juga: Paradoks Pembangunan PLTA Upper Cisokan: Energi Terbarukan, Ruang Hidup Terabaikan

Mengenal Karst Citatah
Karst Citatah merupakan bentang alam purba punya nilai unik dari sisi ekologis, geologis, hingga arkeologis. Kawasan ini membentang dari daerah Rajamandala, Kecamatan Cipatat sampai Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang. Berdasarkan pemetaan Badan Pengelolaan Lingkungan Hidup Daerah (BPLHD) Provinsi Jawa Barat tahun 2009, karst Citatah memiliki panjang sekitar 27 kilometer dengan luas wilayah sekitar 10.320 hektar meliputi lahan sawah 1.794 hektar dan tanah darat 8.526 hektar.
Badan Geologi menyebut kawasan Karst Citatah–Rajamandala berada pada deretan perbukitan setinggi sekitar 700–900 meter di atas permukaan laut. Jalur perbukitan itu terbentang dari wilayah Tagogapu di bagian timur–timur laut, melewati sisi utara Padalarang, lalu terus ke arah barat–barat daya hingga kawasan Saguling di selatan Rajamandala.
Rangkaian bukit tersebut merupakan hasil lipatan batuan laut berumur Tersier, yang tersusun oleh batu lempung Formasi Batu asih, batu gamping Formasi Rajamandala, batu pasir–batu lempung Formasi Citarum, serta breksi dari Formasi Saguling. Di koridor Tagogapu–Citatah–Saguling, bentang alam yang paling mencolok adalah bukit-bukit karst yang berkembang pada batu gamping Formasi Rajamandala.
Dosen Geologi pada Fakultas Ilmu dan Teknologi Kebumian ITB, Astyka Pamumpuni mengatakan formasi Karst Citatah-Rajamandala mulai terbentuk pada periode sekitar 35 juta tahun lalu. Umur tersebut menjadikannya karst ini jadi satu-satunya kawasan karst tertua di Pulau Jawa.
Pada zaman tersebut, kawasan itu masih berupa lautan dangkal. Endapan kapur yang ada sekarang merupakan hasil pembentukan terumbu karang yang tumbuh di dasar perairan. Jejak geologi ini sekaligus menunjukkan bahwa dataran tinggi Bandung pada masa lampau pernah menjadi wilayah laut dangkal sebelum akhirnya surut dan mengering.
"Setelah terangkat ke permukaan terjadilah peralutan oleh air hujan sehingga membentuk rekahan, ceruk, batu bolong-bolong, gua dan sungai bawah tanah," kata Astyka.
Setelah kawasan itu tidak lagi tergenang air, area tersebut jadi ruang hidup aneka flora-fauna hingga manusia prasejarah salah satunya di Gua Pawon. Berdasarkan hasil pemetaan BPLHD Jabar, ada sedikitnya 30 gua tersebar di area karst Citatah.
"Keunikan bentuk bantuan karst, kemunculan air tanah, ornamen, serta umurnya yang tua membuat karst ini unik," papar Astyka.
Budi Brahmantyo, dalam buku Wisata Bumi Cekungan Bandung (2009), menulis batu gamping yang terbentuk dari proses karstifikasi mempunyai potensi alami yang besar. Banyaknya retakan dan pembentukan lubang, gua, dan sungai bawah tanah di dalam tubuh batuan, formasi batu gamping bisa menjadi tem pat penampungan cadangan air bersih.
Baca Juga: Jejak Sejarah Gempa Besar di Sesar Lembang, dari Zaman Es hingga Kerajaan Pajajaran
Di sisi lain, proses karstifikasi menyebabkan terbentuknya morfologi dan bentang alam yang unik yang umumnya berupa perbukitan runcing dengan lembah-lembah dan dinding batuan terjal. Di kawasan karst Citatah, hal itu bisa dilihat dari adanya perbukitan seperti Pasir Balukbuk, Pasir Karang Panganten, Pasir Pawon, Gunung Masigit, Pasir Bancana, Gunung Guha, Gunung Manik, Gunung Hawu dan Pabeasan.
Budi menerangkan di dalam batu-batu gamping itu, tersimpan pula jutaan fosil binatang laut yang sekaligus menjadi saksi bisu atas keberadaan laut yang menggenangi daerah itu puluhan juta tahun lalu pada Kala Oligosen hingga Miosen Awal. Fosil-fosil itu dapat dilihat dengan jelas pada pecahan-peca-han batu gamping yang tersebar di daerah ini.
"Proses geologi kemudian mengangkat batu gamping itu dari dasar laut sampai ke ketinggiannya saat ini, dan mengerosinya sehingga menghasilkan bentang alam yang unik dan menakjubkan. Unik, karena di sekitar Bandung hanya di Padalarang lah terdapat perbukitan batu gamping," tulis Budi.
Dampak Kerusakan Karst
Di tengah melimpah potensi ekologis, geologis, dan arkeologis karst Citatah, eksploitasi industri ekstraktif berupa tambang dan kegiatan penggilingan batu terus menjadi ancaman. Selain kerusakan ekosistem karst, kegiatan industri pertambangan telah membawa dampak negetif lain berupa polusi debu, kehilangan sumber mata air, masalah perizinan, hingga pelanggaran hak buruh.
Potret polusi debu dan asap tungku tradisional misalnya, masih terjadi di 4 desa yakni Desa Padalarang, Gunung Masigit, Citatah, dan Cipatat. Dampak polusi dapat dilihat secara kasat mata dari jejak putih di daun tanaman, genting rumah, hingga lantai rumah yang berdekatan dengan pabrik.
Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (DPMPTSP) mencatat jumlah industri pengolah batu kapur di Bandung Barat mencapai 54 perusahaan. Jika dirinci, puluhan industri itu tersebar 43 perusahaan di Kecamatan Cipatat, 11 di Kecamatan Padalarang, dan masing-masing 1 perusahaan di Ngamprah dan Lembang.
Ironisnya dari data tersebut, Dinas Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Provinsi Jawa Barat mencatat hanya 36 kegiatan tambangdi Bandung Barat yang sudah mengantongi izin. Sedangkan sisanya masuk kategori ilegal karena izin belum lengkap. Bahkan pada Juni 2025, ada 14 tambang ilegal di Bandung Barat dihentikan.
Baca Juga: Sejarah Padalarang dari Gua Pawon ke Rel Kolonial, hingga Industrialisasi dan Tambang Zaman Kiwari

Berdasarkan temuan Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB), lebih dari separuh dari total 10.000 hektare kawasan tersebut telah rusak akibat aktivitas penambangan. Di area itu diperkirakan beroperasi sekitar 100 perusahaan yang mengekstraksi batu, kapur, dan marmer, serta memproduksi tepung batu dan olahan batu alam, dengan melibatkan sedikitnya 5.000 pekerja.
Andri Prayoga, Peneliti pada Perhimpunan Rakyat Pemerhati Karst Citatah (PRPKC) mengatakan kegiatan penambangan di kawasan karst makin hari kian masif. Kondisi itu memicu percepatan kerusakan di area pegunungan karst. Menurutnya, pada awal tahun 2000, kegiatan tambahan didominasi oleh praktik penambangan tradisional milik masyarakat. Sedangkan pasca tahun 2017, industri ekstraktif memiliki modal besar, teknologi alat berat, serta perluasan kosesi tambang.
"Dulu banyaknya pertambangan rakyat dengan alat tradisional dan luasan konsesi tak lebih dari 5 hektare. Sekarang konsesi tambang bisa capai 10 hektare dengan metode teknologi kontemporer. Jadi sekarang ada percepatan dan perluasan luasan area kerusakan," jelas Andri.
Dari sederet pegunungan karst Citatah sampai Rajamandala hampir seluruhnya telah tersentuh pertambangan. Lokasi yang benar-benar belum digali ekskavator tinggal di area Cipaneguh blok Gunung Guha. Lokasi tersebut relatif bisa terselamatkan karena masuk kawasan hutan serta telah ditetapkan sebagai Kawasan Bentang Alam Karst (KBAK) Citatah ditetapkan sebagai kawasan lindung geologi melalui Peraturan Menteri ESDM Nomor 17 Tahun 2012 dan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Republik Indonesia Nomor 1830 K/40/MEM/2018.
"Jadi makin ke sini (tambang) makin massif. Blok tebing karst dari desa Ciburuy, Padalarang sampai Bojong Picung Cianjur sudah ada aktivitas tambang. Paling tinggal di daerah Cipaneguh," jelasnya.
Peneliti dari Pusat Riset Arkeologi Prasejarah dan Sejarah BRIN, Lutfi Yondri mengamini tentang kondisi kritis karst Citatah. Aktivitas tambang itu ikut merusak 29 gua yang tersebar di kawasan itu. Padahal, di dalam gua masih punya potensi peninggalan budaya seperti di Gua Pawon.
"Ada 29 titik gua di kawasan karst Citatah, di luar Gua Pawon, yang telah didata Pak Budi Brahmantyo. Yang jadi masalah, penelitian kita tentang jejak budaya di sana tak secepat pengrusakan gua oleh tambang," kata Lutfi.
Apalagi berdasarkan survei awal dan beberapa laporan masyarakat kerap mendukung adanya simpulkan peninggalan budaya di gua-gua itu. "Dari 29 titik gua, kita sudah survei beberapa seperti Komplek Gua Ketug, itu ada 6 ruang gua. Tapi datanya tidak seperti data Gua Pawon. Gua Pare Batu lapisan tak seperti Pawon tapi indikasi Paleolitik ada di situ," jelasnya.
"Gua lain seperti di Gunung Tanjung dari bekas peledakan sempat ditemukan rangka manusia tapi tak sempat diselamatkan karena hancur. Terus kemudian, ada Gua Peteng. Ini belum disentuh sama sekali," ungkap Lutfi.
Perbukitan kapur di kawasan Citatah tampak tandus. Struktur batuannya yang berongga dan penuh celah membuat air hujan mudah meresap ke dalam tubuh bukit, lalu tertampung menjadi kantong-kantong air bawah tanah yang biasanya keluar kembali secara teratur di bagian kaki bukit.
Baca Juga: Jejak Kehidupan Prasejarah di Gua Pawon Karst Citatah Bandung Barat
T. Bachtiar, Anggota Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) dalam bukunya Bandung Purba (2012) mencatat adanya gangguan sumber air akibat tambang di kawasan karst Citatah. Di bagian utara Gunung Masigit dan Pasir Pawon, misalnya, pernah ada deretan mata air yang mengalir deras dari lerengnya. Aliran itu kemudian memunculkan sebuah permukiman tak jauh dari sumber air, yang akhirnya dikenal sebagai Kampung Cipanyusuan—nama yang merujuk pada kedekatannya dengan mata air.
"Namun kondisi tersebut kini berubah. Hampir seluruh mata air itu telah lenyap. Hanya satu yang masih tersisa di sisi utara Pasir Pawon, itupun dengan debit yang terus menurun," tulis T. Bachtiar.
Kawasan pegunungan Sanghyang salah satu gunung karst di Cipatat memiliki fungsi sebagai daerah resapan. Banyaknya pepohonan serta struktur batuan karst membuat area ini menyimpan banyak cadangan air. Berdasarkan penuturan warga setempat, sedikitnya ada 5 mata air besar yang keluar dari perbukitan Gunung Sanghyang. Diantaranya, mata air Cipaneguh, mata air Pasir Sepat, mata air Cisaladah, mata air Ciketung, dan mata air Cijawer.
Mata air itu dipakai untuk kebutuhan minum dan pertanian di kampung Pojok, kampung Cijuhung, kampung Sirnagalih, kampung Cibarengkok, kampung Lapingsari dan kampung Gunung Batu Desa Ciptaharja. Serta sebagian warga Desa Cipatat.
"Ratusan warga sangat bergantung pada sumber air ini. Mereka memanfaatkan air dengan cara memasang pipa dan membuat irigasi untuk pertanian," kata Ibnu, tokoh pemuda Desa Ciptaharja.
Sejak dulu, kata Ibnu, Gunung Sanghyang menjadi gentong air tak tergantikan. Meski beberapa tahun terakhir debitnya berkurang untuk pemakaian lahan pertanian. Sungai-sungai besar bersumber dari hulu mata air ini tak mencukupi untuk sawah. Malah saat musim kemarau, airnya kering.
"Lima mata air ini masih aktif sampai sekarang meski debitnya dari tahun ke tahun terus berkurang, terutama debit air sungai, makin kecil," tambah Ibnu.
Ibnu menyebut berkurangnya debit air dari Gunung Sanghyang disebabkan sejumlah faktor diantaranya berkurangnya tanaman tegakkan serta masifnya kegiatan tambang di beberapa titik. Bahkan letak tambang makin mendekati sumber mata air seperti Cisaladah dan Ciketung.
Gunung tersebut kini dieksploitasi tambang kapur oleh beberapa perusahaan diantaranya PT Multi Marmer Alam/Akarna Marindo di kawasan Gunung Guha, Indoraya/Sanghyang Mineral di Gujung Sanghyang Lawang, serta Pumarin dan Indoprima/ PT Citatah di kaki Gunung Cibalukbuk.
"Kalau dulu kami bertani 2 kali setahun. Sekarang karena debit air kecil, kalau beruntung setahun cuma sekali menanam padi. Karena air gak stabil, banyak sawah yang dialihkan jadi lahan taman palawija," pungkasnya.
Baca Juga: Merayakan Sejarah Panjat Tebing di Citatah 125, Menjaga Karst untuk Generasi Mendatang

Perlindungan Karst: dari Aksi Jalanan ke Kampung Berseri
Usaha menjaga kelestarian perbukitan kapur yang termasuk dalam Formasi Rajamandala sebenarnya telah disuarakan sejak lama. Aktivis lingkungan bersama kelompok peneliti sudah berkali-kali melakukan berbagai bentuk aksi maupun pertemuan dengan pihak terkait.
Deden Syarif Hidayat adalah salah satunya. Memimpin anak muda yang tergabung dalam Forum Pemuda Karst Citatah (FP2KC), ia melaksanakan serangkaian upaya konservasi karst sejak tahun 2009. Langkah itu dimulai dengan gerakan mengedukasi masyarakat tentang pentingnya pelestarian gunung kapur sebagai pusat laboratorium ilmu sejarah dan geologi dan penunjang utama penghidupan warga.
Masyarakat diberi pengetahuan tentang fungsi karst sebagai sumber air, tempat keragaman flora-fauna, dan benteng alamai dalam mencegah potensi bencana kekeringan, banjir, serta longsor. "Kita sadar bahwa karst ini punya nilai penting bagi nilai ilmiah, ekonomi, serta ekologi. Makanya kita lakukan kajian soal ini, hasilnya kami edukasi dengan berbagai cara kepada masyarakat. Kita gelar diskusi, nonton bareng, dan beragam kampanye supaya masyarakat ikut tahu soal nilai penting karst bagi kehidupan," papar Deden.
FP2KC tak sendiri, mereka berkolaborasi dengan sejumlah aktivis mahasiswa, kelompok masyarakat pegiat lingkungan, atlet panjat tebing, dan para peneliti dari Badan Geologi, serta Kelompok Riset Cekungan Bandung (KRCB) untuk memetakan bentang alam karst. Gerakan edukasi dan kampanye penyelamatan karst itu meluas ke jalur gerakan advokasi hingga aksi massa.
"Kami menghimpun sejumlah elemen masyarakat untuk melaksanakan serangkaian langkah konservasi karst. Tak hanya edukasi, kami melaksanakan penelitian lapangan hingga aksi massa. Upaya ini sempat membuahkan hasil dengan terbitnya moratorium izin tambang karst dari Pemprov Jabar, pada tahun 2009," papar Deden.
Bukan hanya moratorium izin tambang, gerakan Deden dan kawan-kawan berhasil menghentikan kegiatan tambang di beberapa lokasi pegunungan karst seperti Pasir Pawon, Gunung Masigit, dan Gunung Hawu. Mereka juga telah mengerem penggunaan bahan peledak untuk tambang, menetapkan cagar budaya di Gua Pawon, serta berhasil penetapan Kawasan Bentang Alam Karst oleh kementerian ESDM di wilayah Cipaneguh.
"Dalam perjalanannya itu bukan tanpa risiko. Saya beberapa kali mendapat tekanan agar menghentikan penyelamatan karat. Bahkan beberapa kali saya diancam jadi sasaran tindak kekerasan," tutur ayah satu anak itu.
Sebagian upaya konservasi karst memang membuahkan hasil, namun tak sedikit pula yang kandas di tengah jalan. Faktanya, mengurangi aktivitas penambangan secara drastis bukan perkara mudah. Apalagi, dorongan penyelamatan karst seringkali bersebrangan dengan regulasi atau lebih jauh lagi: kerap dibenturkan dengan kebutuhan perut masyarakat karena ada ratusan warga yang masih menyandarkan penghidupan dari industri tambang.
"Regulasi sering tumpang tindih bahkan mudah berubah. Zona-zona konservasi karst yang semula ditetap ditetapkan bisa kapan saja hilang oleh perubahan tata ruang wilayah. Terlebih, persoalan kebutuhan dasar atau mata pencaharian sering jadi alasan. Karena gak ada juga langkah serius alih profesi dar tambang ke pendekatan ekonomi berkelanjutan," papar Deden.
Karena kondisi itu, Deden memutuskan mengalihkan fokus perjuangannya. Dari yang semula menuntut penutupan tambang, ia berbelok menuju upaya pemberdayaan ekonomi warga. Bersama masyarakat Kampung Cidadap, Desa Padalarang, ia menawarkan cara baru memanfaatkan kawasan batu gamping Citatah tanpa merusaknya. Mereka hadir bukan dengan alat berat untuk menggali bukit, tetapi membawa gagasan pengelolaan alternatif yang menekankan konservasi, edukasi, dan kegiatan wisata.
Salah satu dukungan penting datang dari Astra Honda Motor yang terlibat sejak 2017. Melalui program tanggung jawab sosial perusahaan, AHM menetapkan Kampung Cidadap sebagai Kampung Berseri Astra, sebuah program pendampingan yang telah diterapkan di berbagai wilayah di Indonesia.
Melalui gerakan Kampung Berseri Astra Cidadap, bukit-bukit karst bekas tambang diubah jadi area wisata tempat berkemah, hammocking, dan rappelling. Tak cuma jadi tempat wisata dan terselamatkan dari tambang, lokasi-lokasi karst seperti Gunung Hawu, Gunung Pabeasan,Karang Panganten, Sanghyang Kenit, Gunung Masigit, dan Pasir Pawon berhasil diubah jadi rumah belajar bagi para atlet pemanjat tebing dan laboratorium alam bagi ilmu kebumian.
"Saya sadar penyelamatan karst ini gak bisa cuma menuntut tambang tutup. Tapi perlu gerak konsisten dengan menunjukan alternatifnya. Sehingga mereka bisa tahu ada alternatif ekonomi tanpa perlu merusak," jelas Deden.
Astra turut mendampingi warga Cidadap melalui berbagai bentuk pelatihan dan penyediaan fasilitas. Mulai dari bantuan ratusan bantuan bibit buah langka, boulder bagi pemanjat cilik, pemasangan biodigester, peralatan hidroponik, dukungan bagi pengembangan wisata, pembangunan MCK, sumur bor dan sumur resapan, hingga bantuan instrumen angklung untuk kegiatan belajar, perlengkapan pengelolaan sampah, serta papan edukasi soal keunikan karst. Kehadiran Astra membuat Kampung Cidadap seakan memiliki mitra dalam setiap langkah penyelamatan.
"Kami tak bisa sendiri. Upaya penyelamatan karst ini harus menggandeng berbagai lapisan masyarakat dan para pihak. Di sini kami banyak dukungan dari Astra, tentu di tempat lain bisa dari pihak berbeda. Siapa pun itu, semangat ini semoga bisa tertular ke wilayah-wilayah lain di tanah air," tutup Deden.
Baca Juga: Masa Depan Bandung Utara Terancam, WALHI Soroti Bobroknya Sistem Perizinan
Kampung Berseri
Udara pagi di Kampung Cidadap, Desa Padalarang, Kecamatan Padalarang, Kabupaten Bandung Barat, terasa sejuk menyapa kulit. Kabut tipis perlahan lenyap ditiup angin bersamaan dengan cahaya matahari yang menembus dinding tebing kapur Gunung Hawu. Bukit kapur raksasa itu putih berdiri kokoh. Serupa tungku, di pusat tebing Gunung Hawu nampak lobang raksasa berlatar vegetasi. Di bagian atap agak kerucut juga terdapat lobang membentuk kawah yang tembus ke lobang tebing.
Di antara celah bebatuan itu, suara gemerincing karabiner terdengar dari ketinggian. Di atas sana, beberapa wisatawan tampak bergelantungan di tali, di antara dua tebing curam Gunung Hawu. Salah satunya adalah Serly (27), wisatawan asal Jakarta ini sedang mencoba teknik rappeling atau kegiatan wisata ekstrem berupa menuruni tebing vertikal setinggi 90 meter.
Dengan perlahan ia menuruni tebing. Pengalaman perdana membuatnya agak gugup karena belum terbiasa dengan penggunaan alat pelindung dan cara kerja tali. Namun setelah 10 menit bergelantung, Serly mulai terbiasa dan berhasil menaklukkan rasa takutnya. Ia pun menyempatkan diri menikmati pemandangan hamparan sawah dan 2-3 kali gaya untuk berfoto.
“Deg-degan banget, tapi seru! Rasanya antara takut dan kagum,” ujarnya sembari tersenyum gugup. “Begitu lihat ke bawah, hamparan sawah dan pemukiman Bandung terlihat indah banget. Kayak lukisan hidup," ucapnya.

Gunung Hawu, yang berada di kawasan karst Citatah, merupakan bagian dari bentang alam karst Padalarang yang terbentuk jutaan tahun lalu akibat proses pelarutan batu gamping. Formasi batu kapur menjulang ini menjadi salah satu ikon geologi Bandung Barat, sekaligus arena wisata ekstrem yang memacu adrenalin. Upaya penyelamatan warga telah merubah kawasan ini dari lokasi tambang jadi tempat tamasya anak muda menguji nyali.
Selain rappling , wisatawan juga bisa mencoba hammocking dan berkemah di puncak gunung Hawu. Dari atas, pemandangan yang tersaji luar biasa: gugusan bukit kapur berwarna putih keabuan berpadu dengan hijaunya pepohonan dan sawah, serta barisan atap rumah warga yang tampak mungil di kejauhan.
Baca Juga: Hikayat Bandung Utara jadi Kawasan Impian Kolonial, Gagal Terwujud di Persimpangan Sejarah
"Kalau bisa tempat ini tetap lestari gak dirusak jadi tambang. Biar saya bisa ke sini lagi, sampai kelak anak cucu saya juga bisa menikmati," tutur Serly.
Ketua Federasi Panjat Tebing Indonesia (FPTI) KBB sekaligus pemandu wisata ekstrem di Gunung Hawu, Hasan Husaeri mengatakan dukungan pelestarian Gunung Hawu dan area karst Citatah penting karena punya tinggi dari sisi keilmuan, ekologi dan saran olahraga.
Hasan menegaskan, kawasan karst bukan sekadar bentang alam indah, tetapi juga ruang hidup yang menyimpan fungsi vital “Karst itu ibarat laboratorium alam. Di dalamnya ada rekam jejak geologi, ekosistem unik, hingga sumber air yang sangat bergantung pada kondisi batuan. Kalau kawasan ini rusak, kita bukan hanya kehilangan tempat untuk berolahraga, tapi juga merusak sistem alami yang menopang kehidupan warga di sekitarnya,” ujarnya.
Ia menambahkan, pelindungan karst Citatah harus dipahami sebagai investasi jangka panjang. “Begitu rusak, karst tidak bisa dipulihkan dalam hitungan puluhan tahun. Maka diperlukan kesadaran bersama antara pemerintah, pelaku wisata, pemanjat, dan masyarakat untuk menjaga kawasan ini tetap lestari,” kata Hasan.
Kini, suasana baru perlahan tumbuh di Cidadap, Desa Padalarang, Bandung Barat. Setelah aktivitas tambang meredup, kampung yang dulu dipenuhi debu dan dentuman alat berat berubah menjadi ruang hidup yang kembali bernapas. Warga menemukan peluang baru dari alam yang kembali pulih—mulai dari jasa wisata, warung kecil, pemandu lokal, hingga penyewaan peralatan.
Kehidupan yang semula buram bak dinding kapur yang tergores tambang, kini memantulkan cahaya. Cerita warga pun menjadi lebih “berseri-seri”, sejalan dengan nama Kampung Berseri yang mereka bangun bersama: kampung yang tumbuh dari kesadaran menjaga karst, dan kampung yang menemukan kembali masa depannya setelah bunyi mesin tambang digantikan tawa wisatawan dan harapan yang tumbuh pelan-pelan.*