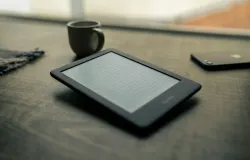AYOBANDUNG.ID - Kota Bandung yang kini dikenal sebagai kota kreatif penuh kafe dan macetnya tak kenal ampun, punya kisah panjang soal transportasi umum. Jauh sebelum warganya berkutat dengan tarif angkot yang suka naik sepihak atau bus DAMRI yang penuh sesak di jam sibuk, Bandung hanya mengenal jalan setapak dan tandu. Di abad ke-18, jalanan di Bandung lebih mirip jalur hiking daripada jalan raya. Orang-orang diangkut dengan tandu, kerbau, kuda, atau pikulan. Menurut Album Bandoeng Tempoe Doeloe karya Sudarsono Katam dan Lulus Abadi, sekitar tahun 1740-an, alat transportasi sehari-hari masih sebatas tenaga hewan dan otot manusia.
Baru pada awal abad ke-19, Gubernur Jenderal Herman Willem Daendels datang dengan ide brilian: membangun Jalan Raya Pos atau Grote Postweg pada 1810. Jalan lurus nan legendaris ini membentang dari Anyer sampai Panarukan, termasuk melintas di Bandung. Daendels mungkin tidak memikirkan macetnya Bandung di masa depan, tapi jalan itu jadi pondasi lahirnya mobilitas modern di tatar Priangan.
Jelang akhir abad ke-19, warga Bandung mulai mengenal sepeda—disebut “kereta angin”. Bayangkan betapa gagahnya orang Belanda bersepeda di tengah perkebunan teh. Namun urusan transportasi umum, pemerintah kolonial lebih serius membangun rel kereta api. Jalur Bandung–Batavia diresmikan 1884, menghubungkan ibu kota dengan Priangan. Kereta api menjadi sarana utama mobilitas antarkota, sementara transportasi dalam kota masih bergantung pada delman dan kereta kuda.
Baca Juga: Sejarah DAMRI, Bus Jagoan Warga Bandung
Setelah Indonesia merdeka, bus mulai masuk panggung utama. Tahun 1946, pemerintah membentuk Djawatan Angkoetan Motor Repoeblik Indonesia (DAMRI). Di Bandung, DAMRI jadi andalan transportasi umum sejak 1950-an. Terminal-terminal bus bermunculan, dari Buahbatu dekat Gedung Merdeka hingga Dago. Bus jadi arena sosial mini: pagi-pagi diisi pegawai negeri, tentara, mahasiswa, dan tukang sayur. Tak ada kelas sosial, semua duduk (atau berdiri) berdempetan.
Tahun 1960-an, Bandung sempat jadi panggung eksperimen bus impor. DAMRI mendatangkan bus Ikarus dari Uni Soviet. Busnya gagah, tapi masalahnya sederhana: suku cadangnya tidak sampai. Begitu hubungan diplomatik dengan Uni Soviet macet gegara G30S meletus, bus Ikarus pun ikut mogok. Akhirnya mereka jadi besi tua sebelum waktunya.
Baru pada 1978 pemerintah kota memberi mandat resmi kepada DAMRI sebagai operator bus kota. Lewat SK Walikota Bandung No. 10/85/1978, DAMRI menggantikan moda roda tiga alias bemo. Awalnya armada bus Tata asal India yang diandalkan, tapi tak lama bus-bus itu pensiun dini. Tahun 1980-an, DAMRI mendatangkan Mercy 1113, bus legendaris yang jadi tulang punggung transportasi kota selama satu dekade.
Di masa jayanya, DAMRI Bandung mengoperasikan lebih dari 200 armada dengan 15 trayek. Sopir dan kondektur jadi duet maut: sopir fokus mengemudi, kondektur sibuk merobek karcis. Konon, di jam sibuk pagi dan sore, bus bisa penuh sampai tak ada ruang gerak. Orang Bandung zaman itu harus pandai “ngaplok” alias menyelinap ke sela penumpang agar bisa ikut naik.

Kehadiran Angkot, Sang Raja Jalanan Bandung
Di sela kejayaan bus, muncul moda kecil nan lincah: angkot. Nama resminya “angkutan kota”, tapi semua orang lebih suka menyebutnya angkot. Awalnya, angkot bermula dari oplet dan mikrobus yang dimodifikasi. Fungsi utamanya sederhana: mengantar penumpang ke pelosok yang tak terjangkau bus besar. Angkot jadi primadona sejak 1980-an, terutama karena sifatnya yang fleksibel, atau dalam bahasa sehari-hari: bisa berhenti sesuka hati.
Tak ada halte resmi yang benar-benar ditaati, karena bagi angkot, setiap trotoar adalah terminal. Sopir angkot dikenal jago “ngetem”, menunggu penumpang hingga penuh sambil memandangi jalan dengan tatapan penuh harap. Penumpang pun sudah maklum, toh tarifnya murah dan angkot bisa masuk gang sempit sekalipun.
Baca Juga: Bandung Teknopolis di Gedebage, Proyek Gagal yang Tinggal Sejarah
Sejak 1970-an, wajah transportasi Bandung didominasi angkot. Uniknya, kehadiran angkot bukan hasil kebijakan pemerintah, melainkan inisiatif masyarakat dan dealer mobil. Dealer-dealer inilah yang membaca potensi jalur, lalu mengajukan izin trayek, misalnya Kalapa–Dago atau Kalapa–Ledeng. Akibatnya, sejak awal 1990-an hingga 2000, satu trayek identik dengan warna angkot hijau yang dikendalikan dealer.
Dominasi angkot makin terasa ketika Damri masuk lagi pada 1980-an. Meski Damri melayani jalur utama, angkot justru mengisi sisanya hingga merajai jalan-jalan Bandung. Fenomena ini membentuk sistem transportasi yang unik: angkot menjadi tulang punggung mobilitas warga, sekaligus menandai ketergantungan kota pada moda berbasis kendaraan kecil. Hingga kini, angkot tetap menjadi warna khas lalu lintas Bandung.
Di masa jayanya pada 1970-an hingga awal 2000-an, angkot menjadi tulang punggung mobilitas kota: menjangkau gang-gang sempit, mengisi kekosongan layanan bus, dan dikenal lewat warna-warna serta rute khasnya yang melekat di memori warga. Namun sejak awal abad ke-21 angkot menghadapi tekanan berlapis—ledakan kepemilikan kendaraan pribadi, buruknya kondisi layanan dan peremajaan armada, serta munculnya pesaing baru seperti ojek dan taksi online membuat daya saing angkot menurun dan banyak trayek yang kehilangan penumpang tetap.

Problem klasik angkot juga tak jauh dari tarif. Biaya menaiki angkot terbar seiring inflasi. Kedengarannya kecil, tapi bagi mahasiswa atau pelajar yang naik angkot dua kali sehari, kenaikan itu bikin kantong kering. Lebih parah lagi, ada sopir yang menaikkan tarif seenaknya di luar aturan resmi.
Selain tarif, kenyamanan juga jadi isu uama. Banyak angkot yang sudah uzur, AC hanya ada dalam mimpi, kursi reyot, dan pintu sering macet. Belum lagi aksi ngetem yang bikin macet jalan utama. Dishub Kota Bandung berkali-kali mencoba memaksa angkot masuk terminal, tapi sopir tetap lebih suka berhenti di pinggir jalan strategis.
Baca Juga: Sejarah Stadion GBLA, Panggung Kontroversi yang Hampir Dinamai Gelora Dada Rosada
Ojek Online dan Bus Rapid Transit Bandung
Pada era 2000-an, Bandung makin padat kendaraan pribadi. Motor dan mobil tumpah ruah di jalan. Bus besar makin susah melaju, sementara angkot semakin liar. Untuk menata ulang, pemerintah meluncurkan Trans Metro Bandung (TMB) sebagai versi “Busway ala Bandung”. Bus koridor ini diharapkan jadi solusi, tapi implementasinya sering tersendat.
Di sisi lain, transportasi daring muncul. Ojek online dan taksi online jadi pesaing berat angkot. Banyak warga lebih memilih naik ojol ketimbang berdesakan di angkot yang ngetem lama. Juli 2025, Kepala Dinas Perhubungan Bandung menyatakan sistem trayek angkot akan diubah agar tetap relevan di era digital, meski tidak dihapus total.

Sejarah sistem bus di Bandung Raya selalu diwarnai tarik ulur antara harapan modernisasi transportasi dan kenyataan di lapangan. Pada awalnya, pemerintah kota mencoba menghadirkan TMB sekitar 2009–2010 sebagai versi lokal bus rapid transit (BRT). TMB diproyeksikan jadi bus rapid transit (BRT) lokal: punya halte khusus, rute tetap, dan tarif standar. Singkat kata, Bandung ingin menyalin Jakarta.
Sayangnya, cita-cita sering kali tumbang di aspal. TMB tak punya jalur khusus, armadanya pun bisa dihitung dengan jari. Warga lebih nyaman naik angkot yang bisa berhenti di mana saja, bahkan di depan pintu rumah kalau sopirnya baik hati. TMB akhirnya tinggal nama: sekadar proyek yang terdengar gagah di awal, tapi meredup tak lama berselang. Sampai kini memang masih ada beberapa bus TMB tersisa, tapi lebih mirip hantu di jalanan—ada, tapi jarang kelihatan.
Pemerintah pusat tampaknya tak rela Bandung gagal begitu saja. Lewat Kementerian Perhubungan, mereka melempar proyek baru bernama Trans Metro Pasundan (TMP) pada 2021–2022. Kali ini bukan hanya Kota Bandung yang kena imbas, melainkan seluruh Bandung Raya, bahkan sampai Sumedang. Busnya lebih modern, halte-haltenya dibangun dengan gaya BRT, dan tarifnya disubsidi. Bedanya dengan TMB: inisiatifnya datang dari Jakarta, bukan dari Balai Kota.
Tapi, TMP pun masih setengah hati. Branding kurang menancap, integrasi dengan angkot nyaris tak ada. Pemerintah daerah tak lebih dari figuran, sementara Kemenhub jadi dalang utama. Meski begitu, TMP semacam pondasi, semacam batu bata pertama, yang kelak disusun ulang oleh pemerintah provinsi.
Baca Juga: Sejarah Hari Jadi Kota Bandung, Kenapa 25 September?
Pada akhir 2024, babak baru dimulai. Pemerintah Provinsi Jawa Barat memutuskan merombak TMP habis-habisan. Mereka menamainya Metro Jabar Trans (MJT), berlaku per 1 Januari 2025. Kali ini pengelolaan diserahkan ke BUMD PT Jasa Sarana. Operatornya tetap campuran: swasta dan BUMN, termasuk Perum DAMRI.
MJT sejak awal diproyeksikan lebih serius. Enam koridor langsung digas: Leuwipanjang–Soreang, Kota Baru Parahyangan–Alun-alun Bandung, BEC–Baleendah, Leuwipanjang–Dago, Dago–Jatinangor, dan Leuwipanjang–Majalaya. Targetnya: 21 koridor pada 2027. Tarif pun ramah kantong: Rp4.900 untuk umum, Rp2.000 untuk pelajar dan lansia. Seakan Pemprov ingin bilang: ini transportasi untuk rakyat, bukan sekadar proyek.
Di tengah transformasi ini, orang bertanya: ke mana DAMRI? BUMN legendaris ini sejak lama setia wara-wiri di Bandung, dari trayek antarkota hingga dalam kota. DAMRI pula yang pertama menguji coba bus listrik di kota ini. Tapi dalam kerangka MJT, DAMRI bukan lagi penguasa panggung, melainkan salah satu pemain. Ia kini hanya operator, bukan pemilik sistem. Perannya bergeser, meski eksistensinya tetap ada. DAMRI jalan terus di trayek non-BRT, sembari melayani sebagian rute MJT.