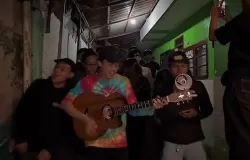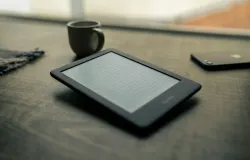Sejak dahulu, masyarakat di berbagai daerah di Nusantara hidup berdampingan dengan sungai, begitu juga masyarakat Sunda dengan sungai Citarum. Dalam cerita lisan, Citarum bukan sekadar aliran air, melainkan nadi kehidupan yang dijaga oleh kekuatan gaib.
Bayangkan suasana ratusan tahun silam, ketika matahari mulai terlihat di ufuk timur, kabut tipis menyelimuti bantaran Citarum. Warga berkumpul di tepian, lalu perlahan mendorong sasajen, berisi bunga, nasi tumpeng kecil, dan dupa dialirkan ke tengah arus.
Mereka memohon dengan khidmat kepada Sanghyang penjaga sungai, agar air tetap jernih dan sawah mereka subur. Riak air yang menelan sesaji seakan sebagai tanda kalau sungai mendengar dan memberikan restu.
Cerita lain tak kalah terkenal adalah legenda Sangkuriang. Ketika Sangkuriang membendung paksa aliran air menjadi danau, namun usahanya gagal karena hasrat menikahi Dayang Sumbi, Ibunya sendiri. Airnya kemudian mencari jalan keluar menuju selatan, membentuk aliran yang kini kita kenal sebagai Sungai Citarum. Mitos yang memperkuat adanya danau purba di Kota Bandung. Dalam mitos ini, manusia yang melawan hukum alam selalu berujung pada bencana.
Kisah tersebut, meski dibungkus mitologi, menyimpan pesan ekologis. Alam memiliki keseimbangannya sendiri, dan manusia dituntut untuk menjaganya. Seperti pepatah Sunda mengatakan, “Lamun ngabalukarkeun karuksakan alam, tungtungna bakal balik ka diri sorangan”, jika merusak alam, akibatnya kembali kepada manusia. Hal tersebut pada hakekatnya, sejalan dengan Kalam Sang Khalik "Jika kamu berbuat baik, (berarti) kamu berbuat baik untuk dirimu sendiri (Al-Isra : 7).
Sungai Citarum dengan panjang sekitar 297 km, dari hulu di Gunung Wayang, Bandung Selatan, hingga bermuara di Laut Jawa. Citarum mengairi sawah, memasok listrik lewat waduk-waduk besar, hingga menjadi sumber air baku. Namun sayangnya, Citarum juga menanggung beban limbah rumah tangga, industri, dan sampah plastik, bahkan bangkai hewan yang terdampak Penyakit Mulut dan Kuku (PMK).
Kota Bandung, meski tidak dilintasi langsung oleh aliran utama Citarum, tetap punya peran besar. Sungai Cikapundung yang membelah kota bermuara langsung ke Citarum di Dayeuhkolot. Artinya, setiap sampah yang dibuang ke Cikapundung pada akhirnya akan jatuh ke “tenggorokan” Citarum.
Tidak heran jika hal tersebut menarik perhatian Presiden Joko Widodo yang memprakarsai program nasional Citarum Harum. Program ini melibatkan banyak nara damping dar unsur TNI, pemerintah daerah, akademisi, hingga komunitas warga, dibawah koordinasi Satuan Tugas Citarum Harum.
Kini, menjaga sungai bukan tentang pekerjaan teknis, melainkan pelajaran moral. Teras Cikapundung, misalnya, telah menjadi ruang edukasi di tengah kota Bandung, tempat anak-anak belajar bahwa sungai adalah sahabat, bukan tempat sampah. Kampus-kampus di Bandung pun mulai menjadikan Citarum sebagai laboratorium hidup, tempat mahasiswa meneliti kualitas air, sosial budaya bantaran, hingga model kebijakan publik.
Orang Sunda punya ungkapan: “Leuweung ruksak, cai beak, manusa balangsak”, jika hutan rusak dan air habis, manusia akan sengsara.
Pepatah ini terasa nyata di Citarum. Bahkan Prabu Siliwangi yang dikenal sebagai raja besar Pajajaran memberikan pesan “Uga Siliwangi”, “Lamun hirup ulah ngahianat ka sasama jeung alam”, dalam hidup, jangan pernah berkhianat kepada sesama dan alam. Pesan leluhur ini seolah kembali menggema saat kita menyaksikan kondisi sungai hari ini.
Mungkin, kalau leluhur dulu memberikan sesaji ke Sanghyang Tikoro untuk menenangkan aliran sungai, kini sesaji terbaik yang bisa kita berikan adalah tindakan nyata dengan: tidak membuang sampah ke sungai, mengurangi limbah, dan ikut terlibat dalam gerakan lingkungan.
Hayu, Jaga Citarum

Bagi generasi muda, khususnya Gen Z di Bandung dan Jawa Barat, Sungai Citarum bukan hanya warisan alam, melainkan juga ruang belajar dan berkarya. Setiap tetes airnya menyimpan cerita leluhur, setiap riaknya menyimpan peluang untuk masa depan yang lebih baik.
Hal sederhana yang bisa kita mulai, membuat konten edukasi di media sosial tentang kebersihan sungai, ikut program komunitas lingkungan, atau menjadikan projek sekolah dan kampus bertema Citarum Harum. Dengan cara itu, mitos dan kearifan lokal tidak berhenti sebagai cerita masa lalu, melainkan hidup kembali sebagai inspirasi gerakan nyata.
Jika karuhun menyampaikan melalui ritual dan sesaji, kini tindakan nyata yang akan menentukan apakah Citarum akan Harum atau tinggal cerita?. Citarum adalah cermin peradaban. Sejarah yang akan menilai apakah kita generasi yang menjaga, atau justru yang merusaknya.
Pepatah Sunda mengingatkan, “Cai téh pangéran nu ngidinan hirup”, air adalah anugerah Tuhan yang memberi kehidupan. Maka, menjaga Citarum sama artinya dengan menjaga diri kita sendiri, menjaga kota kita, dan menjaga masa depan generasi yang akan datang. (*)